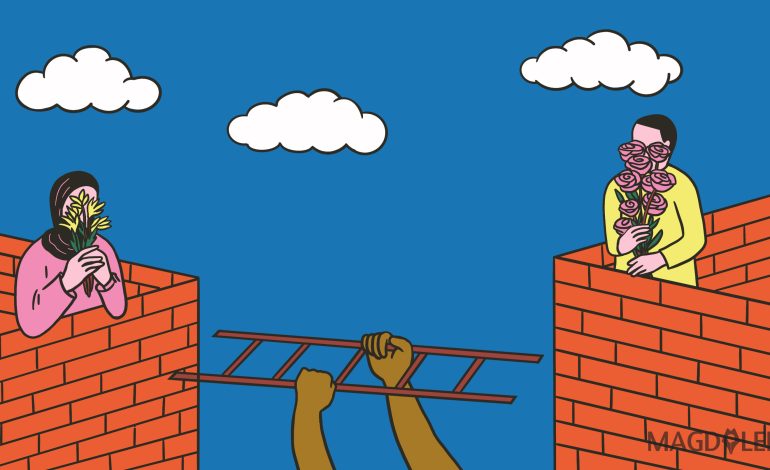Andai Jadi Ibu, Ini yang Takkan Saya Lakukan pada Anak
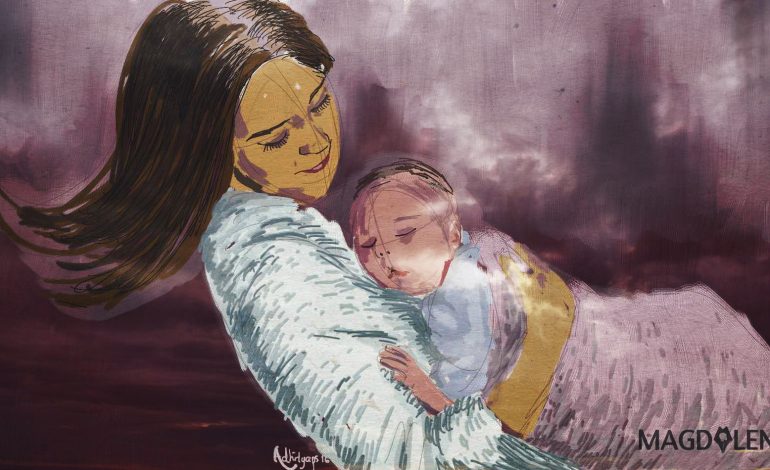
Dulu, setiap mendengar lika-liku kehidupan teman-teman, saya selalu merasa beruntung karena tumbuh di keluarga harmonis dengan orang tua lengkap. Awalnya ini membuat bertanya-tanya, kok diri saya baik-baik saja, seperti tidak ada masalah.
Namun, saat mewawancarai seorang psikolog anak, ia mengatakan pada usia awal 20-an, seseorang cenderung baru menemukan kerentanan dalam dirinya, terutama berkaitan dengan isu keluarga. Ternyata, memang benar saya baru menemukannya belakangan ini—mungkin ini salah satu dampak positif dari kebanyakan di rumah selama pandemi (meskipun memang seharusnya begitu).
Ketika teman-teman memiliki permasalahan dari peristiwa besar, milik saya justru tak kasatmata, tapi terjadi terus menerus hingga membentuk kepribadian. Alhasil, sekarang saya harus memperbaiki “kerusakan” yang terbentuk, lewat cara ibu dan bapak bersikap kepada anaknya.
Baca Juga: 8 Hal Penting Sebelum Memutuskan Ingin Memiliki Anak
Walaupun sampai sekarang saya belum tahu apakah saya menginginkan anak atau tidak, setidaknya saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan beberapa hal ini jika menjadi seorang ibu.
-
Body Shaming
Sebuah unggahan Magdalene di Instagram pada Agustus lalu, tentang bagian-bagian tubuh yang kadang bikin insecure membuka luka yang tidak terlihat dalam diri saya. Kebetulan semua bagian tubuh dalam visual itu pernah jadi “sasaran” nasihat ibu, mulai dari bulu kaki, punggung berjerawat, perut buncit, sampai stretch mark di perut dan paha.
Sejak usia belasan tahun, Ibu dan Bapak sering mengomentari tubuh saya dan mengingatkan pentingnya merawat tubuh. Kalau pun enggak cantik, penampilan perempuan harus terlihat “pantas”, katanya. “Kamu jadi perempuan kok badannya begitu, emangnya enggak malu? Nanti enggak ada laki-laki yang naksir loh.”
Akibatnya? Saya sulit menerima diri sendiri.
Saya pernah membaca wawancara Dr. Leslie Sim, seorang clinical director program tentang gangguan makan di Mayo Clinic dan psikolog anak, bersama USA Today. Katanya, ibu memiliki peran penting dalam mempengaruhi citra diri anak perempuannya. Bahkan, orang tua dengan jenis kelamin sama dengan anak adalah panutan mereka.
Seandainya punya anak, saya akan mengajarkan mereka melihat dan memahami keberagaman bentuk tubuh. Mereka harus tahu bahwa realitasnya, populasi perempuan dan laki-laki bertubuh sempurna seperti di iklan televisi itu tak seberapa.
Begitu juga dengan warna kulit. Namanya orang Indonesia dan tinggal di negara beriklim tropis, normal jika kita berkulit gelap atau sawo matang. Enggak perlu terobsesi punya kulit seputih susu.
Mau bagaimanapun bentuknya, mereka perlu belajar menghargai tubuh. Pun ketika mengingatkan pentingnya merawat diri, saya ingin mereka melakukannya sebagai bentuk mencintai diri, bukan memuaskan orang lain.
Semoga saya enggak akan melakukan body shaming pada anak dengan embel-embel “demi kebaikan”, yang menyakiti dan mempengaruhi kepercayaan diri mereka.
Baca Juga: Perisakan Anak Betul-betul Merusak
-
Terlalu Protektif
Bisa dikatakan saya cukup kehilangan masa remaja yang menyenangkan karena sikap ibu dan bapak, yang enggak mengizinkan pulang di atas jam enam sore. Padahal, saya ingin menikmati serunya kehidupan anak SMA. Maklum, sudah anak tunggal, perempuan pula.
Otomatis saya enggak bisa menghadiri beberapa undangan sweet seventeen maupun nongkrong bareng teman-teman sampai malam, karena enggak enak kalau buru-buru pulang duluan.
Bagi orang tua, mungkin terlalu protektif adalah salah satu bentuk kasih sayang. Namun, mereka enggak sadar kalau itu membatasi ruang berkembang anak.
Menurut Healthline, orang tua dengan pengasuhan semacam ini akan menghasilkan anak-anak yang suka berbohong. Mereka akan melakukan manipulasi untuk mengantisipasi reaksi tidak diinginkan dari orang tuanya. Jadi, kalimat “overprotective parents raise the best liars” tidak populer di media sosial tanpa alasan.
Contoh nyatanya, saya jadi tidak terbuka dan sering berbohong pada orang tua supaya enggak kehilangan momen bareng teman-teman. Bukan berarti saya membuat kebohongan besar dan bertindak macam-macam, melainkan ngaku jalanan macet padahal ingin pulang terlambat, atau bilang pergi ke daerah Jakarta Selatan saat kenyataannya main ke Jakarta Barat—biar dipikirnya enggak kejauhan.
Berdasarkan pengalaman ini, saya enggak ingin anak-anak kelak kehilangan masa mudanya yang seharusnya dinikmati dengan bebas. Betul, saya belum tahu rasanya khawatir sebagai orang tua, tapi selama mereka bisa memegang kepercayaan, saya enggak akan menghalangi kebahagiaannya mengeksplor masa muda.
Baca Juga: Hormati Orang Tuamu Tapi Bela Dirimu Sendiri
-
Kurang Menghargai Privasi
Sebagai anak berusia 8 tahun, saya lagi senang-senangnya menceritakan keseharian di diary dan menulis cerpen di buku catatan. Masih jelas di ingatan saya, ibu suka mengambil kesempatan untuk membaca dan menceritakan tulisan saya ke beberapa saudara. Entah apa maksudnya, karena enggak lama kemudian mereka berkomentar dan menertawakan saya.
Lalu saat berhenti ngekos akibat pandemi dan pulang ke rumah orang tua, lagi-lagi ibu mengabaikan privasi saya. Ia senang tidur di kamar saya, masuk kamar tanpa mengetuk pintu, dan tidak kunjung paham kalau saya butuh ruang sendiri—ia menganggap menemani anak adalah bentuk dukungan.
Padahal, anak yang membutuhkan jarak dan ingin memiliki privasi adalah bagian dari pertumbuhan sebagai pribadi dewasa. Kita mulai mencari tahu jati diri, keinginan, kebutuhan, mulai menghadapi dan belajar menyelesaikan tantangan hidup.
Arain dkk. menjelaskan dalam “Maturation of the adolescent brain” (2012), kebutuhan privasi menjadi salah satu kebutuhan karena otak berkembang pesat, dengan kemampuan berpikir dan mengembangkan minat sosial baru.
Jadi, enggak semua urusan anak perlu diketahui orang tua atau mereka menemani anaknya melulu. Lagi pula, bersikap protektif terhadap informasi tentang diri sendiri artinya seseorang ingin mandiri dan memiliki otoritas atas dirinya. Dan sebagai orang tua, semestinya Ibu bisa belajar mengerti dan menghargai itu.
-
Meremehkan Kemampuan
Sewaktu SD, saya paling anti pakai sepatu bertali karena enggak tahu cara memasukkan tali ke dalam lubang dan mengikatnya.
Jangankan bersabar. Ibu dan Bapak mengajarkan dengan nada dan tatapan judgy, dan saya harus bisa mengikatnya di hadapan mereka. Alhasil, cuma keringat dingin yang muncul di tangan karena takut salah ketika saya berkali-kali mendengar mereka bilang, “Masa gitu aja enggak bisa?”
Belum lagi saat memilih kuliah jurnalistik dan ingin jadi reporter, ibu menanggapi, “Memangnya kamu bisa menulis?” Kalimat-kalimat sederhana namun bernada menghakimi itu tertanam di pikiran saya, bikin saya sedikit-sedikit mempertanyakan kemampuan diri.
Psikoterapis asal New York, Alana Barlia menjelaskan, situasi ini dinamakan inferiority complex. Ia datang dari pengalaman masa kecil seseorang karena berkembang di lingkungan yang tidak pernah memvalidasi dirinya.“Itu terbentuk di alam bawah sadar sehingga memengaruhi cara berpikir dan perilaku,” tuturnya kepada Bustle.
Enggak heran, pengaruh kata-kata Ibu dan Bapak begitu kuat. Sampai saat ini, saya selalu merasa kurang dan enggak mampu menulis sebaik orang lain.
Maka itu, nantinya saya ingin belajar memberikan afirmasi dan validasi kepada anak-anak, sekecil apa pun itu. Dan, enggak mesti prestasi di sekolah, karena banyak yang lebih berharga daripada kemampuan akademis.
Saya akan mendorong ambisi mereka dan ingin mereka percaya bahwa mereka bisa melakukan banyak hal hebat.
-
Silent Treatment
Jarang ada kata “maaf” yang diucapkan, jika Ibu, Bapak, dan saya melakukan kesalahan.
Ujung-ujungnya, kami menghilangkan konflik dan menghindari konfrontasi dengan memberikan silent treatment pada satu sama lain, lalu menunggu berhari-hari hingga capek sendiri dan kembali bersikap biasa saja, seolah masalah dan kesalahan tersebut tidak pernah terjadi.
Tapi, saya teringat perkataan Kipling Williams, seorang profesor psikologi di Purdue University, dalam sebuah artikel The Atlantic. Ia menuturkan, silent treatment digunakan karena mampu membuat orang lain merasa bersalah dan dapat keluar dari permasalahan tanpa terlihat abusive.
Kenyataannya, tindakan ini termasuk emotional abuse bagi orang yang melakukan kesalahan. Sementara, pelaku silent treatment akan terjebak dalam kemarahan dan perasaan negatif.
Oleh karena itu, ketika bulan lalu melakukan kesalahan fatal, saya memanfaatkan kejadian itu untuk berusaha memiliki kebesaran hati. Saya berhasil mengucapkan “maaf” pada Ibu dan Bapak. Semoga mereka sadar dan tergugah untuk belajar mengatakannya di lain waktu.