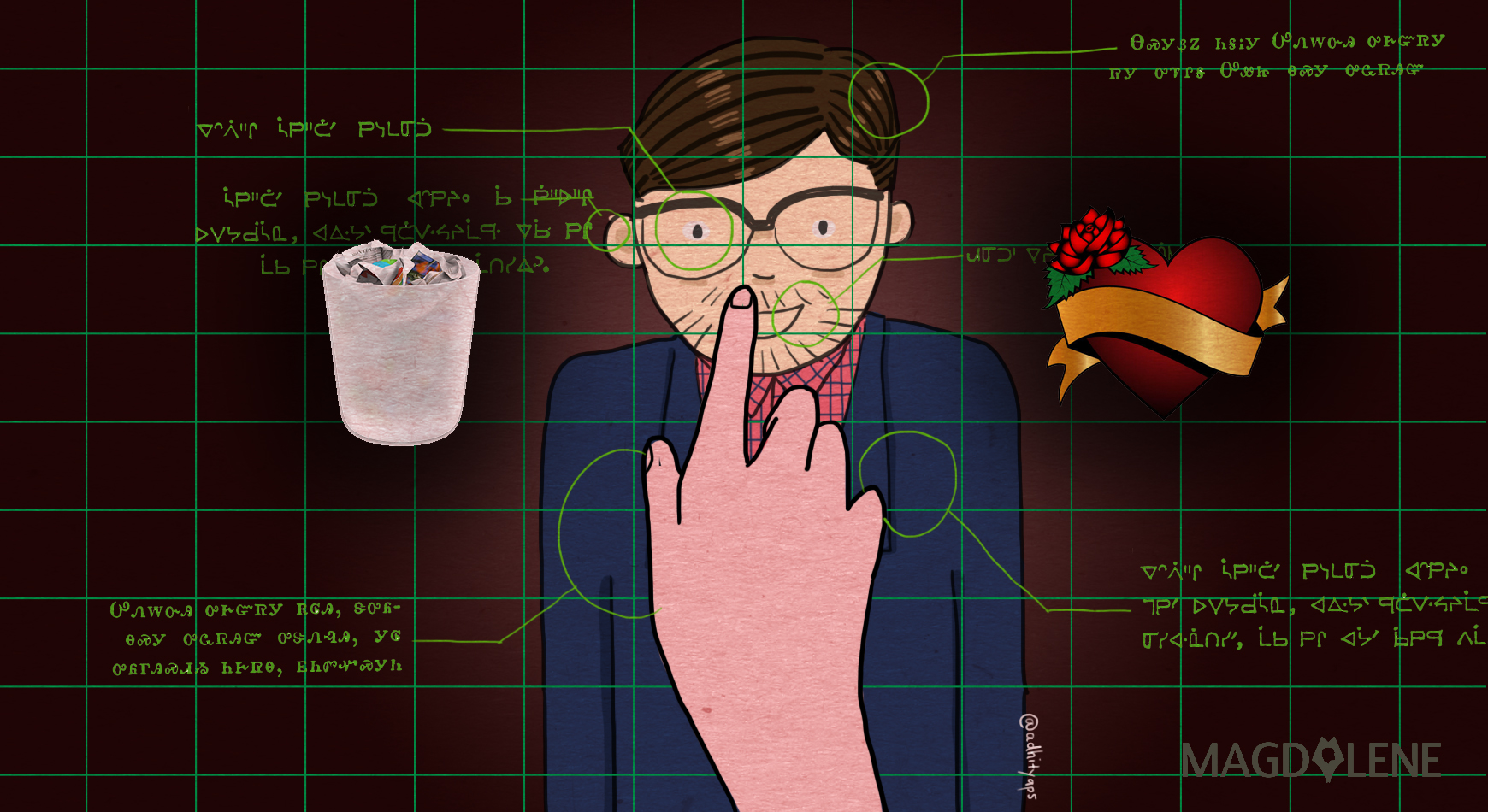Lelaki Marah Ditinggal Pasangan Makan Duluan, Tanda Maskulinitas Toksik

Beberapa waktu lalu, lini masa Twitter kembali ramai dengan pengakuan sender di akun confession. Kali ini perkara suami yang marah pada istrinya, akibat ditinggal makan malam duluan sebelum pulang kerja. Sebagai kepala keluarga, ia merasa direndahkan dan enggak dihormati, lantaran harus makan “makanan sisa” istrinya.
Kenyataannya, itu bukan cerita di dunia maya belaka. Sebagai anak, “Dian”–bukan nama sebenarnya–pernah melalui situasi tersebut di keluarganya.
Saat sang ayah masih bekerja, Dian, ibu, dan adiknya, harus menunggu ia tiba di rumah untuk makan malam bersama. Biasanya, ayah Dian tiba di rumah pukul enam sore. Namun, keluarganya diperbolehkan makan malam duluan jika ayahnya pulang lebih larut. Asalkan memberi kabar terlebih dahulu.
Baca Juga: 5 Tanda Kamu Punya Maskulinitas Rapuh
Dian mengatakan, sebagai kepala keluarga, ayahnya merasa perlu dihormati. Ia juga tipe suami yang kebutuhannya perlu disiapkan. Hal itu terlihat dari kebiasaan ayah Dian, yang meminta istri atau Dian mengambilkan nasi sampai lauk. Bahkan, ada urutan mengambilnya.
“Aku pernah ambil (makanan) duluan, dimarahin,” ungkap Dian pada Magdalene. Urutan itu seharusnya diawali dari ayah, ibu, diikuti Dian dan adiknya.
Kebiasaan itu berakhir ketika Dian duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA). Itu karena Dian dan adiknya mulai punya kesibukan masing-masing. Ayahnya pun sering pulang di atas jam enam sore. Itu juga yang membuat ayah Dian mulai mengambil makan sendiri.
Kedua realitas di atas merupakan maskulinitas toksik dalam relasi romantis–maupun keluarga–yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ego laki-laki terluka, ketika perannya sebagai kepala keluarga dianggap kurang dihargai. Sementara, posisi mereka dipandang paling tinggi secara struktural.
Penyebabnya tak lain tak bukan adalah budaya patriarki yang mengakar. Akibatnya, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan. Bahkan, menjadi keharusan bagi perempuan untuk mengutamakan kebutuhan suaminya.
Di samping itu, peran latar belakang budaya seseorang berasal turut berperan. Misalnya keluarga Dian yang berasal dari Jawa Tengah. Ia mengatakan, orang tuanya berasal dari keluarga patriarkal. Kebiasaan menunggu kepala keluarga untuk makan malam bersama juga dilakukan kakek neneknya–dari pihak ayah maupun ibu. Maka itu, pola yang sama dilakukan orang tuanya, dan tidak menimbulkan perdebatan dalam relasi orang tuanya.
Pada dasarnya, budaya Jawa menekankan laki-laki sebagai kepala keluarga, sosok yang kuat, dan jadi panutan. Sementara perempuan melaksanakan tugas domestik, diharapkan patuh terhadap kemauan suami, tidak membantah, dan bersikap pasrah. Itu bahkan tertulis dalam Serat Centhini (1814), kesusastraan Jawa yang ditulis oleh Adipati Anom Amangkunagara III. Lebih dari itu, budaya Jawa memandang perempuan ideal berdasarkan sifat lemah lembut, dan tidak lebih hebat dari laki-laki.
Ciri-ciri tersebut membuktikan maskulinitas toksik yang dilanggengkan turun-temurun. Bahkan, masih diterapkan dan diinternalisasi sampai saat ini. Karena itu, contohnya sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam relasi romantis yang ikut terdampak.
Baca Juga: Menikah: Menghidupkan atau Mematikan Diri Perempuan?
Dampak Maskulinitas Toksik pada Relasi
Maskulinitas toksik yang muncul dalam hubungan bukan hanya perkara menunggu pasangan pulang kerja untuk makan bareng, atau mengambilkan mereka makanan. Ada contoh lainnya yang enggak disadari, tapi nyata dalam hal-hal kecil.
Misalnya mengontrol pengambilan keputusan terkait finansial. Ketika laki-laki ingin membeli sesuatu yang diinginkan, mereka tinggal membelinya. Namun, perempuan memerlukan persetujuan pasangannya, atau mengutamakan kebutuhan keluarga terpenuhi.
Enggak jarang, nasihat untuk tidak boros dan memprioritaskan keperluan primer diucapkan laki-laki. Masalahnya, segelintir dari mereka kerap membeli barang sesuka hati, tanpa pertimbangan seperti yang diutarakan pada pasangannya.
Contoh lainnya, laki-laki yang mengutamakan kepentingannya. Mereka meminta pasangannya membatalkan janji dengan teman-temannya, tanpa pernah melakukan hal yang sama. Atau saat bertengkar karena lupa melupakan janji kencan, bukannya meminta maaf dengan tulus justru minta dimaklumi karena “namanya juga laki-laki, nggak jago mengingat hal-hal detail”. Ada juga yang menentukan dan mengomentari penampilan pasangannya, agar menyesuaikan keinginannya.
Dengan kata lain, laki-laki merasa berhak mengontrol tubuh dan kehidupan perempuan. Mereka menganggap punya peran dominan dalam hubungan tersebut. Namun, ibarat bom waktu, dampak budaya patriarki ini akan berdampak pada berbagai aspek dalam relasi romantis.
Center for Modern Relationships–lembaga terapis seks dan hubungan di Amerika Serikat, mencatat tiga dampak dari maskulinitas toksik pada hubungan.
Pertama, komunikasi. Efektivitas komunikasi ditentukan berdasarkan cara mengekspresikan, keaktifan mendengar, memberikan empati, dan belajar mengartikulasikan emosi. Meskipun terdengar sederhana, sebagian laki-laki kesulitan meregulasikan emosinya. Mereka cenderung defensif ketika harus membicarakan perasaannya.
Yang diekspresikan justru reaksi mereka atas tindakan yang menyakiti. Marah, misalnya, bersikap agresif, atau menghindari pembicaraan.
Ini kemudian berkaitan dengan poin kedua, yakni bersikap rentan. Pasalnya, kerentanan emosional, atau emotional vulnerability, adalah hal penting dalam relasi. Aspek ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hubungan. Seperti membangun kepercayaan, terhubung dengan pasangan secara fisik dan emosional, serta mempertahankan rasa aman.
Dalam hal ini, kerentanan emosional merujuk pada kemampuan dan kemauan mengakui, serta mengekspresikan emosi. Karena itu, dibutuhkan kemauan untuk membuka diri. Termasuk mau mendiskusikan pembahasan rumit, atau memengaruhi perasaan. Sayangnya, sebagian laki-laki enggan melakukannya karena melibatkan emosi–merasa sedih, malu, cemas, dan insecure.
Beberapa reaksi itu merupakan dampak dari kurang diajarkan mengomunikasikan perasaannya sejak kecil. Laki-laki juga ditanamkan sebagai sosok yang kuat, dominan, dan lebih hebat dari perempuan.
Akibatnya berdampak ketika laki-laki menjalin hubungan romantis. Ego mereka rentan tersakiti oleh tindakan atau perkataan pasangannya–karena berlawanan dengan nilai-nilai dan cara pandang masyarakat terhadap laki-laki.
Ketiga, keintiman fisik. Perkara menunjukkan kejantanan enggak hanya melibatkan emosi, tapi juga hubungan seks. Ada dua hal yang jadi tolok ukur kejantanan laki-laki; memiliki hasrat seksual dan performa dalam memberikan kepuasan terhadap pasangannya.
Secara enggak langsung, tolok ukur itu memberikan tekanan terhadap laki-laki. Ada anggapan kurang maskulin, kalau salah satu atau dua-duanya tidak terpenuhi. Dampaknya, laki-laki jadi mengalami disfungsi ereksi dan kecemasan, yang berkaitan dengan keintiman fisik bersama pasangan. Pada akhirnya akan menciptakan jarak dalam hubungan, baik fisik maupun emosional.
Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk menghindari maskulinitas toksik dalam hubungan?
Baca Juga: Kekerasan dalam Relasi Romantis, Di Mana Jalan Keluar?
Tips Atasi Maskulinitas Toksik dalam Hubungan
Akibat dibentuk oleh budaya, maskulinitas toksik bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi. Namun, bukan berarti konsep ini tidak dapat dipatahkan. Menurut penulis Taneasha White dalam tulisannya di Healthline, laki-laki perlu mengidentifikasi dan mengakuinya. Barulah diikuti dengan berbagai upaya.
Contohnya dengan berefleksi untuk mengenal bagaimana maskulinitas toksik itu melekat dalam diri. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu pernah menyangkal sesuatu karena terlalu feminin? Atau menghakimi orang lain yang kurang maskulin?
Peran pasangan dibutuhkan dalam proses ini, untuk membantu menelusuri latar belakang budaya, keluarga, lingkungan pertemanan, dan tempat bekerja. Dari situ akan diketahui cara lingkungan tersebut, memaknai arti menjadi laki-laki. Apakah masih lekat dengan peran gender dan stereotip, atau sudah mendobraknya?
Selain itu, bangun percakapan dengan orang-orang di sekitar yang ekspresi gendernya berbeda. Menurut White, langkah ini dapat memberikan perspektif lain tentang bagaimana kamu, sebagai laki-laki, menghadapi situasi sekaligus menyelesaikan permasalahan. Sebab, ada kemungkinan selama ini masih didominasi oleh bias yang berkaitan dengan maskulinitas. Atau melihat segala sesuatu dari sudut pandang laki-laki.
Mendengarkan pernyataan orang lain mungkin akan membuatmu kurang nyaman, karena enggak menyangka tindakan yang dilakukan berbeda dengan yang diinginkan. Perlu diingat, perilaku sebelumnya dilandaskan oleh maskulinitas toksik, yang saat ini berusaha dipatahkan.
Lalu, coba bangun percakapan dengan orang-orang yang masih mengamini maskulinitas toksik. Salah satunya teman laki-laki yang enggan menggunakan skincare. Tanyakan alasannya, apakah ia meyakini perawatan tubuh umumnya dilakukan perempuan? Namun, pastikan percakapan itu bukan untuk membenarkan argumentasi salah satu pihak.
Yang terakhir dan perlu ditekankan, pahami ini sebagai proses panjang dan perlu dilakukan perlahan. Enggak masalah kalau masih sulit mengakui–bahkan malu dengan tindakan-tindakan sebelumnya, karena setiap orang memiliki proses belajarnya masing-masing. Sambil memperbaiki pandangan diri terhadap maskulinitas toksik, perilaku tersebut dalam relasi romantis juga akan berubah.