Perempuan Queer Indonesia di AS: Ketidakpastian dan Ancaman di Era Baru Trump
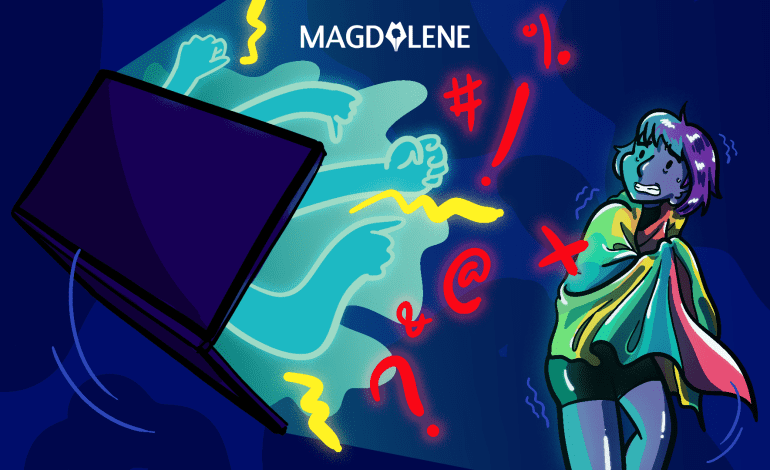
Saat Asri, 27, menyimak berita tentang perintah eksekutif terbaru dari Presiden Donald Trump, perasaannya campur aduk antara marah dan takut. Sebagai seorang transpuan yang merupakan bagian dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat, ia merasa hidupnya yang sudah mapan mulai terancam.
Bekerja sebagai manajer komunikasi di kantor inisiatif transgender milik pemerintah kota San Francisco, Asri sudah lama menyadari bahwa politik AS bisa sangat mempengaruhi kehidupan komunitas transgender. Tapi dampak langsung dari kebijakan Trump kali ini terasa jauh lebih nyata.
“Aku rasa mereka benar-benar ingin menghapus keberadaan kami,” ujar Asri saat dihubungi Magdalene Rabu lalu (5/3). Perintah eksekutif Trump yang mewajibkan pengembalian identitas gender ke jenis kelamin saat lahir di semua dokumen sipil federal, seperti paspor, jaminan sosial, hingga izin kerja, membuatnya merasa identitasnya sedang dihapus paksa oleh negara.
“Aku lihat teman-teman trans, mulai dari figur publik sampai orang biasa, bercerita di media sosial tentang bagaimana dokumen pribadi mereka dipermasalahkan karena identitas gender mereka,” ujar Asri.
“Mereka sudah melakukan banyak hal untuk bisa hidup dengan identitas gender yang mengafirmasi mereka. Tapi sekarang, kalau bepergian atau kena pemeriksaan polisi, mereka dipaksa keluar dari kenyamanan itu karena gender marker yang tidak sesuai.”
Ketakutan ini bukan hanya soal ketidaknyamanan administratif. Jika seseorang dengan identitas gender yang tidak sesuai dihentikan oleh petugas yang transfobik, situasinya bisa berujung pada diskriminasi atau bahkan kekerasan.
“Kami jadi rentan untuk diintimidasi atau dipermasalahkan,” tambah Asri.
Baca juga: Di Balik Tuduhan Transgender pada Imane Khelif: Misoginis, Rasisme, dan Transfobia
Ancaman kebijakan Trump terhadap komunitas LGBT
Sejak kembali ke Gedung Putih untuk kedua kalinya, Trump bergerak cepat mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif yang kontroversial, termasuk kebijakan yang menarget komunitas transgender. Salah satu dampaknya yang paling menonjol adalah penggantian gender marker pada paspor milik aktris trans AS, Hunter Schafer, 26. Schafer, yang sebelumnya diakui sebagai perempuan di semua dokumen sipil, menunjukkan paspor barunya di TikTok dengan gender marker “M” untuk male (laki-laki).
“Karena presiden kita banyak omong, aku sempat berpikir, ‘Aku baru akan percaya kalau aku melihatnya sendiri.’ Dan hari ini saya melihatnya,” ujar Schafer dalam video yang diunggah pada 22 Februari.
Selain menyasar komunitas transgender, kebijakan Trump dan Partai Republik juga mengancam kesetaraan pernikahan di AS. Sejumlah legislator Republik di sembilan negara bagian telah mendesak Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali keputusan Obergefell v. Hodges yang menetapkan pernikahan sesama jenis sebagai hak konstitusional di seluruh AS.
Josh Shiver, anggota dewan perwakilan dari Michigan, memimpin upaya ini. Menurutnya, keputusan Obergefell telah meningkatkan “persekusi terhadap kebebasan beragama.” Jika keputusan ini dicabut, kewenangan untuk mengatur pernikahan akan dikembalikan ke pemerintah negara bagian, dan ini ancaman nyata bagi komunitas LGBT yang tinggal di negara bagian konservatif.
Komposisi Mahkamah Agung yang saat ini didominasi oleh hakim konservatif memperbesar kemungkinan pengguguran keputusan Obergefell. Dua hakim konservatif, Clarence Thomas dan Samuel Alito, sudah pernah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan ini. Alito bahkan menyebut bahwa Obergefell membuat orang yang memiliki pandangan tradisional tentang homoseksualitas menjadi sasaran persekusi pemerintah.
Baca juga: Trump Tutup Keran Bantuan Obat HIV: Apa Dampaknya buat ODHIV di Indonesia?
Keresahan perempuan queer Indonesia di AS
Bagi Nora, 34, kabar tentang ancaman terhadap kesetaraan pernikahan ini terasa seperti mimpi buruk yang kembali terulang. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk bisa terbuka kepada keluarganya tentang identitas seksualnya sebagai seorang lesbian, Nora merasa hidupnya kembali tidak aman.
“Aku tidak pernah khawatir soal ini,” ujar Nora kepada Magdalene (5/3). “Dulu aku pikir masalahku hanya dengan keluargaku sendiri. Sekarang, negara pun ikut campur dalam urusan ini.”
Saat berusia 17 tahun, Nora ketahuan berpacaran dengan perempuan. Ibunya, yang sangat religius, memanggil pendeta untuk mendoakannya agar “kembali normal.” Namun, sang pendeta justru memperlakukannya dengan lebih baik daripada ibunya sendiri, dengan tidak memberikan penilaian atau penghakiman pada dirinya.
Usai pertemuan itu, Nora sadar bahwa menjadi lesbian bukanlah kesalahan. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya, ia akhirnya berani melela kepada ibunya. Belakangan, sang ibu mulai menerima identitas seksual Nora. “Sekarang aku bahkan bisa memperkenalkan pasanganku ke keluargaku,” ujarnya.
Tapi kabar tentang upaya mencabut kesetaraan pernikahan kembali membuatnya khawatir. “Aku tidak pernah berpikir aku akan menikah. Tapi aku ingin opsi itu tetap ada untuk orang-orang di komunitasku. Karena tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang dari gender yang sama,” katanya.
Baca juga: Dapat Banyak Nominasi Oscars, Kenapa Emilia Pérez Dianggap Kontroversial?
Politik yang berbeda di setiap negara bagian
Kebijakan Trump menyoroti ketimpangan politik yang nyata di AS. Politik AS dijalankan dengan sistem dua partai, yakni Demokrat yang cenderung liberal dan Republik yang lebih konservatif. Hal ini membuat kebijakan terkait isu gender dan seksualitas sangat bergantung pada partai yang berkuasa di masing-masing negara bagian.
Asri, yang tinggal di California—negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat—masih bisa mempertahankan gender marker “X” di dokumen pribadinya. “Di California, aku masih bisa mendapatkan SIM atau KTP dengan gender marker yang sesuai dengan identitasku,” ujarnya.
Tapi situasinya berbeda di negara bagian yang dikuasai Partai Republik, di mana layanan kesehatan untuk transisi bahkan tidak tersedia. “Untuk transisi, kamu harus pergi ke negara bagian ‘berwarna biru’, dan itu tidak murah. Asuransi di negara bagian konservatif biasanya tidak menanggung biaya perawatan di luar wilayah,” ujar Asri.
Nora, yang tinggal di negara bagian konservatif, merasa langsung merasakan dampaknya. “Aku tinggal di area yang cenderung liberal, tapi hanya 15 menit dari sini, aku merasa tidak aman untuk berpakaian maskulin karena takut dihakimi atau diserang,” katanya.
Perempuan queer Indonesia di AS bertahan di tengah ancaman
Asri dan Nora sadar bahwa empat tahun ke depan akan menjadi periode yang sulit. “Trump akan terus memperkaya sekutunya dan menekan kelompok-kelompok marginal seperti trans, perempuan, imigran, dan komunitas kulit berwarna,” ujar Asri.
Untuk bertahan, Asri berencana tetap tinggal di California dan memperkuat jaringan komunitasnya. “Aku tidak akan keluar dari California karena risiko terlalu besar, terutama untuk seseorang dengan status imigran sepertiku,” ujarnya.
Nora juga berencana memperkuat dukungan komunitas. “Aku akan terus menjadi relawan dan membangun komunitas yang bisa saling mendukung. Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian,” ujarnya.






















