#MadgeKaleidoskop: Dari ‘Koloni’ hingga ‘Paya Nie’, 5 Buku yang Sayang Dilewatkan

Dalam satu tahun terakhir, rak buku #MadgeReview bertransformasi jadi ruang temu beragam narasi krusial yang mengeksplorasi makna kemanusiaan di tengah situasi yang sering kali dipaksa senyap. Melalui metafora binatang dalam fabel yang menyentil ketimpangan sosial, hingga kumpulan cerpen yang menggali trauma mendalam Tragedi 65, literasi hadir sebagai upaya merawat empati.
Hal ini pun terpancar dari suara perempuan di tengah kecamuk konflik Aceh serta perjuangan atas hak reproduksi, yang sekaligus menegaskan bahwa literasi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap pengabaian isu-isu marginal dalam percakapan arus utama.
Dari sekian banyak judul dan diskursus yang terbit tahun ini, tentu tidak semua bisa terangkum dalam ulasan kami. Namun, sorotan terhadap karya-karya dalam daftar ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan narasi penting lainnya yang luput dari amatan.
Pilihan buku yang hadir di bawah ini adalah upaya kami untuk merangkum ingatan sepanjang 2025, sekaligus menjadi pengingat atas isu-isu yang harus tetap dibincangkan dan terus diperjuangkan pada 2026 mendatang.
Baca juga: 5 Buku Okky Madasari untuk Tingkatkan Kemampuan Berpikir Kritis
Koloni karya Ratih Kumala

Dalam novel Koloni, Ratih Kumala menggunakan fabel dunia semut sebagai metafora tajam untuk mengkritik struktur patriarki dan realitas sosial-politik modern. Melalui karakter ratu semut muda bernama Darojak, pembaca diajak menyelami perjuangan perempuan dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensi di tengah dominasi yang timpang. Novel ini tidak hanya berbicara tentang pembagian kasta dan kerja, tetapi juga memotret seksualitas dan kontrol tubuh sebagai instrumen kekuasaan yang jujur dan berani.
Lebih dari sekadar kisah serangga, Koloni menjadi cermin retak bagi kondisi kepemimpinan dan situasi politik di Indonesia. Dengan gaya narasi yang menggigit namun mudah dinikmati, Ratih menyisipkan sindiran terhadap penguasa yang haus kekuasaan dan enggan lengser, serta dampak pembangunan yang merusak ruang hidup. Secara keseluruhan, buku ini menjadi pengingat bahwa di balik tatanan sebuah koloni, selalu ada pergulatan antara ambisi pribadi, naluri bertahan hidup, dan upaya tak henti untuk merawat kemanusiaan.
Rumah Dukkha karya Dhianita Kusuma
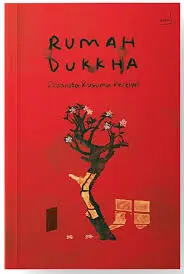
Rumah Dukkha karya Dhianita Kusuma Pertiwi membuka kembali luka lama sejarah Indonesia melalui 20 cerita pendek yang berfokus pada pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966. Dhianita meminjam suara para korban, penyintas, dan pelaku untuk membongkar propaganda negara yang selama ini melabeli anggota PKI dan organisasi sayapnya, seperti Gerwani, sebagai sosok yang tidak manusiawi.
Melalui narasi yang personal, Dhianita berupaya menyoroti bagaimana seksualitas dijadikan alat penundukan dan bagaimana trauma tersebut tidak hanya berhenti pada individu, tetapi mengalir menjadi trauma generasional bagi anak-cucu mereka.
Dhianita juga dengan berani mengeksplorasi kengerian penyiksaan di penjara hingga rasa bangga para penjagal yang terdoktrin, memberikan gambaran utuh tentang betapa hancurnya tatanan sosial akibat stigma yang dipelihara. Sebab itu, Rumah Dukkha bukan sekadar karya fiksi, melainkan ruang refleksi krusial untuk menuntut hak atas kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi yang hingga kini masih diperjuangkan oleh para penyintas.
Baca juga: Lima Rekomendasi Buku yang Wajib Kamu Baca soal Tragedi 1998
Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu karya Sasti Gotama
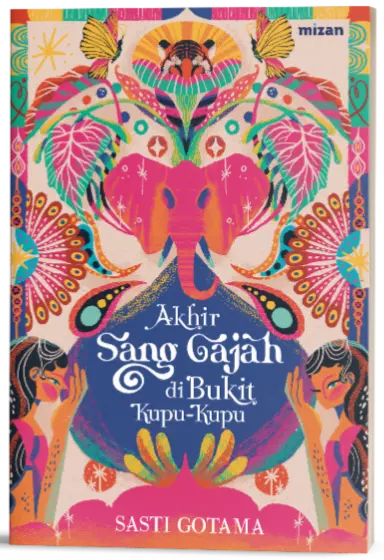
Pemenang penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa kategori kumpulan cerpen ini, Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu karya Sasti Gotama menyajikan narasi eksperimental yang mengeksplorasi isu-isu marginal mulai dari pergundikan di era kolonial, otonomi dan kekerasan pada tubuh perempuan, hingga diskriminasi terhadap perempuan aseksual yang terjebak dalam kebijakan pronatalis.
Salah satu cerita pendeknya yang dapat banyak pujian berjudul Saksi Glori, Sasti menggunakan metafora unik, seperti kesaksian organ tubuh. Ia memberikan suara pada medulla oblongata hingga akar rambut untuk menyuarakan pengalaman korban pelecehan seksual dan pemerkosaan yang sering kali dibungkam oleh masyarakat.
Selain itu, Sasti juga menggali ingatan kolektif tentang Tragedi 1965 melalui kisah-kisah yang menyentuh nurani. Sasti menghadirkan potret kengerian pembantaian di pinggiran Sungai Brantas sebagai pengingat akan sejarah kelam yang coba dikubur oleh penguasa.
Concerning My Daughter karya Kim Hye-jin
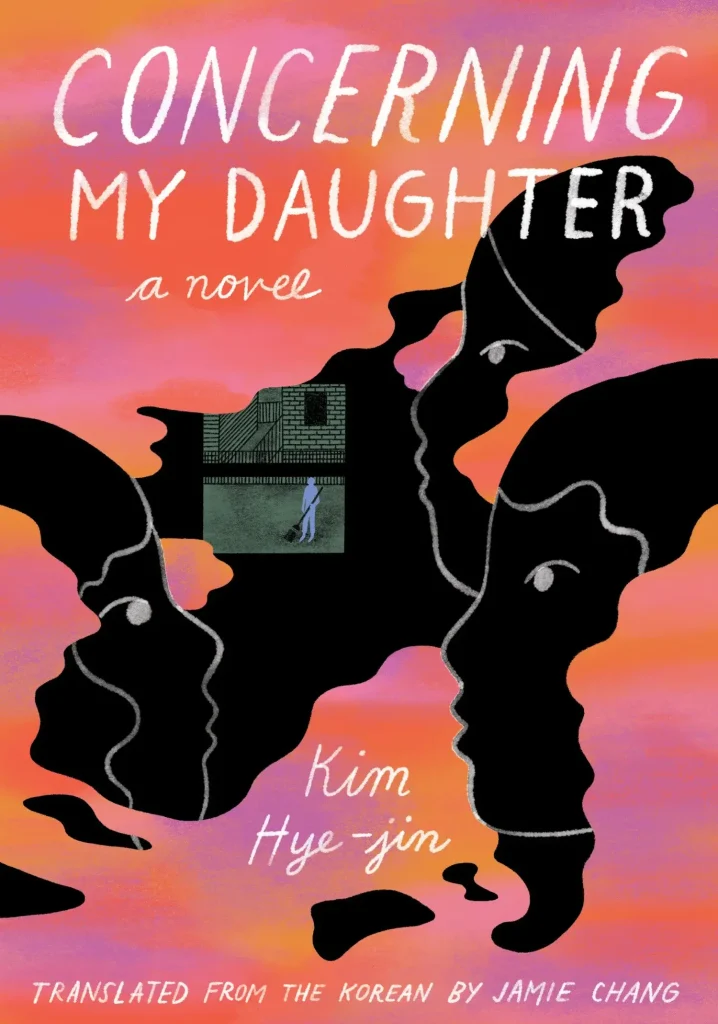
Novel Concerning My Daughter karya Kim Hye-jin menyajikan potret getir kehidupan lesbian di Asia melalui perspektif seorang ibu. Pembaca diajak menyelami konflik batin seorang ibu yang kasih sayangnya berkelindan dengan prasangka sistem patriarki dan norma heteroseksual yang kaku. Melalui kepulangan sang anak ke rumah bersama pasangan perempuannya, novel ini membongkar bagaimana cinta keluarga sering kali menjadi alat kontrol yang menyesakkan, di mana keberadaan perempuan dianggap hanya sah jika melalui institusi pernikahan dan keturunan.
Bagi komunitas queer, kisah ini terasa sangat nyata dan personal karena menyoroti ketakutan akan kesendirian di masa tua serta sulitnya mendapatkan pengakuan di ruang paling privat, yaitu rumah. Kontras antara pekerjaan sang ibu di rumah jompo dengan penolakannya terhadap pilihan hidup anaknya sendiri memberikan kritik tajam atas nilai-nilai kemanusiaan yang sering kali tumpang tindih dengan stigma.
Baca juga: Apa yang Sebenarnya Terjadi di 1965: 5 Buku Panduanmu
Paya Nie karya Ida Fitri

Novel Paya Nie karya Ida Fitri merupakan catatan tajam yang mengangkat suara perempuan-perempuan Aceh di tengah konflik bersenjata antara militer dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berlatar di sebuah desa yang dikelilingi rawa, kisah ini mengikuti empat perempuan yang bertahan hidup dengan menganyam rumput rawa sambil memendam trauma akan pelecehan, kehilangan, dan kematian yang ditorehkan selama masa konflik.
Melalui karakter-karakternya, Ida membongkar bagaimana perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata. Perempuan terpaksa memikul beban ganda atau berlapis ketika laki-laki dalam keluarga mereka baik ayah, suami, maupun anak hilang atau tewas akibat konflik. Mereka juga rentan mengalami kekerasan domestik karena ruang hidup mereka yang semakin menyempit. Tidak kalah penting, tubuh mereka seringkali dijadikan alat politik dan simbol kehormatan yang dirusak untuk menghancurkan moral komunitas.






















