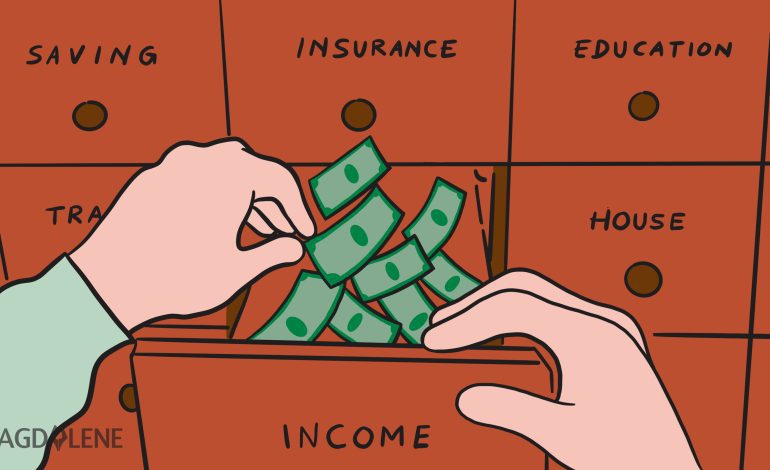Mari Ngobrol Serius tentang BL Asia: Sebuah ‘Queer Gaze’

Pandemi menjebloskan saya ke dunia Boys’ Love, tepatnya saat bulan-bulan pertama work from home. Waktu itu, 2Gether: the Series jadi buah bibir di media sosial saban pekan, selama kurang lebih tiga bulan penayangannya. Saya pun larut dalam percakapan tersebut.
2Gether bercerita tentang Tine (Win Metawin) yang minta tolong Sarawat (Bright Vachirawit) jadi pacar pura-puranya. Sepanjang 13 episode, kita akan disuguhkan narasi Tine yang perlahan-lahan jatuh hati betulan pada Sarawat, yang–plot twist-nya–ternyata sudah naksir Tine sejak lama.
Cheesy. Super soapy.
Saya bukan penggemar romcom, dan kaget sendiri ketika kisah cinta ultradrama khas remaja ini berubah jadi eskapisme menggembirakan, dari perasaan suntuk terkurung di rumah. Berawal sebagai penonton iseng, lama-lama saya jadi penggemar Sarawat-Tine. Makin lama, malah terjun bebas jadi penggemar BrightWin, nama pasangan dua aktor yang memerankan mereka. Terlebih, setelah keduanya ikut bersuara mendesak pembebasan aktivis LGBTQ James Panumas Singform dan Tattep Ruangprapaikitseree, yang ditangkap saat demo prodemokrasi di Thailand, 2020 lalu.
Baca juga: 6 Film Gay Thailand Rekomendasi 2021
Namun, yang lebih seru adalah perjalanan berkenalan dengan genre ini dan proses memaknainya.
Membela dan Membenci BL, Serta Zona Abu-abu di Antaranya
Sebelum terpapar 2Gether, saya sudah pernah mencoba-coba nonton beberapa BL pendahulunya. Macam TharnType (2019), Waterboyy: the Series (2017), atau yang lebih lama, Make It Right (2016). Kendati senang karena genre ini mengangkat percintaan queer jadi plot utama, waktu itu saya memutuskan kalau BL bukan buat saya. Bukan karena plotnya yang receh atau dialognya yang cringey, tapi karena ketiga serial di atas punya kesamaan problematik: Adegan seks tanpa consent yang diromantisasi.
Rumus umum yang ada di serial-serial BL adalah dua protagonis laki-laki dengan karakter bertolak belakang, lalu jatuh cinta. Biasanya, yang satu lebih aktif, dominan, dan agresif (maskulin), yang lainnya pasif, submisif, dan cenderung menerima (feminin). Adegan seks atau ciuman tanpa consent sering kali dipakai jadi jembatan yang mendekatkan dua karakter ini.
Dalam tiga contoh serial di atas, adegan perkosaan itu jelas sekali. Type (TharnType), Apo (Waterboyy), dan Book (Make It Right) terang-terangan punya adegan menolak dan berkata tidak/ jangan berkali-kali, saat love interest mereka mencoba melakukan intercourse pertama. Seks tanpa consent ini justru dipotret sebagai ekspresi sayang dari karakter dominan, yang meski ditolak si pasif, tapi justru membuka jalan buat keduanya menjalin komitmen lebih serius.
Narasi ini jelas bermasalah dan berbahaya. Stigma dan stereotip mesum pada orang-orang homoseksual di kehidupan nyata sudah berumur panjang, bahkan dilanggengkan dalam media dan pembingkaian homofobik mereka. Namun, kata Akiko Mizoguchi, aktivis queer dan penulis Theory of BL Evolutions, formula ini umum hadir dalam karya-karya BL.
“Rape as an expression of love” dan pembagian peran dominan-submisif, kata Akiko, adalah narasi yang direfleksikan dari hubungan romantis heteroseksual yang konvensional dan problematik. Maksudnya, pembagian peran antara pasangan homoseksual di BL sering kali hanya proyeksi atau refleksi dari hubungan heteroseksual yang dijadikan referensi penulisnya, yang mayoritas adalah perempuan straight.
Baca juga: Fetish terhadap Hubungan Gay: Ketika Ship dan Fanfiction Jadi Toksik
Ditilik dari sejarahnya, hal ini masuk akal. BL yang muncul di Jepang pada 1970-an adalah bentuk dari perlawanan (sekaligus pelarian) komikus-komikus perempuan yang mengklaim balik manga Shojo, genre kisah cinta heteroseksual yang populer di kalangan pembaca perempuan muda. Mereka lalu menciptakan Shoonenai, manga yang bercerita tentang kisah cinta dua protagonis laki-laki–cikal bakal BL.
Karakter-karakter BL ini, menurut Fujimoto Yukari, profesor Teori Budaya Manga di Universitas Meiji, sering kali adalah representasi gambaran diri ideal perempuan-perempuan yang merasa ditekan konstruksi gender di masyarakat. Adinda Zakiah dalam Boys Love di Mata Penonton Perempuan (2021) mengungkap, “Dengan menonton BL, penonton perempuan dapat membayangkan bagaimana rasanya berada dalam hubungan ‘lain’, untuk lari sejenak dari identitas yang tetap (fixed) serta realitas saban hari.”
Masalahnya, BL yang dibuat dengan straight woman gaze atau perspektif perempuan heteroseksual memang jauh dari realitas hubungan queer asli di dunia nyata. Atau mungkin, lebih tepatnya, tidak merepresentasikan gambaran atau realitas percintaan pasangan homoseksual, yang lebih cair dan penuh struggle dari narasi serba romantis dalam dunia BL. Pembagian peran aktif-pasif, promosi gagasan monogami, dan standar kecantikan yang tinggi, putih, mulus, mancung, khas protagonis BL adalah contoh-contoh potret keliru tersebut.
BL memang sering kali lebih fokus memprioritaskan emosi para karakternya, dibanding menyelipkan narasi melawan norma atau mengadvokasi hak-hak LGBTQ (seperti yang dilakukan kebanyakan film-film gay khas Hollywood dan Barat). Kebanyakan BL, terutama dari Thailand dan China, bahkan cenderung mengabaikan stigma atau stereotip yang umum lengket pada laki-laki hemoseksual.
Misalnya, dalam 2Gether, Sarawat dan Tine tak pernah sekali pun dapat teriakan, cacian, atau makian homofobik setelah mereka mengumumkan berpacaran. Mereka malah dapat dukungan besar dari para kawan-kawan terdekatnya dan fans Sarawat di kampus–sebuah situasi yang tak mungkin dirasakan pasangan homoseksual di dunia nyata.
Bahkan, dalam Waterboyy: the Series, akar kemarahan karakter Waii (Earth Pirapat) pada ayahnya yang berpacaran dengan pemuda lebih muda bukan karena ia memelihara sikap homofobik. Ia lebih marah pada ayahnya karena punya hubungan romantis baru, seperti anak yang tak ingin punya orang tua tiri.
Plot-plot yang mengabaikan realitas orang LGBTQ yang masih diopresi di dunia nyata, sebetulnya di titik tertentu cukup memberdayakan. Sebab, serial-serial ini menjadi contoh atau alat kita, penonton, untuk mengimajinasikan dunia baru tanpa sikap homofobik, queerfobik, alias dunia yang belum pernah kita tinggali.
Beda BL Asia dan Film Gay Soal Advokasi
Perbedaan lain BL Asia dengan film-film gay umumnya, adalah unsur advokasinya. Beberapa judul BL memang sengaja memasukan beberapa isu penting macam narasi coming out dan coming in, atau penerimaan dari orang tua dan keluarga, tapi itu bukan tujuannya. Tak pernah.
Patrick W. Galbraith, penulis The Moe Manifesto dan profesor kajian budaya di Universitas Senshu, menyebut naskah-naskah BL dibuat untuk memuaskan fantasi perempuan straight sebagai target pasar utamanya. Bukan keinginan untuk meruntuhkan patriarki, misalnya. Hal ini adalah pengetahuan awam para penggemarnya.
Baca juga: 5 Serial Boys Love yang Bikin Pipi Merona Merah
Kehadiran BL memang lebih disetir roda kapital, terutama beberapa tahun belakangan. Setelah populer di Jepang, BL ternyata makin tenar di negara serumpun Asia lainnya, terutama kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada 2020 saja, 2Gether cuma satu dari sekitar 270-an judul BL yang tayang tahun itu, angka terbanyak produksi BL sepanjang sejarah manusia.
Jumlah produksi yang membludak ini bisa dipandang baik, sebagaimana yang disampaikan para aktivis dan scholar yang mendukung pembebasan hak-hak LGBTQ. Misalnya Fujimoto, yang bilang karya-karya BL membantu mendobrak norma-norma sosial, dalam interviewnya dengan Nippon. “Mereka mengguncang norma sosial, kearifan konvensional, dan stereotip dengan memebrikan penggambaran sensitif tentang hubungan manusia yang beragam,” katanya.
Namun, saya lebih sepakat dengan Ágnes Zsila dan Zsolt Demetrovics dalam The Boys’ Love Phenomenon: A Literature Review. Mereka bilang, potret hubungan romantis dua laki-laki yang makin sering tampil di layar kaca, ponsel, ataupun laptop memang patut dirayakan, tapi perlu diingat bahwa hal itu tak menjamin sikap pro-gay juga akan membaik di media.
Di sini, otokritik dalam kalangan fandom sendiri jadi penting. Narasi-narasi BL yang masih serupa–biasanya latar yang di situ-situ saja (kebanyakan sekolah), peran gender seme-uke, dan adegan intim yang abai consent–harus terus dibenahi. Dua tahun terakhir, peran otokritik itu tampak berjalan baik. Tema-tema sekolah memang masih mendominasi, tapi kisah cinta karakter dengan profesi lain mulai ramai diproduksi. Bahkan, GMMTV, produser BL raksasa di Thailand, menyajikan Not Me, sebuah BL yang bicara tentang anarkisme, tahun ini. Produksinya digarap serius dengan menunjuk Anucha Boonyawatana, sutradara transgender dan aktivis LGBTQ yang dikenal dengan karya-karya arthouse-nya, macam Malila (2017), The Blue Hour (2015), dan Down the River (2004).
Keragaman narasi begini yang perlu terus didorong terus, agar kita sebagai penonton tak terjebak dalam jualan representasi yang dielu-elukan pemegang kapital. Ingat, representasi di layar kaca saja tak cukup untuk meruntuhkan monster sebenarnya: Represi patriarki.