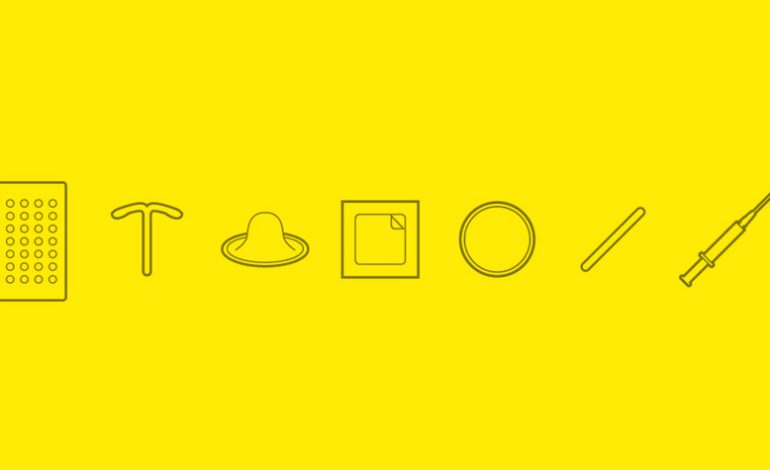Label Pelakor Arawinda: Tak Adil Gender, tapi Kok Langgeng di Medsos?

Hari-hari ini kita diributkan dengan kasus dugaan perselingkuhan yang diduga menyeret artis peran Arawinda. Masalahnya, seperti kasus serupa yang sudah-sudah, cuma orang ketiga saja yang namanya viral di internet. Tak cuma menerima body shaming, cancel culture, pemeran Yuni itu juga diedit profilnya di Wikipedia dengan tambahan label “pelakor”. Sementara, lelaki yang mengkhianati pernikahan monogami dengan istrinya, lolos dari bulan-bulanan media dan media sosial.
Dalam kosakata tentang hubungan intim antara lelaki perempuan, ada istilah “pelakor”, yang mungkin belum masuk secara resmi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tapi saya perhatikan sudah menjadi pemahaman umum. Sepertinya ini sebuah istilah yang muncul dari dunia hiburan atau infotainment berkaitan dengan dunia keartisan atau kalangan selebritas.
Pelakor adalah singkatan dari “perebut lelaki/suami orang”, sebuah istilah yang cukup kasar dan penuh stigma. Dalam hubungan yang biner suami istri, istilah itu merujuk kepada perempuan lajang (bisa belum menikah, bersuami, atau tidak lagi menikah) yang distigma secara sosial sebagai perempuan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain dengan cara yang tidak terhormat.
Jelas, stigma serupa itu harus dipersoalkan. Sebab bagi saya, istilah pelakor ini menggambarkan kentalnya ketidakadilan gender dalam masyarakat. Dalam rangka studi gender dan kriminalitas, saya saat ini sedang mendalami isu ini.
Istilah pelakor tampaknya telah mendegradasi perempuan menjadi makhluk yang semata-mata mengandalkan seksualitasnya untuk mencapai tujuan hidup dengan cara-cara yang rendah. Istilah ini menggambarkan opini masyarakat bahwa dalam kasus perselingkuhan, perempuan adalah pihak yang bersalah dan karenanya mendapat cap “pelakor”. Sementara itu laki-laki yang masuk dalam hubungan itu sering kali dipermaklumkan sebagai pihak yang sah-sah saja melakukannya, atau paling jauh dianggap sedang terperosok ke dalam godaan perempuan.
Kita perlu benar-benar mempelajari apa yang memotivasi perempuan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah berpasangan. Terlebih, untuk mempertanyakan mengapa lelaki beristri atau bahkan beranak mengambil risiko sebegitu besar dengan mempertaruhkan rumah tangganya dan masa depan anak-anaknya.
Baca juga: Perempuan Simpanan: Korban Atau Tak Bermoral?
Pelakor Lebih Jahat dari Pekerja Seks?
Nyatanya, istilah pelakor juga menyederhanakan fakta hubungan-hubungan sosial yang rumit ke dalam generalisasi yang menyamakan mereka dengan pekerja seks. Stigma lain adalah, caranya yang dianggap jauh dari sikap sportif bahkan jika dibandingkan dengan pekerja seks yang jelas-jelas menjual jasa layanan seksual. Karenanya, mereka sering dianggap lebih “jahat” dari pekerja seks.
Ini karena cara yang dilakukan dianggap curang tanpa harus melanggar aturan agama, manakala hubungan curi-curi itu dilakukan secara agama melalui praktik nikah siri. Hal ini membuat masyarakat, khususnya sesama perempuan, geram kepada perempuan lain yang dianggap sebagai penggunting dalam lipatan hubungan suami istri orang lain.
Stigma terhadap pelakor adalah bagaimana caranya yang dianggap jauh dari sikap sportif, bahkan jika dibandingkan dengan pekerja seks, sehingga mereka sering dianggap lebih “jahat” dari pekerja seks.
Banyak aspek yang dapat dilakukan untuk studi tentang perempuan yang mengambil jalan menjadi pelakor dan laki-laki yang masuk ke dalam hubungan itu. Dalam studi kriminologi yang sedang saya dalami, terdapat kaitan erat antara budaya patriarki dengan prostitusi, seperti yang ditulis oleh Anuja Agrawal, seorang profesor sosiologi, dalam bukunya Chaste Wives and Prostitute Sisters: Patriarchy and Prostitution among the Bedias of India (2008).
Hasrat melakukan hubungan ekstramarital sering kali tak semata-mata karena kebutuhan untuk “jajan”, melainkan untuk mengeksplorasi maskulinitas lelaki yang merasa membutuhkan pemuja, sanjungan, atau hal-hal sejenis yang hanya dapat dilakukan dalam hubungan-hubungan ekstra dan non-formal di luar perkawinannya.
Baca juga: Gundik yang Hidup Lagi
Hubungan ekstramarital dalam format perselingkuhan jelas berbeda dengan hubungan sepintas lalu seperti dalam dunia prostitusi. Apalagi jika mulai muncul kebutuhan untuk adanya ikatan yang lebih formal, minimal secara agama melalui perkawinan siri itu. Praktik hubungan non-formal dalam hubungan gelap namun sah secara agama ini dianggap lebih menenangkan dibandingkan menjadi pekerja seks, namun dinilai lebih jahat dan culas. Namun penilaian negatif senantiasa ditujukan kepada pihak pelakor dan bukan pasangannya.
Dilihat dari aspek gendernya, jenis hubungan serupa itu sepertinya dibutuhkan oleh lelaki yang juga membutuhkan rasa aman terkait nama baik, status dan stabilitasnya. Jadi tak semata untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dari dosa melainkan yang lebih penting adalah rasa aman dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjatuhkan status sosialnya. Padahal perselingkuhannya sendiri jelas sebuah perbuatan yang menggali lubang dosa sosial yang lain kepada pasangan sah dan anak-anak serta masa depan lembaga perkawinannya.
Aspek lain yang bisa dikaji adalah risiko yang harus ditanggung oleh perempuan pelakor. Status perkawinan “gelapnya” sangat berisiko pada aspek hukumnya. Jikapun masuk ke dalam perkawinan siri, statusnya secara hukum jelas tidak setara dengan perempuan yang dinikahi secara formal. Padanya tak ada hak yang diakui sebagai istri ketika terjadi perceraian atau sengketa hukum keluarga. Demikian juga risiko yang ditanggung oleh anak-anaknya jika kebetulan sang pelakor itu kemudian memiliki anak.
Pelakor adalah sebuah dunia yang penuh risiko untuk dijalani perempuan kecuali perempuan yang memiliki “agenda setting” untuk masuk ke dalam perkawinan dengan cara-cara yang penuh risiko serupa itu. Tapi ini lagi-lagi sebuah prasangka yang lagi-lagi sangat bias gender dengan menyederhanakan persoalan.
Ilustrasi oleh Karina Tungari