‘Perempuan Selalu Benar’ Sebuah Generalisasi Seksis
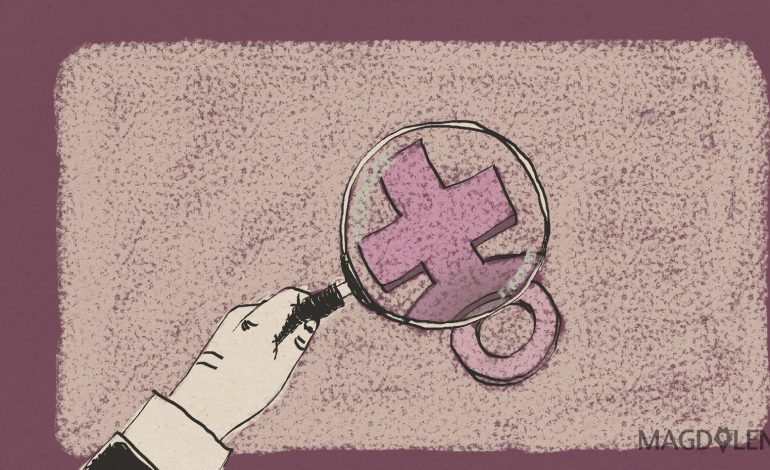
Iya, deh…iya, kamu benar. Kan perempuan selalu benar.
Pernah dengar teman, keluarga, atau pasangan ngomong begini? Atau justru sering? Ketika ada adu argumentasi dengan seseorang, ungkapan macam ini menjadi salah satu hal yang (di)lumrah(kan) dilontarkan laki-laki saat malas atau tidak bisa menjawab pernyataan terakhir perempuan lawan bicaranya.
Tentu saja ungkapan ini tidak bermakna denotatif belaka. Tersirat sarkasme yang menekankan pada gender seseorang di sana, yang lazimnya dikatakan saat sang laki-laki sebenarnya tidak sepakat dengan si perempuan, tetapi bertingkah seakan perempuan tersebut maha betul.
Ungkapan tadi jauh dari bentuk sanjungan. Sebaliknya, ia adalah suatu serangan yang sepatutnya dilawan dalam keseharian. Saya memandang ungkapan ini sepadan dengan ungkapan “laki-laki enggak boleh nangis atau cengeng” atau “waria itu galak-galak” yang poinnya menekankan pada generalisasi menyesatkan nan seksis bin misoginis.
Baca juga: Stop Jadikan Humor Seksis Wajar
Menyesatkan karena pada faktanya, manusia berjenis kelamin dan gender apa pun pastinya pernah dan bisa kembali melakukan kesalahan. Menyesatkan karena ketika perempuan melakukan kesalahan dan laki-laki berujar ia selalu benar, mereka hanya ingin menertawakan perempuan sebagai badut yang melakukan kebodohan lebih lanjut, seolah-olah “perempuan selalu benar” menjadi tepuk tangannya. Menyesatkan karena penempatan perempuan di posisi superior “selalu benar” berkontradiksi dengan kondisi di lapangan, ketika perempuan sering disalahkan atas pemikiran atau tindakannya.
Baru-baru ini, saya mendapati contoh kasus perempuan disalahkan dari salah satu grup yang fokus pada kesehatan mental ibu yang saya ikuti di Facebook. Dalam sebuah unggahan, “Ibu Dahlia” (28) bercerita bahwa dirinya sudah sebulan mengandung anak kelima setelah empat kali melahirkan dengan operasi caesar. Anaknya yang paling kecil masih berumur 18 bulan dan hanya mau mengonsumsi ASI.
Dokter yang menanganinya sudah angkat tangan dan menyarankan dia melakukan sterilisasi karena risiko melahirkan lagi besar sekali. Malangnya, tidak ada satu pun keluarganya yang setuju dan mau menandatangani pilihan tindakan sterilisasi itu.
Kondisi kian pelik karena sekarang masih dalam masa pandemi dan Ibu Dahlia takut memeriksakan dirinya ke dokter. Keinginan untuk bercerita ke keluarganya pun hanya bisa ia pendam lantaran malu dan tidak mau merepotkan orang tua karena mereka sudah sibuk mengurusi nenek Ibu Dahlia yang sudah pikun. Sementara, sang suami tampak tidak begitu peduli dengan situasi peliknya, yang juga harus bekerja mencari nafkah dan kelelahan luar biasa. Beban Ibu Dahlia kian berat karena sang suami pernah membentaknya jika mendapati ia menangis, dan anak-anaknya kerap berulah karena merasa diabaikan.
Ratusan komentar mengekori cerita Ibu Dahlia ini. Banyak yang merasa kasihan dan menyemangati, tetapi saya juga menemukan komentar-komentar yang bisa membuat Ibu Dahlia makin merasa bersalah saat dia menanyakan apa hukumnya menggugurkan kandungan dalam situasi tersebut.
“Tidak boleh, itu adalah anugerah Allah buat Bunda. Apa setelah lahiran Bunda enggak KB?”
“Dosa, Mbak, jangan.”
“Pasrah dan serahkan semua pada Allah. Baiknya setelah ini ber-KB, insyaAllah ada jalan terbaik buat Bunda.”
Perempuan selalu salah
Terkait penggunaan alat kontrasepsi oleh Ibu Dahlia, saya masih menangkap isyarat menyalahkan perempuan. Perempuan sering kali dibebani dengan tanggung jawab untuk memakai alat kontrasepsi, entah suntik, pil, IUD, atau sterilisasi. Padahal, urusan sanggama dan prokreasi itu urusan kedua gender. Perempuan sering kali diwajarkan menerima segala risiko atau efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, sementara laki-laki yang sebenarnya juga bisa berpartisipasi menggunakan kondom atau melakukan vasektomi “lebih imun” dari sasaran pertanyaan bernada penyalahan macam tadi.
Itu isu tentang risiko kematian ibu. Perempuan sering dianggap salah juga dalam kasus-kasus lain seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Sampai sekarang, masih ada toh yang bilang “Kamu pakai baju mini-mini, sih” atau “Salah sendiri buka aurat” waktu perempuan bercerita dirinya dilecehkan laki-laki.
Penempatan perempuan di posisi superior “selalu benar” berkontradiksi dengan kondisi di lapangan, ketika perempuan sering disalahkan atas pemikiran atau tindakannya.
Atau soal keharmonisan rumah tangga. Isyarat penyalahan perempuan bisa kita temukan dalam program-program “sekolah istri” atau “sekolah ibu”, serta pernyataan-pernyataan pejabat publik. Dalam Kompas (5/10/2020) misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa program pendidikan pranikah bagi calon pengantin diutamakan kepada perempuan. Alasannya? Perempuanlah yang akan jadi ibu rumah tangga, mengandung dan melahirkan, dan diharapkan menghasilkan generasi unggul yang terhindar dari stunting.
Padahal tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan menghasilkan generasi unggul itu tanggung jawab suami dan istri. Tapi ketika ada sesuatu tidak beres dalam rumah tangga, hanya perempuanlah yang disalahkan.
Baca juga: Perempuan dan Beban Tanggung Jawab Ketahanan Hubungan
Pemikiran bahwa tugas domestik ranahnya perempuan saja adalah pemikiran seksis yang usang, yang justru berpotensi mendatangkan konflik rumah tangga. Karena ketika perempuan dibebani secara eksklusif tugas-tugas domestik, tanpa ada kepekaan dan keterlibatan suaminya, ia akan lebih mudah “meledak” karena keletihan fisik dan psikis. Ketika ada satu pihak yang tidak sejahtera dalam rumah tangga, bagaimana caranya mendukung keharmonisannya?
Penyalahan perempuan atas gagalnya rumah tangga juga bisa terlihat dari anggapan bahwa perempuan mandiri secara ekonomi berkontribusi terhadap kenaikan angka perceraian. Anggapan ini konyol karena keberdayaan perempuan sejatinya justru mendukung kestabilan rumah tangga, dalam hal ini aspek finansial. Sama konyol dan menyalahkannya dengan lirik lagu lawas dari Rhoma Irama, “Emansipasi Wanita”, yang mengatakan “karena kaum wanita memenuhi kantoran, akhirnya banyak pria menjadi pengangguran”.
Satu lagi, aplikasi peran gender normatif dan penyalahan perempuan saya temukan juga dalam drama Korea Reply 1988 yang baru saya tonton. Memang adegan ini terlihat jenaka, tetapi perempuan juga dianggap salah ketika menyatakan perasaannya.
Joey, teman Deok-Sun si pemeran utama, baru saja menyatakan cinta dan ditolak pada kencan butanya. Lantas, Maggie, teman Deok-Sun yang lain menyalahkannya karena perempuan jelek seperti mereka tidak seharusnya menyatakan cinta duluan. Saya tertawa menonton adegan ini, sekaligus merasa getir karena merefleksikan ketimpangan dalam realitas. Masih jamak tabu dalam pergaulan soal perempuan menyatakan perasaan lebih dulu, ditambah lagi standar kecantikan arus utama yang begitu beracun membuat seseorang yang “terlahir jelek” sering dianggap salah dalam bertindak.
Padahal, apa yang salah sih dari menjadi perempuan dan ekspresif soal perasaan? Memang dengan memendam perasaan sampai si laki-laki menembak duluan bakal bikin relasi lebih awet nantinya kalau jadi? Bakal bikin kedua orang itu jauh lebih bahagia dibanding kalau si perempuan menembak duluan? Kan soal itu wallahualam.
Cerita-cerita yang cuma secuil dari banyaknya pengalaman perempuan disalahkan di masyarakat ini sebenarnya sejalan dengan makna konotatif “perempuan selalu benar” tadi. Keduanya sama-sama menyudutkan perempuan, hanya saja yang satu membungkusnya dengan peyorasi. Keduanya sama-sama mesti dipatahkan dan dianggap tidak lagi lazim untuk dilakukan dalam keseharian.






















