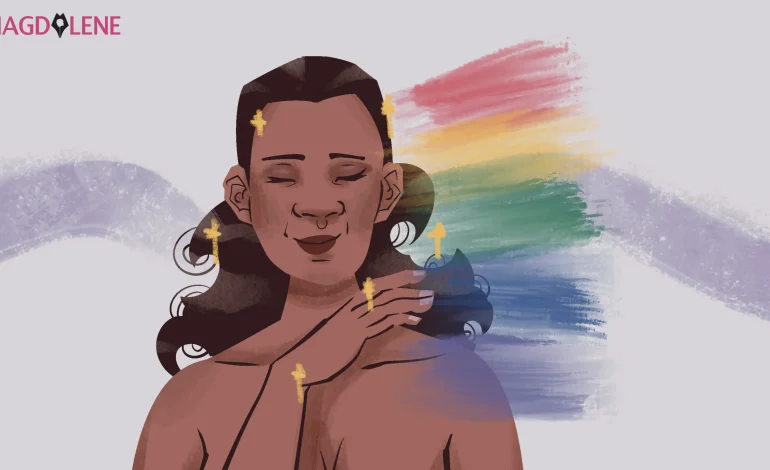‘Paya Nie’: Perempuan, Kekerasan, dan Ingatan Konflik yang Terlupakan

Peringatan: gambaran kekerasan seksual dan KDRT
Di tengah rawa yang sunyi, empat perempuan menyusuri semak demi mengumpulkan binyeut, rumput rawa yang mereka anyam menjadi tikar, demi dapur yang tetap mengepul. Tangan mereka cekatan, tubuh mereka akrab dengan tanah berlumpur. Tapi bukan hanya purun yang mereka bawa pulang dari rawa itu. Mereka juga membawa kisah tentang luka, pelecehan, kehilangan, dan rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi.
Inilah inti dari Paya Nie, novel karya Ida Fitri yang mengangkat suara perempuan-perempuan Aceh di masa konflik bersenjata. Ditulis pada 2019, novel ini bukan sekadar fiksi, tapi tumbuh dari memori personal penulis sebagai saksi hidup konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan militer Indonesia.
Dari lembah sunyi bernama Salamanga, lahirlah kisah empat perempuan—Ubiet, Mawa Aisyah, Cuda Aminah, dan Kak Limah—yang mencoba bertahan di tengah kecurigaan, militerisasi, dan ketakutan yang menyelimuti kampung mereka.
Baca Juga: ‘Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu’: Kekerasan Perempuan dan Jejak Pembantaian ’65-66
Tubuh perempuan di medan kekerasan
Di tengah rawa, sambil bekerja, mereka saling berbagi cerita. Dari canda yang menghangatkan, percakapan bergulir pada kekerasan yang mereka alami. Kak Limah membuka kisahnya sebagai korban pelecehan seksual dari Mail, suami temannya sendiri. Mulai dari diintip saat mandi hingga pelecehan terang-terangan. Mail juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Khadijah.
Kekerasan ini didiamkan karena Khadijah ingat pesan ibunya: surga istri ada pada kebahagiaan suaminya. Kalimat yang mencerminkan bagaimana tafsir patriarki dan nilai-nilai agama bisa membungkam perlawanan terhadap kekerasan.
“Aku tak mau membuat arwah ibuku tak tenang,” ujar Khadijah.
Dalam situasi konflik, kekerasan semacam ini kian menjadi. Militerisasi ruang publik membuat perempuan terpaksa lebih banyak berada di rumah, yang justru tidak selalu aman. Para lelaki yang mengalami tekanan psikis dan kekerasan di luar, melampiaskan frustrasi mereka ke dalam rumah. Inilah yang disebut krisis maskulinitas: ketika peran lelaki sebagai pencari nafkah dan pelindung runtuh, kekerasan menjadi jalan pintas untuk menegaskan “kejantanannya”.
Lembaga kerja sama negara-negara kaya OECD dalam Development Policy Papers (2019) menyebutkan bahwa dalam konteks konflik, laki-laki kerap kehilangan rasa kontrol dan harga diri. Kekerasan terhadap pasangan dan anak menjadi mekanisme pertahanan, sekaligus pelampiasan atas ketidakberdayaan. Dalam masyarakat yang kental budaya patriarkinya, perempuan pun menjadi korban dalam relasi kuasa yang semakin timpang.
Sayangnya, pelaporan kekerasan kerap buntu. Dalam struktur sosial yang mengutamakan nama baik keluarga, kekerasan dianggap urusan domestik. Perempuan yang mencoba bersuara justru dihadapkan pada stigma, rasa malu, dan ancaman pengucilan. Seperti Khadijah, banyak perempuan lebih memilih diam daripada kehilangan dukungan komunitas.
Baca Juga: A.W. Prihandita, Pemenang Nebula Award yang Menentang AI
Pemerkosaan sebagai alat politik
Kekerasan dalam Paya Nie tak berhenti di ranah domestik. Ida juga mengangkat kekerasan yang dilakukan aparat bersenjata terhadap perempuan lokal. Mereka diperkosa, dilecehkan, bahkan dibunuh, kerap di depan publik atau tahanan lain untuk menciptakan rasa takut dan tunduk.
Menurut data Asia Justice and Rights (AJAR), lebih dari 30 persen perempuan korban konflik di Aceh mengalami kekerasan seksual, banyak di antaranya saat penyisiran desa atau razia militer. Laporan ini diperkuat oleh investigasi KontraS, yang mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan oleh aparat adalah bagian sistematis dari operasi militer di Aceh.
Penelitian Elisabeth Wood berjudul Variation in Sexual Violence during War (2006) menjelaskan bagaimana tubuh perempuan dijadikan simbol kehormatan komunitas. Dalam logika militer patriarkal, merusak tubuh perempuan berarti merusak harga diri lawan. Karena itu, pemerkosaan digunakan sebagai strategi penghancuran moral dan ikatan sosial. Bukan hanya pelecehan seksual, ini adalah kekerasan politik yang menargetkan komunitas secara kolektif.
Dalam konflik, norma sosial yang biasanya melindungi perempuan melemah. Pemerkosaan pun digunakan sebagai peragaan kekuasaan dan hyper-masculinity. Militer menunjukkan dominasinya bukan lewat senjata saja, tetapi juga melalui tubuh perempuan.
Baca Juga: Queer and Palestine: Cara Priscilla Yovia Melawan lewat Bacaan
Paya Nie bukan hanya novel, tetapi sebuah pengingat kolektif akan luka perempuan dalam konflik. Ida Fitri menyuarakan suara-suara yang lama dibungkam. Ia menolak agar kekerasan yang terjadi hanya dikenang sebagai statistik. Ia mengajak kita untuk mendengar dan memihak.
Di balik setiap kebijakan militer, selalu ada harga mahal yang dibayar oleh tubuh dan jiwa perempuan. Melalui karya ini, pembaca diajak tidak hanya untuk berempati, tetapi juga untuk menuntut pemulihan yang adil. Bahwa kekerasan harus diakui, korban harus disembuhkan, dan sejarah harus ditulis kembali dari suara mereka yang selama ini tak terdengar.