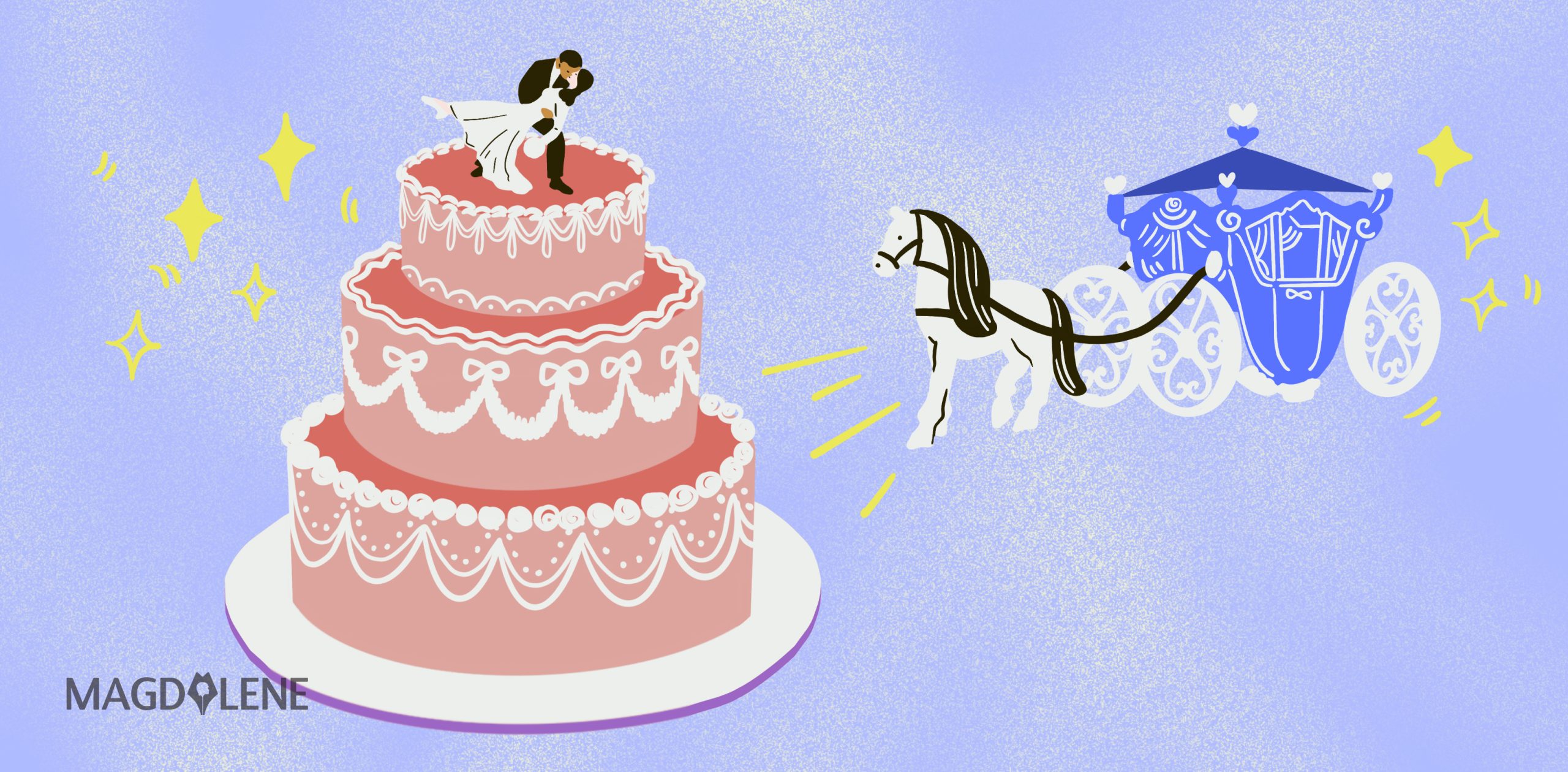Penggundulan Siswa Berjilbab di Lamongan: Pelanggaran HAM Berbalut Narasi Agama
Ada pelanggaran hak anak dalam kasus penggundulan paksa siswa SMP Lamongan. Dampaknya tak cuma trauma tapi juga dismorfia.

Sebanyak 19 siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur dibotaki paksa, (23/8). Pelaku, guru Bahasa Inggris Endang berdalih telah mengingatkan siswa untuk mengenakan ciput (dalaman hijab) berkali-kali tapi tak diindahkan. Karena itulah, Endang menggunduli paksa para korban dengan alat cukur elektrik.
Dilansir dari Tempo.co, Kepala Sekolah SMPN 1 Sukodadi Harto mengungkapkan, pihak sekolah langsung mengklarifikasi ke para wali murid di rumah. Sekolah kemudian mengadakan pertemuan dengan para wali murid keesokan harinya, (24/8).
Saat itu, Endang hadir untuk memberikan klarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh wali murid. Pertemuan yang ia klaim sebagai mediasi ini berakhir damai. Kasus selesai dan Endang pun diberi pembinaan oleh Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Tubuhku Bukan Milikku: Perkara Ruwet Dipaksa Berjilbab
Pendisiplinan Tubuh yang Picu Trauma
Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengatakan, tindakan Endang adalah pelanggaran hak anak karena telah masuk dalam bentuk kekerasan.
Secara spesifik jika mengacu pada undang-undang, Endang melanggar Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Bivitri melanjutkan, tindakan pemaksaan busana yang dilakukan Endang, juga termasuk dalam kekerasan seksual berwujud kontrol seksual. Maksudnya, tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mengancam atau memaksakan perempuan, menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik’.
“Tubuh perempuan adalah medan politik yang sekaligus merupakan alat kekuasaan suatu masyarakat. Ini terlihat jelas dari pelanggaran atas tubuh anak-anak perempuan ini. Tubuh mereka dikontrol. Ketika dirasa tidak pantas, mereka dipaksa untuk mengikuti (aturan-aturan yang ada). Mereka menangis, tidak bisa melawan. Alat cukur sudah disiapkan. Ini bentuk kekerasan seksual yang sistematis,” tutur Bivitri pada Magdalene, (31/8).
Kekerasan macam ini mestinya tak cukup diselesaikan dengan jalan damai. Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch (HRW) menuturkan, keputusan berdamai tidak menghormati hak anak atau the best interest of the child dan justru merugikan.
Anak-anak yang menjadi korban, kata dia, merasa diperlakukan sewenang-wenang lantaran dipermalukan di depan umum. Para korban diperlakukan tak adil, sehingga harus mendapatkan pelayanan psikologi bahkan psikiater karena mengalami trauma.
“Ada yang menghindari gerbang sekolah. Ada yang cenderung sembunyi di tempat tak banyak guru. Banyak yang terpaksa pindah sekolah lain. Mereka trauma. Sedihnya, ada kasus dimana si anak akhirnya home schooling,” kata Andreas pada Magdalene.
Pernyataan Andreas pun sejalan dengan temuan laporan Human Rights Watch pada 2021. Dalam laporan yang berjudul “Aku Ingin Lari Jauh” Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia”, HRW menemukan pemaksaan berbusana berdampak besar pada tekanan kejiwaan korban.
Setidaknya pada 24 dari total 34 provinsi di Tanah Air, sejumlah anak perempuan yang memilih kemerdekaan dalam berpakaian, terpaksa meninggalkan sekolah atau mengundurkan diri karena tekanan. Mereka stres karena terus-menerus dirundung, ditekan guru atau pejabat, dan dipaksa pakai jilbab.
Stres akibat pemaksaan berbusana menurut Ifa Hanifah Misbach, kepala klinik psikologi dari Rumah Sakit Melinda 2 Bandung rentan memicu “body dysmorphic disorder” (dismorfofobia). Gejala paling umum, mereka merasa ada yang salah dengan bagian tubuhnya, entah rambut, kepala, dan dada yang harus ditutupi. Mereka lantas mengalami gangguan kecemasan tinggi karena terus memikirkan penampilannya.
Ifa mengatakan, gangguan ini juga membuat para korban merasa terkucil dan kesepian secara mental karena tidak ada pihak yang mendukung mereka saat dirundung. Perempuan menjadi merasa tidak memiliki kuasa akan tubuh sendiri, kurang semangat hidup, dan kehilangan identitas, ujarnya.
“Jika tubuh kita terluka, kita dapat mendiagnosis masalah dan menyembuhkan mereka. Tetapi kesehatan mental kita terluka, bagaimana kita menanganinya? Kita tidak pernah tahu bekas luka yang kita ciptakan dengan berbagai tekanan sekolah yang intens ini,” kata Ifa dikutip langsung dari laporan HRW.
Selain menimbulkan gangguan kejiwaan pada korban, Andreas melanjutkan cara “berdamai” dalam kasus kekerasan seperti ini juga mengabaikan hak pemenuhan keadilan bagi para korban. Dalam perjalanannya meneliti kasus pemaksaan berbusana, Andreas juga menilai, cara “damai” kerap tidak bersifat genuine atau tulus.
Sering kali orang tua murid terpaksa setuju berdamai karena ada tekanan baik dari pihak sekolah, dinas pendidikan, aparat penegak hukum, maupun kelompok agama. Dalam beberapa kasus, Andreas menemukan ada usaha sekelompok orang yang ia sebut jihadis melakukan teror pada korban dan keluarga korban.
“Mereka (korban dan keluarga korban) tahu pilihan mereka enggak banyak. Mereka diancam pada jihadis. Ada yang hampir kehilangan rumahnya. Ada yang di-doxing, dikirimi pesan-pesan intimidatif, diancam dibunuh anak dan istrinya. Ada juga yang sampai harus lari dari rumah. Bertahun-tahun ngalamin trauma itu sampai akhirnya ke psikolog, masuk RSJ (Rumah Sakit Jiwa). Ada itu kasusnya,” kata Andreas.
Baca Juga: Berjilbab atau Tidak Tetap Hadapi Stigma
Di Balik Maraknya Peraturan Pemaksaan Busana
Andreas Harsono menyebut sejak pertama kali diperkenalkan di Sumatera Barat pada 2001, Indonesia telah memiliki 120 aturan daerah wajib jilbab dan 73 di antaranya masih berlaku. Sanksi atas pelanggaran peraturan ini berkisar dari peringatan lisan, dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, hingga hukuman penjara sampai tiga bulan.
Dalam laporan HRW yang sama disebutkan, sebagian besar dari hampir 300.000 sekolah negeri di Indonesia, terutama di 24 provinsi yang mayoritas besar penduduknya Muslim, mewajibkan anak perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab sejak sekolah dasar. Meski pejabat sekolah mengakui tak ada kata wajib jilbab, peraturan tersebut tetap bisa dipakai untuk menekan anak perempuan dan orang tua mereka agar membuat siswi memakai jilbab.
Maraknya peraturan pemaksaan berbusana menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang jadi pemicu dari menjamurnya peraturan diskriminatif ini?
Ruby Kholifah, The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia berkata pada Magdalene, kontestasi politik di Indonesia, terutama politik Islam, punya andil besar dalam membentuk peraturan pemaksaan berbusana.
Politik Islam sendiri secara definisi dijelaskan oleh Mohammed Ayoob dalam tulisannya Political Islam: Image and Reality (2004) merupakan interpretasi Islam sebagai sumber identitas dan tindakan politik. Islam sebagai sebuah tubuh keimanan seharusnya diatur dan diimplementasikan dengan cara tertentu.
Hal ini dapat merujuk pada berbagai individu atau kelompok yang menganjurkan pembentukan negara dan masyarakat sesuai dengan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam tertentu. Simbol agama dalam hal ini jadi paling banyak digunakan sebagai basis untuk mendorong atau menyamaratakan pemahaman prinsip-prinsip Islam.
Di Indonesia, politik Islam mulai tumbuh subur di pasca-Reformasi. Ruby menjelaskan, dengan demokrasi terbuka, banyak kelompokagama akhirnya memakai instrumen demokrasi untuk mendorong prinsip-prinsip Islam dalam bernegara dengan dalih kebebasan berekspresi.
Jika pada Orde Baru jilbab dicurigai dan orang yang memakainya diintimidasi, pada era setelahnya, jilbab bertransformasi menjadi simbol transformasi kesalehan, kelahiran kembali (hijrah), dan identitas Muslim.
“Transformasi ini berjalan bersamaan dengan demokratisasi yang memberikan ruang pada kebangkitan politik Islam Indonesia dan ekspresi keislaman di ruang publik. Mereka dengan rapih masuk ke dalam sekolah melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) atau rohis, tubuh pemerintahan, dan membangun basis partai politiknya sendiri. Beragama jadinya harus dengan koridor-koridor tertentu yang menimbulkan intoleransi,” jelas Ruby.
Prinsip-prinsip Islam pada prosesnya tak hanya muncul dalam ruang privat tetapi meluas jadi pengekangan. Satu contoh yang menggambarkan pengaruh kontestasi politik Islam terhadap peraturan pemaksaan berbusana adalah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2014 tentang “Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah” (sekarang sudah tidak berlaku).
Baca Juga: Larangan Berjilbab India, Bukti Tubuh Perempuan Masih Terjajah
Regulasi ini menetapkan pakaian seragam nasional dan variasi bagi para siswi Muslim. Tidak ada referensi ke agama atau identitas kelompok lain yang mungkin memberikan variasi pada seragam sekolah standar nasional.
Mendikbud kala itu, Muhammad Nuh, mengatakan regulasi ini dibuat untuk menjamin kebebasan berpakaian siswi Muslim. Akan tetapi, menurut laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Human Rights Watch yang dikutip dari artikel The Conversation, peraturan tersebut justru menjadi legitimasi bagi pihak sekolah mewajibkan pelajar Muslim yang belum berjilbab untuk berjilbab dengan cara-cara tertentu.
Bivitri menambahkan, regulasi pemaksaan berbusana seperti ini juga diperkuat dengan peraturan daerah yang diskriminatif. Komnas Perempuan dalam siaran pers mereka pada 2021 menyatakan, setidaknya ada 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana yang mengadopsi interpretasi tunggal dari simbol agama mayoritas.
Ke-62 kebijakan daerah ini terbit antara kurun 2000 hingga 2015 dan tersebar di 15 provinsi, yang terdiri dari 19 peraturan daerah dan 43 peraturan dan kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi juga kota/kabupaten.
Menurut Bivitri, cara berbusana yang diadopsi menjadi hukum negara ini membuat orang menormalisasi persekusi tubuh perempuan. “Masyarakat, pihak sekolah yang di dalamnya ada guru semacam dapat afirmasi bahwa ya mereka berhak mendikte dan memberikan hukuman bagi anak perempuan yang tidak menaati peraturan tersebut,” tutur Bivitri.
Persekusi ini sayangnya tak diimbangi dengan sikap tegas dari pemerintah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, pemerintah akhirnya jadi enggan mengambil tindakan yang tegas yang mungkin akan membuat kelompok agama mayoritas balik menyerang mereka.
“Dalam aspek tata hukum negara, pemerintah sebenarnya bisa bertindak tegas, tapi ya karena tidak mau dituding anti islam makanya pemerintah pusat enggak mau ambil sikap tegas,” jelasnya.
Regulasi yang Tak Cukup
Andreas Harsono menerangkan, Kementerian Pendidikan sudah melakukan langkah yang memadai untuk mengatasi perundungan dan kekerasan seksual termasuk lewat peraturan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Lewat peraturan yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2023 lalu, Kemendikbud Ristek pemaksaan untuk menggunakan seragam bagi peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan. Sayangnya menurut Andreas implementasi peraturan ini terhambat salah karena ada puluhan aturan daerah wajib berbusana Islam, setidaknya pada 24 provinsi.
Sama seperti yang sudah dijelaskan Bivitri, peraturan-peraturan daerah justru memberikan ruang bagi sekolah untuk menafsirkan aturannya sendiri dan menjustifikasi pemaksaan berbusana. Hal ini pun semakin diperparah karena menurut Andreas sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada pembagian kewenangan institusi pendidikan.
“Di Indonesia, sekolah menengah menjadi kewenangan milik pemerintah provinsi. Sekolah menengah pertama dan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Hanya universitas yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan. Ini membuat guru-guru lebih takut pada bupati, wali kota dan gubernur daripada pada Menteri Pendidikan. Bedakan dengan universitas di mana Kementerian Pendidikan bisa langsung menindak dosen bermasalah,” kata Andreas.
Pemberian wewenang berbeda pada setiap institusi pendidikan jelas berdampak pada pemberian sanksi tegas pada tenaga pendidik yang bermasalah. Ini juga menjadi celah bagi sekolah-sekolah untuk mengimplementasikan aturan pemaksaan berbusana mereka dengan justifikasi perda diskriminatif.
Walau terkesan tidak ada jalan keluar, menurut Bivitri ada beberapa cara yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mencegah pemaksaan berbusana ini tidak lagi terjadi.
Pertama, walau pemerintah pusat tidak memiliki wewenang lagi dalam mencabut perda yang sudah disahkan yang tercantum dalam putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 oleh Mahkamah Konstitusi pada Juni 2017, Kementerian Dalam Negeri memiliki alat atau tools untuk mencegah disahkannya perda diskriminatif.
“Tools ini yang namanya Fasilitasi Rancangan Produk Hukum. With or without legislation, Kemendagri bisa memberikan arahan kepada kepala daerah untuk tidak memberikan peraturan diskriminatif karena wewenang penerbitan nomor registrasi peraturan daerah dan setingkatnya ada di mereka,” jelas BIvitri.
Ia pun melanjutkan dengan wewenang ini Kemendagri seyoganya punya kuasa bahkan untuk membuat panduan lebih konkret untuk mencegah peraturan daerah atau setingkatnya yang sifatnya diskriminatif. Tools yang dimiliki oleh Kemendagri juga tambah Bivtri pada kenyataannya juga berhubungan erat dengan harmonisasi perda dengan perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam hukum tata urutan perundangan yang dimuat melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Perda menempati tata urutan hierarki terbawah.
Dalam hal ini tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, baru pada Peraturan Daerah atau Perda. Jika mengacu pada tata urutan hierarki ini maka sebenarnya perda jelas tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di tingkat nasional.
Kedua, untuk menjamin ketidak berulangan kasus pemaksaan berbusana Bivitri mendorong Kemendikbud Ristek membuat sistem pengawasan yang lebih baik. Peraturan secara tertulis saja tidak cukup jika tak ada sistem pengawasan yang mumpuni. Sistem pengawasan ini salah satunya bisa dengan membangun whistleblowing system atau mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana ke direktorat pendidikan.
“Kalau ada sistem ini, jadinya pemerintah enggak usah nunggu satu kasus viral dulu baru bertindak,” tegasnya.
Sistem ini kemudian juga diintegrasi dengan pemberian sanksi tegas pada pihak-pihak sekolah yang melakukan pelanggaran. Seringan-ringannya menurut Bivitri adalah dengan sanksi administratif.
Ketiga, untuk memastikan tenaga pengajar tidak menjadi pelaku kekerasan sudah saatnya Kemendikbud Ristek mulai menggalakkan pendidikan guru berperspektif HAM. Bivitri mengungkapkan harus ada upaya dari pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma tenaga pengajar dengan membuat pelatihan dan bimbingan khusus bagi mereka.
Pendidikan ini menjadi penting lantaran kekerasan yang terjadi semua berawal dari pemahaman prinsip-prinsip moralitas agama. Dalam hal ini, moralitas agama selalu memahami pedagogi dalam hitam putihnya tanpa bisa membedakan bahwa suatu hal bersifat diskriminatif atau tidak.
Ruby Kholifah menambahkan, media juga punya tanggung besar dalam memutus rantai kekerasan ini. Buatnya media seringkali melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan dalam framing pemberitaannya. Hal ini sayangnya diperparah dengan mudahnya akses informasi di internet yang bisa diakses masyarakat tanpa diimbangi literasi media yang membuat masyarakat mudah termakan isu.
“Masyarakat kita masyarakat yang sakit, jadi kita butuh pemberitaan yang sifatnya edukatif bukan mendiskriminasi atau menstigma lagi. Maka dari itu media punya peran penting memantik percakapan kritis. Ini agar praktik diskriminatif tidak dinormalisasi,” tutup Ruby.