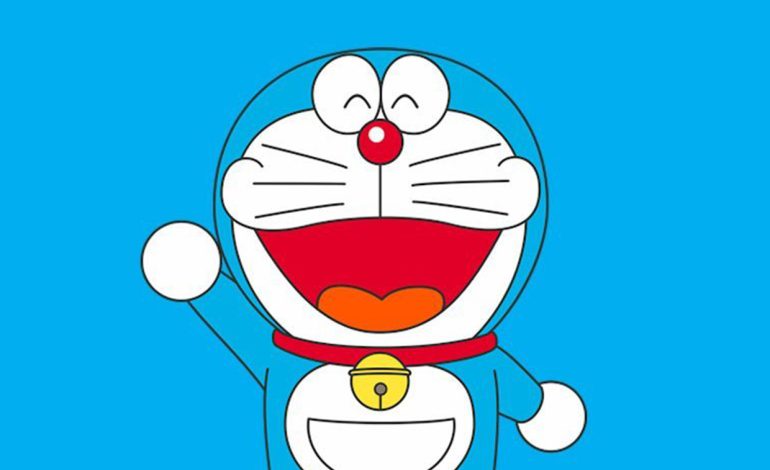Tari Jaipong: Potret Otoritas Tubuh yang Direnggut

Kalau ada satu kesan mendalam yang Nurul Ajijah dapatkan selama sembilan tahun menjadi penari jaipong, itu adalah pengalaman buruknya saat dilecehkan di atas panggung. Itu tidak hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali. Biasanya itu terjadi ketika Nurul mengisi acara atau undangan di daerah perkampungan yang jauh dari perkotaan.
“Aku pernah di-jogetin penonton bapak-bapak. Dia mau ngasih uang. Tangannya sudah mau masuk banget ke ikat pinggang aku. Akhirnya aku berusaha menghindar. Tetap menari, tapi sambil pelan-pelan menghindar,” kata Nurul, 20 tahun, yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan seni tari di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI), Bandung.
Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi Nurul. Kini, ia lebih bisa menentukan mana undangan yang harus ia terima dan mana yang harus ia tolak. Ia akan terlebih dahulu mencari tahu tempat dan konsep acara dari undangan yang memintanya untuk menari.
Baca Juga: 5 Dokumenter Layak Tonton Soal Ketubuhan Perempuan
Pengalaman buruk Nurul adalah hanyalah salah satu contoh yang mencerminkan bagaimana tari jaipong sarat akan stigma di tengah masyarakat. Yang paling melekat adalah anggapan bahwa tari jaipong adalah tarian yang vulgar dan erotis, sehingga para penari jaipong seperti Nurul juga turut terkena imbas dari anggapan miring itu. Tanpa sedikit pun niat untuk menggoda penonton ataupun mendapatkan uang dari mereka, menurut Nurul, selalu saja ada penonton yang menganggap dia begitu, tanpa terlebih dahulu mengetahui motif kedatangan dia ke sebuah acara.
“Itu salah mereka (penonton). Soalnya kan ada batasan. Sebelum pertunjukan udah dikasih tahu batasan-batasannya sampai mana. Tapi masih ada aja yang berani buat ngelakuin hal kayak gitu, berusaha memuaskan diri sendiri,” kata Nurul.
“Padahal gerakan tari jaipong enggak ada yang buat menggoda penonton. Aku juga enggak ada niat ke sana. Kalau terkesan ada yang erotis itu pembawaannya dari dulu,” ia menambahkan.
Bila dilihat dari kacamata jenis-jenis tari khas Jawa Barat, tari jaipong memang memiliki karakteristiknya sendiri yang membuat orang mudah membedakannya dengan tari-tari klasik khas Jawa Barat. Selain iringan musiknya yang bertempo cepat, tarian ini juga memiliki gerakan yang dinamis. Para penari perempuannya juga membawakan aura yang bebas, seolah mendobrak segala anggapan bahwa penari harus lemah lembut bak putri kerajaan.
Baca juga: Bolehkan Penari Berjilbab?
Hal itu juga tampak dari bagaimana penari jaipongan mendandani dirinya ketika akan tampil menari. Pakaiannya adalah kebaya modern yang dihiasi dengan berbagai hiasan berwarna cerah. Bukan kain yang dililit kencang membalut pinggang sampai ke kaki, bawahan yang mereka kenakan biasanya adalah paduan celana dengan kain yang longgar. Riasan wajah yang menor, biasanya dicirikan dengan warna bibir yang merah terang, juga dilengkapi dengan hiasan rambut yang menempel di sanggul besar yang dipasang tinggi di atas kepala.
Tari Jaipong Lahir dari Hasil Pergaulan Rakyat
Gerak dan tampilan penari jaipong itu terbentuk dari sejarah kelahirannya. Menurut seniman dan pengamat budaya Sunda, Atang Supriatna, tari jaipong lahir dari hasil pergaulan rakyat di wilayah pinggiran Jawa Barat.
“Tari jaipong itu lahir dari kesenian rakyat, tepatnya di pinggiran Jawa Barat, yaitu daerah Subang dan Karawang. Kesenian rakyat itu lahir dari rakyat tanpa ada aturan yang ketat. Dia hadir sebagai ekspresi kegembiraan dan kesenangan, bahkan ekspresi pernyataan diri. Bukan dari ekspresi yang berestetika tinggi,” jelas Atang.
Latar belakang itulah yang kemudian melahirkan jaipongan sebagai tarian yang fleksibel, baik dari segi gerakan, iringan musik, sampai tata busana dan tata rias. Bukan semata cerminan nilai estetika, banyak aspirasi dan gambaran kehidupan rakyat yang dituangkan di dalamnya.
“Dia (jaipongan) tidak memiliki aturan dan pakem gerakan. Ada struktur tarinya, hanya saja secara bentuk tidak seperti tari-tari klasik,” ujar Atang.
Mengenai gerakannya yang sering disebut-sebut erotis, Atang tak memungkirinya. Tapi, ia menggarisbawahi bahwa tidak adanya pakem bukan berarti tarian ini bisa dibawakan semena-mena tanpa pertimbangan etis.
“Jaipongan kan lahir dari 3G, geol, gitek, geboy (ketiganya merupakan gerakan pinggang dan pinggul) sebagai bentuk gerak alamiah perempuan-perempuan Sunda. Geol, gitek, geboy memang riskan. Tetapi ketika sudah masuk citra estetik, sudah masuk kemasan, dikemas sedemikian rupa sehingga jaipongan menjadi seni yang bermartabat,” katanya.
Stigma yang meliputi tari jaipong membawa berbagai dampak bagi pelaku seni jaipong, dari pelecehan seksual dan verbal, sampai dilarang untuk tampil di beberapa pertunjukan.
Atang juga menyinggung adanya perbedaan semangat dan fungsi tari jaipong bagi masyarakat di perkotaan dan perkampungan di Jawa Barat. Tari jaipong di kota-kota besar, ujarnya, sudah diadaptasi sehingga menjadi metode pembelajaran tari, biasanya di sanggar-sanggar seni. Sementara di daerah perkampungan, tari jaipong adalah bentuk hiburan rakyat. Di sinilah tari-tari jaipong yang masih membawa semangat partisipatif, di mana penari dan penonton bisa menari bersama, banyak masih diadakan.
Stigma Tari Jaipong dan Otoritas Tubuh
Meski sudah mengalami banyak perkembangan dan penyesuaian gerakan, banyak orang masih menyamakan tari jaipong hiburan dan tari jaipong pertunjukan. Inilah salah satu penguat stigma terhadap tari jaipong. Dulu, motif ekonomi kental meliputi para penari jaipong di perkampungan. Tapi kini penari jaipong bukan hanya ingin meraih keuntungan materiil, tapi juga memiliki motif akademis, seperti halnya Nurul.
Stigma yang meliputi tari jaipong membawa berbagai dampak bagi pelaku seni jaipong, dari pelecehan seksual dan verbal, sampai dilarang untuk tampil di beberapa pertunjukan.
Dalam penelitian yang berjudul Bahasa Tubuh Jaipongan: Seksualitas di Atas Panggung, peneliti tari jaipong dan guru besar ISBI Bandung, Endang Caturwati, mencatat pencekalan terhadap penari jaipong yang menimpa penari Tati Saleh dan Yati Mamat pada tahun 1980an. Keduanya dicekal oleh istri Gubernur Jawa Barat Aang Kunaefi, Enden Sarimanah, lantaran dinilai menari secara erotis dan sensual. Tapi kedua penari tersebut mmengatakanengaku bahwa segala gerakan dan komponen yang keduanya tampilkan di atas panggung tidak terlepas dari olah tari jaipongan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan selalu ada di bawah bayang-bayang laki-laki dan kekuasaan politik.
Dua dekade kemudian, pada tahun 2009, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa tari jaipong harus diperhalus, terlebih gerakan 3G-nya, karena terkesan erotis dan tidak senonoh.
Pengajar antropologi seni Imam Setyobudi dan Mukhlas Alkaf, lewat penelitiannya yang berjudul “Antropologi Feminisme dan Polemik Seputar Tubuh Penari Perempuan Jaipongan Menurut Perspektif Foucault” yang dipublikasikan di Jurnal Humaniora Universitas Gadjah Mada (2011) mengatakan, stigma masyarakat terhadap tari dan penari jaipong menunjukkan sebuah struktur relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki.
Baca juga: ‘Liberation’ Tarian dan Perjuangan Perempuan
Masyarakat mewajarkan agresivitas seksual penonton laki-laki yang menyentuh tubuh penari jaipong, sementara penari hanya boleh menunjukkan perilaku yang pasif kendati dijadikan objek seks tanpa persetujuannya, ujar mereka. Dan ketika wacana tersebut mulai masuk ke pembahasan di ranah publik, perempuan lagi-lagi menjadi pihak yang direpresi, bahkan tubuhnya selalu dikendalikan pihak lain yang bukan dirinya sendiri.
Isu otoritas tubuh memang tak bisa absen disinggung dalam pembahasan mengenai tari jaipong. Kepada Magdalene, Endang Caturwati menyampaikan bahwa hal itu merupakan buah dari kompleksitas dimensi seni dan budaya di Indonesia yang melahirkan struktur yang penuh stigma terhadap penari perempuan.
Sebelum tari jaipong lahir di Jawa Barat, beberapa daerah di Indonesia mengenal istilah ronggeng, sebutan bagi penari dan penyanyi perempuan yang biasanya mengisi acara hiburan rakyat di desa-desa, kata Endang. Tapi bahkan sampai saat ini, ronggeng jadi memiliki makna peyoratif.
Menurut Endang, ini disebabkan karena dahulu, penjajah kolonial menjadikan ronggeng sebagai penari hiburan yang juga melayani penonton lewat hubungan seksual. Padahal, semula ronggeng merupakan sebutan bagi seorang penari dan penyanyi yang bisa mengobati orang dan memimpin upacara-upacara adat tertentu.
“Ronggeng ini adalah objek eksploitasi penjajah. Karena kondisinya begitu, sekolah dia (para ronggeng) jadi tidak tinggi, dia jadi kawin-cerai karena faktor ekonomi. Padahal dia menari untuk mencari nafkah dan menghidupi anak-anaknya, bukan karena dia lenjeh menggoda laki-laki. Imbasnya sampai sekarang, penari jaipong pun dianggapnya miring,” kata Endang.
“Kalau pada akhirnya laki-laki tergoda (dengan penari jaipong), salah sendiri, kenapa tergoda? Kan dia (penari jaipong) memang cantik.”
Di tengah gelombang konservatisme agama yang marak hari ini, hal-hal yang mencerminkan kebebasan berekspresi seperti tari jaipong kerap dijadikan objek yang dibungkam atas nama nilai agama dan kesusilaan. Endang mengatakan, konservatisme agama pernah menghambat perkembangan tari jaipong di beberapa wilayah di Jawa Barat. Salah satunya yang terjadi di Cianjur, saat masyarakat setempat pernah menolak pementasan tari jaipong untuk ditampilkan di daerahnya. Tapi, menurutnya, tari jaipong tidak akan mati begitu saja, selama masih ada penggemar dan masyarakat yang mendukung.
Baca Juga: Perempuan Penulis Mencari Ruang Aman di Dunia Sastra yang Maskulin
“Justru, harusnya ingat, loh. Penyebaran agama Islam oleh Wali Songo itu lewat seni, seperti seni wayang dan seni tari. Kalau enggak lewat seni dan budaya, itu enggak bakal bisa masuk,” ujarnya.