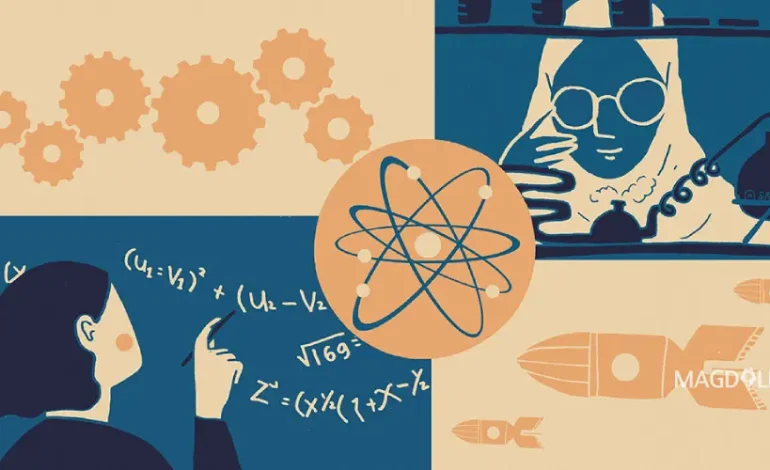‘The Most Hated Man on the Internet’: Tangan-tangan Misogini di Jagat Maya

Peringatan: Ada spoiler dan penggambaran kekerasan seksual
Siang itu kehidupan Kayla Laws, pramusaji restoran itu berubah 180 derajat. Semua bermula dari panggilan telepon temannya. Ia diminta segera membuka laman IsAnyoneUp karena foto-foto telanjangnya tersebar tanpa consent, dan diletakkan dalam halaman utamanya. Tak hanya itu, profil Facebook, alamat, dan nomor ponselnya diumbar di website tersebut. Jantungnya makin copot saat menyaksikan komentar-komentar bernada merendahkan untuknya.
Dalam kondisi gemetar, ia pulang ke rumah dan mengunci dirinya di kamar. Selama beberapa hari enggan keluar. Sementara, puluhan nomor yang tak ia kenal meneleponnya. Mentalnya hancur, pun kepercayaan dirinya serasa dicabut paksa.
Menyedihkan ketika mengetahui Kayla bukanlah satu-satunya perempuan yang harus mengalami hal ini. Ribuan foto telanjang perempuan lainnya juga diunggah tanpa consent di website IsAnyoneUp.
Dari produser The Tinder Swindler (2022) dan Don’t F**k with Cats (2019), kisah Kayla dan perempuan korban lain diangkat secara blak-blakan dalam The Most Hated Man on the Internet. Serial terbatas yang hanya memiliki tiga episode ini menawarkan dokumenter true crime yang mengangkat suara korban secara empatik–pendekatan yang masih jarang ditemui dalam dokumenter true crime.
Baca Juga: 3 Catatan Penting dari Film Kekerasan Seksual ‘Cyber Hell’
Kegigihan Seorang Ibu Mengungkap Kejahatan
Charlotte Laws mungkin bisa dinobatkan sebagai salah satu detektif amatir terbaik abad ini. Ibu dari Kayla Laws ini adalah sosok yang menjadi salah satu poros cerita The Most Hated on the Internet. Berbekal pengalamannya melihat anak perempuannya hancur karena kekerasan berbasis gender online (KBGO), ia gigih memperjuangkan keadilan untuk anaknya dan ribuan perempuan di IsAnyoneUp. Ia tak peduli dengan peringatan suaminya, pun tak gentar dengan ancamanan pembunuhan dan pemerkosaan dari The Family, pengikut setia sang pelaku Hunter Moore.
Charlotte bekerja keras dari pagi hingga malam seorang diri. Ia menenggelamkan dirinya pada investigasi mandiri tersebut. Ia paham jika ia tak “terobsesi” dengan kasus ini sebagaimana Moree terobsesi menghancurkan ribuan hidup perempuan, ia tak akan bisa memenjarakan Moore.
Maka ribuan jam ia lalui dengan mengumpulkan bukti, menghubungi para jurnalis, mewawancarai, dan menemui 40 korban sendirian di berbagai negara bagian di Amerika. Semua ia lakukan sukarela dan atas dasar kemanusiaan. Bahwasanya perempuan juga punya hak hidup aman dan diperlakukan layaknya manusia bermartabat. Charlotte sebenarnya bisa saja dengan mudah melupakan kasus ini, apalagi foto anaknya Kayla sudah dihapus dari website berkat suaminya yang seorang pengacara.
Ia bisa dengan mudah menutup mata terhadap perempuan korban lain yang dia ajak bicara, tapi dia tidak melakukannya. Dia memutuskan untuk jadi medium bagi para perempuan ini mendapatkan kembali hak dan suaranya. Ia paham korban dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki harapan, sehingga ia ingin menjadi harapan bagi para korban.
Tindakan Charlotte mengingatkan penonton pada pernyataan Albert Einstein.
“Dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang hanya menonton dan tanpa melakukan apa-apa.”
Charlotte dan keberaniannya seakan memberikan tamparan bagi masyarakat tentang pembiaran. Bahwasanya kini umat manusia seakan sudah tak peduli lagi dengan sesamanya. Mereka lebih memilih jadi bystander, menutup mata dan telinga atas kekerasan dan ketidakadilan karena alasan kenyamanannya sendiri. Ya, memang untuk bisa bertindak butuh privilese tapi bukan berarti kita selamanya diam. Adalah tugas moral kita bertindak sekecil apa pun.
Maka tak heran, apa yang Charlotte lakukan bak mimpi buruk Moore dan The Family. Sebab, pada akhirnya, ada perempuan yang berani ambil tindakan, ada perempuan yang berusaha mengusik kuasa para laki-laki yang gemar menginjak-injak martabat mereka.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Film India yang Urai Patriarki dengan Gamblang
Misogini, Akar dari Kejahatan Moore dan Pengikutnya
Kendati The Most Hated Man on the Internet memberikan gambaran detail tentang siapa Hunter Moore, pengalaman korban, dan proses pengusutan yang dilakukan Charlotte, serial ini terasa mengganjal buat penontonnya. Pasalnya, selama kurang lebih 153 menit, tak ada penjelasan mengenai akar dari kejahatan seksual yang dilakukan Moore dan banyak pengguna laki-laki dari IsAnyoneUp. Dari banyaknya ahli laki-laki yang diwawancarai, mulai dari praktisi hukum hingga agen FBI, tak satu pun perempuan ahli dalam bidang gender yang ditanyai mengenai perspektif dari kasus itu.
Padahal sejak awal, serial ini menekankan bagaimana Moore selaku pencipta website adalah laki-laki yang tak memiliki empati terhadap perempuan. Dari intensi awal ia menciptakan website saja sudah terlihat jelas untuk memberikan ruang balas dendam mantan dari laki-laki.
Perempuan pun di sini diperlakukan hanya sebagai objek seksual. Ia mendapatkan kesenangan dengan mempermainkan perempuan, memosisikan perempuan di bawah kuasanya untuk memamerkan betapa jantan atau maskulinnya ia kepada pada pengikut setianya, The Family. Ia bahkan tak malu menjuluki dirinya sendiri sebagai professional life ruiner.
Dengan IsAnyoneUp, ia menghancurkan kehidupan perempuan yang bahkan tak ia kenal. Ia menyukai ketenaran dari caranya menghancurkan kehidupan korbannya. Ketenaran yang ia dapatkan ribuan laki-laki dan para pengikutnya yang memuja tindakan keren dan “revolusionernya”. Jumlah orang yang datang ke halaman website ia kian meningkat hingga Moore bisa menghasilkan 13.000 dollar Amerika per bulan di 2012.
Normalisasi tindakan Moore dan para pengikutnya ini tak lain berakar pada misogini, kebencian terhadap perempuan. Misogini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, kekerasan, dan objektifikasi seksual. Dalam kasus Moore, misogini ini termanifestasikan dalam bentuk revenge porn.
Dalam artikel The Guardian yang ditulis oleh Dr Laura Hilly dan Kira Allmann dari Universitas Oxford disebutkan, revenge porn bertujuan untuk mempermalukan, memeras, dan menyakiti perempuan. Revenge porn membatasi kebebasan berbicara perempuan dan mematikan eksistensi mereka secara perlahan.
Baca juga: ‘Our Father’: Cerita Korban Pemerkosaan Medis Cari Keadilan
The Most Hated Man on Internet menekankan bagaimana teknologi bisa jadi ruang bagi orang atau kelompok untuk melakukan kekerasan. Seolah-olah pelecehan dan kekerasan daring dapat terjadi pada siapa saja. Padahal ini bukan masalahnya. Kebencian terhadap perempuanlah yang jadi masalahnya, bukan teknologinya. Layaknya ruang fisik, teknologi adalah ruang dari perpanjangan tangan misogini.
Teknologi sebagai perpanjangan tangan misogini dibangun di atas landasan pemikiran, perempuan sebagai sang liyan, tak setara, dan milik publik. Alhasil, setiap orang berhak mengomentari, mempermalukan, membungkam, dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri.
Pada akhirnya, serial terbatas The Most Hated Man on the Internet hanya menguliti kekerasan berbasis gender di kulit terluarnya saja. Serial ini hanya menyajikan sensasionalisme dari Moore dan usaha Charlotte dan korban dalam membalikkan keadaan. Namun, luput memberikan perspektif baru dan refleksi terhadap penonton tentang bahaya laten misogini. Kebencian terhadap perempuan yang sudah lama ternormalisasi yang seharusnya jadi fokus utamanya.