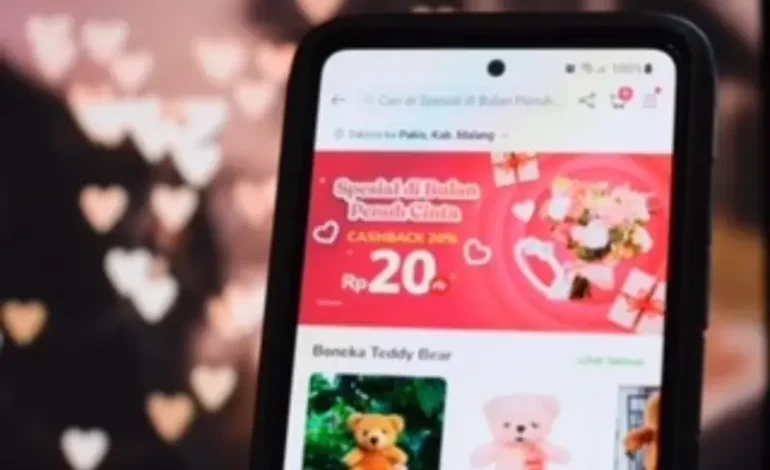Tiga Diskusi Menarik dari Dokumenter ‘The Tinder Swindler’
‘The Tinder Swindler’ membawa banyak diskursus. Mulai dari penonton kita yang masih gemar melakukan ‘victim-blaming’ sampai trauma ditipu kenalan di aplikasi kencan.

VG, media di Norwegia merilis laporan berjudul The Tinder Swindler pada 2019. Laporan itu mengungkap kejahatan pria bernama Shimon Hayut, yang bertahun-tahun menipu banyak perempuan lewat Tinder. Hayut menyamar sebagai Simon Leviev, pewaris pengusaha berlian kaya raya di Israel.
Laporan investigasi tersebut kemudian viral dan disadur media-media besar lain. The Atlantic menulisnya dengan judul The Truth About Dentistry, sementara The New York Times mengangkatnya dalam laporan Who is the Bad Art Friend?
Netflix, si perusahaan konten raksasa, juga tak mau ketinggalan. Produser dokumenter viral Dont Fuck With Cats (selanjutnya disebut Cats), Felicity Morris, ditunjuk sebagai sutradara untuk menggarap The Tinder Swindler ke dalam format dokumenter–yang kemudian mengadopsi judul original laporan investigasinya.
Di minggu pertama rilis, The Tinder Swindler dapat respons yang cukup baik. Nama Tinder, aplikasi cari jodoh yang populer di kalangan milenial dan Generasi Z ini tentu saja punya peran. Tak sedikit penontonnya, atau mereka yang mengulas dokumenter ini di media sosial, tertarik menonton karena teasing “penipu” dan “Tinder” dipampang sebagai judul.
Baca juga: ‘RuPaul’s Drag Race Ajari Soal Toleransi, Keberagaman, dan Inklusivitas
Diskusi yang muncul setelah menonton pun ternyata cukup beragam. Banyak yang suka, ikut geram, atau bersimpati pada korban-korban Hayut. Namun, tak sedikit yang melabeli para korban perempuan ini bodoh, kecuali satu orang (yang muncul di akhir-akhir dokumenter).

Sumber: Mirror.co.uk
Berikut adalah tiga diskusi menarik yang muncul setelah menonton The Tinder Swindler (soft spoiler alert):
Penonton Misoginis (Lagi-lagi) Menyalahkan Perempuan
“Respons terhadap dokumenter kriminal terbaru Netflix ini betul-betul mengganggu saya,” tulis jurnalis Jade Hampton di The Independent.
“Saya terganggu dengan narasi yang saya lihat membanjiri media sosial, bahwa para (korban) perempuan ini ‘semuanya bodoh,’” sambungnya.
Banyak penonton merasa tidak akan mudah percaya pada Shimon Hayut, seperti korban-korbannya. Terutama korban pertama yang memberikan kesaksian di dokumenter ini, Cecilie, yang menyebut alasannya memercayai Hayut karena punya mimpi ingin hidup seperti dongeng Beauty and the Beast.

Sumber: IMDB
Pola pikir menyalahkan korban (victim blaming) memang sulit diputus dari akarnya, selama patriarki masih ada. Di Twitter Indonesia, ada utas Henry Manampiring juga dibingkai dengan perspektif heteronormatif: Dokumenter ini dijadikan pengingat buat perempuan untuk berhati-hati, dan melanggengkan stereotip bias macam “laki-laki tukang ngutang adalah red flag”.
Daripada melihatnya sebagai peringatan yang cuma ditujukan untuk perempuan, pengalaman ditipu yang dirasakan Cecile, Pernilla, dan Ayleen harusnya tak perlu kita banding-bandingkan. Lebih berfaedah untuk melihat pola apa saja yang dimanfaatkan Shimon Hayut–penjahat sebenarnya di sini–untuk menipu target-targetnya, dan bagaimana ia memanfaatkan celah-celah kapitalisme dan patriarki dalam tiap operasinya.
“Kita dibesarkan di masyarakat yang patriarkal, terobsesi dengan dongeng Disney. Lalu, saat dongengnya betulan kejadian, tapi ternyata melenceng, kenapa malah itu jadi salah korban? Kenapa bukan salahnya si pelaku yang punya niat buruk?” tulis Hampton.
Baca juga: 8 Film Asia Bertema Transgender yang Wajib Ditonton
Simon Leviev, Penjahat Kelas Kakap yang Manfaatkan Celah Kapitalisme
Tak seperti Cats yang dibikin jadi docu-series, Felicity Morris memilih membingkai The Tinder Swindler dalam format dokumenter pada umumnya, dengan durasi kurang dari dua jam. Teknik whodunnit yang jadi kekuatan utama Cats juga tak dipakai Morris lama-lama. The Tinde Swindler fokus membongkar profil penjahat utama mereka: Simon Leviev.
Sayangnya, dengan durasi demikian, dokumenter ini tak terlalu berhasil membongkar modus operandi Hayut. Kita cuma dipaparkan temuan tentang latar belakangnya, identitas asli, keluarga, dan semua informasi yang terasa tak terlalu penting dibandingkan jawaban dari pertanyaan: Bagaimana caranya pria seumuran Hayut bisa pindah negara secepat dan semudah itu?
Baca juga: ‘Drag Race Holland’: Saat Institusi Queer Gagal Pahami Konsep Gender Nonbiner
Buat saya, pertanyaan itu jadi menarik, karena informasinya yang sengaja tak terlalu banyak jadi fokus dokumenter ini. Sebagaimana latar belakang finansial tiga korban utamanya, yang juga tidak terlalu dapat sorotan utama. Kepingan-kepingan ini penting untuk menjawab, kenapa penipuan yang dilakukan Hayut mungkin terjadi.
Namun, dari semua informasi yang ada di dokumenter ini, setidaknya kita bisa paham kalau Hayut cukup pintar mengelabui aturan-aturan di negara-negara yang dia kunjungi untuk, misalnya, bikin visa kilat, sewa jet pribadi kilat, dan mengelabui SEO Google.
Trauma Ditipu Kenalan di Aplikasi Kencan
Salah satu budaya yang belum pernah dirasakan nenek-kakek kita dan buyut-buyut mereka adalah cari jodoh lewat aplikasi kencan. Artinya, kita tak bisa belajar dari mereka, jika tersandung atau menghadapi hal-hal buruk tak terduga dari kultur ini.
Itulah makanya, dokumenter The Tinder Swindler mudah menarik perhatian generasi kiwari. Ditipu kenalan di aplikasi kencan ternyata sering terjadi, sampai-sampai bisa disebut pengalaman kolektif. Selain tema victim-blaming, media sosial juga ramai dibanjiri cerita-cerita mereka yang mengalami hal serupa.
Meski judulnya tak melulu “ditipu finansial”, seperti yang dialami korban-korban Hayut, tapi pendokumentasian The Tindler Swindler bisa jadi validasi buat mereka para korban. Pun, tambahan diskursus buat generasi manusia yang baru memasuki kultur kencan lewat aplikasi.
Simak tulisan-tulisan spesial kita edisi Valentine di sini, di sini, dan di sini.