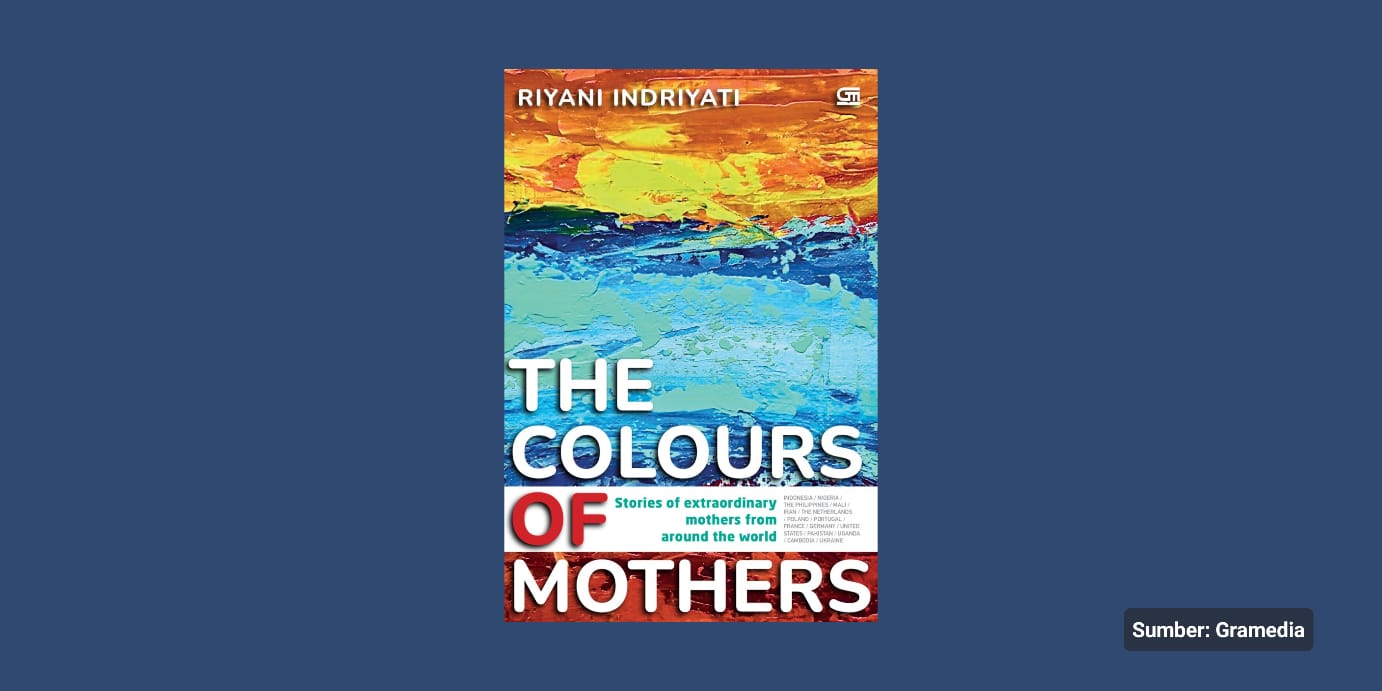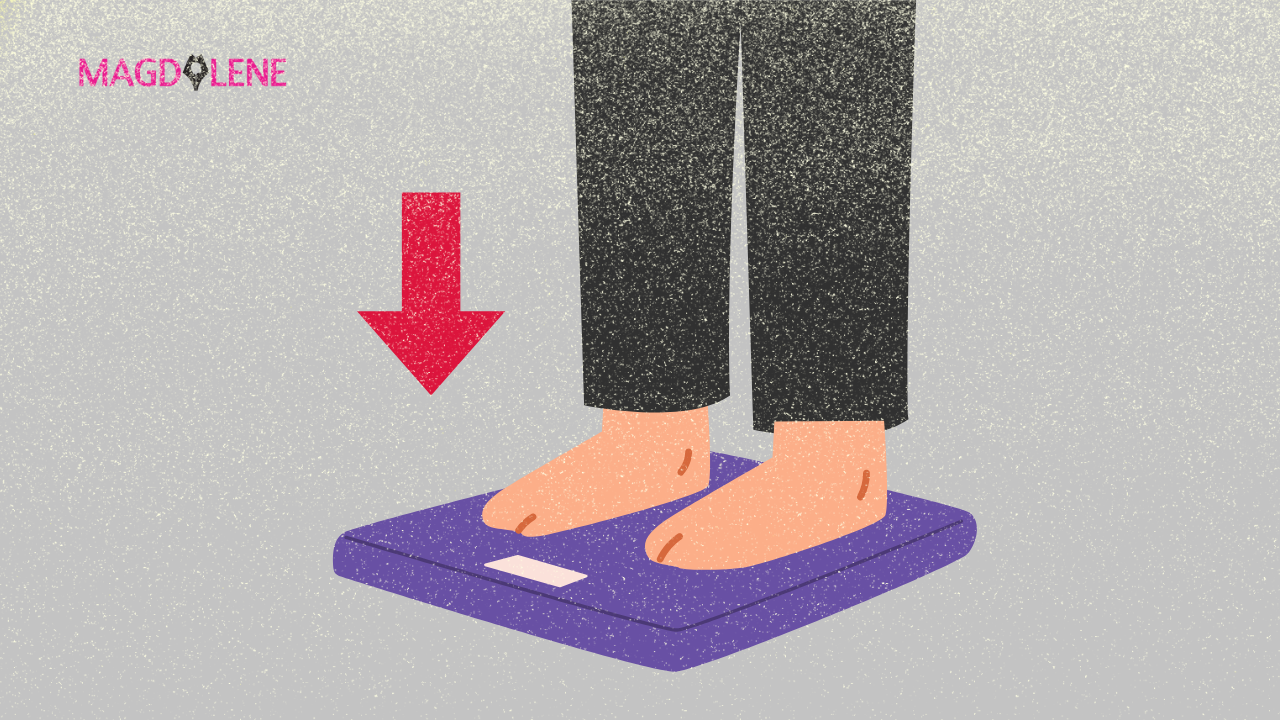‘Muslimah Bukan Agen Moral’: Menyoal Praktik Beragama yang Dangkal
‘Muslimah Bukan Agen Moral’ menguliti fenomena dakwah digital bersamaan dengan cara beragama masyarakat yang dangkal.

Sebanyak 19 siswa SMP Negeri 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur dibotaki paksa, (23/8). Pelaku, guru Bahasa Inggris Endang berdalih sudah berulang kali mengingatkan siswa untuk mengenakan ciput (dalaman hijab) tapi tak pernah sekalipun diindahkan para siswa. Itu sebabnya Endang menggunduli paksa para korban dengan alat cukur elektrik.
Kasus pemaksaan berbusana muslimah di Lamongan bukan kasus pertama di Indonesia. Ia adalah kasus berulang yang menurut Andreas Harsono, peneliti dari Human Rights Watch (HRW) mulai marak sejak pertama kali peraturan ini diperkenalkan di Sumatera Barat pada 2001. Kini Indonesia tercatat telah memiliki 120 aturan daerah wajib jilbab dan 73 di antaranya masih berlaku.
Sanksi atas pelanggaran peraturan ini berkisar dari peringatan lisan, dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, hingga hukuman penjara sampai tiga bulan.
Dalam laporan HRW pada 2021 disebutkan, sebagian besar dari hampir 300.000 sekolah negeri di Indonesia, terutama di 24 provinsi yang mayoritas besar penduduknya Muslim, mewajibkan anak perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab sejak sekolah dasar. Meski pejabat sekolah mengakui tak ada kata wajib jilbab, peraturan tersebut tetap bisa dipakai untuk menekan anak perempuan dan orang tua mereka agar membuat siswi memakai jilbab.
Maraknya kasus pemaksaan jilbab di Indonesia merefleksikan bagaimana busana ini dianggap sebagai parameter kesalehan perempuan. Jilbab buat masyarakat Indonesia disangkutpautkan dengan moral dan religiusitas perempuan, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda.
Dengan pandangan ini maka tidak heran semakin panjang jilbabnya, semakin tertutup badan perempuan, semakin alim dan salehlah perempuan itu. Sebaliknya, semakin pendek jilbab perempuan apalagi tidak memakai sama sekali, semakin terlihat seberapa tipis kesalehan serta iman perempuan.
Baca Juga: ‘Invisible Women’: Data Laki-laki yang Utama, Perempuan Nanti Saja
Menggugat Pandangan Perempuan sebagai Agen Moral
Maria Fauzi, esais dan pendiri Neswa.id (Ruang Muslimah Indonesia) dalam buku terbarunya Muslimah Bukan Agen Moral (2023) berusaha menyentil realitas ini dalam bukunya. Ia mempertanyakan pandangan kita tentang agama yang seakan disekat-sekatan oleh batas moralitas saja. Batasan ini sayangnya selalu menyasar pada perempuan.
Ia dengan tegas mengkritik bagaimana selama ini perempuan dipaksa menanggung beban peradaban yang berat sebagai agen moral. Tak jarang perempuan pun dianggap sumber kerusakan moral bangsa. Karena itu, untuk jadi perempuan “baik”, perempuan harus selalu tunduk pada standar dan norma sosial agama yang dibuat masyarakat, kata Maria.
Ini adalah bukti nyata dari objektifikasi tubuh perempuan. Aih-alih dipandang sebagai subjek bebas yang memiliki otoritas dan kehendak, objektifikasi yang dilakukan membuat perempuan dianggap sebagai objek semata yang perlu dikontrol eksistensinya.
Kritikannya ini sejalan dengan ungkapan Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex (1949), objektifikasi pada tubuh perempuan terjadi karena tubuh perempuan dipandang secara bersamaan sebagai tempat dosa dan kebajikan. Perempuan akhirnya didisiplinkan atau diatur sedemikian rupa, salah satunya lewat pemaksaan berbusana.
Objektifikasi sayangnya juga berdampak pada penyempitan makna Muslimah di ruang-ruang publik. Dalam bukunya ini, Maria mengatakan bagaimana Muslimah dalam pandangan masyarakat hanya diperuntukan bagi perempuan Muslim yang berjilbab. Identitasnya menjadi tunggal, sehingga perempuan Muslim yang tak berhijab dikecualikan dalam pemaknaannya. Mereka yang tidak berjilbab seakan tidak mendapat tempat aktualisasi baik dalam ekspresi keberagaman maupun spiritualitas.
Maria pun mencontohkan pengalaman teman-temannya. Teman-temannya, Muslim yang tak memakai jilbab merasa dirinya tereksklusi dalam berbagai majelis taklim. Semua anggota yang berjilbab besar nan panjang hingga bercadar membuatnya merasa canggung dan minim ilmu agama.
Para anggota juga acap kali memakai bahasa yang kadang kala memakai istilah-istilah arab yang tidak mereka kenali. Perasaan ini terkelusi ini pun makin besar terutama kalau teman-temannya sudah diintimidasi disuruh memakai jilbab saat kajian.
Akibatnya salah satu teman Maria pun memutuskan berjilbab. Alasannya sederhana, agar ia mudah diterima dan untuk menghindari intimidasi. Pengalaman teman Maria inilah sayangnya jadi realita pahit Muslimah masa kini. Muslimah yang kini dibatasi identitasnya dalam identitas tunggalnya saja dan enggan merangkul ekspresi keagamaan lainnya.
Baca Juga: “Bagaimana Cara Mengatakan ‘Tidak’?” Tampilkan Perempuan di Lingkaran Kekerasan
Agama yang Siap Pakai
Dalam satu dekade ini, menimba ilmu agama semakin mudah. Cuma dengan modal internet, kita sekarang sudah bisa mengikuti pengajian online atau tahfidz Quran (menghafal disertai tadabbur atau memahami ayat Al-Quran yang sedang dihafalkan). Tinggal pilih saja pendakwah mana yang ingin diikuti, dalam hitungan detik kita bisa langsung menimba ilmu agama tanpa harus pusing dengan kendala jarak, waktu, bahkan uang.
Kemudahan ini sungguh bermanfaat. Apalagi bagi orang-orang yang sedari kecil tidak pernah dibekali ilmu agama dan ingin mendekatkan diri dengan Tuhannya. Tetapi dari kemudahan di era digital ini, Maria juga menyampaikan kritikannya. Ia melihat bagaimana narasi agama yang berkembang di era digital justru mengalami reduksi esensi. Dalam ruang digital, agama hari ini disampaikan hanya sebatas pada diskursus fiqih dan kesalehan saja.
Hal ini diperparah dengan makin banyaknya tafsir-tafsir keagamaan yang cenderung konservatif. Tafsir-tafsir yang mendominasi ruang keagamaan masyarakat Indonesia menutup ruang diskusi dan pemikiran kritis terhadap suatu interpretasi agama yang sebenarnya lekat dengan bias-bias individu penafsirnya.
Maka tidak mengherankan di dalam ruang digital, agama pun jadi barang siap pakai. Sebagai barang siap pakai, agama menurut Maria berhasil hadir dalam bentuk informasi yang disajikan langsung tanpa perlu diracik terlebih dahulu oleh yang membaca. Tujuannya adalah adalah agar topik-topik yang berhubungan dengan agama bisa dipahami lebih mudah orang-orang awam.
Lewat agama sekali pakai, pemahaman agama yang mendalam seperti yang dilakukan para kiai dan nyai yang belajar bertahun-tahun hingga paham bahasa Arab tidak dibutuhkan. Siapa saja bisa memahami agama dan menjalankan agama dengan cepat serta praktis. Kehidupan pun jadi terasa lebih gampang karena pertanyaan terkait agama direduksi sebatas haram dan halalnya suatu hal saja. Mendatangkan dosa atau tidak. Spiritualisme beragama bukan lagi jadi tujuan utama.
Efek dominonya pun terasa dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia terutama dalam gaya hidup halal. Segala bentuk produk dan jasa halal ditawarkan untuk menyempurnakan praktik agama sekali pakai masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam laporan The State of the Global Islamic Economy Report 2022 yang mencatat pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal mencapai USD 184 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat sebesar 14,96 persen pada tahun 2025 yaitu USD 281,6 miliar atau 11,34 persen dari pengeluaran halal global.
Baca Juga: As Long As Lemon Trees Grow’: Trauma dan Perlawanan dalam Konflik Suriah
Agama untuk Kaum Urban Saja
Prof. Noorhaidi Hasan, pakar di bidang politik Islam dan pengajar Indonesia dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pernah menyatakan dalam penelitiannya Islam di masyarakat Indonesia kini sudah jadi bagian dari ekspresi politik, transaksi hukum, kegiatan ekonomi, serta praktik-praktik sosial dan budaya.
Islam tidak lagi sekadar seperangkat ritual atau kepercayaan tetapi juga menjadi komoditas simbolis yang relevan dengan tuntutan kelas sosial akan gaya hidup. Munculnya para dakwah kekinian yang sudah ada sejak tahun 2000-an awal lewat sosok Aa Gym dan almarhum ustad Jefri mendorong perubahan ini yang disusul dengan mikroselebritas dan influencer dakwah yang marak satu dekade belakang. Sayangnya perubahan ini memunculkan problem baru.
Dalam penelitian yang diterbitkan Springer menurut Hasan, secara bertahap agama muncul sebagai simbol elitisme yang melibatkan penggunaan dan konsumsi simbol-simbol agama. Ia mencontohkan jilbab. Jilbab yang dipahami sebagai parameter kesalehan Muslimah kini juga mengalami komodifikasi. Hasan menyebutnya sebagai transformasi jilbab menjadi seragam baru bagi perempuan Muslim Indonesia yang perlu dimiliki dan dipakai dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
Jilbab tak ayal jadi bagian gaya hidup syar’i. Baik laki-laki atau perempuan mendorong perempuan untuk memakainya sebagai bentuk berhijrah dan kesalehan tetapi juga secara implisit sebagai penerimaan sosial. Praktik agama seperti ini yang dikritik oleh Maria.
Di banyak akun Instagram dan status temannya sendiri Maria melihat timbul penghakiman ekstrem terhadap Muslimah yang tidak memakai jilbab dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam satu unggahan instagram misalnya Maria menuliskan bagaimana perempuan yang keluar tidak memakai jilbab yang benar dosanya akan terus mengalir selama ia di luar rumah.
Maria pun jadi teringat seorang ibu-ibu ia temui di jalan suatu hari. Ibu-ibu itu berjilbab dan berkaus pendek dengan rok menyingsing yang terlihat tengah mengayuh sepeda. Di dadanya terlilit kain jarik yang membungkus anaknya dan sebuah keranjang lusuh berisi rantang, cerek, dan beberapa alat makan untuk dibawanya ke sawah.
Pertemuan kilatnya dengan perempuan itu membuat Maria berefleksi tentang bagaimana praktik agama hari ini cenderung bersifat eksklusif. Agama seakan diperuntukan hanya untuk masyarakat urban dengan kelas sosial tertentu saja, yaitu Muslimah yang bisa membeli pakaian syar’i dan memakainya untuk kegiatan sehari-hari.
Praktik agama ini menurut Maria tidak melihat ada realita lain dari kehidupan Muslimah yang beragam. Tidak semua Muslimah mampu membeli pakaian syar’i yang harganya bisa sampai ratusan ribu. Tak semua Muslimah juga bisa memakai pakaian ini untuk kegiatan sehari-hari. Dengan pakaian panjang-panjang misalnya Muslimah yang harus bekerja di sawah dan mengayuh sepeda akan kesulitan bergerak. Ini bisa berdampak pada penghidupan mereka karena efektivitas kerja jadi menurun. Bahkan mereka bisa mengalami kecelakaan dalam bekerja.
Tapi sayang dengan sekat bias kesalehan dan agama yang jadi komoditas simbolis, realitas ini tak pernah dipandang. Dengan mudah kita jadi menghakimi Muslimah yang tidak berjilbab atau berjilbab “tidak benar”. Padahal seharusnya menurut Maria, agama harus dimaknai selaras dengan realitas sosial masyarakat yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini agar agama bisa jadi pegangan dan solusi individu tanpa membebaninya lagi dengan tanggung jawab moralitas semu.
Refleksi Maria terhadap praktik agama Islam masyarakat Indonesia kini tak berhenti sampai di sini saja. Melalui bukunya ada topik-topik menarik lainnya termasuk soal terorisme dan perempuan yang ia kupas dengan kritikan tajam yang membangun. Tetapi dari secara garis besar buku ini memang memberikan porsi yang cukup banyak dalam menggugat praktik agama yang kian semakin simbolis dan kehilangan esensinya.
Praktik ini berdampak pada perempuan. Mereka terus jadi sasaran korban persekusi oleh saudaranya sendiri dan Maria ingin memberitahu para pembacanya bahwa sudah saatnya kita menyadari hal ini sebagai suatu masalah yang harus kita temukan solusinya bersama-sama.