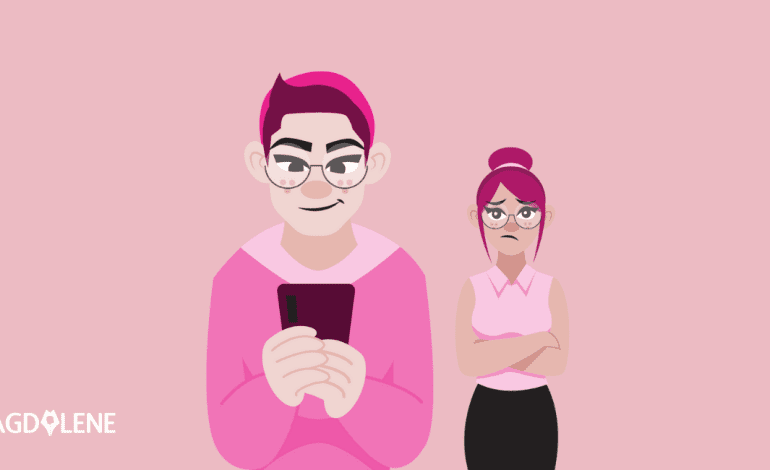‘Close’ Hegemoni Maskulinitas yang Membunuh Persahabatan Laki-Laki

Peringatan: Spoiler dan Bunuh Diri!
Close (2022), film garapan sutradara muda Lukas Dhont dan ditulis oleh Dhont dan Angelo Tijssens belakangan jadi perbincangan hangat. Dalam perhelatan penghargaan film bergengsi Academy Awards atau Oscar ke-95, Close masuk dalam nominasi Best International Feature Film setelah sebelumnya telah memenangkan Penghargaan André Cavens untuk Film Terbaik dari Asosiasi Kritikus Film Belgia.
Di Indonesia sendiri, film ini jadi sorotan setelah layangan streaming berbayar KlikFilm secara resmi menayangkannya. Banyak orang terutama laki-laki di media sosial seperti Twitter mengaku merasakan sedih yang mendalam ketika menonton film ini. Tak sedikit pula yang mengatakan cerita film garapan Dhont ini beresonasi dengan pengalaman pribadi mereka.
Close sendiri dimulai dengan sebuah gambaran indah tentang persahabatan masa kecil dua remaja laki-laki usia 13 tahun, Leo (Eden Dambrine) dan Remi (Gustav De Waele) yang sedang bermain. Keduanya terlihat berlari melintasi ladang bunga, mengendarai sepeda, dan menciptakan permainan, yang tak henti-hentinya berbahagia bersama satu sama lain. Dalam balutan palet warna cerah, penonton dibiarkan merasakan kehangatan persahabatan mereka berdua.
Rasa sayang berupa tindakan selalu hadir dalam ikatan persahabatan mereka. Leo dan Remi kerap kali berpelukan, tidur berhimpitan dalam ranjang yang sama, saling menyandarkan kepala pada bahu masing-masing, dan bergandengan tangan. Semua afeksi ini mereka lakukan seperti oksigen yang butuh dihirup. Membuat mereka hidup sekaligus membuat mereka bahagia.
Sayangnya, dunia yang hangat penuh afeksi ini harus tiba-tiba hilang. Saat kedua remaja laki-laki ini mulai masuk sekolah menengah dan berada di kelas yang sama, intimasi pertemanan Leo dan Remi dipandang sebagai anomali. Ini sayangnya berujung pada penghakiman dan perundungan oleh teman-teman sekelas mereka.
Baca Juga: Review ‘Women Talking’: Ketika Suara Korban Kekerasan Seksual Didengarkan
Hegemoni Maskulinitas yang Membunuh Persahabatan Laki-Laki
Leo dan Remi, dua remaja laki-laki yang tumbuh dalam keluarga hangat yang tak pernah menghakimi ekspresi afeksi mereka harus dibuat kaget dengan respons teman-teman mereka atas persahabatan mereka. Hari pertama masuk, salah satu anak laki-laki di dalam kelasnya sudah memandang mereka aneh. Lalu, pada saat mereka duduk di kantin sekolah, keduanya tiba-tiba dibanjiri pertanyaan oleh teman-teman perempuan yang “menuduh” mereka berpacaran.
Leo yang mendengar pertanyaan itu langsung menyangkal keras. Ia berulang kali berkata ia hanya berteman saja dengan Remi dan memang kedekatan itu hadir karena mereka sudah kenal sejak kecil. Tapi tak peduli seberapa banyak Leo menjelaskan, teman-teman mereka tidak cukup percaya dengan sangkalan Leo. Buat mereka, tak ada persahabatan laki-laki yang sebegitu intimnya.
Teman laki-laki mereka juga berpikir hal yang sama. Mereka mulai melihat Leo dan Remi dengan tatapan jijik. Dengan kekerasan verbal, mereka mulai melayangkan hinaan homophobik kepada keduanya. Membuat Leo secara khusus merasa risih dan mulai menjauhkan diri dari Remi.
Leo sudah tidak lagi ingin tidur satu ranjang dengannya, menolak dekat-dekat dengannya selama di sekolah, menolak mengunjungi rumahnya, menunggunya untuk berangkat dan pulang bersama. Sampai titik yang paling ekstrem, Leo memutuskan untuk menjauh dengan berteman dengan sekelompok remaja laki-laki yang merundungnya dan masuk dalam tim hoki es. Mengalienasi Remi sepenuhnya. Menolak kehadirannya mentah-mentah.
Perundungan yang dialami oleh Leo yang disusul oleh perubahan sikap Leo kepada Remi tak lain adalah bentuk dari mengakarnya hegemoni maskulinitas di masyarakat. R.W Connell sosiolog berkebangsaan Australia, orang yang pertama kali mencetuskan istilah ini menyatakan hegemoni maskulinitas dapat didefinisikan sebagai konfigurasi praktik gender yang menjamin adanya kuasa atas dominasi laki-laki terhadap perempuan.
Dalam bukunya Masculinities (2005), Connel menjelaskan praktik ini tidak hanya membangun hierarki kuasa laki-laki atas perempuan, tetapi juga berusaha memisahkan laki-laki dengan sifat-sifat feminin yang dibangun lewat nilai-nilai heteroseksualitas.
Karena itu, hegemoni maskulinitas sangat bergantung pada maskulinitas toksik atau bentuk maskulinitas yang dominan di mana laki-laki menggunakan dominasi, kekerasan, dan kontrol untuk menegaskan kekuasaan dan superioritas mereka.
Menjadi maskulin dalam hegemoni maskulinitas berarti tidak menjadi feminin baik dalam berpenampilan maupun dalam bersikap. Ia tidak diungkapkan dan dipertahankan melalui emosionalitas dan afeksi yang berlebihan. Sebaliknya ia diungkapkan dan dipertahankan melalui agresi, pengabaian kerentanan, dan kekuatan fisik.
Baca Juga: 3 Catatan Penting dari Film Kekerasan Seksual ‘Cyber Hell’
Adapun untuk bisa terus mempertahankan maskulinitas toksik ini, pemolisian laki-laki harus dilakukan. Artinya, setiap laki-laki yang bersikap atau berpenampilan feminine misalnya yang tidak sesuai dengan standar maskulinitas harus didisiplinkan. Hal ini karena mereka sudah masuk ke dalam kategori maskulinitas tersubordinasi yang dapat mengganggu tatanan dominasi.
Cara pemolisian ini umumnya dilakukan melalui pengucilan dan “pemberian sanksi”. Jika mengacu pada kasus Leo dan Remi sendiri, pemolisian ini hadir dalam pemberian sanksi sosial, yaitu berupa pemberian penghakiman dan perundungan verbal dalam bentuk hinaan homophobik yang dilakukan teman laki-laki mereka. Hal yang pada prosesnya menghancurkan relasi Leo dan Remi yang sudah dibangun bertahun-tahun dan membuat Remi teralienasi dari sahabatnya.
Pemolisian Laki-Laki yang Berakibat Fatal
Pemolisian bukan akhir dari hegemoni maskulinitas. Ini justru jadi awal dari indoktrinasi dan pelanggengan hegemoni maskulinitas dalam level individu lalu kelompok. Dengan menetapkan aturan maskulinitas pada laki-laki dan memolisikan mereka yang dianggap menyalahi “aturan”, laki-laki secara sosial dibentuk untuk meneruskan kekangan atas dirinya sendiri dan mempertahankan hegemoni maskulinitas itu sendiri. Sharon R. Bird, profesor Sosiologi dan profesor Studi Perempuan dan Gender di Eberly College of Arts and Sciences dalam penelitannya Welcome to the Men’s Club: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic Masculinity (1996) hal ini dilakukan dalam tiga cara.
Pertama adalah dengan membangun keterpisahan emosional pada diri mereka masing-masing. Membuat laki-laki jadi kesulitan mengekspresikan dan mengelola emosi mereka sendiri. Hal ini tergambarkan lewat Leo yang secara tersirat mengalami normative male alexithymia (NMA). NMA sendiri adalah kondisi subklinis yang dijelaskan oleh psikolog klinis Ronald F. Levant untuk menggambarkan ketidakmampuan laki-laki dalam mengungkapkan perasaannya, yang diakibatkan oleh konformitas terhadap norma-norma maskulin.
Dikutip dari penelitian Emily N. Karakis dan Ronald F. Levant dari Universitas Akron, laki-laki yang yang mengalami NMA memiliki kepuasan hubungan dan kualitas komunikasi yang lebih rendah, serta rasa takut yang lebih besar terhadap keintiman. Hal ini terlihat sekali dalam Leo dari caranya yang mulai takut berdekatan dengan Remi. Menolak segala ekspresi afeksi intim yang dilakukan Remi.
NMA juga tergambar dari cara Leo tak pernah bisa menangis pasca kehilangan Remi. Ia juga tidak bisa menyampaikan perasaannya, apa pun itu kepada orang-orang terdekatnya dan guru yang sengaja memberikan uluran tangan padanya.
Kekangan hegemoni maskulinitas kemudian juga diciptakan lewat persaingan dan daya saing antar laki-laki. Laki-laki secara tidak sadar dibentuk untuk melihat bahwa hubungan mereka dengan sesama laki-laki harus diciptakan dan dipertahankan lewat kompetisi. Kompetisi adalah dianggap cara yang “benar” untuk mempertahankan maskulinitas mereka dan dalam Close hal ini diperlihatkan dengan keputusan Leo bergabung dalam tim hoki.
Baca Juga: ‘The Woman King’: Angkat Kekerasan Seksual, tapi juga Kaburkan Sejarah
Dalam tim hoki es, untuk pertama kalinya Leo diperkenalkan dengan cabang olahraga yang sangat maskulin. Lekat dengan kekerasan dan kekuatan fisik. Setiap pertandingan ia harus bisa melawan teman-temannya di dalam ring. Menegaskan dominasi atas orang lain lewat kekerasan dan kekuatan fisik. Dan di dalam ruang loker, candaan fisik juga menjadi sesuatu hal yang lumrah.
Terakhir, hegemoni maskulinitas juga dipertahankan melalui objektifikasi seksual terhadap perempuan. Objektifikasi seksual ini penting karena menggarisbawahi bagaimana laki-laki dikonseptualisasikan bukan hanya sebagai sesuatu yang berbeda dengan perempuan, melainkan juga sebagai sesuatu yang lebih baik daripada perempuan. Dalam Close, cara ini tidak begitu mendapatkan porsi screentime yang banyak.
Tetapi justru itu menariknya, hanya dalam satu adegan singkat di mana ujaran seksis yang mengobjektifikasi dilontarkan teman baru Leo yang kemudian ia respons dengan gelak tawa, penonton bisa melihat perubahan signifikan Leo. Ia ingin diterima dalam hegemoni maskulinitas. Dianggap layak untuk diberikan predikat sebagai “laki-laki” sejati.
Akibat yang ditimbulkan dari ketiga cara ini pun sangat fatal. Dalam laporan khusus The National Institute of Mental Health 2020 yang dikutip oleh Vox, maskulinitas yang dilanggengkan dan diinternalisasi oleh laki-laki membuat laki-laki cenderung lebih kesepian dan memiliki keinginan bunuh diri.
Niobe Way, profesor psikologi di New York University dan salah satu Direktur Pusat Penelitian Budaya, Pengembangan, dan Pendidikan di NYU bahkan mengatakan kesepian laki-laki sudah jadi epidemi yang mengkhawatirkan. Dengan maskulinitas yang mengekang, anak laki-laki yang tadinya dapat mengekspresikan hubungan emosional dan cinta satu sama lain, pada saat mereka tumbuh dewasa harus kehilangan kemampuan ini.
Mereka dilatih untuk memilih hubungan di tingkat permukaan saja bahkan mengisolasi diri. Ini membuat kesepian jadi satu-satunya teman akrab laki-laki. Membuat mereka rentan mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental di saat bersamaan.
Dalam Close, kesepian laki-laki diperlihatkan dari raut wajah dan respons Leo pada kelompok pertemanan barunya. Walau Leo sudah memiliki banyak teman baru, ia sama sekali tidak bisa puas dengan pertemanannya. Setiap percakapan atau kegiatan yang dilakukan Leo dengan teman-temannya tak bisa membuat Leo tertawa atau tersenyum dengan tulus. Pada saat ibu Remi menanyakan pertanyaan sederhana apakah dia suka dengan rutinitas barunya sebagai salah satu pemain tim hoki es, Leo pun bahkan kesulitan untuk menjawabnya. Ia kesepian padahal banyak orang di sekitarnya.
Pada akhirnya, dengan durasi 1 jam 44 menit Close berhasil jadi sajian menyayat hati yang melankolis dan reflektif. Film ini membuat kita bertanya tentang posisi kita sebagai masyarakat. Apakah kita salah satu dari pelaku pelanggengan hegemoni maskulinitas ini? Atau kita justru adalah keduanya? Korban dan juga pelaku yang secara tak sadar telah berkontribusi secara sosial memenjarakan laki-laki seumur hidup mereka dalam lingkaran kesepian dan kekerasan tanpa ujung. Hingga tak sedikit ini membunuh mereka secara perlahan.