Nurbaya Dukung Deforestasi, Bukti Maskulinitas yang Terinternalisasi
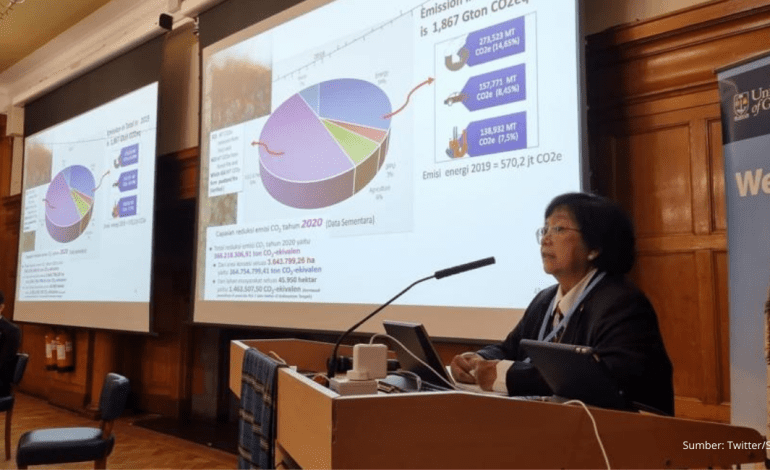
Pada (1/11), Jokowi bersama dengan lebih dari 100 pemimpin negara berjanji akan berada di garda depan untuk mewujudkan target nol-deforestasi sebelum 2030. Sebagai pemimpin negara yang menyumbang sepertiga hutan hujan dunia, komitmen Jokowi ini jadi angin segar untuk masa depan Bumi.
Apalagi mengingat suhu Bumi terus meningkat hingga rerata 1,1 derajat C, merujuk pada laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), badan ilmu iklim terbesar di dunia. Sebuah angka yang belum ada apa-apanya karena dalam skenario terburuk, pemanasan global bisa menyentuh 4,4 derajat C pada 2100. Dampaknya sudah barang tentu lebih buruk dari mencairnya es di kutub Bumi, banjir bandang Eropa, kebakaran hutan Australia dan Amerika Serikat (AS), atau rentetan katastropi di negeri sendiri.
Komitmen Jokowi yang tertuang dalam pidatonya itu mestinya tak akan jadi cuap-cuap belaka jika realitas di Indonesia sejalan dengan pernyataannya. Mengklaim deforestasi turun drastis dalam dua dekade terakhir, padahal deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) jadi 4,8 juta ha (2011-2019), menurut Greenpeace Indonesia dalam laman resminya. Menyebut kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020, faktanya, penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 jika dibandingkan 2019 yang mencapai 296.942 hektar ini adalah angka kebakaran yang luasnya setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta.
Sialnya, salah satu ujung tombak untuk mengurangi deforestasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar justru membuat pernyataan yang bikin sejumlah aktivis lingkungan garuk-garuk kepala. Dalam cuitannya di Twitter, (3/11), politisi Nasdem itu bilang, deforestasi tak bisa jadi alasan menghentikan pembangunan massif di Indonesia.
“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” twit dia di akun @SitiNurbayaLHK.
Menyetop pembangunan atas nama zero deforestation, kata dia, justru mengangkangi amanat Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menetapkan nilai dan tujuan membangun sasaran nasional demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi dalam pernyataannya itu, ia menegaskan keputusan untuk mencapai target nol deforestasi tak tepat dan tak adil. Berbeda dengan Eropa yang menggolongkan upaya penebangan pohon depan rumah sebagai deforestasi, hal ini tak bisa diterapkan di Tanah Air.
“Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya,” kata Siti Nurbaya lagi.
Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia kepada Magdalene, (9/11) menuturkan, pernyataan Nurbaya sangat mengecewakan. “Sangat disayangkan seorang Menteri LHK membenturkan pembangunan nasional dengan upaya menjaga lingkungan. Seharusnya ia memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat, ketimbang berpihak terhadap pembangunan skala besar yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan.”
Dalam hematnya, kebijakan yang terus membuka ruang terjadinya deforestasi adalah bentuk keberpihakan pada bisnis ekstraktif dan berbasis lahan. Padahal kita sama-sama tahu, imbuhnya, tidak ada pembangunan dan pertumbuhan yang bermanfaat di atas lingkungan yang buruk atau Bumi yang tidak layak dihuni.
“Perlu diingat, saat ini kita berada dalam kondisi krisis iklim di atas Bumi yang sama. Kalau tidak ada tindakan yang signifikan untuk menurunkan atau menjaga suhu Bumi di bawah 1,5 derajat C serta mitigasi iklim, maka kehancuran (sudah tentu) di depan mata. Lantas, pembangunan seperti apa yang kita banggakan?” ujarnya.
Baca juga: Tentukan Masa Depan Bumi, COP26 Jangan Dipolitisasi
Perempuan adalah Kelompok Rentan dalam Krisis Iklim
Tahun lalu, penelitian International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyimpulkan, kerusakan alam akibat ulah manusia memicu kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sande, anak 13 tahun asal Malawi dinikahkan paksa orang tua karena keluarganya kekurangan makanan usai lahan pertanian kering kerontang. Di Ethiopia dan Sudan Selatan, saat cuaca panas esktrem, anak-anak perempuan dijual untuk dinikahkan dengan imbalan hewan ternak. Di Bangladesh, perempuan lebih mungkin mati karena banjir bandang lantaran mereka jarang pergi mencari perlindungan di pengungsian darurat.
Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia—daerah termiskin di Indonesia bersama dengan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo—angka penjualan perempuan terbilang tinggi. Menurut laporan Vice, sepanjang 2021 saja, sudah 83 warga NTT pulang dalam peti mati karena terjebak penyalur TKI ilegal. Kemarau berkepanjangan di NTT, akibat krisis iklim, memaksa banyak orang mempertaruhkan nasib hingga ke Malaysia dan negara penyalur buruh migran lainnya. Tak jarang, mereka justru jadi korban perdagangan manusia karenanya.
Apa yang terjadi pada banyak perempuan hari-hari ini akibat ketidaksetaraan gender di berbagai bidang. Perempuan tak punya akses dan kontrol atas sumber daya, akses ke pendidikan dan informasi, pun hak yang sama pada proses pengambilan keputusan. Bahkan, meskipun 43 persen perempuan mengisi sektor pertanian global menurut catatan The Global Netizen (2020), ruang gerak mereka tetap dibatasi di sana-sini. Mereka dilarang meminjam uang untuk pupuk dan peralatan, tak punya hak katas tanah pertanian, kesulitan mengakses pasar untuk menjual hasil panen mereka. Dalam kondisi yang lebih buruk, saat kualitas tanah dan air kian mengkhawatirkan, mereka pula yang pertama dieksploitasi dan jadi korban.
Baca juga: Bencana hingga Kematian di Depan Mata, Kenapa Kita Masih Cuek pada Krisis Iklim?
Sama-sama Perempuan, Nurbaya Tersandera Maskulinitas
Melihat buramnya nasib perempuan, termasuk perempuan Indonesia, di tengah ancaman krisis iklim, pernyataan Nurbaya relatif menyakiti kita. Sebagai pejabat perempuan, apa yang ia lakukan justru kontraproduktif dengan semangat untuk mengarusutamakan kepentingan perempuan.
Nurbaya adalah salah satu contoh bahwa paras maskulin dalam politik itu adalah keniscayaan. Maskulin secara harfiah didefinisikan oleh Merriam Webster Dictionary sebagai sifat-sifat yang hanya mendasarkan pada kualitas atau sifat jenis kelamin laki-laki, menjadi maskulin atau jantan. Konsepsi maskulinitas sangat bervariasi antarbudaya, tetapi ada dua hal yang sama jika merujuk pada Encyclopedia of Applied Psychology (2004) karya Deborah L. Best dan Dustin J. Foster. Dua hal itu yakni: Pada tingkat yang berbeda-beda, setiap masyarakat menetapkan ciri atau tugas berdasarkan jenis kelamin, dan status perempuan lebih rendah daripada lelaki.
Baca juga: Konferensi Iklim Didominasi Laki-laki, Saatnya Tingkatkan Keterlibatan Perempuan
Dalam politik Indonesia, paras maskulin ini sebenarnya tampak dari kebijakan afirmatif 30 persen yang lebih banyak menjadi tempelan, alih-alih mendudukkan perempuan yang benar-benar memperjuangkan hak-hak perempuan. Kalau pun ada politisi perempuan yang benar-benar peduli dengan nasib perempuan, mereka rentan berubah jadi maskulin karena lingkungan yang dari awal sudah didominasi laki-laki.
Untuk konteks krisis iklim di Indonesia pun demikian. Nurbaya yang notabene adalah seorang perempuan, justru membuktikan bahwa ia gagal melawan maskulinitas politik. Ia bisa jadi paham, perempuan adalah kelompok rentan ketika krisis iklim makin gawat. Ia tahu rentetan bencana, dari banjir, longsor, kekeringan ekstrem, kelaparan, seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih sulit dibandingkan laki-laki. Namun, ia memilih untuk pasang badan dan mengambil tempat sebagai agen pendukung pembangunan. Sebuah pembangunan yang meminggirkan keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Bisa jadi ia terseret arus maskulinitas atau jangan-jangan, memang ia sendiri sudah maskulin dari sononya?






















