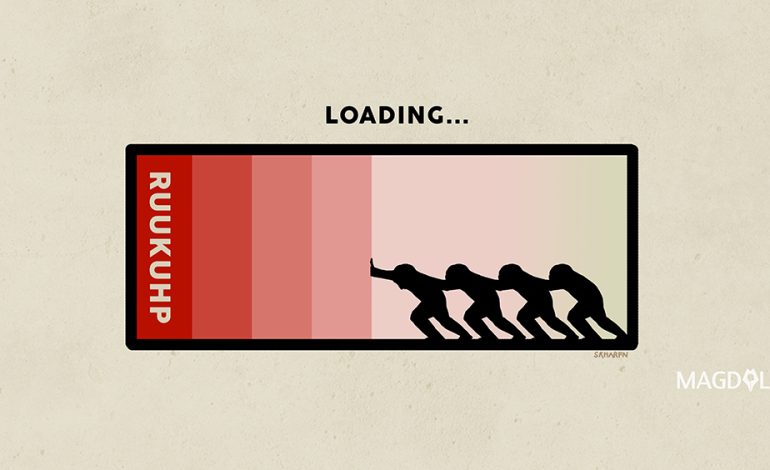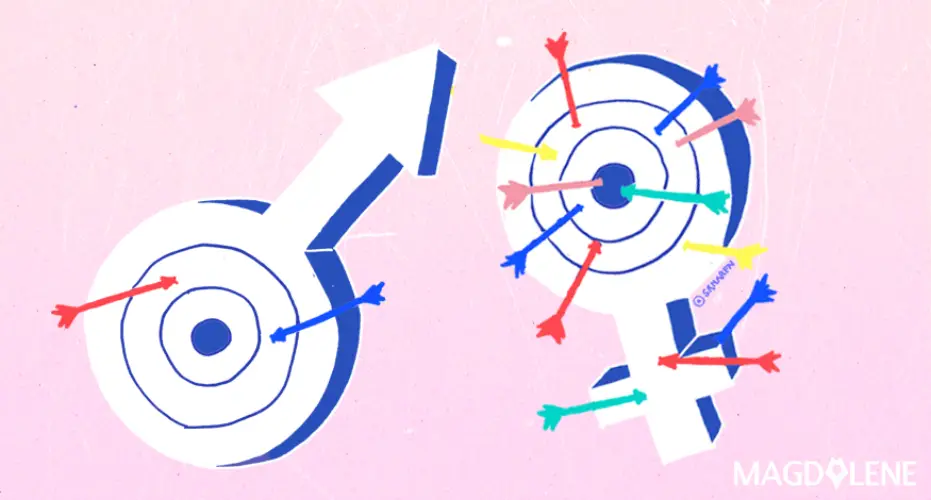Saya Dianggap Kuman, Dilarang Temui Anak’: Kisah ODHA yang Alami Stigma

Kejadiannya sekitar September 2006. Saat itu suami terbaring lemah di salah satu Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit. Karena riwayatnya yang aktif mengonsumsi narkoba jenis suntik, dokter menyarankan ia untuk dicek laboratorium, termasuk cek HIV. Saya setuju.
Beberapa jam kemudian, tenaga kesehatan menghampiri kami dan memberikan sepucuk kertas. Saya membaca isinya, “Ya Tuhan, suami saya positif HIV.” Yang bikin makin nelangsa, kondisi suami saya cukup gawat karena banyak penyakit penyerta.
Mungkin karena itu, dokter juga menyarankan saya dan anak untuk dites HIV. Singkat cerita orang tua membawa anak saya yang masih berusia 4 tahun untuk dicek bersama. Hasilnya, anak negatif, saya positif. Saya bertambah sedih. Ya saya tahu, HIV rentan menular lewat berhubungan seksual dengan mereka yang positif.
Baca juga: Bagaimana Perempuan Indonesia dengan HIV/AIDS Berjuang dengan Stigma
“Tapi bagaimana bisa saya bisa bertahan mengurus anak dan suami, sedangkan kondisi saya begini?”
Akhirnya saya memutuskan untuk menitipkan anak ke kakak suami. Saya sadar, kondisi kakek neneknya tak memungkinkan untuk menjaga anak saya. Sementara, saya fokus pada pengobatan diri dan pasangan.
Suatu hari, ketika sedang merawat suami, kondisi saya melemah. Seluruh persendian lemas, hingga akhirnya keluarga memutuskan untuk melarikan saya ke rumah sakit. Sesuai prediksi, kekebalan saya ambles. Kondisi makin parah karena saya menderita anemia akut. Saya pun dirawat total nyaris satu bulan.
Anehnya selama dirawat itu, tak ada satu pun anggota keluarga yang datang menjenguk. Saya juga tidak sempat mencari tahu kondisi terbaru suami. Yang saya tahu, kondisinya cukup mengkhawatirkan, hingga ia mesti dirawat intensif. Sembari menahan sakit fisik yang tak kunjung lenyap, saya terus mencoba menelepon anggota keluarga suami. Setidaknya agar ada yang bantu mengurus kami selama di rumah sakit.
Nihil. Tak ada satu pun anggota keluarga yang merespons telepon saya. Saya memutuskan untuk meninggalkan nomor kontak kepada perawat di rumah sakit. Siapa tahu suatu hari, ada anggota keluarga yang tergerak menghubungi.
Kondisi saya berangsur membaik. Saya pulang ke ke rumah orang tua di Bogor. baru beberapa menit tiba, mama langsung meluncur dan berbisik, “Yuk, kita siap-siap ke Jakarta lagi. Suamimu sudah pulang.”
Baca juga: Kasus HIV Naik dalam Satu Dekade, Bagaimana Mengatasinya?
Saya merasa kabar ini agak janggal. “Kenapa mereka enggak pulang sekalian bareng saya?”
Namun pertanyaan itu saya simpan dalam hati. Betul saja, sampai di rumah keluarga suami, kejanggalan itu terjawab. Bendera kuning berkibar. Banyak orang berkerumun di sana. Napas saya langsung sesak. Ada jasad suami yang terbujur kaku di tengah ruangan. Dia pergi untuk selamanya, dan saya jadi orang terakhir yang diberi tahu.
Anehnya, dari pertama datang sampai proses pemakaman, saya dilarang untuk keluar kamar oleh keluarganya. Bahkan sekadar datang ke tempat peristirahatan mendiang suami pun saya dilarang. Tentu saja saya kecewa, tapi saya tak bisa protes apa-apa karena tampaknya semua orang tengah sibuk berduka, atau takut pada saya. Entah.
Setelah selesai semua prosesi pemakaman, keluarga besar pun berdiskusi. Hasil diskusi, mulai saat itu saya akan tinggal bersama orang tua. Sementara, anak semata wayang saya harus dititipkan kepada kakak.
“Anak kami yang urus, mulai dari biaya sampai pendidikan dengan catatan dia akan (kami) bawa keluar kota dan kamu enggak boleh menemuinya,” ujar kakak saya.
Saya kaget mendengar keputusan tersebut. Orang tua saya muntab. Saya kemudian mendesak anggota keluarga agar mengizinkan saya untuk menemui anak. Dengan wajah tak ikhlas, mereka mengizinkan. Nahasnya, belum sempat melangkah masuk, sudah terdengar suara teriakan dari si empunya rumah.
“Tunggu saja di sana. Anakmu sudah rapi.”
Saya dilarang masuk rumah. Kakak ipar dengan langkah ragu menyemprotkan cairan pembunuh bakteri ke arah saya. Sementara, anak cuma diam tak melihat wajah saya. Hati ibu mana yang tak hancur, anak di depan mata, tapi saya bahkan tak bisa memeluknya.
Sepanjang jalan itu, kami akhirnya tak banyak bicara. Bahkan hari-hari setelahnya, saya mulai depresi, trauma berat karena perlakuan mereka. Saya pun mengurung diri, berpikir untuk berhenti minum obat anti-retroviral (ARV). Di titik itu, saya merasa seperti sampah dan aib dalam keluarga.
Baca juga: Bagaimana Menjadi Positif HIV Membuka Mata Saya
Di saat saya makin terpuruk, mama menegur, “Sampai kapan kamu seperti ini? Kamu mau anakmu menjadi yatim piatu? Banyak orang di luar sana dengan kondisi yang lebih prihatin, tapi mereka tetap semangat. Ingat hidupmu tanggung jawabmu bukan orang lain.”
Kata-kata itu seperti petir yang membuat saya menemukan kembali semangat hidup. Jujur saya akui, saat itu memang tidak banyak informasi seputar HIV yang bisa didapat.
Akhirnya saya mencoba menyibukkan diri dengan mendatangi beberapa lembaga yang berkecimpung di isu HIV. Saya mulai aktif dalam kegiatan orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), menghadiri acara kelompok dukungan sebaya (KDS), saling berbagi pengalaman, penguatan, dan penerimaan status. Dari situ, pengetahuan tentang HIV bertambah sedikit demi sedikit. Demikian halnya dengan kepercayaan diri saya yang tumbuh berkat adanya support system di komunitas ODHA.
Karena semangat yang tinggi untuk lebih baik lagi, saya pun ditawari untuk bekerja di salah satu lembaga sebagai peer support (pendamping sebaya). Ini adalah titik balik saya dan pengalaman mahal yang selalu saya syukuri sampai hari ini.
Sudah 16 tahun saya hidup dengan HIV dan stigma itu tetap ada. Namun setidaknya, sekarang saya tak cuma diam dan pasrah menghadapi stigma, tapi sudah berjuang menghapus itu lewat komunitas saya.
Ini adalah artikel keenam dari series tulisan pelatihan jurnalis komunitas IAC di Bali, Oktober 2022. Baca artikel lainnya yang terbit setiap Rabu di Magdalene.co.
- Orang dengan HIV/ AIDS juga Bisa Berdaya
- Surat untuk Mendiang Puput: ‘Matahari di Sana Lebih Cerah, Nak!’
- Perempuan HIV di Tengah Bencana
- KTP untuk Transgender Sejak Kapan?
- Putus Nyambung ARV: Separuh Badan Lumpuh tapi Saya Harus Tetap Tumbuh
- Saya Positif HIV, Menikah, Punya Anak, dan Hidup Bahagia