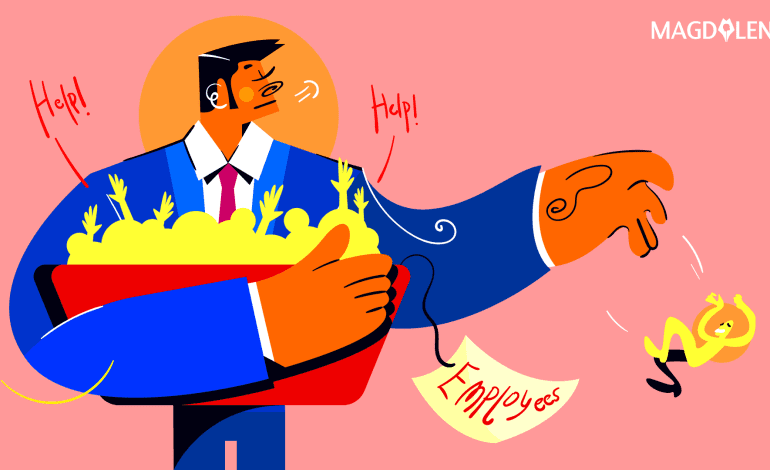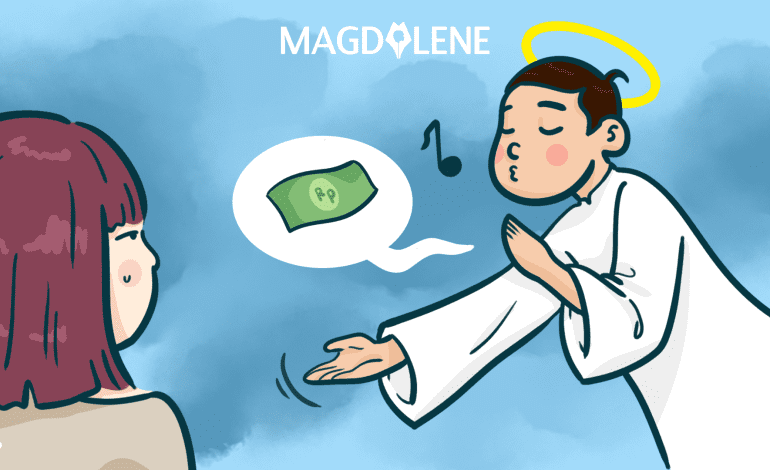Atas Nama Baik Pesantren Jombang, Kekerasan Seksual Dipinggirkan

Perempuan di bawah umur asal Jawa Tengah, IP mendatangi kantor Women’s Crisis Center (WCC) Jombang pada 2017. Kepada tim WCC Jombang, ia mengaku telah diperkosa anak pemilik Pondok Pesantren Majma’al Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah, Mochammad Subchi Azal Tsani alias Gus Bechi. Setelah diskusi, WCC sepakat untuk mengumpulkan bukti dan melaporkan kasus ini ke kepolisian, tapi IP tak pernah kembali hingga Direktur Women’s Crisis Center Jombang, Ana Abdillah melupakan kasusnya.
Baru pada 2018, Rani, salah satu saksi mata di Pesantren Shiddiqiyyah melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan Bechi pada tiga santri perempuan di sana. Kekerasan itu terjadi saat santriwati mengikuti seleksi tenaga kesehatan di klinik Pesantren Shiddiqiyyah pada 2017. Bechi yang sedianya ikut meresmikan klinik itu meminta santri perempuan untuk mengikuti sesi wawancara khusus di tengah hutan dan jauh dari keramaian. Di sana, Bechi meminta santri perempuan untuk melepas pakaiannya dan mengikuti ritual mandi kemben. Rani tak ikut ritualnya, tapi beberapa temannya datang dan jadi korban.
Mereka pun melapor kepada Kepolisian Resor Jombang, tapi dengan alasan kurang bukti, kasus dihentikan penyelidikannya pada 21 Oktober 2019. Rani dan kawan-kawan tak menyerah, mereka bahkan menyinggung nama IP yg juga jadi korban Gus Bechi sebelumnya. Usut punya usut, Bechi telah memberikan uang tutup mulut puluhan juta pada IP, tapi akhirnya ia ikut menjadi pelapor kasus kekerasan seksual tersebut. Rani dalam hal ini mengalami kekerasan fisik, kepalanya dibenturkan, ia dan keluarga juga diancam bakal dibunuh karena vokal membela korban hingga medio 2021 ini.
Baca juga: Menertawakan Kesucian
Jika ditotal ada enam korban kekerasan seksual Gus Bechi yang beberapa di antaranya didampingi oleh WCC. Dalam diskusi Instagram Live, (23/7), Ana Abdillah menceritakan peliknya mendampingi korban kekerasan seksual di pesantren seperti di Shiddiqiyyah. Yang paling utama adalah ganjalan di bidang hukum yang relatif belum cukup memihak korban (hingga berita ini ditulis, belum ada putusan hukum berkekuatan tetap soal hukuman penjara untuk pemerkosa itu). Selain itu, melakukan tugas pendampingan kekerasan seksual pada korban juga rentan memicu trauma berlapis. Apalagi kasus kekerasan seksual di pesantren Jombang ini dilakukan sejak 2017 dengan disertai berbagai ancaman jika membuka mulut.
Dalam hal ini, Anna bercerita, pelaku yang anak kiai itu menggunakan modus operandi memanipulasi korban dengan dua doktrin. Pertama, doktrin vagina yang kurang lebih berbunyi: “Vagina perempuan adalah jalan mulia, karena dari situlah pemimpin dilahirkan. Melakukan hubungan seksual adalah perbuatan mulia. Ayah ngeman sampean (Ayah peduli padamu). Makanya vagina sampean jangan sampai dimasuki orang lain.”
Berikutnya, Gus Bechi juga mengaku pada para santri perempuan, ia menguasai ilmu metafakta yang membuatnya bisa menikahi siapa saja. Adalah beruntung bagi santri perempuan yang bisa diajak untuk menikah (baca: berhubungan seks) dengannya. Dalam liputan Tirto, 2020 disebutkan, Bechi mendaku diri sebagai “penjaga lingkaran emas” dengan masing-masing memiliki satu “sayap”. Sayap yang dimaksud ia adalah istri.
Sebenarnya kasus yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyyah Jombang ini cuma satu dari fenomena gunung kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam tersebut. Di Jawa Tengah, Direktur Legal Resources Cencer untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM ) Jawa Tengah, Fatkhurozi memaparkan, dari 2009 sampai 2012, sebanyak 85 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kekerasan yang dimaksud meliputi sodomi, perkawinan paksa, perkawinan di bawah umur, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain.
Jika mengetik kata kunci kekerasan seksual di pesantren secara acak, Google akan menghadirkan beragam kasus, mulai dari sodomi 15 anak yang dilakukan pimpinan pesantren dan guru mengaji di Kabupaten Lhokseumawe, Aceh. Tahun lalu, guru pesantren Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, JM (52) juga diamuk karena diduga memperkosa para santriwati. Di Bantul, Yogyakarta, kasus kekerasan seksual dialami oleh beberapa santri yang dipaksa melakukan seks oral oleh salah satu gurunya.
Baca juga: Problem Pembahasan Kekerasan Seksual dalam Fikih Islam
Saat Atas Nama Baik Pesantren Disalahartikan
Saya menghubungi Nurul Bahlul Ulum, aktivis Cherbon Feminist untuk meminta komentarnya soal ini. Kepada Magdalene, (27/7) ia mengamini, pesantren belum jadi ruang aman untuk santri-santrinya, termasuk santri perempuan. Ini ironis, katanya, mengingat kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang-orang yang paling fasih bicara narasi Islam, tapi justru paling depan menzalimi perempuan dan anak.
Dalam hematnya, ada dua sebab utama kenapa pesantren belum jadi ruang aman. Pertama, adanya pola pikir seragam yang menyatakan perempuan cuma sebatas objek seksual.
“Sepengalamanku menjadi santri, kami tak pernah diajarkan bahwa perempuan bisa berdaya sendiri. Perempuan adalah objek seksual katanya, tak ada kesalingan dalam hubungan seksual. Padahal mestinya, dasar keIslaman adalah kerelaan bersama, ini berlaku pula dalam hubungan seksual,” ujarnya.
Pola pikir patriarkal itu makin kekal gara-gara teks Alquran, Hadis, dan buku-buku ditafsirkan secara tekstual oleh kiai, guru, dan santri-santri di pesantren. Ini sekaligus jadi faktor kedua. Menurut perempuan yang juga aktif di Mubadalah itu, pesantren kerap meminggirkan konteks di mana teks-teks Islam itu lahir. Misalnya, mereka bisa saja melarang perempuan sebagai pemimpin dalam Islam, padahal konteks sejarahnya bisa dilihat di era Ratu Kisra yang diberi privilese memimpin ketika penerus trah monarki masih berusia kanak-kanak. Contoh lainnya, kata dia, banyak kiai yang meminta santrinya buru-buru menikah, karena buat sebagian dari mereka, menikah sama dengan upaya melegalkan seks. Celakanya lagi, di pesantren, Fikih Islam juga kerap dipahami secara tekstual semata.
“Perempuan haram menolak hubungan seks dengan suami jika tak ingin dilaknat sampai Subuh, perempuan harus begini dan begitu. Narasi keislaman yang ditafsirkan ala kadarnya itu yang digunakan sebagai alat bagi para lelaki brengsek untuk melegitimasi kekerasan seksual yang mereka lakukan,” ucapnya pada Magdalene.
Tak ada yang salah salam teks-teks Islam, hanya saja Nurul mengritisi metode pemaknaannya yang nir-perspektif gender. Padahal, kata dia, interpretasi teks itu bisa saja disertai dengan perspektif keadilan gender agar perempuan jadi lebih aman. “Penting buat kiai, ustaz, ustazah untuk punya perspektif keadilan gender. Patriarki langgeng dan abadi di pesantren, tapi bisa dilakukan melalui penyadaran berkesinambungan. Kasih edukasi ke pengurus pesantren, kasih juga edukasi ke santrinya agar tidak dimanipulasi. Ini memang tanggung jawab besar,” ungkapnya.
Baca juga: 5 Cara Atasi Bias Gender di Pondok Pesantren
Selain itu, usaha lain untuk memutus rantai kekerasan seksual di pesantren adalah dengan membuka diri bagi lembaga pendampingan, konseling, dan pelatihan gender di kota setempat. Lembaga ini juga bisa menjadi wadah bagi santri-santri yang mengalami kekerasan seksual dan mencari ruang aman. Pun, mereka membantu para korban untuk memulihkan trauma karena kekerasan seksual yang dialami.
“Atas nama baik pesantren, kita tak boleh menutupi kasus kekerasan seksual. Ayo turun tangan, jangan cuma bisa ngajak ngaji dan memaknai secara tekstual saja. Menurut saya, keberanian mengangkat kasus ini bukan untuk mencoreng nama pesantren, sebab jika tetap menutup mata, maka kasus akan terus buram,” katanya lagi.
Dorong Pengesahan UU PKS
Menghapus kekerasan seksual di pesantren membutuhkan kehadiran negara, kata Nurul. Karena itulah negara mau tak mau harus memastikan perlindungan bagi siapa saja, termasuk korban kekerasan seksual di pesantren.
“Kita enggak bisa lagi menunggu, mau menunggu berapa banyak korban lagi di pesantren, mau menunggu berapa banyak lagi korban anak dan perempuan di mana-mana. Sahkan RUU PKS,” tandasnya.
Menurut dia, RUU PKS jadi satu-satunya harapan di bidang hukum agar perlindungan dan pemulihan terhadap korban bisa diselenggara.
“Kasus korupsi itu masalah tapi itu tak memicu trauma besar. Berbeda dengan kekerasan seksual yang lebih gila dari korupsi, traumanya seumur hidup. Nah, RUU PKS diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk menghukum pelaku sekaligus melindungi dan memulihkan korban,” kata dia.
Bukankah penjagaan terhadap jiwa raga ini diajarkan oleh Islam demi kemaslahatan umat manusia. Jika itu terus ada, maka kita sedang mengingkari prinsip itu dan kezaliman bakal terus langgeng nanti,” tutupnya.