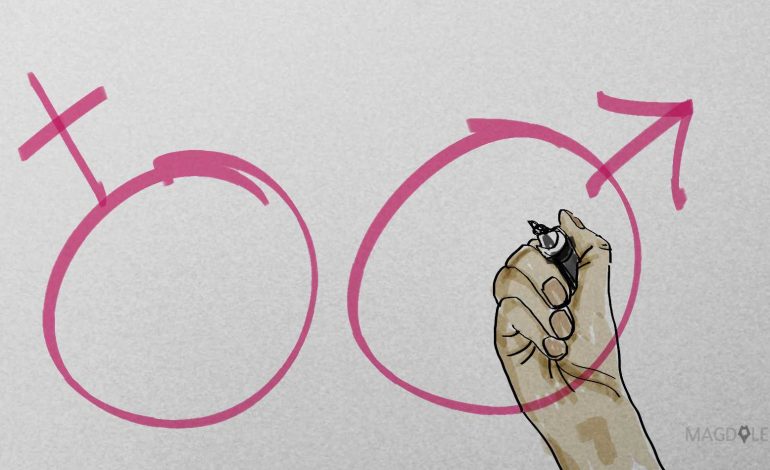Adakah Ruang Bagi LGBT untuk Beragama?

Jumat siang itu, azan salat Jumat berkumandang dan “Randi” bergegas berjalan kaki menuju masjid yang tak jauh dari tempat kerjanya di Jakarta Timur. Namun sesampainya di sana, ia menjadi gelisah dan jantungnya berdebar lebih cepat akibat isi khotbah yang disampaikan sang ustaz.
“Saat itu ustaz mengatakan kalau LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transeksual) itu dosa, menjijikkan, berbahaya, dan dilaknat Allah. Bahkan layak untuk ‘dibasmi’,” ujar pemuda berusia akhir 20-an itu kepada Magdalane.
Di tengah situasi yang menurutnya “mencekam” itu, Randi tetap duduk diam, tak beranjak pergi, dan tetap mendengarkan khotbah yang disampaikan ustaz hingga selesai. “Seperti membeku,” katanya.
Sebagai gay muslim, ia merasa bahwa tempat yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesejukan di tengah banyaknya seruan kebencian, diskriminasi, dan persekusi terhadap kelompoknya, justru tidak mengakui eksistensi dirinya sama sekali.
“Di khotbah itu juga dibilang kalau ibadah LGBT itu tuh enggak diterima. Boro-boro ibadah kita diterima. Ibarat kata dianggap manusia aja enggak,” kata Randi, yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Selatan.
Meski demikian, peristiwa dua tahun lalu itu tidak membuat Randi berhenti salat dan melakukan ibadah lainnya. Bedanya, ia sudah sangat jarang ke masjid dan lebih memilih salat di kamar kost sendiri.
Menurut Randi, kita sebagai manusia tidak pernah tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak diterima. Itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan kita, ujarnya.
“Tujuan gue beribadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Diterima atau enggaknya, sebagai muslim gue tetap menjalankan ibadah,” tambahnya lagi.
Pengalaman yang serupa terjadi pada “Nina”, seorang pemeluk agama Kristen yang sejak sekolah dasar sudah menyadari bahwa dia memiliki ketertarikan terhadap sesama perempuan.
Ia mengenang saat ia masih remaja belasan tahun di Yogyakarta, pada 2005, dan salah seorang pendeta di gereja mengaitkan LGBT dengan manusia-manusia yang menjatuhkan diri mereka ke dalam lubang dosa.
“Saat itu aku merasa marah dan gelisah, meski aku tetap mendengarkan khotbah sampai selesai. Tapi setelah khotbah itu, aku tidak pernah ke gereja lagi,” ujar Nina, penulis lepas berusia 30 tahun yang kini tinggal di Jakarta.
Meski demikian, Nina tetap mengakui agama Kristen sebagai kepercayaannya dan masih meyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan pembawa terang.
“Menguatkan iman tidak harus dengan selalu rajin ke gereja. Gereja memang gedung yang dibuat untuk ibadah. Dan menurutku, ibadah bisa dilakukan berdua saja antara aku dan Tuhan Yesus,” ujarnya.
Pemahaman agama tanpa konteks
Kisah Randi dan Nina hanya segelintir saja dari kelompok LGBT atau kelompok minoritas gender yang memiliki kebimbangan atas relasi mereka dengan agama, terlepas dari apa pun agama yang dianut mereka.
Sentimen anti-LGBT di Indonesia beberapa tahun belakangan ini juga tak lepas dari berbagai pandangan keliru terhadap kelompok LGBT. Dalam konteks agama sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas agama arus utama dan para pemuka agama kerap kali menyudutkan dan bahkan mengobarkan kebencian terhadap kelompok LGBT.
Sementara itu negara, bukannya melindungi kelompok minoritas, malah membiarkan situasi ini dan bahkan menjadi pemicu ketakutan publik. Minggu ini, misalnya, pemerintah kabupaten Cianjur bahkan meminta masjid untuk berkhotbah tentang bahaya LGBT setiap khotbah Jumat.
Lalu bagaimana dengan hak kelompok LGBT – yang faktanya sudah menghadapi berbagai tantangan mulai dari stigma buruk, persekusi, diskriminasi, serta diasingkan – untuk beragama? Bagaimana dengan mereka yang membutuhkan penopang dan perlindungan yang seharusnya dihadirkan agama sebagai sandaran bagi umatnya?
Akademisi Islam Lailatul Fitriyah, yang akrab dipanggil Laily mengatakan, pendirian ulama yang bertentangan dan tidak humanis terhadap kelompok LGBT, disebabkan oleh keyakinan yang memandang proses terbentuknya hukum Islam dan proses terbentuknya tradisi Islam sebagai sesuatu yang tertulis di atas batu.
“Asumsinya adalah, bahwa kalau sudah menjadi hukum Islam, itu kemudian tidak bisa lagi diubah. Bahwa hukum Islam yang berasal dari abad ke-11 misalnya, harus sampai sekarang tetap seperti itu,” kata Laily kepada Magdalene.
“Padahal, kalau kita belajar sejarah atau hukum Islam, proses terbentuknya sangat bergantung pada dinamika masyarakat,” tambahnya.
Ia memaparkan, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada sekitar abad 16, dinamika masyarakat menjadi patriarkal, dan hukum yang ditulis pada saat itu menjadi lebih opresif terhadap perempuan ketimbang hukum yang bersumber di abad ke-8 atau ke-7, saat Nabi Muhammad baru meninggal.
“Jadi hukum itu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat, sifat masyarakat saat itu. Sayangnya, apa yang terjadi sekarang, asumsinya adalah kalau namanya hukum Islam, berarti sudah tidak bisa diubah, dan tidak bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat,” tambah Laily.
Ada asumsi di kalangan ulama bahwa dalam Alquran sudah tertulis adanya larangan secara positif terhadap homoseksualitas dan hal tersebut tidak bisa lagi diperdebatkan.
Ia menjelaskan bahwa ada asumsi di kalangan ulama bahwa di dalam Alquran tercantum larangan secara positif terhadap homoseksualitas, dan hal tersebut tidak bisa lagi diperdebatkan.
“Padahal, sebagian besar dari isi Alquran adalah norma. Dan norma adalah sesuatu yang lebih umum, bukan lagi hukum yang mutlak,” tutur Laily, mahasiswi program doktoral di Departemen Teologi, Universitas Notre Dame, AS.
Terkait narasi Nabi Luth yang sering digunakan sebagai landasan untuk menyerang kelompok LGBT, menurut Laily, ayat-ayat yang disebutkan itu bukan hanya soal homoseksualitas, dan tidak ada penyebutan bahwa ada praktik homoseksualitas secara konsensual yang dilakukan oleh masyarakat saat itu.
“Yang paling jelas disebutkan dalam narasi itu adalah bagaimana praktik seksualitas masyarakat saat itu sangat berdasarkan pada asas koersif. Artinya, pesannya bukan lagi pada homoseksualitas, tapi bagaimana praktek seksual yang dilakukan oleh masyarakat Nabi Luth saat itu adalah praktik seksual yang koersif, tidak konsensual, dan tidak ada persetujuan, alias pemerkosaan,” kata Laily, yang sedang dalam proses memperoleh gelar Doktor dari Departemen Teologi di Universitas Notre Dame, Amerika Serikat.
“Pesan itu yang kemudian dihilangkan ketika bicara tentang narasi Nabi Luth sebagai dasar untuk melarang homoseksualitas,” tegas Laily.
Pesan dari narasi ini juga tidak disambungkan dengan pengetahuan sosio-historis. Jadi hanya berlandaskan Alquran saja, tanpa dilatarbelakangi dengan konteksnya seperti apa, tambahnya.
Allah merengkuh kecairan
Sementara itu, dalam lensa Kristen, Pendeta Suarbudaya Rahardian dari Gereja Komunitas Anugerah di Jakarta Pusat, mengatakan bahwa LGBT adalah sebuah keragaman, orientasi seksual, dan ekspresi gender yang secara teologis dihayati sebagai anugerah Allah.
“Kami sebagai gereja percaya bahwa Tuhan yang diyakini dalam agama Kristiani adalah Tuhan yang mendobrak norma-norma heteronomativitas,” kata Suarbudaya dalam wawancara dengan Magdalene.
Ia memaparkan, Roh Kudus adalah bagian dari keilahian yang diyakini dalam agama Kristen, itu juga direpresentasikan dalam Alkitab sebagai entitas yang disapa sebagai Sophia, sebagai kebijaksanaan yang bersifat feminin, tapi di bagian lain juga dia disapa sebagai maskulin.
“Jadi kecairan penyebutan ini memang mewarnai Allah trinitas. Itu yang memberikan orang Kristen sebuah imajinasi bahwa kalau Allah saja merengkuh kecairan itu, apalagi manusia yang Dia ciptakan. Itu sebabnya kita punya kesimpulan, di luar heteronormativitas, LGBT harus diberi ruang untuk diakomodasi oleh gereja, karena Allah pun juga demikian,” kata Suarbudaya.
Ia sendiri diutus oleh oleh Lembaga Misionaris Baptis dari Inggris untuk membuat satu komunitas di Jakarta bagi kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalkan oleh gereja.
Suarbudaya merasa prihatin dengan gereja-gereja konservatif yang melakukan persekusi teologis dan moral terhadap LGBT, kelompok marginal yang seharusnya wajib didampingi gereja.
“Gereja-gereja arus utama harus bersuara untuk LGBT. Karena hari-hari ini, LGBT, apalagi di Indonesia, adalah kelompok yang sangat rentan. Kelompok yang ditindas, dianiaya, dan dikriminalisasi dan dipersekusi,” ujarnya.
Dalam konteks Alkitab sendiri, Suarbudaya mengatakan akar-akar homofobia dalam agama Kristen dan teks-teks yang sangat heteronormatif, homofobik, bahkan memberi nasihat eksplisit untuk menganiaya kelompok LGBT, harus diluruskan.
“Teks kitab suci tidak ditulis secara langsung untuk pembaca di semua tempat dan semua zaman. Pada hakikatnya, teks kitab suci ditujukan pada satu masa tertentu, di situasi geopolitik tertentu, sosial tertentu, kepada orang tertentu,” katanya.
Maka dari itu, sebagai orang Indonesia di abad-21, kita tidak bisa membacanya seolah-olah itu ditujukan buat kita, dan perlu menggunakan lensa-lensa tertentu untuk bisa memahaminya.
“Menurut saya, kalau mau fair, jika membaca teks Alkitab secara harafiah tentang LGBT yang tertulis di kitab Imamat, ‘Laki-laki yang tidur dengan laki-laki harus dirajam sampai mati.’ Kalau anda membaca ayat seperti itu, maka anda harus juga membaca teks di pasal yang sama dimana ketika seorang anak yang membantah orangtuanya, ia harus dirajam pakai batu sampai mati,” ujar Suarbudaya.
“Maka tidak mungkin ada orang Kristen konservatif yang mau merajam anaknya sampai mati karena anaknya membantah untuk cuci piring, misalnya,” lanjutnya.

Hak warga negara yang sama dan terjamin
Suarbudaya mengatakan, teks dalam alkitab tidak bisa dibaca apple to apple dengan kondisi masyarakat saat ini. Lensa yang harus dipakai adalah lensa Yesus Kristus, apa yang Yesus katakan mengenai sebuah isu jika ia masih hidup sekarang.
Ia mengatakan, dalam kitab Roma 1, ada ayat favorit yang sering dikutip oleh kelompok-kelompok anti-LGBT, yakni “Orang akan meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya dan menyala-nyala birahi dengan sesama laki-laki.”
Ide tentang hubungan seksual yang menyala-nyala dengan sesama laki-laki itu dilarang Rasul Paulus karena dua hal. Pertama, karena ide tentang hubungan seksual sesama jenis itu merusak relasi yang sudah ada, yaitu relasi pernikahan.
“Bagaimana ada seorang pria yang meninggalkan loyalitas kepada istrinya yang sudah sah, dengan hubungan ekstramarital, hubungan di luar nikah, dalam hal ini homoseksual,” ujar Suarbudaya.
“Tapi itu juga bentuk relasi yang akan dikutuk kalau terjadi pada relasi heteroseksual, jadi poinnya bukan tentang homoseksualnya,” tambahnya.
Pada zaman Kekaisaran Yunani, ada kata arsenakotai yang identik dengan penyembahan Dewi Artemis di kuil-kuil dengan melakukan hubungan seks anal dengan laki-laki muda dan di bawah umur.
Gereja-gereja arus utama harus bersuara untuk LGBT. Karena hari-hari ini, LGBT, apalagi di Indonesia, adalah kelompok yang sangat rentan. Kelompok yang ditindas, dianiaya, dan dikriminalisasi dan dipersekusi.
“Paulus melarang praktik itu karena jelas itu bukan konsensual, hubungan yang eksploitatif. Seperangkat larangan terhadap hubungan homoseksual itu harus dipahami dari pranata-pranata apa yang terjadi saat itu. Celakanya, hari ini kita membaca teks itu dilepaskan dari konteksnya,” katanya.
Pada Juni 2015, Gereja Komunitas Anugerah Salemba mendeklarasikan secara terbuka menerima rekan-rekan LGBT, dan bukan membuat mereka “menjadi hetero” melainkan menerima seutuhnya keadaan mereka.
Sementara itu, dalam instrumen hukum di Indonesia melalui hak asasi manusia (HAM), Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara, mengatakan bahwa hak beragama kawan-kawan LGBT tidak berbeda dengan warga negara yang lain.
“Mereka memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing masing tanpa rasa takut akan ancaman, intimidasi atau teror dari kelompok lain,” kata Beka ketika dihubungi Magdalene.
“Saat ini, Komnas HAM pada posisi meminta pada negara melalui aparatnya untuk menghormati sekaligus melindungi kebebasan beribadah dan berkeyakinan kawan-kawan LGBT sehingga tidak mengurangi hak asasi mereka.”
Artikel ini merupakan bagian pertama dari serial liputan mengenai “Keberagaman Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, didanai oleh fellowship Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ardhanary Institute.