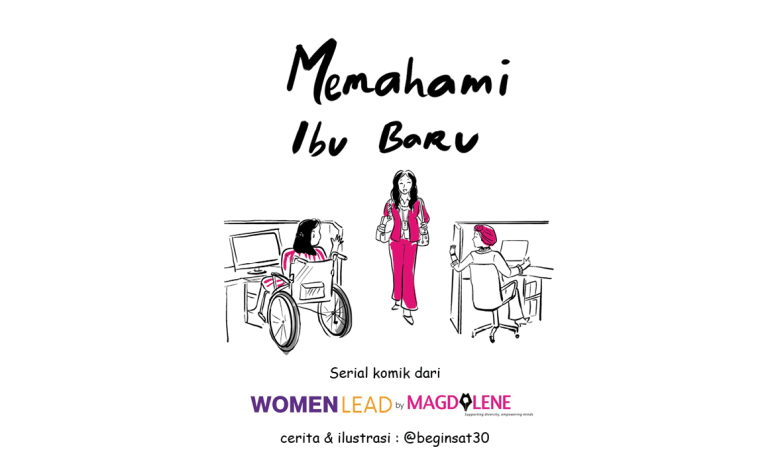Banyak Versi Film Cinderella, Apakah Kisahnya Cukup Feminis?

Dari semua dongeng putri-raja klasik, cerita Cinderella lah yang selalu mengalami pembaruan versi di layar kaca. Mulai dari kartun, real live action dengan sentuhan fantasi, hingga versi modern yang dibungkus sebagai film remaja.
Beberapa waktu lalu, koleksi film Cinderella juga dikabarkan akan bertambah. Kali ini sepatu kaca yang masyhur itu digunakan oleh penyanyi Camila Cabello. Melihat cuplikan foto maupun trailer film, pengisahannya juga tidak jauh dari dongeng fantasi di negeri kerajaan nun jauh di sana. Meskipun begitu, sutradaranya Kay Cannon menggadang-gadang akan memberikan versi Cinderella yang relatable untuk semua perempuan.
“Perubahan paling besar ada pada Cinderella dan Pangeran karena Cinderella menjadi sosok alfa dan Pangeran sebagai sosok beta dalam cerita. Dan hal itu bukan yang normalnya terjadi; dia (Pangeran) berevolusi. Dalam cerita ini, semua orang di sekitar Cinderella belajar darinya dan berubah,” ujarnya dikutip dari Entertainment Weekly.
Upaya pemberdayaan karakter perempuan di cerita dongeng, seperti yang dilakukan Cannon, sejatinya bukan sesuatu yang baru. Beberapa tahun belakangan ini Disney merilis film anak-anak dengan karakter perempuan yang tidak butuh penyelamatan laki-laki, seperti Frozen (2013), spin-off The Sleeping Beauty, Maleficent (2014), dan Moana (2016). Dengan merilis film itu, Disney seakan-akan memperbaiki kesalahan mereka yang menampilkan kisah princess tidak berdaya bertahun-tahun lalu.
Jika ditilik lagi, pesan cerita Cinderella versi populer saat ini yang juga dari Disney, yaitu segala kemalangan akan hilang dengan kecantikan yang memikat pangeran, memang sangat tidak relevan. Dikabarkan media, Cinderella-nya Cabello dan Cannon dengan sentuhan feminisme itu akan rilis bulan ini. Namun, jika mengingat Cinderella yang terus menerus mengalami pembaruan dan usaha pemberdayaan industri film, muncul pertanyaan: apakah kisah Cinderella tidak pernah mencapai posisi feminis, sehingga harus terus dibuat ulang?
Baca juga: Merebut Takdir bersama Elsa, Maleficent, dan Merida
Apakah Ada Versi Film Cinderella Feminis?
Kita memang familier dengan cerita Cinderella dengan ibu peri yang memberi gaun indah, tikus-tikus yang disulap jadi kuda, dan kereta labu yang hilang pukul 12 malam. Namun, sebelum dikemas oleh Disney tahun 1950-an, cerita Cinderella sudah ada berabad-abad yang lalu.
Era Mesir kuno sebelum Masehi, misalnya, memiliki kisah tentang perempuan budak dari Yunani bernama Rhodopis dengan sepasang sepatu emas. Suatu hari, satu dari sepatu itu dicuri oleh elang yang kemudian menjatuhkannya ke paha seorang Firaun. Dia kemudian menganggapnya sebagai pertanda dari Dewa Horus dan mencari siapa pemilik sepatu tersebut untuk dinikahi.
Selain itu, di Tiongkok ada juga kisah semacam Cinderella pada abad kesembilan, yakni kisah Ye Xian atau Yeh Shen dengan ikan ajaib yang dapat mewujudkan impiannya. Sayangnya, ikan itu bernasib malang karena dibunuh oleh ibu tirinya. Ada juga Ye Xian yang dikisahkan memiliki tulang ikan ajaib yang memberikannya gaun dan sepatu emas. Pada akhirnya dia juga menikah dengan seorang raja berkat sepatu itu.
Tidak berhenti di situ, pada abad ke-17 di Italia muncul cerita pendek berjudul Cenerentola tentang pemaksaan pernikahan seorang perempuan dengan seorang raja.
Alexander Sergeant, akademisi film dari University of Portsmouth, mengatakan kisah Cinderella sebenarnya mengandung banyak potensi feminis. Hal itu dilihat dari cara kisahnya disampaikan dari mulut ke mulut oleh sesama perempuan di jalur perdagangan Silk Road atau Jalur Sutra. Singkatnya, Cinderella adalah cerita untuk dan dari perempuan.
Baca juga: Cruella dan Cara Disney Menulis Ulang Karakter Antagonis Perempuan
Narasi lewat berkisah itu semakin didukung karena perempuan saat itu tidak memiliki akses untuk menulis. Temanya pun merefleksikan budaya yang ‘mengecilkan’ mereka, yaitu tentang kekerasan perempuan di ranah domestik dan kerja keras tanpa ampun. Sergeant menyebutnya sebagai cerita tentang keinginan perempuan yang ditolak masyarakat.
Namun, tentu saja potensi untuk dikembangkan menjadi cerita yang feminis lenyap karena campur tangan laki-laki. Versi Cinderella yang kita kenal saat ini dikemas oleh penulis asal Perancis, Charles Perrault pada 1697. Versi Perrault disebut serupa dengan Cenerentola, tapi dengan sentuhan berbunga yang menghilangkan agensi Cinderella. Saat ini Perrault juga dikenal sebagai sosok yang memopulerkan cerita Cinderella.
“Adaptasi ini secara tidak sadar merefleksikan nilai misogini, menelanjangi cerita dari potensi feminisnya dan membuatnya tentang sihir, bukan representasi,” tulis Sergeant dilansir dari The Conversation.
Mencari Pemberdayaan dalam Film
Pada 1812, pendongeng The Brothers Grimm kemudian mengadopsi cerita Perrault dengan twist horor: Mata saudara tiri Cinderella dipatuk burung sampai berdarah-darah. Belum lagi si tokoh utama harus memotong jari kaki biar kakinya muat di sepatu kaca. Setelahnya, Cinderella pun mulai masuk layar kaca ditandai dengan versinya Disney-nya. Tahun 1955 muncul live action Cinderella pertama dengan judul The Glass Slipper yang terus berkembang sampai tahun 1990-an. Salah satu yang paling progresif, dalam hal keberagaman ras adalah msikal Cinderella (1997). Film itu dibintangi musisi kulit hitam Brandy sebagai Cinderella, pangeran yang diperankan aktor Filipina-AS, Paolo Montalban, dan Whitney Houston sebagai ibu peri.
Pada era 2000-an muncul Cinderella modern lain seperti Another Cinderella Story (2008) yang dibintangi Selena Gomez dengan cerita Cinderella ingin menjadi penari pop yang sukses. Ada juga A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011) dengan aktris Lucy Hale sebagai Cinderella yang ingin jadi penyanyi sukses. Sayangnya, versi film modern dan remaja ini suka nanggung karena Cinderella dibuat berdaya, tapi terlalu banyak plot hole dan alur klise yang memunculkan pertanyaan apakah sosok Cinderella itu berdikari. Bagaimana pun, memang rasanya sulit menilai sebagai feminis karena masih tersangkut oleh kekangan kisah versi Perrault, walaupun film itu tidak ada unsur magisnya.
Baca juga: Putri Duyung Disney Berkulit Hitam, Kenapa Tidak?
Dilemma yang serupa juga ada pada Cinderella (2015) yang di-remake oleh Disney. Ella (Lily James) digambarkan sebagai sosok berdikari lewat kemampuannya berkuda dan berani untuk ‘berhadapan’ langsung dengan Pangeran Kit (Richard Madden). Kisah cintanya dibuat setara ketika Ella memang meminta untuk dilihat sebagai dirinya bukan kecantikannya. Perubahan ini tentu saja dibarengi pasar yang semakin melek tentang isu sosial.
Namun, lagi-lagi Ella mengalami sedikit langkah mundur ketika kebebasan dari siksa ibu tiri dicapai melalui jalur menikahi pangeran. Bukannya feminis anti-cinta, tetapi sejak awal Ella punya kebebasan untuk meninggalkan rumahnya yang penuh kekerasan. Alasan selama ini dia menolak ‘pergi’ dari keluarga jahatnya adalah karena ia ingin menjaga rumah peninggalan orang tuanya. Tapi toh ketika ada tawaran menikah, dia memilih jalur pembebasannya dengan tinggal di kastil bersama Pangeran Kit, alih-alih membebaskan dirinya bertahun-tahun lalu. Ella berujung dengan Cinderella Complex, luluh di tangan protagonis laki-laki atas nama membangkitkan ‘nostalgia’ masa kecil.
Bisa dibilang versi Cinderella yang cukup berdaya ada pada Cinderella-nya Anne Hathaway, Ella Enchanted (2004). Tidak hanya menyentil isu ‘berat’ seperti segregasi, sosok Ella dibuat pemberani dan mau melawan orang yang jahat. Sayangnya, dia menjadi lemah karena hal ‘teknis’, yaitu dikutuk menjadi anak penurut. Namun, dia menyelesaikan masalahnya, yaitu sikapnya yang mau-mau saja disuruh melakukan hal aneh, dengan caranya sendiri tanpa bantuan ibu peri. Selain itu, dia juga mendukung Pangeran Char menggulingkan raja yang zalim.
Berkaca dari film-film itu, potensi feminis Cinderella yang ‘dihilangkan’ bisa dibangkitkan kembali tergantung cara pengemasannya dan tujuan industri film. Apakah dibentuk untuk keuntungan komersial semata atau memang mencari perubahan dan memberikan representasi. Selain itu, versi Cinderella yang diproduksi juga tidak melulu harus lewat lensa kulit putih atau penggambaran Cinderella yang sangat western mengingat asal muasalnya secara global.
Namun, jika dilihat lebih lanjut, Cinderella terus mengalami makeover tidak hanya karena menjadi feminis. Pesan tentang perbuatan baik dibalas dengan hal-hal positif dan si jahat (walaupun digambarkan sangat satu dimensi) mendapatkan karma memberikan rasa puas tersendiri. Selain itu, formula from rags to riches yang magis (dari miskin jadi kaya) semacam mewujudkan impian semua orang.