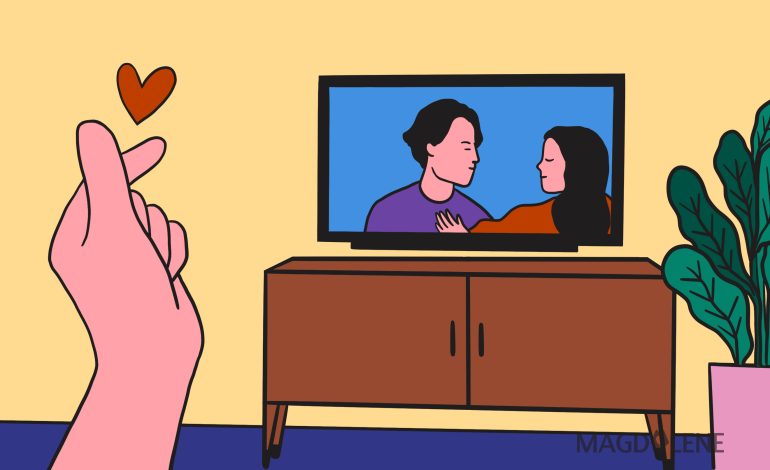Setahun Setelah Pandemi, Beban Perempuan Korban Kekerasan Kian Berat

Kekerasan berbasis gender adalah salah satu dampak pandemi yang paling terabaikan, dengan ketersediaan layanan yang tidak memadai. Studi global menunjukkan bahwa situasi pandemi sangat berbahaya bagi perempuan. Setelah setahun lebih COVID-19 mewabah, korban kekerasan seksual di Indonesia menghadapi tantangan lebih besar untuk menyelesaikan kasusnya dan mendapat keadilan.
Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan protokol penanganan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19. Meski demikian, masih banyak perempuan korban yang tidak dapat menjangkau layanan ini.
Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada ruang nyata, namun juga terjadi di dunia virtual seiring adanya penggunaan gawai secara intensif untuk kegiatan daring. Korban kekerasan berbasis gender online (KGBO) meningkat drastis pada masa pandemi ini.
Makin Banyak Perempuan Alami KDRT
Presiden Joko Widodo “Jokowi” mendeklarasikan darurat kejahatan seksual di Indonesia sejak 2016. Namun hingga kini, produk hukum perlindungan korban yang lebih baik masih belum ada.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hingga kini belum juga disahkan. Artinya, pemerintah sendiri belum serius menangani kejahatan seksual.
Antara 2017 dan 2020, sebelum pandemi COVID-19 melanda, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan. Pada masa pandemi, situasi lebih merugikan lagi bagi perempuan. Perempuan, baik yang bekerja publik maupun ibu rumah tangga, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mereka sangat rentan mengalami KDRT. Mereka terpaksa berada bersama dengan pelaku kekerasan untuk waktu yang lebih lama.
Baca juga: Kekerasan terhadap Perempuan di NTT: Peningkatan dan Kendala Penanganan
Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum memiliki payung hukum perundang-undangan yang secara khusus terkait penanganan korban kejahatan seksual secara komprehensif.
Gunung Es Data Kasus
Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan bahwa terjadi penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021. Ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan lembaga penyedia layanan dalam penanganan dan pendokumentasian kasus selama pandemi. Padahal pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam masa pandemi 2020.
Akses korban terhadap berbagai layanan bantuan seperti bantuan hukum, bantuan psikologis, dan bantuan sosial juga menjadi terhambat.
Hasil survei Komnas Perempuan menyebutkan bahwa rumah tangga yang pengeluarannya meningkat memiliki peluang semakin sering mengalami kekerasan —terutama kekerasan fisik dan seksual. Ini mengindikasikan persoalan ekonomi berpotensi memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga pada masa pandemi.
Bagi banyak perempuan, kebijakan pembatasan sosial lebih merugikan daripada penyebaran virus itu sendiri karena mereka secara psikologis dan fisik terbelenggu oleh pelaku kekerasan di dalam rumah mereka. Sementara, korban kesulitan untuk melapor.
Stigma Sosial Hambat Korban Kekerasan Seksual Bersuara
Korban kekerasan seksual rentan mengalami stigma sehingga mereka cenderung takut dan trauma melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya.
Stigma yang cenderung diterima korban berasal dari lingkungan sosial, bahkan di institusi tempat mereka memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual untuk memiliki perspektif korban.
Korban kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki juga cenderung mendapat stigma sosial karena anggapan umum bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Padahal korban kekerasan seksual tidak pandang gender. Laki-laki menjadi korban kekerasan seksual adalah nyata adanya.
Pada banyak kasus, korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan jika pelaku kekerasan merupakan kerabat dekat. Dengan dalih menjaga nama baik keluarga, korban kekerasan seksual dibungkam di dalam rumah untuk tidak bersuara.
Situasi pandemi semakin memperburuk ketimpangan gender. Stigma terhadap perempuan semakin parah. Sikap menyalahkan korban juga membuat mereka sulit bersuara.
Pembuktian Kasus yang Rumit
Tanpa ada pandemi saja, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual menghadapi banyak hambatan mendapatkan keadilan.
Pembuktian kasus menjadi hambatan dalam pengungkapan kekerasan seksual di masa pandemi. Korban menjadi cenderung diam dan tidak melapor karena minimnya alat bukti kasus. Misalnya, kasus kekerasan gender berbasis online yang sudah masuk ke pengadilan pun menghadapi kendala penanganan karena sulitnya proses pembuktian yang menggunakan forensik digital.
Contoh lain, misalnya, kasus kejahatan seksual pemerkosaan yang korbannya laki-laki dewasa, pembuktian kasusnya cukup rumit karena pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman.
Laki-laki korban pemerkosaan tidak memiliki akses keadilan, serta mengalami trauma yang besar.
Hambatan korban dalam mengakses keadilan semakin berlapis ketika terduga pelaku adalah pejabat publik/tokoh publik atau atasan di tempat kerja. Takut dipecat, takut dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik, dan lainnya menjadi pertimbangan yang sulit bagi korban.
Baca juga: Rilis Sikap: Melawan Pandemi Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan
Terbatasnya Akses Layanan
Akses layanan bagi korban kekerasan seksual pada masa pandemi ini menjadi terbatas. Pada satu sisi, korban kekerasan harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak penyedia layanan. Namun pada sisi lain, petugas layanan yang menangani mengalami dilema dan harus membuat antisipasi yang cermat agar tidak memperburuk penularan COVID-19.
Stres, jaringan sosial dan perlindungan sosial yang buruk, dan akses ke layanan yang terbatas dapat memperburuk keadaan risiko kekerasan bagi perempuan.
Korban kekerasan berbasis gender berada dalam risiko tinggi mengidap masalah kesehatan yang parah dan pulih dalam waktu lama, termasuk kematian karena luka-luka yang mereka derita atau tindakan bunuh diri.
Sementara, banyak perempuan banyak yang tidak menggunakan layanan lapor secara daring karena kurangnya literasi dan akses digital.
Langkah dari Komunitas Terkecil
Pemerintah semestinya melakukan langkah-langkah dan tindakan minimum secara terkoordinasi untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender pada masa darurat (pandemi).
Pertama, pemerintah bisa mempercepat akses dan literasi digital perempuan. Penting untuk menyebarluaskan kesadaran dalam menggunakan layanan berbasis digital, misalnya call center pengaduan seperti di negara lain yang memungkinkan siapa saja melaporkan kejadian darurat kekerasan berbasis gender.
Selain itu, juga penting menata ulang kebijakan pemerintah dalam mendukung percepatan akses digital hingga ke pelosok desa di Indonesia.
Kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan seksual pada level desa atau kelurahan. Kekerasan seksual yang terjadi pada masa pandemi ini kemungkinan lebih banyak terjadi di ruang lingkup komunitas terkecil atau keluarga.
Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran pemerintah lokal (desa/kelurahan/RT/RW) untuk menangkal kekerasan seksual terjadi di wilayahnya. Desa/kelurahan tidak hanya bersiaga terhadap COVID-19 saja, tetapi juga terhadap kekerasan seksual di lingkungannya.
Ketiga, pemberlakuan hukum adat. Pada kejadian kejahatan/kekerasan seksual di ranah adat, komunitas harus menegakkan hukum adat seberat-beratnya bagi pelaku dan memperhatikan kebutuhan pemulihan korban. Dalam pemberlakuannya, hukum adat perlu beriringan dengan hukum pidana.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.