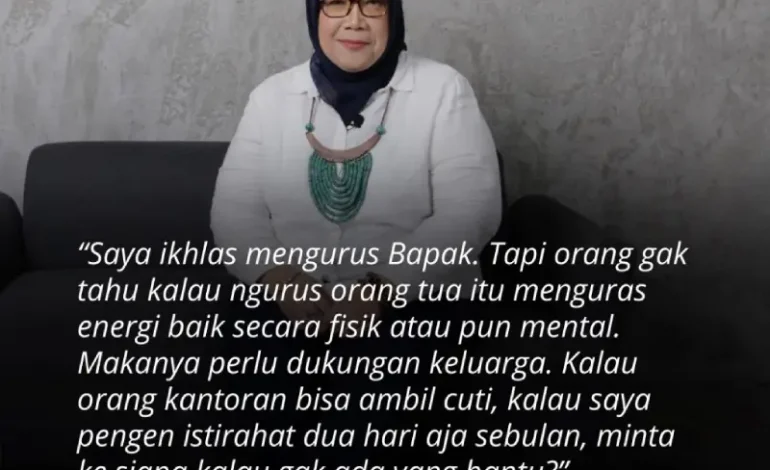Baliho ‘Mama Semok’ dan ‘Mama Muda’: Benarkah Ini Objektifikasi dan Seksualisasi Diri?

Berkendara di sekitar kawasan pintu tol Cisalak-Sukmajaya, Depok, Jawa Barat belakangan jadi berbeda. Menuju pemilihan umum atau pemilu 2024, kawasan ini berubah total jadi “surganya” para calon anggota dewan legislatif (caleg). Baliho dari berbagai ukuran yang berisi jargon menyelimuti kawasan ini dari segala penjuru.
Dari puluhan baliho itu, ada satu yang menonjol. Baliho itu milik Lydia Octavia, caleg DPRD Kota Depok, Dapil Sukmajaya yang terpasang sejak pertengahan Januari. ‘Mamah Semok’ Siap Melayani Depok begitu bunyi jargon kampanye Lydia. Jargon itu diletakkan persis di sebelah potret pribadinya dengan sosok Kaesang dan Jokowi berada di belakang.
Tak perlu menunggu lama, baliho ‘Mama Semok’ Lydia pun dapat banyak kecaman. Banyak warganet terutama mereka pengguna X (dulu Twitter) berpendapat Lydia telah mengobjektifikasi bahkan menseksualisasi diri sendiri demi kepentingan politik pribadi. Ada yang bahkan mengatakan cara Lydia ini telah mempermalukan R.A Kartini yang telah memperjuangkan hak perempuan agar bisa teredukasi.
Lydia bukan satu-satunya. Perempuan caleg lain dari partai yang sama juga kena hujat karena baliho yang dinilai bermuatan objektifikasi dan seksualisasi diri. Dia adalah Desi Dwi Jayanti, caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil Jakarta Pusat. Dapat temukan di jalan protokol Jakarta Pusat, salah satunya di kawasan Stasiun Gondangdia dan Masjid Cut Meutia, Desi menyematkan jargon ‘Mamah Muda’ dalam balihonya.
Dalam cuitan beberapa warganet, jargon ‘Mamah Muda’ ini dinilai cuma mengandalkan appearance alias tampilan saja. Hal ini bagi sebagian warganet dipahami sebagai kecacatan politik. Desi mengobjektifikasi dirinya padahal tidak punya program atau visi misi yang jelas. Mereka pun jadi bertanya-tanya jika seandainya Desi terpilih apa yang kemudian jadi fokus pelayanan publiknya.
Baca Juga: Bentuk Diskriminasi Gender di Tempat Kerja dan Cara Mengatasinya
Benarkah Intensinya Objektifikasi dan Seksualisasi Diri?
Nuansa objektifikasi dan seksualisasi memang selalu jadi isu nomor satu yang dibahas warganet ketika mereka melihat baliho Lydia dan Desi. Di satu sisi kerasnya respons masyarakat setidaknya kata Rizka Antika, peneliti bidang gender, HAM, dan demokrasi menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terutama di ranah digital terkait isu gender.
Akan tetapi tingginya kesadaran ini tidak bisa berhenti dimaknai dalam satu sisi. Perlu juga mengetahui intensi asli langsung dari kedua caleg ini, untuk tahu apakah benar ini cuma seksualisasi dan objektifikasi semata. Pasalnya, berbeda dari asumsi masyarakat, baik Lydia dan Desi menyatakan intensi mereka sejak awal bukan untuk mengobjektifikasi atau menseksualisasi diri.
Lydia dalam wawancaranya bersama Magdalene mengungkapkan pemakaian kata semok dalam jargon kampanyenya datang bukan dari kependekan kata seksi dan semok. Sebaliknya, kata semok yang ia rujuk berasal dari pipi tembam atau pipi chubby seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Ia yang adalah seorang ibu dua anak pemilik pipi tembam memutuskan untuk memakai kata ini sebagai jargon yang kemudian ia beserta tim desainnya ramu menjadi akronim baru dari kalimat “Siap Melayani Depok”. Melayani dalam penuturan Lydia juga bukan hadir dalam konotasi negatif, tetapi hadir lewat tanggung jawab Lydia nantinya jika terpilih sebagai anggota dewan di Komisi A harus bisa siap kapanpun melayani rakyat.
Desi di sisi lain memakai jargon ‘Mamah Muda’ karena identitas ibu muda sudah melekat dalam diri perempuan berusia 36 tahun ini. Ia menikah ketika masih usia 22, karena itu sering dipanggil mama muda oleh teman-teman dan kenalannya.
Tak hanya itu, karena partai yang mengusungnya juga terkenal disi oleh anak-anak muda, Desi pun memantapkan langkah untuk menyematkan identitas pribadi serta identitas partainya untuk melancarkan isu prioritas kampanye yang ia punya. Isu perempuan dan anak.
“Mamah pasti ibu. Mamah pasti perempuan. Dan mereka peduli dengan anaknya. Ini jadi isu prioritas yang aku bawa jadi dengan Mamah Muda, Tagline dan target audience sudah match. Makanya ketika turun ke wilayah yang kumpul juga emak-emak. Mereka merasa terwakilkan dengan ‘Mamah Muda’ ini,” jelasnya.
Mama muda secara spesifik imbuh Desi sebenarnya juga tidak selamanya berkonotasi negatif. Buat sebagian orang, termasuk di dalamnya teman, kolega muda generasi Z atau gen Z serta ibu-ibu di akar rumput yang ia temui kata mama muda berati ibu muda yang berdaya.
“Jadi tidak semua orang bersepakat kalau ini adalah hal yang negatif,” jelasnya.
Adapun reaksi negatif berada di luar kuasa mereka. Masyarakat punya pemahamannya sendiri terhadap diksi-diksi yang dipilih Lydia dan Desi. Sebab itu, reaksi-reaksi negatif yang pasti akan muncul telah mereka antisipasi dari awal, masuk dalam pemetaan kampanye jauh-jauh hari. Pengakuan ini pun memantik pertanyaan baru.
Mengapa Lydia dan Desi sebagai perempuan caleg tetap memilih gimik jargon ini walau tau bakal ada reaksi negatif dari masyarakat?
Jawabannya sederhana. Reaksi-reaksi negatif yang mereka sudah antisipasi ini punya potensi besar di baliknya, yaitu meningkatkan level popularitas yang harapannya bisa dipanen menjadi tingginya tingkat elektabilitas atau menjaring suara pemilih.
Potensi ini lalu jadi bagian strategi kampanye mereka. Lydia yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang psikologi misalnya memahami bahwa sesuatu yang dilempar ke publik baru akan mendapat atensi kalau diberikan stimulus-stimulus tertentu, dalam hal ini yang berbau atau berkonotasi negatif.
“Semok kan dipahami orang-orang sebagai singkatan seksi dan montok. Sudah ada stigma atau pelabelan negatif di situ sama dengan kata melayani. Karena saya backgroundnya psikologi saya paham perlu ada stimulus untuk menarik perhatian. Jadi ini memang sebuah pacingan untuk menggebrak Depok,” kata Lydia.
Sebelum dirinya viral karena baliho ini, Lydia sempat mencetak baliho tanpa jargon ‘Mama Semok’. Dalam baliho itu ia lebih menonjolkan program kerjanya, PSI Berkarir. Program kerja khusus untuk membagikan informasi lowongan kerja termasuk tips and trick menghadapi wawancara, pengembangan diri serta pengetahuan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sayangnya, baliho itu tidak mendapatkan atensi apa-apa dari publik.
“Pas pakai baliho PSI berkarir enggak viral. Dianggap biasa aja sama masyarakat, tapi pas dijadikan akronim luar biasa responnya. Bahkan pasca viral aku dapat subsidi dari relawan Prabowo Gibran dan dari beberapa organisasi,” tutur Lydia.
Sama halnya dengan Lydia, Desi juga mengetahui ada pemaknaan khusus dari mama muda di masyarakat apalagi mereka yang aktif di media sosial. Dalam pencarian kata mama muda di media sosial seperti X contohnya yang muncul selalu bermuatan seksual dengan gambar perempuan muda berpose dan berbaju seksi. Tau akan pemaknaan ini, Desi berusaha memberikan narasi tandingan kepada masyarakat soal mama muda. Sosok yang menurut Desi lebih berdaya dan tidak hanya dilekatkan dalam peran domestiknya.
Desi juga jujur narasi tandingannya ini bagian strategi kampanye di tengah sengitnya pertarungan politik yang ada. Jika ia tidak bisa memberikan sesuatu yang unik atau baru, ia bakal cepat tergilas apalagi ia tidak punya modal kapital yang besar. Ia bukan artis atau pejabat yang sudah punya nama.
“Dapil itu cuma ada 12 kursi, padahal ada total 216 caleg DPRD DKI dapil 1 (Jakarta Pusat) yang akan berlaga di Jakarta pusat. Gimana bisa stand out dengan orang yang punya nama. Makanya ini bisa dibilang ini USP atau unique selling point. Digunakan untuk menimbulkan curiosity,” kata Desi.
Ia lalu menambahkan kesengajaan untuk tidak mencantumkan visi misi juga dalam baliho juga strategi. Desi melihat visibilitas balihodi jalan hanya sedikit, mungkin hanya satu atau dua detik saja. Kalau ia membubuhkan visi misi yang panjang dan padat dalam baliho, masyarakat juga akan kesulitan memahaminya secara utuh. Sebaliknya, taktik yang dilakukan desi adalah dengan memakai jargon ‘Mamah Muda’ dengan membubuhkan call to action menuju website.
“Biar orang yang tadi cuma sekedar kepo bisa lebih lega membaca apa sih isu prioritasnya. Tapi ya yang penting mereka curious dulu. Dapet respons banyak, karena bad marketing is a marketing as well,” tambah Desi.
Baca Juga: Mundurnya Jacinda Ardern dan Tantangan Perempuan Pemimpin
Susahnya Menjaring Suara
Jargon-jargon kontroversial yang diusung Lydia dan Desi sebagai strategi kampanye nyatanya menyimpan realita pahit di baliknya. Nurul Amalia Salabi, peneliti dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan memang ada faktor sistemik dari sistem pemilu yang dipilih, yaitu proporsional daftar caleg, terhadap munculnya tagline-tagline yang dalam kacamata feminis seksis. Dalam sistem ini, caleg dituntut harus bisa membuat perbedaan antara dirinya dengan banyak sekali caleg lainnya.
“Semua caleg, di tengah ada ratusan ribu caleg di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota, ditambah DPD, mereka harus memikirkan self-branding yang mudah diingat pemilih. Jadi, tidak heran mereka memilih tagline-tagline yang bombastis, lucu-lucuanan, bahkan terkesan seksis,” jelas Amalia.
Tugas perempuan caleg, tambah Rizka juga lebih berat lantaran permasalahan bias gender masih membayangi mereka. Mengutip studi Aspinall, ahli politik Indonesia asal Australia pada 2021, sebanyak 62 persen responden di Indonesia setuju atau sangat setuju kalau laki-laki lebih memiliki kapasitas menjadi pemimpin politik dibandingkan perempuan. Dalam penelitian itu, Aspinall juga menunjukkan kalau responden perempuan menganggap perempuan, apalagi yang memiliki anak, tidak sepantasnya memegang jabatan publik.
“Pilihan politik yang bias gender ini pun sayangnya juga diperkuat dengan interpretasi agama, sehingga membuat PR perempuan caleg untuk menggaet suara publik semakin susah,” imbuh Rizka.
Belum cukup pada pandangan bias gender pemilih, perempuan caleg juga harus dihadapkan dinamika pemilih Indonesia yang masih didominasi oleh pemilih emosional. Berdasarkan studi peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati pada pemilu 2014- 2019 jumlah pemilih rasional konsisten hanya berkisar 5 hingga 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan selebihnya pemilih emosional.
“Dengan dinamika pemilih seperti ini ya enggak heran perempuan caleg playing the game by its rule. Apa yang dilakukan kak Lydia untuk grab attention (menarik perhatian) ini banyak dilakukan, apalagi attention span masyarakat Indonesia juga semakin sedikit. Jadi daripada mengeluarkan cost banyak ya udah dengan cara ini saja,” kata Rizka.
Strategi jargon-jargon kontroversial pun semakin tidak bisa dihindari karena perempuan caleg juga acapkali dihadapi keterbatasan dana kampanye. Baik Lydia atau Desi mengungkapkan sumber dana kampanye mereka sebagian besar murni berasal dari tabungan atau penghasilan mereka sendiri. Sisanya dana itu datang bukan dalam bentuk dana uang, tetapi langsung seperti spanduk, baliho, atau produk UMKM buat dipakai ketika acara-acara.
“Jadi harus dihemat-hemat karena masih mengandalkan penghasilan bulanan pribadi sebagai buruh pabrik dan dibantu dari usaha suami sebagai tukang galon. Subsidi tidak ada dari partai,” ucap Lydia.
Apa yang terjadi pada Lydia dan Desi nyatanya memang jamak dialami perempuan caleg. Perludem dalam studi mereka soal dana kampanye perempuan caleg pada 2019 misalnya menemukan sebagian besar dana kampanye berasal dari kantong pribadi perempuan caleg, sedangkan donasi dari partai politik, perseorangan, maupun kelompok sangat minim.
Jika pun donasi didapatkan, jumlahnya sangat sedikit dan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki akses dan jejaring politik yang cukup kuat. Sedangkan akses pendanaan dari publik dalam bentuk uang hampir tidak berjalan secara signifikan, layaknya dukungan pendanaan dalam wujud fresh money dari partai politik yang tidak ada sama sekali.
Perludem juga mencatat akses subsidi dana kampanye dari negara melalui pembiayaan kampanye di iklan media massa cetak/elektronik, alat peraga, dan bahan kampanye tidak sepenuhnya mampu meminimalisir tingginya dana kampanye yang dikeluarkan oleh calon. Bahkan terdapat juga perempuan caleg yang tidak mengetahui akses pendanaan negara untuk beberapa jenis kampanye tersebut.
Terakhir, yang tak kalah pentingnya meski Lydia dan Desi tidak secara spesifik mengalami kendala ini, banyak partai politik kata Amalia tidak memberikan ruang yang luas bagi perempuan pengurus partai untuk tampil lebih banyak di ruang publik.Padahal menurut Amalia, ketika seseorang tidak dikenal publik, dia akan lebih sulit untuk terpilih karena masyarakat tidak mengenal dia.
“In berdasarkan riset Burhanuddin Muhtadi di mana semakin tidak dikenal seseorang, semakin dia butuh uang banyak untuk memperkenalkan diri. Padahal dari riset Perludem yang ada, mayoritas perempuan caleg kesulitan membiayai dana kampanye mereka,” tuturnya.
Baca juga: Rancangan Perda Anti-LGBT: Lagu Lama di Musim Pemilu
Upaya Merebut Ruang?
Tak mengherankan jika kemudian lapisan kendala yang dialami perempuan caleg berakibat langsung pada menurunnya jumlah perempuan di daftar calon pada pemilu 2024 yang kata Amalia juga bakal mengancam keterwakilan perempuan di parlemen. Hanya satu partai politik, yaitu PKS, yang mengajukan perempuan minimal 30 persen di semua dapil. PKB jadi partai dengan dapil terbanyak yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, yaitu 29 dapil. Setelahnya ada PDIP dengan 26 dapil. Demokrat 24 dapil. Golkar Gerindra 22 dapil.
“Ini berpotensi mengurangi jumlah perempuan di parlemen. Dari tren yang ada, semakin banyak jumlah perempuan yang dicalonkan, semakin banyak juga yang terpilih. Nah, di 2024 jumlah caleg perempuan berkurang persentasenya, maka dikhawatirkan jumlah perempuan yang teprilih juga akan berkurang,” jelas dia lagi.
Realitas ini pun jadi semacam refleksi buat kita bersama. Jargon-jargon yang dianggap mengobjektifikasi dan menseksualisasi diri yang dipakai perempuan caleg tak lagi bisa dimaknai hitam putih. Keputusan untuk memakai jargon-jargon ini lahir dari kesadaran penuh perempuan. Ini datang dari agensi mereka sendiri untuk mendobrak sistem yang merugikan mereka dan dominasi politik maskulin yang sudah mandarah daging. Maka tendensi jargon-jargon itu pun berubah menjadi upaya merebut ruang.
Rizka pun berpesan kendati demikian, perempuan caleg tidak bisa selamanya mengandalkan cara yang sama. Boleh bagi perempuan caleg menggunakan cara ini sebagai entry point, tapi ada tugas yang kemudian lebih utama dilakukan. Tugas untuk membangun kampanye berkelajutan yang substansial.
“PR besar selanjutnya adalah membangun keberlanjutan campaignnya. Bagaimana bisa memanfaatkan engagement dia beyond dari gimmick atau negative clickbait lebih penting agar masyarakat notice you as women have the ability dan credibility as caleg,” jelas Rizka.
Di sisi lain, tambah Amalia, perempuan caleg juga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Permasalahan sistemik tidak bisa mengandalkan solusi individual semata. Sehingga kata Amal ada berapa solusi yang bisa diambil. Pertama, peningkatan bantuan keuangan partai oleh negara, yang dikhususkan untuk peningkatan kapasitas perempuan pengurus partai, termasuk strategi kampanye yang efektif dan inklusif.
Kedua, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kehadiran perempuan di pemerintahan. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) bisa membuat panduan ceramah kepada para pemuka agama, untuk mempromosikan agama yang ramah pada perempuan.
Ketiga, merevisi UU Parpol, yang bisa mereformasi partai politik dengan mewajibkan partai politik memiliki minimal 30 persen pengurus perempuan pada kepengurusan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Harapannya dengan solusi ini, perempuan tak lagi harus mengalami berbagai kendala hanya untuk bisa duduk di kursi anggota dewan. Kursi yang baik Lydia dan Desi ungkap mereka perjuangkan untuk membuat daerah mereka masing-masing lebih maju.