Kesepian dan Isolasi: Musuh dan Tema Utama Karya Sastra Jepang
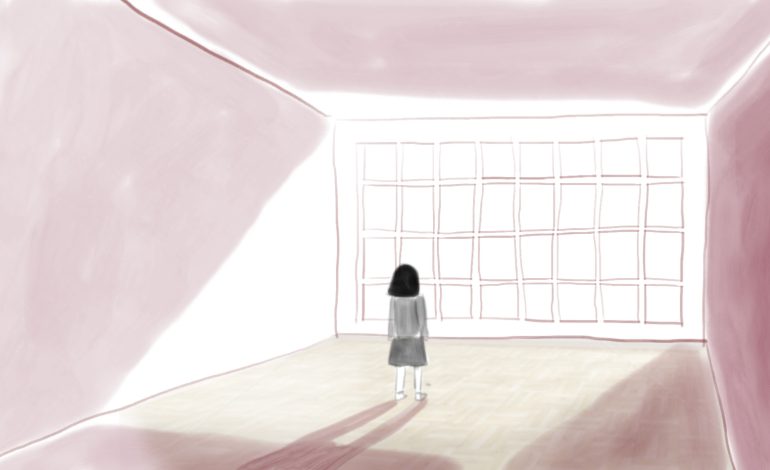
Kasus kematian dan bunuh diri akibat isolasi dan kesepian terus menjadi masalah utama di Jepang. Selama pandemi, kasus kematian akibat hal tersebut meningkat karena masyarakat mengalami tekanan mental maupun finansial yang bertambah, terutama pada perempuan yang merasa semakin terisolasi.
Untuk mengatasi masalah itu, Februari lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, menunjuk Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian. Ia berpesan agar Tetsushi mempromosikan berbagai aktivitas yang mempererat ikatan masyarakat dan mencegah bertambahnya jumlah masyarakat yang terisolasi.
Motoyuki Shibata, penerjemah dan editor untuk majalah sastra kontemporer Jepang, Monkey, mengatakan bahwa kesepian merupakan hal “normal” yang dirasakan masyarakat Jepang sehari-hari. Karenanya, penulis Jepang memiliki unsur rasa kesepian di dalam hasil karyanya. Tetapi, hal itu tidak dianggap sebagai tema yang spesial atau unik karena kesepian adalah hal yang dinilai sangat biasa di Jepang.
Ia mengatakan kesepian bisa terjadi di mana saja, bahkan kesepian itu juga terjadi ketika bersama keluarga karena ikatan itu tidak menentukan kedekatan dan menjadi jaminan seseorang bisa lepas dari kesepian.
“Misalnya, pada karya Sayaka Murata yang menunjukkan hubungan keluarga, tetapi karakter dalam buku tersebut meragukan ikatan dengan keluarganya dan merasa nyaman ketika bersama dirinya sendiri,” ujar Shibata pada diskusi Reading The People of Asia (Japan)– Loneliness and Japanese Literature, pada Makassar International Writers Festival 2021 (25/6).
Ia mengatakan, rasa ketertarikan masyarakat internasional, khususnya Indonesia, pada karya literatur Jepang tentang perasaan kesepian dan isolasi disebabkan karena hal tersebut akan menjadi masalah besar untuk negara lain di masa depan. Namun, untuk saat ini Jepang yang menghadapi isu tersebut secara drastis kemudian membahasnya dalam karya sastra kontemporer.
“Naskah kontemporer Jepang mengangkat tentang isolasi dan hubungan keluarga yang semakin menipis, misalnya Natsume Soseki yang menggambarkan hubungan keluarga dengan negatif,” kata Shibata.
Baca juga: MIWF 2021 Angkat Isu Kesenjangan Sosial Indonesia Timur dan Barat
Murata, penulis novel Gadis Minimarket, mengatakan kesepian bisa dirasakan semua orang di negara lain dan tidak menjadi fenomena khusus di Jepang. Selain itu, ia merasa iri dengan negara lain, terutama negara Barat, yang bebas mengekspresikan emosi dan perasaan dengan gestur tubuh, seperti berpelukan.
“Seperti yang disebutkan oleh Shibata, karya saya membahas tentang kesepian dalam keluarga. Topik tentang kesepian ini juga ada di setiap negara dengan bentuknya sendiri. Menurut saya kesepian yang ada di Jepang bentuknya lebih ‘mulus’,” ujar Murata.
Keharusan untuk Seragam di Jepang
Murata mengatakan secara garis besar ada dua bentuk kesepian, yaitu kesepian yang dirasakan saat sendiri dan kesepian saat bersama dengan orang lain. Ia memilih untuk mengangkat tema kesepian saat bersama orang lain dalam bukunya karena hal itu lebih menyakitkan dan secara pribadi dekat dengan hidupnya.
“Kesepian itu memperkaya hidup karena saya bertemu dengan orang hebat di dunia fantasi. Dunia fantasi itu juga membuka pintu bahwa dunia nyata juga sama indahnya.”
Meskipun tumbuh dan sering merasa kesepian, Murata mengatakan bahwa ia menemukan dunia fantasi yang membantunya dalam menulis novel karena ia bertemu langsung dengan karakter yang ada dalam pikirannya. Ia menilai kesepian yang dirasakannya menjadi sebuah berkah karena ia mampu memperkenalkan dunia imajinasi yang indah itu ke dunia nyata lewat buku-bukunya.
“Kesepian itu memperkaya hidup saya karena saya bertemu dengan orang hebat di dunia fantasi. Dunia fantasi itu juga membuka pintu bahwa dunia nyata juga sama indahnya,” ujarnya.
Tidak hanya tentang rasa kesepian dan kesenjangan saat bersama keluarga, Murata juga menyinggung tentang keharusan untuk menjadi ‘seragam’ agar dinilai normal di masyarakat Jepang dalam Gadis Minimarket dan Earthlings. Ia sering mengangkat cerita tentang perempuan dipaksa tunduk di bawah peraturan sosial karena tidak menyukai kekangan tersebut. Ia merasakan bahwa ketika melihat masyarakat yang sengaja dibuat ‘seragam’ ada antena yang memberitahukannya bahwa itu adalah peristiwa yang janggal.
“Keseragaman itu seperti sebuah ritual. Semua orang harus sama dan jika tidak sesuai dan melakukan ‘ritual’ itu, mereka (masyarakat) akan menjadi ganas dan menyerang yang menolak dikekang. Hal itu sangat mengerikan,” ujarnya.
Baca juga: Heteronormativitas, ‘Colonial Gaze’ Hambat Representasi Beragam dalam Sastra
Novel ‘Gadis Minimarket’ dan Anonimitas Masyarakat Jepang
Murata mengatakan, dalam Gadis Minimarket ia juga menyoroti tentang kesukaan masyarakat Jepang akan anonimitas. Sayaka yang juga pernah bekerja di sebuah minimarket mengatakan, pelanggan suka menganggap pegawai sebagai mesin otomatis karena merasa nyaman jika identitas bahkan kebiasaan berbelanja mereka tidak diketahui oleh siapa pun.
“Pelanggan berharap penjaga toko tidak sadar bahwa dia selalu berbelanja di sana dan membeli apa. Jika pelanggan itu sadar bahwa penjaga toko tahu tentang kebiasaannya dia akan merasa malu. Jadi semua orang harus bertindak seakan-akan pertama kali bertemu,” jelasnya.
Baca juga: Penulis Perempuan Mencari Ruang Aman di Dunia Sastra yang Maskulin
Menanggapi tentang fenomena tersebut, Shibata mengatakan, masyarakat Jepang memang takut jika kehadirannya dirasakan orang lain dan selalu ingin menjadi transparan. Meskipun begitu, kecenderungan tersebut lebih banyak terjadi di daerah urban karena masyarakat pedesaan cenderung sudah mengenal satu sama lain.
“Masyarakat kota ingin menjadi transparan karena ikatan antara satu sama lain semakin menipis dan menjauh. Masyarakat kemudian terbiasa dengan kerenggangan dan takut jika didekati orang lain atau ada bonding,” ujarnya.
Ia mengatakan, karya Murata yang menyinggung fenomena tersebut menjadi angin segar pada sastra Jepang karena tidak takut mendobrak nilai-nilai yang mengungkung.
“Yang lebih menyegarkan karena Murata tidak menceramahi dan menunjukkan bahwa memang begini adanya, mungkin itu cara dia mengungkapkan ide dan menjadi menarik bagi pembaca di dalam atau luar Jepang,” kata Shibata.






















