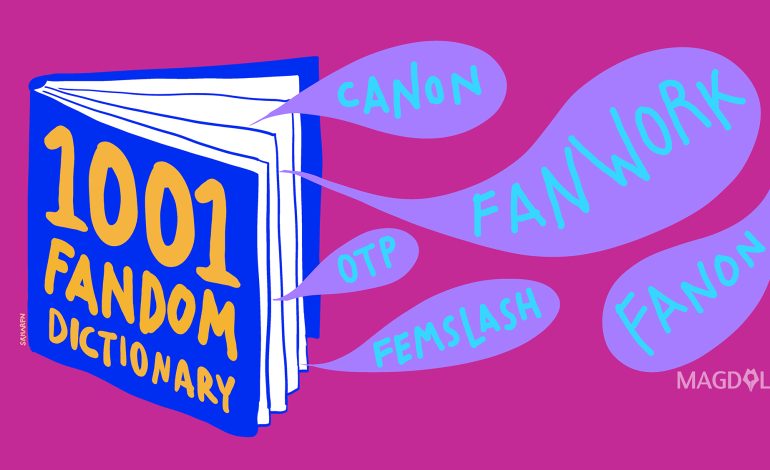Ini yang Dikritik Seniman Soal AI Generatif

Kritik dari seniman dan pekerja kreatif terhadap AI generatif bukan soal menolak kemajuan atau mempertahankan eksklusivitas seni. Bukan pula karena mereka lupa bagaimana teknologi seperti kamera digital atau ponsel telah memperkaya kehidupan kita. Justru banyak seniman aktif menggunakan teknologi digital, termasuk AI, dalam proses berkarya mereka.
Namun, kritik ini menyasar isu yang lebih mendasar: pelanggaran hak cipta, dampak lingkungan, bias dalam algoritma, potensi hilangnya mata pencaharian jutaan pekerja kreatif, hingga dominasi segelintir perusahaan teknologi raksasa, atau yang kerap disebut Big Tech.
Gelombang kritik ini kembali menguat seiring tren penggunaan AI untuk menghasilkan gambar bergaya khas Studio Ghibli. Aplikasi seperti ChatGPT, Dall-E, dan Midjourney merupakan bagian dari generasi baru AI generatif yang berbeda dari teknologi AI sebelumnya. Mereka dikembangkan dan dipasarkan secara masif, dengan cara kerja dan dampak yang lebih kompleks.
Yang menjadi sorotan adalah bagaimana AI generatif dikembangkan dan digunakan, serta dampaknya terhadap hak kekayaan intelektual, lingkungan, keberagaman, dan keberlangsungan profesi kreatif. Mari kita lihat beberapa poin utamanya.
Baca juga: #VampirData: Bagaimana Teknologi AI Mengisap Sumber Daya
1. Masalah hak cipta yang terabaikan
Banyak model AI generatif dilatih menggunakan jutaan karya seni, musik, dan tulisan yang diambil dari internet tanpa izin atau kompensasi kepada pembuat aslinya. Beberapa pengembang beralasan bahwa hukum hak cipta dianggap “menghambat inovasi”, bahkan ada pula yang berdalih bahwa ini bagian dari strategi geopolitik agar Amerika Serikat (AS) “menang” melawan negara lain dalam kompetisi AI.
OpenAI, misalnya, telah mendesak pemerintah AS agar diberi pengecualian dari aturan hak cipta, padahal selama ini hukum tersebut menjadi payung perlindungan bagi para kreator. Jika kebijakan itu diubah di AS, bukan tak mungkin akan menjadi preseden bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Ratusan musisi dan aktor ternama seperti Ben Stiller dan Paul McCartney telah menandatangani surat keberatan atas permintaan dari perusahaan pembuat ChatGPT yang disokong Microsoft itu. Gugatan hukum dari para penulis top dan media besar seperti The New York Times, yang meminta kompensasi US$750 untuk setiap karya yang dicuri, juga menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele.
2. Dampak lingkungan yang tak terlihat
Penggunaan AI generatif membutuhkan komputasi intensif. Satu perintah sederhana (prompt) pada ChatGPT, misalnya, memerlukan energi sekitar 10 kali lipat dari pencarian internet biasa, sekaligus menyedot sejumlah besar air untuk mendinginkan server.
AI generatif mempercepat kebutuhan pembangunan pusat data besar, yang memicu konsumsi energi—sebagian masih bersumber dari batu bara—dan menambah beban terhadap krisis iklim. Google mencatat peningkatan jejak karbon 48 persen akibat pengembangan AI, dan Microsoft mencatat kenaikan hampir 30 persen. Angka ini diprediksi terus meningkat.
Baca juga: Ayu Purwarianti, Perempuan Saintis di Balik Prosa.AI
3. Bias dan ketimpangan dalam hasil
Model AI belajar dari data yang bersumber dari internet, yang belum tentu netral atau bebas diskriminasi. Akibatnya, hasil AI bisa mencerminkan stereotip atau bias terhadap kelompok minoritas. Seorang karyawan Google bahkan kehilangan pekerjaannya setelah menyuarakan kekhawatiran soal bias ini. Ketika data pelatihan tidak dikurasi secara etis, AI bisa memperkuat ketimpangan yang sudah ada, alih-alih membantu mengatasinya.
4. Ancaman bagi pekerja kreatif
Selain persoalan hak cipta, banyak pekerja kreatif juga menghadapi tekanan ekonomi karena kehadiran AI generatif. Laporan dari Data & Society menunjukkan bahwa AI sering digunakan perusahaan untuk menekan biaya dengan mengurangi klien, memotong upah, bahkan menggantikan pekerja lepas.
Padahal dalam praktiknya, hasil AI masih membutuhkan sentuhan manusia. Sayangnya, pekerjaan yang dilakukan tetap sama, tapi nilainya justru dianggap menurun.
Selain keempat isu utama tersebut, ada juga kekhawatiran lain. Teknologi deepfake telah digunakan untuk membuat konten yang melecehkan perempuan. Misinformasi kian sulit dikendalikan, dan beberapa studi menunjukkan bahwa ketergantungan pada AI bisa melemahkan kemampuan berpikir kritis masyarakat.
Untuk itu, janji-janji manfaat dari AI generatif yang digaungkan oleh Google, Meta, Amazon, hingga OpenAI perlu kita telaah dengan cermat. Kita perlu ingat: mereka adalah korporasi besar yang berorientasi pada keuntungan.
Seperti industri besar lainnya, mereka tentu ingin produk mereka diterima seluas mungkin. Dan untuk itu, janji-janji manfaat akan dibuat semenarik mungkin. Tugas kita sebagai masyarakat adalah mendengarkan dengan kepala dingin, dan berpikir secara kritis.
Sayangnya, selama beberapa dekade terakhir, para raksasa teknologi ini kerap dibiarkan berkembang tanpa banyak kritik. Mereka berhasil membungkam suara-suara di dalam perusahaan, membungkus teknologi sebagai “keniscayaan zaman”, dan memainkan strategi pemasaran yang canggih. Akibatnya, publik menjadi kurang terbiasa mempertanyakan teknologi yang digunakan sehari-hari.
Baca juga: Oscars 2025: Kemenangan ‘The Brutalist’ dan Kontroversi Film-film yang Pakai AI
Kini, Big Tech tak hanya mengarahkan perkembangan AI di masa depan, tetapi juga memengaruhi opini publik dan melobi kebijakan di tingkat global.
Seniman dan pekerja kreatif di Indonesia pun mulai menunjukkan solidaritas terhadap gerakan global yang menuntut etika, transparansi, dan keadilan dalam pengembangan teknologi.
Pada akhirnya, kritik terhadap AI generatif bukan bentuk anti-teknologi. Justru karena para seniman paham nilai inovasi, mereka juga bisa mengenali ketika sebuah teknologi mulai melenceng dari prinsip etis dan kemanusiaan. Dan hari ini, sebagian teknologi itu dikuasai oleh segelintir entitas yang lebih mengutamakan keuntungan, ketimbang kebermanfaatan bersama.
Ilustrasi oleh Karina Tungari