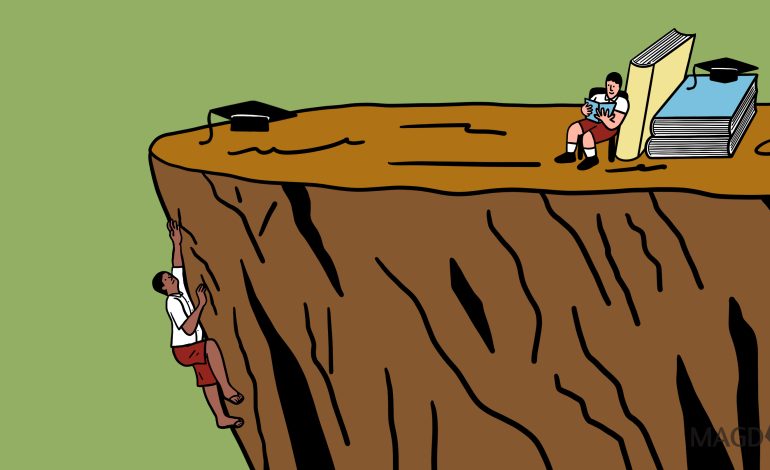Lelaki yang Datang di Jam Makan Siang

Aku tengah mengelap meja dapur ketika lelaki itu datang. Jam dinding di sebelah kiri dapur menunjukkan sudah pukul 12 lewat 8 menit. Sebenarnya bukan dapur, tapi kamar sekaligus dapur sekaligus ruang tamu, karena aku tinggal di apartemen sempit tipe studio di kawasan pinggiran Jakarta.
“Cepat sekali sampai, apa tadi tidak ada meeting?” tanyaku. Aku mengeringkan lap dapur kemudian berjinjit mengambil piring dan sendok.
Laki-laki itu mengangguk kecil, melemparkan jasnya ke arah sofa, dan langsung menuju meja makan kecil dekat pintu. Sembari menarik kursi, dia melihat-lihat menu makanan hari ini yang sudah aku sajikan di meja. Hari itu aku memasak sayur singkong, kering tempe, dan gulai daging untuk dia.
Keningnya yang halus mengernyit ketika melihat satu mangkuk ikan berkuah. “Ini apa?” tunjuknya.
“Oh, itu nanti kupindahkan. Itu buatku nanti malam. Aku tadi memasak sop ikan salmon yang kubeli di supermarket,” jawabku segera.
Baca juga: Bukan Perawan Maria – Sebuah Cerita Pendek
Aku bergegas membawa lap untuk memindahkan mangkok panas itu dari pandangannya. Dia tidak suka masakan ikan berkuah, buah pisang, dan beberapa hal lain yang sebenarnya aku tidak mengerti kenapa. Selera kami sebenarnya dibilang mirip juga tidak, tapi dibilang berbeda juga tak terlalu. Setidaknya kami bisa setuju pada daging panggang meski dengan saus yang berbeda: Saus barbeque untuknya dan saus lada hitam untukku. Aku menyukai buah dan ikan, tidak menyukai makanan yang digoreng dan berminyak, sedangkan dia memilih sesuatu yang digoreng renyah dengan minyak menggenangi wajan.
Aku mengambilkannya gelas berisi air dingin, menaruhnya dengan hati-hati di sebelah kanan piringnya. Kemudian mengambil centong nasi dan mengisi piringnya, setelahnya baru ku isi piringku sendiri meskipun aku sebenarnya belum terlalu lapar. Dia selalu ingin ditemani ketika makan, dan akan bersungut-sungut sambil menggumam apabila tidak ada yang menemaninya. Padahal tidak banyak yang dibicarakan, karena ia terlalu sibuk dengan gawainya. Interaksi kami cuma sebatas gerak-gerik isyarat dengan tangan. Entah minta diambilkan air, dibawakan sendok baru, pendingin ruangan dinyalakan, gorden ditutup, atau diambilkan lap.
Setelah makan yang singkat tanpa percakapan, ia menunjuk ke arah sofa yang sekaligus menjadi tempat tidurku. Aku mengangguk, mengangkat piring dan alat makan yang kotor ke wastafel, membiarkan air mengalir dari keran sebentar, mencuci tangan dan wajahku, kemudian menuju ke arah lemari. Aku menghela napas dan mengambil satu set pakaian dari laci lemari paling bawah, lantas menaruhnya di sisi sofa.
Aku mulai membuka kancing bajuku, celanaku, pakaian dalamku, hingga tidak ada yang tersisa, kemudian mulai mengenakan satu setel pakaian tadi. Aku kemudian mendekat dan mulai melepaskan pakaiannya satu per satu. Dia mulai mengecupku, menyayangiku, kemudian seperti biasa, mencintaiku sampai puas dan menggeram. Apakah itu cinta? Aku tidak tahu, aku tidak pernah yakin.
Dia akan berkata aku cantik, cantik sekali. Aku berusaha menutup mataku sepanjang proses itu dan mencari pikiranku sendiri di antara sakit yang amat sangat. Aku sangat mencintainya kala ia memanggil namaku. Namun, yang kutatap hanya langit-langit sambil memikirkan harga cabai yang menjulang tinggi, harga bawang yang sudah lebih murah dari kemarin, dan harga kentang yang lebih murah kalau membeli di pasar yang berbeda.
Baca juga: Dua Lubang di Rumah Bia
Jika pikiranku sudah buntu, kuulangi lagi dengan memikirkan harga bahan-bahan makanan yang lain, harga sandal warna biru dibandingkan sendal warna merah, atau bahkan apakah token listrik bulan ini lebih cepat habis dibandingkan bulan lalu.
Setelah penderitaan singkat yang dibilang cinta itu selesai, dia melirik jam yang masih terpasang di lengan kirinya, beranjak ke kamar mandi dan meninggalkan aku yang masih menghitung harga-harga di kepalaku. Tidak lama, dia keluar dari kamar mandi, mengenakan kembali seluruh bajunya, menyisir rapi rambutnya, memakai sepatunya, kemudian membuka pintu kamarku dan pergi kembali ke kantor. Selalu seperti itu.
Setelahnya, aku kadang-kadang langsung berlari ke wastafel untuk mencuci piring, membiarkan air mengalir ke tanganku. Atau kadang aku sengaja memecahkan piring dan gelas, membiarkan pecahannya membentuk luka dan membuat warna air menjadi merah. Kadang aku bergegas ke kamar mandi, meringkuk di bawah pancuran shower dan menggosokkan sikat toilet di tubuhku, merasa jijik, meraung marah dan berteriak seperti orang gila. Namun, setelah itu semua, aku tetap mengambil baju itu, memasukkannya ke mesin cuci, dan esoknya mengenakan baju itu lagi ketika ia datang di siang hari.
Aku pernah merengek karena kelelahan. Dia menemukanku tertidur di sofa berbalut selimut dengan kipas angin mengarah tepat ke wajahku. Namun yang dia lakukan adalah membangunkanku dengan ketus. Di tengah kepala yang berputar membentuk beliung, aku memaksa diriku bangun. Kedua bola mataku mulai mengisi diri mereka dengan air mata yang menggenang. Kemudian raut wajahnya berubah kesal dan memutuskan untuk pergi.
“Aku tidak punya waktu untuk air matamu,” katanya.
Baca juga: Tujuh Bayangan Cermin Perempuan
Aku tidak mengerti mengapa membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Teman-teman sudah lelah menasihati, hingga aku merasa harus menarik diriku sendiri. Aku masih terpaku dan terjebak di sini, sementara mengetahui esok hari ia bakal datang lagi. Ia akan selalu datang seperti biasa di siang hari, tergantung seberapa lama jalanan Jakarta menghentikan deru mobilnya.
Setiap siang yang berjelaga, aku selalu menantikan kedatangannya. Setiap sore yang sepi, aku kembali memuntahkan rasa malu, marah, dan rasa takut yang teramat sangat.
Hari itu, adalah hari aku menangis tanpa henti. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi gelas dan piring yang tersisa dari kamarku. Aku berusaha merogoh tempat sampah dan mengumpulkan sisa-sisa pecahan yang tersisa. Dalam kaburnya pandanganku, aku berdoa semoga selalu ada pertemuan-pertemuan lainnya yang menenggelamkan dirinya, jalan Jakarta akan menelannya utuh, menihilkan bunyi pintu yang dibuka.
Dengan sisa tenagaku aku mengemas barang-barangku, dan mengirimkan pesan singkat kepadanya. “Maaf, tidak akan ada makan siang mulai hari ini”