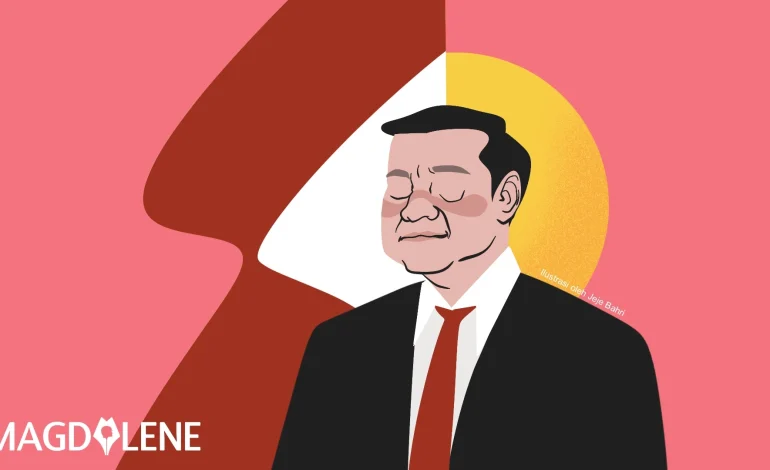Ragukan Guru Besar hingga Ahli di ‘Dirty Vote’, Warga +62 Harus Berhenti Menyangkal Pakar

Saat Dirty Vote (2024) dirilis di Youtube beberapa hari lalu, respons masyarakat terbelah. Ada yang mengatakan filmnya mengungkap fakta tentang tingkah laku penguasa, sebagian menilai filmnya bertendensi menjatuhkan salah satu pasangan calon (paslon).
Respons yang kedua patut jadi sorotan. Dalam menyertakan data, dokumenter garapan Dandhy Laksono itu melibatkan tiga pakar hukum tata negara: Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya memiliki kapasitas akademis di bidangnya.
Namun, sebagian warganet memandang, pemaparan Feri, Bivitri, dan Zainal enggak masuk akal, penggiringan opini, dan bagian dari kampanye terselubung yang ditunggangi pihak tertentu.
Hal serupa terjadi ketika guru besar di sejumlah perguruan tinggi menyatakan sikap, atas rusaknya demokrasi di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK), demi memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menuju bangku eksekutif sebagai wakil presiden. Kemudian pemanfaatan fasilitas negara untuk proses kampanye, dan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan secara masif demi meningkatkan suara elektoral.
Alih-alih khawatir melihat sivitas akademika turun gunung, sejumlah golongan menanggapi bahwa kritik guru besar enggak memengaruhi pilihan mereka. Ada yang menduga guru besar berpihak pada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta menilai sikap senioritas dengan titelnya sebagai “guru besar”.
Padahal, guru besar yang buka suara semakin menunjukkan demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Begitu pun dengan Dirty Vote, yang memaparkan fakta tentang keculasan pemerintah, demi melanggengkan kekuasaan dan menguntungkan kelompok elite.
Masyarakat boleh cemas, melihat sebagian orang menutup mata terhadap kredibilitas pakar. Apalagi jika kepakaran ditiadakan. Dalam The Death of Expertise (2017), Tom Nichols menyatakan matinya kepakaran akan membahayakan demokrasi. Sebab, pemimpin mampu memprovokasi masyarakat demi memperoleh kekuasaan. Di samping itu, pemerintah pun membutuhkan pakar dalam pengambilan keputusan.
Berkaca dari publik yang menentang fakta dan meragukan akademisi, muncul sebuah pertanyaan: Apa yang membuat mereka meragukan orang-orang berkredibilitas?
Baca Juga: Waspada Terjebak Pencitraan ‘Keluarga Harmonis’ Politikus
Idolisasi, Bias Konfirmasi, dan Akademisi yang Tertindas Kekuasaan
Demografi Pemilu tahun ini didominasi oleh Gen Z, mencapai 22,85 persen dari total pemilih berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbeda dengan Pemilu 2019 yang kebanyakan pemilihnya adalah Generasi Milenial.
Data tersebut sejalan dengan pemanfaatan TikTok sebagai alat kampanye digital. Tak hanya politisi yang menggunakan platform tersebut untuk menggaet pemilih muda, mereka juga ikut mengedit dan mengunggah video sebagai dukungan terhadap paslon. Membuat persona paslon seperti tokoh idola, dengan ciri khas masing-masing.
Di paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, ada fenomena kpopisasi dari pendukung. Mereka mengampanyekan Anies dan Muhaimin seperti penggemar idol Korea Selatan terhadap idolanya.
Misalnya bikin photo card dan light stick, mengedit foto dan video, hingga mendatangkan food truck saat Desak Anies. Tak lupa kehadiran Tom Lembong, Co-Captain Timnas AMIN yang belakangan diidolakan.
Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membangun citra “pemimpin gemoy” lewat berbagai gimmick. Seperti joget, memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk konten kampanye, dan kecintaan Prabowo pada kucing yang dianggap friendly grandpa.
Sedangkan paslon Ganjar dan Mahfud disebut “El Chudai” oleh penggemar, mengadopsi penguin sebagai ikon, serta tampil dengan gaya berpakaian mencolok di debat capres dan cawapres.
Founder dan CEO Think Policy sekaligus Co-Initiator Bijak Memilih Andhyta F. Utami, menyebut fenomena ini sebagai idolisasi—di mana pertarungan capres dan cawapres diperlakukan layaknya kontestasi idola.
“Idolisasi yang bikin masyarakat defensif dengan fakta dan informasi,” ujar Andhyta saat menghadiri acara Remotivi pada (12/2).
Baca Juga: Agar Pemilu Tak Dikuasai Oligarki Melulu: Ganti Sistem dan Pembiayaan Pemilu
Ia menambahkan, orang yang mengidolisasi cenderung memiliki bias konfirmasi dalam mengakses informasi. Maksudnya, pencarian bukti yang mendukung keyakinan dan hanya dari satu sisi, kemudian mengabaikan penjelasan yang bertentangan.
Efeknya meliputi beberapa hal: Bias konfirmasi membuat orang bergantung pada informasi awal yang diterima, salah menafsirkan hubungan antara dua peristiwa, menolak berbagai bukti yang berlawanan dengan kepercayaan, serta polarisasi sikap.
Di buku yang sama, Nichols juga menyebutkan tentang bias informasi yang memiliki ruang di internet. Tak lain tak bukan disebabkan oleh algoritma, membuat pengguna mengakses informasi berdasarkan preferensi.
Hal itu menjelaskan cara sebagian masyarakat menanggapi pernyataan sikap sivitas akademika, maupun dokumenter Dirty Vote. Mereka terkurung dalam gelembungnya sendiri, dan meyakini fakta yang dipaparkan bertendensi merugikan pihak tertentu saat pemilu.
Sementara menurut Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media dan Budaya Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo, ada dua faktor lainnya. Pertama, budaya di Indonesia yang tak menghargai akademisi. Ini disebabkan oleh kultur yang mengutamakan kesuksesan berbentuk materi. Akibatnya, keilmuan dan kebudayaan dinomorduakan.
Kedua, penguasa memosisikan akademisi di bawah mereka. Kunto mencontohkan sejumlah politisi yang memiliki gelar Honoris Causa (HC). Contohnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ada yang menerima gelar dari perguruan tinggi di dalam, maupun luar negeri.
Di Indonesia, HC diberikan oleh senat universitas, tanpa keterlibatan eksternal. Dalam laporan Magdalene tahun lalu disebutkan, kriteria pemberian gelar HC sebatas berjasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Tak terkecuali sosok yang terafiliasi politik. Bisa dikatakan, pemberian gelar menyesuaikan kebutuhan universitas—yang disayangkan cenderung membangun relasi dengan elite politik dan ekonomi.
“Itu bikin S-3 kelihatannya gampang, seakan-akan akademisi melacurkan diri demi rupiah,” kata Kunto.
Ia kemudian menarik sejumlah rektor universitas yang tersangkut kasus korupsi dalam lima tahun terakhir. Di antaranya Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani yang ditangkap pada 2022, dan Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gede Antara pada 2023. Peristiwa seperti ini yang menurunkan wibawa rektor, dan merusak kredibilitas akademisi.
Kejadian tersebut sekaligus membuktikan pemilihan rektor di perguruan tinggi yang bermasalah, setidaknya selama lima tahun terakhir. Kunto menyinggung suara pemerintah dalam pemilihan rektor, yang lebih besar daripada akademisi. Yakni suara terbanyak milik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) bersama Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Terlebih MWA biasanya dikepalai oleh menteri atau pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi.
Berarti, tanda-tanda hilangnya kepakaran sudah dialami sejak beberapa tahun terakhir. Bila realitas yang dihadapi sekarang berlanjut hingga terjadi skenario terburuk—alias kepakaran benar-benar mati—kemungkinannya Indonesia menjadi negara yang tak harmonis dari segi alam, budaya, dan masyarakat.
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi ini?
Baca Juga: Fakta-fakta Menarik Pemilu 2024: Dominasi Pemilih Gen Z Sampai Pemungutan Sistem Noken di Papua
Matinya Kepakaran Adalah Tanggung Jawab Pemerintah
Sebenarnya, masyarakat yang tak percaya dengan fakta dan kredibilitas pakar mencerminkan pemerintah. Kalau kamu ingat, waktu virus corona mulai terdeteksi di Indonesia, sejumlah pejabat negara justru meremehkan. Sebut saja Mantan menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Lalu Mahfud MD semasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan.
Akibatnya terlambat penanganan hingga mengorbankan ratusan ribu jiwa masyarakat. Padahal, World Health Organization (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sikap para pejabat publik menunjukkan pengabaian terhadap sains. Tak heran, semasa pandemi segelintir masyarakat Indonesia lebih percaya teori konspirasi, dibandingkan tenaga kesehatan.
Atau respons Presiden Jokowi terhadap kritik sivitas akademika. Ia menyebutkan, itu demokrasi yang harus dihormati, tanpa bertindak apa pun. Staf khusus pun sempat mempertanyakan, mengapa kritik disampaikan menjelang pemilu. Sedangkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menganggap, kritik tersebut adalah skenario dari pihak tertentu.
Cara pemerintah menanggapi ilmuwan dan akademisi, mengesankan mereka enggak berperan signifikan di kehidupan bernegara. Padahal, masyarakat memerlukan keteladanan agar mau menghargai pakar.
Menurut Kunto, ada dua hal yang bisa dilakukan agar masyarakat kembali mendengarkan pakar. Yaitu memberikan ruang bagi ilmuwan untuk menjadi contoh, seperti dalam penyusunan undang-undang. Dalam hal ini, pakar bukan hanya menjadi token, melainkan punya partisipasi bermakna.
Selain itu, ilmuwan sendiri harus mampu berbicara dengan bahasa publik yang lebih sederhana, agar mudah dimengerti. Dengan kata lain, pejabat negara dan ilmuwan harus berdampingan dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau kebijakan nggak sejalan dengan saran ilmuwan, dampaknya pasti bencana. Baik sosiologis maupun lingkungan,” tutup Kunto.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari