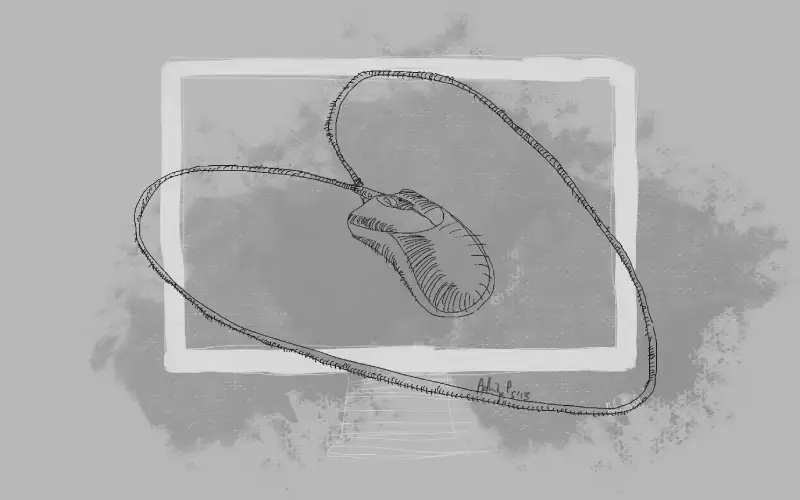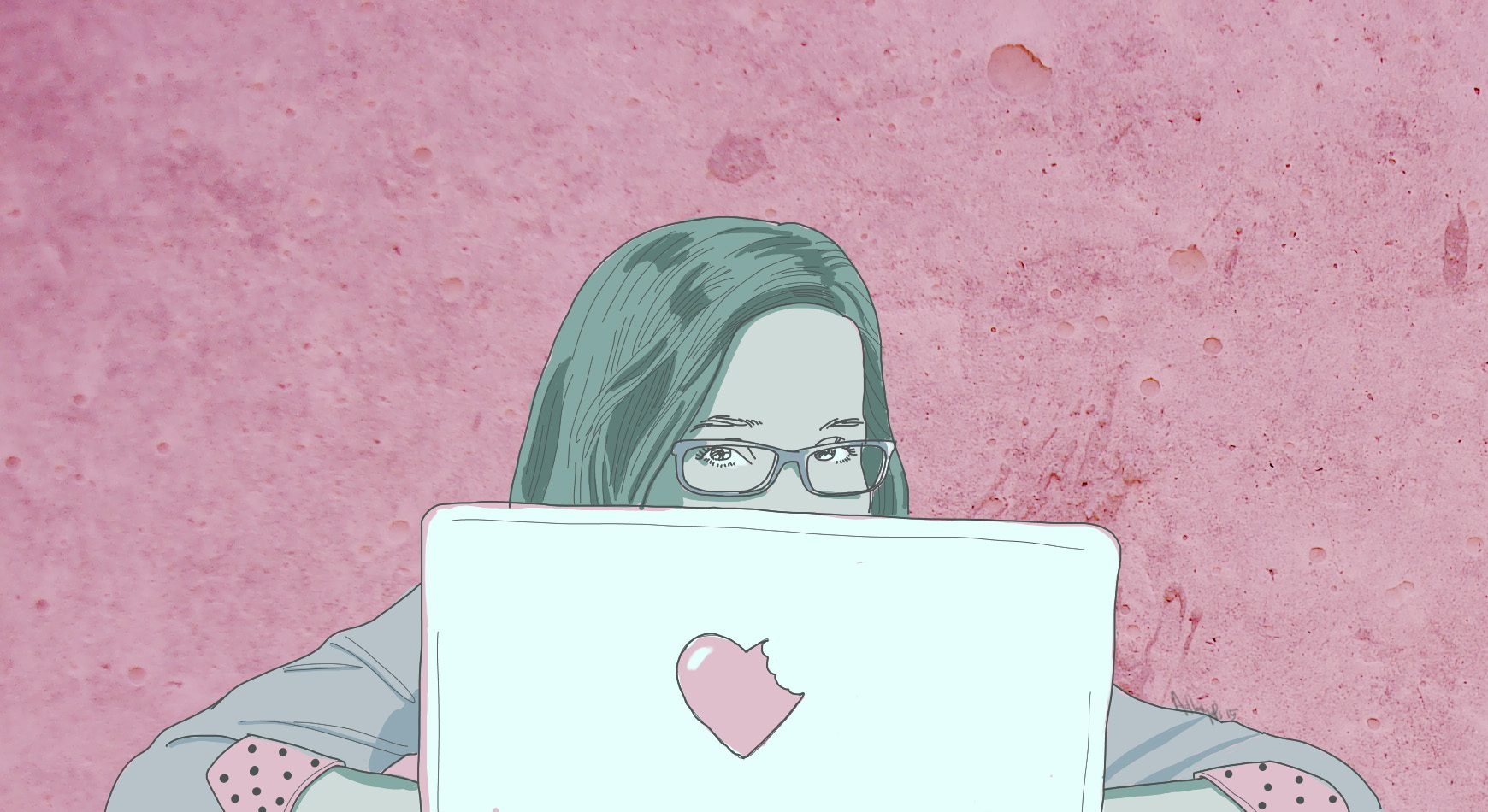Mitos Mertua-Menantu Tak Akur, Masihkah Relevan?

“Pernikahan saya hancur karena mantan ibu mertua,” ujar teman saya, “Silvia” sambil bersungut-sungut.
Perempuan berumur 35 tahun itu pantas kesal. Rumah tangga yang telah ia jalani selama 4,5 tahun kandas karena bekas ibu mertuanya kerap ikut campur. Tak hanya mengatur tentang bagaimana menjadi istri idaman, ibu yang sempurna, ia juga sering meminta uang pada suaminya setengah memaksa. Padahal kala itu, Silvia mengaku sedang membutuhkan biaya agak banyak untuk cicilan rumah bulanan.
“Komplet, rumah tangga terasa seperti neraka kalau ada dia,” tandasnya.
Silvia mulanya tinggal terpisah rumah dengan mantan ibu mertua. Namun, sejak hamil dan melahirkan anak semata wayangnya, sang ibu memutuskan pindah rumah sementara dengannya. Orang tua Silvia sendiri tinggal terpisah jauh di luar Jakarta, sehingga dari awal ibu mertua berniat membantu dan menemaninya. Semua baik-baik saja, sampai akhirnya ia merasa eks ibu mertuanya lebih sering mengatur-atur dan meneriakinya.
“Saya kira masih di batas wajar karena dia mungkin khawatir dengan cucunya. Harus melahirkan normal, harus bisa menyusui, harus bisa memasak untuk suami, dan membereskan urusan rumah. Saya diposisikan sebagai perempuan serba bisa yang tak bisa merasakan lelah dan tertekan,” kenangnya pada saya.
Silvia adalah pekerja lepas yang mengerjakan tugas desain untuk para kliennya. Ia tak berkantor, sehari-hari lebih banyak berdiam dalam kamar, kadang begadang dan lupa makan jika tenggat kerja sudah mepet. Ibu suaminya tak suka dengan kebiasaan Silvia. Buat dia, seorang perempuan yang notabene sudah jadi istri harus merelakan waktunya mengabdi untuk suaminya. Ini termasuk menyediakan teh panas, memijat kaki suami, mengerjakan semua urusan domestik sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga, atau memasak di dapur.
“Saya pernah muntap ketika menguping mantan ibu mertua saya menyuruh suami menceraikan saya hanya karena saya dinilai tak becus mengurus rumah. ‘Ceraikan saja, masih banyak perempuan bener yang mau sama kamu,’” ujarnya menirukan perkataan sang ibu.
Masalahnya, kejadian seperti ini sudah sering kali terjadi dan Silvia tak pernah dibela suaminya. Silvia juga merasa direndahkan harkatnya sebagai perempuan akibat terlalu sering dimaki-maki. Beberapa kali ia menyebut Silvia sebagai perempuan yang senang membantah, keras kepala, bahkan pernah sekali waktu mengatai dia dengan label tak pantas.
Silvia sebenarnya masih bisa menahan diri sampai akhirnya sang ibu sudah mulai rutin meminta uang kepada suami—yang entah digunakan untuk apa. Padahal masa-masa pandemi membuat ia harus mengetatkan ikat pinggang, tapi suaminya justru tanpa pikir panjang menggelontorkan uang. “Saya stres berat. Posisi habis melahirkan, butuh banyak uang, dikata-katai karena ASI tak keluar, disebut-sebut enggak bisa urus rumah, eh, sekarang uang masih diminta juga,” ungkapnya.
Reaksi bekas suaminya pun bikin sakit hati lagi-lagi ia cenderung membela sang ibu. Suami selalu menekankan berkali-kali, ibunya sudah tua, tipikal konservatif, harus dihormati, harus dimengerti. Lantaran tak tahan lagi menghadapi konflik berkepanjangan, Silvia mengajukan gugatan cerai, yang anehnya disambut dengan tanpa perlawanan oleh suami dan ibunya itu. Silvia kini menjanda, tapi merasa jauh lebih bahagia.
Baca juga: ‘Love for Sale 2’ dan Stereotip Menantu Perempuan Idaman
Konflik Mertua-Menantu Tak Cuma Mitos
Kisah yang dialami Silvia barangkali adalah contoh paling ekstrem dari konflik mertua-menantu perempuan yang berujung perceraian. Sampai sebelum saya mengalami sendiri relasi horor-nir-romantis dengan ibu mertua, saya selalu menganggap kisah-kisah ini tak cukup representatif untuk menyimpulkan bahwa hubungan mertua-menantu memang sudah selaiknya tak akur.
Meski bukan berupa data riset ilmiah, stereotip tidak akurnya mertua dan menantu perempuan juga banyak dilanggengkan melalui berbagai judul film dan sinetron di dalam dan luar negeri.
Kalau kamu iseng mencari kata kunci mertua-menantu, maka yang keluar adalah rentetan judul sinetron atau sinema di Indosiar, seperti “Aku Menantu yang Dibenci Mertua, “Aku Menantu yang Diusir”, “Menantu Durhaka”, “Menantu yang Mengemis Restu Mertuanya”, hingga “Rumah Tanggaku Hancur Karena Mertua”. Bahkan di 2007, Sinemart, salah satu Production House spesialis sinetron-sinetron dramatis Indonesia mendedikasikan diri untuk menggarap judul “Mertua dan Menantu”.
Kalau dilihat dari data ilmiah, sebuah riset yang dilakukan selama 26 tahun terhadap 373 pasangan di Amerika menunjukkan, seorang suami yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga istrinya menurunkan risiko perceraian sebesar 20 persen. Sementara, istri yang terlalu rapat dengan keluarga suami justru meningkatkan risiko perceraian, tutur psikolog Terri Orbuch dari Oakland University mengomentari survei itu.
Menurutnya, istri yang terpaksa (baca: dipaksa) dengan orang tua suaminya mungkin merasa sulit untuk menetapkan batasan. Lalu seiring waktu mungkin menganggap hubungan dekat mereka dengan dia sebagai campur tangan.
“Karena hubungan sangat penting bagi perempuan, identitas mereka sebagai istri dan ibu adalah inti dari keberadaan mereka. Sementara, mereka menafsirkan apa yang dikatakan dan dilakukan mertua sebagai gangguan terhadap identitas mereka sebagai pasangan dan orang tua,” kata penulis buku Finding Love Again: 6 Simple Steps to a New and Happy Relationship (2012) itu seperti dikutip The Guardian.
Riset soal konflik mertua-menantu perempuan tak hanya dilakukan oleh Orbuch. Dr. Terri Apter dari Newnham College melengkapi sebab-sebab kenapa menantu perempuan sering kali tak akur dengan mertua. Pertama adalah perasaan saling cemburu baik dari mertua atau menantu perempuan. Mertua merasa perhatian yang mestinya diberikan padanya teralih ke menantu, sedangkan menantu merasa sudah waktunya suami memindahkan fokus pada keluarga baru, alih-alih ibunya sendiri. Singkatnya adalah berebut perhatian dari laki-laki.
Baca juga: Sinema Indosiar, Perempuan Durhaka, dan Derita Nestapa
Kedua, persaingan antara ibu mertua vs menantu ini mirip seperti konflik di taman kanak-kanak di mana untuk menyingkirkan lawannya, cukup keluarkan sejuta sindiran, tindakan meremehkan, dan kritik. Kendati menantu perempuan adalah sosok yang dewasa, tapi atas nama usia, ibu mertua merasa dirinya lebih superior, sehingga berhak mengatur-atur menantunya.
Tak hanya itu, persaingan ini juga didorong oleh ketakutan ibu mertua yang dalam beberapa hal takut jika ditelantarkan setelah anak lelakinya lebih membela istrinya. Sebaliknya, menantu juga merasa berhak punya “suara” di rumah itu, sehingga muncul lah pertanyaan rumit: Siapa sebenarnya perempuan di keluarga? Si menantu dalam riset Apter disebut-sebut mendambakan peran sebagai perempuan penting di kehidupan suaminya, apalagi jika mereka tinggal satu rumah.
‘Perumahan Mertua Indah’
Ya, sebab lainnya yang paling jamak dari ketegangan mertua-menantu adalah ruang gerak yang terbatas jika mereka terpaksa tinggal satu atap, baik di rumah baru atau rumah mertua. Ruang gerak terbatas ini tak hanya dalam arti harfiah tapi juga ruang gerak untuk mengatur ekonomi, belanja sehari-hari, hingga rencana mengelola masa depan termasuk memiliki anak. Celakanya, dalam riset yang dilakukan Susanne Huber, dkk. (2017) dan diterbitkan oleh Royal Society Open Science terhadap 2,5 juta responden di 14 negara, perempuan yang tinggal serumah dengan mertua memiliki anak yang cenderung lebih sedikit.
Baca juga: Tak Semua Orang Tua Mulia: Relasi Anak-Anak dengan Orang Tua Toksik
Tinggal bersama mertua, menurut pengalaman Silvia di atas juga bisa menjadi bumerang karena potensi gesekan yang lebih besar mengancam di depan mata. Tak ada jarak, tak ada privasi, tak ada kebebasan untuk memutuskan sendiri hal-hal penting di rumah tangga. Itulah mengapa sebagian besar perempuan lebih nyaman tinggal terpisah dengan mertua pasca-menikah demi menghindari perselisihan hingga memupuk kemandirian. Sebab, biar bagaimanapun, tinggal dengan mertua, berelasi dengan mertua tak melulu buruk. Hanya saja beberapa riset mengafirmasi, kalaupun ada hubungan yang harmonis antara menantu-mertua, itu tak bisa jadi generalisasi bahwa ketegangan dua perempuan ini sekadar mitos.
Sebenarnya tak ada formula paten untuk memperbaiki hubungan menantu perempuan dan mertua. Beberapa orang menyarankan, salah satu kuncinya adalah meyakinkan pada mertua bahwa kita adalah sosok yang tepat untuk menjadi istri anaknya. Komunikasi tatap muka dengan calon ibu mertua pun menjadi salah satu jembatan untuk mengantisipasi ketegangan klasik tersebut. Namun, solusi ini tentu saja akan mental jika diterapkan pada kasus ekstrem di mana mertua memang selalu membenci kita dengan atau tanpa alasan.
Jika sudah begini, maka solusi terbaiknya hanya satu: Mengutamakan pernikahan. Pasalnya, individu yang merasa didukung oleh pasangannya dalam konflik dengan mertua akan mengalami pernikahan yang lebih memuaskan. Dalam konteks ini, peran suami memang jadi kunci.