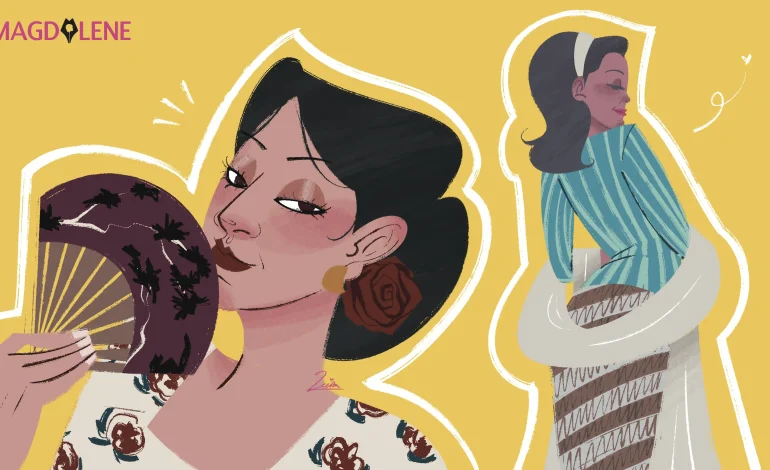Pengadilan HAM Dinilai Gagal Hadirkan Keadilan

Saiful Hadi, salah satu korban tragedi Tanjung Priok 1984, masih mengingat bagaimana ia memperjuangkan hak-haknya bersama penyintas lain. Ia menghadiri serangkaian sidang yang berlangsung pada 2003-2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada sidang putusan di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan korban berhak mendapatkan kompensasi. Pada akhirnya, karena semua terdakwa divonis bebas di tingkat banding dan kasasi, tak satu pun korban yang memperoleh haknya.
“Kami melakukan advokasi kemana-mana, termasuk ke PTUN, tapi kami tetap enggak bisa berbuat apa pun. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini ternyata tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu sendiri,” ujarnya dalam diskusi dan peluncuran buku ‘Dua Dasawarsa Nirpidana : Kelemahan UU Pengadilan HAM dan Gagalnya Negara Menegakkan Keadilan’ yang diadakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) di Jakarta, (17/7) lalu.
Baca juga: Seramnya Pencabutan Nama Soeharto dari Tap MPR dan Wacana “Pahlawan Nasional”
Buku yang disusun oleh KONTRAS dan para peneliti Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM (Insersium) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) ini mengetengahkan analisis tentang implementasi UU Pengadilan HAM yang tidak maksimal dalam memenuhi rasa keadilan korban.
Peneliti KONTRAS yang juga mantan Ketua Insersium FH Unhas Javier Maramba Pandin menuturkan, sejak disahkannya UU Pengadilan HAM, hanya ada empat peristiwa (Tanjung Priok, Abepura, Timor Timur, dan Paniai) yang disidangkan dari 15 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dari keempat kasus tersebut, tak ada seorang pun yang dipidana.
“Setidaknya ada 35 orang yang pernah didudukkan sebagai terdakwa dan dituntut, tetapi 16 di antaranya bebas di tingkat pertama, menyisakan 19 orang lain. Dari 19 orang yang mengajukan banding, 17 di antaranya juga bebas pada tingkat banding, menyisakan 2 orang yang jadi harapan penegakan hukum dan pemberantasan impunitas. Sayangnya, 2 orang tersebut divonis bebas lagi di tingkat kasasi,” kata Javier.

Baca juga: 17 Tahun Aksi Kamisan: 4 Catatan Penting yang Harus Kamu Tahu
Gagalnya Keadilan Transisi
Di bawah rezim otoriter, pelaku pelanggaran HAM tetap berkuasa, sedangkan para korban sulit mendapatkan keadilan. Setelah pemerintahan otoriter jatuh, penting menghadirkan keadilan transisi (transitional justice), yaitu proses dan mekanisme untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lampau. Tujuannya untuk memastikan akuntabilitas, menegakkan keadilan, dan mencapai rekonsiliasi.
Sri Lestari Wahyuningroem, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran (FISIP UPN) Jakarta menilai transisitional justice di Indonesia gagal sehingga impunitas terhadap pelaku tak terelakkan.
“Pengadilan HAM, termasuk yang terjadi dengan Tanjung Priok, faktanya adalah, dari proses dan outcome, dia itu flaw. Jadi bagaimana mungkin menghadirkan keadilan yang dari prosesnya pun sudah cacat?” katanya.
Keadilan transisi di Indonesia juga gagal karena negara ini berada dalam dua kondisi di mana terjadi “konsesi taktis” dan kelanjutan warisan rezim otoriter.
“Kalau diamati, misalnya, waktu pemerintahan Jokowi hampir selesai, ada pembentukan tim PPHAM (Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu). Kita menyambut itu dengan satu harapan tapi kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah bagian dari tactical consession. Dengan demikian itu menjadi red carpet untuk Prabowo bisa maju. Tactical concession itu udah kelihatan sejak pemerintahan Habibie dan itu terus-menerus dilakukan,” jelasnya.
Di sisi lain, Dian Rositawati, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang juga dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, menggarisbawahi kegagalan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur pelanggaran HAM berat di persidangan.
“Dulu, di tiga kasus itu (Tanjung Priok, Abepura, dan Timor Timur), isu hukumnya di dalam putusan adalah kegagalan dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban komando. Kedua, kegagalan membuktikan unsur sistematik atau meluas,” katanya.
Dian menambahkan, beberapa substansi UU Pengadilan HAM perlu direvisi, seperti menegaskan arti kata ‘meluas’ dan ‘sistematis’ pada pasal 9. “Di UU Nomor 26 Tahun 2000 memang tidak ada penjelasan dari serangan yang sistematis atau meluas. Namun di berbagai yurisprudensi internasional dan di Rome Statute itu tersedia. Jadi kita bisa merefer ke situ,” ujarnya.
Baca juga: Tubuh Perempuan Dijadikan Target: Kekerasan terhadap Pembela HAM di Aksi Protes
Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, diperlukan adanya kemauan politik dan menurut pandangan Sri, hal ini tak dimiliki oleh pemerintah. Hal yang lebih penting dilakukan saat ini adalah penguatan masyarakat sipil yang selama 20 tahun terakhir melemah. Akar rumput, baik komunitas akademisi, korban, dan aparat penegak hukum perlu bersinergi dalam mewujudkan agenda bersama.
“Kita bisa memulai dengan revisi UU itu tadi. Kali ini harus kita lakukan dengan benar, dan dengan partisipasi akar rumput kita. Kalau dulu (pembuatan undang-undangnya) dilakukan secara cepat, hal itu jangan diulangi lagi,” pungkas Sri.
Ilustrasi oleh Karina Tungari