Saya Takkan Pernah Dianggap Manusia: Trauma LGBT di Lingkungan Agama
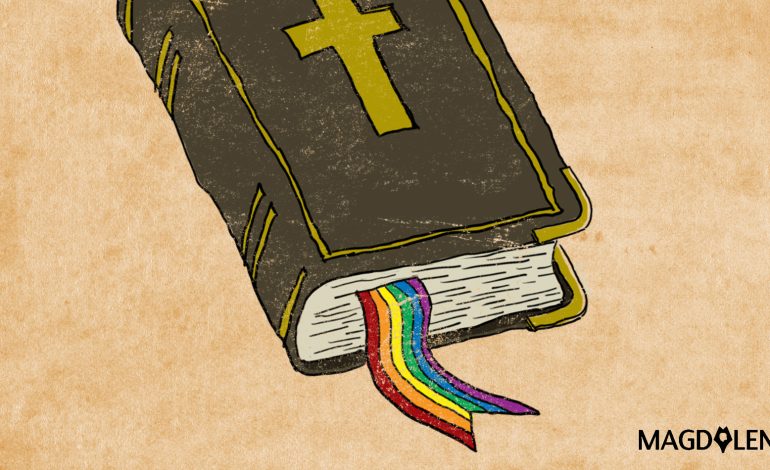
Awal tahun ini, kala pemerintah Australia membahas undang-undang diskriminasi agama (religious discrimination bill) yang kontroversial, sejumlah pihak mempertanyakan isu penting terkait perlindungan bagi murid-murid gay dan transgender di sekolah-sekolah keagamaan.
Ini muncul setelah sekolah keagamaan Citipointe Christian College di Brisbane menuai kritik karena mengirim kontrak pendaftaran ulang ke orang tua siswa yang memuat pasal-pasal terkait gender dan seksualitas. Pasal tersebut mengibaratkan bahwa orientasi homoseksual sama parahnya dengan bestialitas (hubungan seksual dengan hewan) dan pedofilia (ketertarikan seksual kepada anak-anak). Kontrak tersebut kemudian dicabut dan sang kepala sekolah mundur sementara.
Sekolah swasta lain di Sydney juga menuai respons tajam karena memuat “pernyataan keyakinan” (statement of faith) dalam dokumen pendaftaran murid. Dokumen itu menyebutkan, hubungan sesama jenis dan identitas transgender “tidak diterima oleh Tuhan”.
Yang dilakukan sekolah-sekolah keagaman di Australia ini bukanlah hal baru. Praktik meminggirkan individu LGBTQIA+ dari ruang religius punya sejarah yang panjang dan berkelok.
Sebagai seorang laki-laki gay dan pastor yang sebelumnya memiliki pandangan konservatif, saya melakukan riset untuk memahami pengalaman orang-orang yang harus melalui dinamika kompleks ini. Saya mewawancarai 24 individu LGBTQIA+ yang telah terlibat di beragam denominasi Kristen konservatif, dan banyak di antaranya yang menempuh pendidikan di sekolah keagamaan.
Wajar jika seseorang berpikir bahwa komunitas LGBTQIA+ dan gereja itu (sebagaimana yang dikatakan salah satu responden saya) “layaknya minyak dan air” – keduanya seakan tidak bisa bercampur. Namun, sebanyak 32 persen pasangan homoseksual di Australia mengaku sebagai pemeluk agama Kristen.
Seiring waktu, kehadiran para individu LGBTQIA+ yang memeluk agama Kristen ini juga semakin terlihat di masyarakat dan suara mereka semakin didengar.
Kisah-kisah dari para partisipan riset saya, hampir seluruhnya menggambarkan trauma keagamaan (religious trauma) yang sangat jelas.
Baca juga: Adakah Ruang Bagi LGBT untuk Beragama?
Memahami Trauma Keagamaan
Trauma keagamaan (religious trauma) didefinisikan sebagai “dampak buruk secara psikoligis yang meluas, yang bisa muncul akibat pesan, keyakinan, dan pengalaman keagamaan yang dialami seseorang”.
Bayangkan seorang murid remaja di sekolah keagamaan yang mulai menyadari orientasinya tidak serta merta heteroseksual. Dalam lingkungan seperti ini, murid tersebut bisa saja diperingatkan setiap hari, seksualitas mereka itu rusak, serta merupakan noda dan sumber rasa malu atau ulah setan.
Mereka juga mendapat peringatan tidak boleh mengalami relasi yang intim karena hal tersebut menandakan bahwa mereka ditakdirkan masuk neraka.
Berdasarkan penuturan para partisipan saya, pesan-pesan semacam ini kerap disampaikan secara halus oleh rohaniwan di koridor-koridor sekolah, secara lantang oleh rekan murid di taman bermain, dan secara formal oleh staf sekolah. Mereka membandingkan orang gay dengan seorang pembunuh. Individu transgender digambarkan sebagai ancaman terhadap lingkungan sosial.
Para orang tua kemudian menyerap pesan-pesan ini dan menerapkannya pada anak-anak mereka, baik secara eksplisit maupun dalam diam.
Dalam riset saya, seorang partisipan menceritakan ulang obrolan yang ia dengar di suatu kelompok anak muda gereja saat ia remaja. Momen ini terjadi ketika ia tengah berproses menyadari dan menerima identitas seksualnya.
Obrolannya hanya tentang hubungan […] dan poin ke-7 dari 15 adalah bahwa ‘menjadi gay itu bukan hal yang nyata’. Saya merasa tertohok saat mendengarnya, apalagi ketika saya tengah di penghujung untuk proses menyadari apa yang terjadi pada saya, kemudian ada orang yang bilang bahwa perasaan ini tidak nyata, bahwa ‘ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan.’
Seorang laki-laki lain yang masih muda menceritakan kepada saya tentang traumanya pada masa remaja ketika ia dipaksa menghadiri konseling.
Itu mungkin adalah titik terendah, karena saya terus-terusan diberi tahu bahwa saya ini sangat buruk, bahwa saya tidak akan pernah jadi apa-apa dalam hidup. Karena perbedaan kecil ini, saya tak akan pernah dianggap manusia, tidak akan dianggap seperti orang-orang lainnya, tidak akan dicintai, tidak akan diterima atau punya pasangan.
Saya juga menanyakan seorang perempuan muda apa yang menurutnya perlu dipahami oleh tokoh-tokoh agama Kristen. Ia menjawab:
Mereka tidak tahu rasanya ingin hampir bunuh diri karena apa yang mereka percayai. Saya mengalaminya, akibat cara mereka memperlakukan saya.
Riset saya menemukan, orang-orang queer bisa jadi mengalami puluhan atau bahkan ratusan momen-momen semacam ini sepanjang kehidupan sehari-hari mereka. Momen-momen inilah yang menyadarkan mereka bahwa mereka tidak sedang berada di lingkungan yang aman.
Seiring waktu, momen yang besar maupun kecil seperti ini (sering disebut sebagai ‘microaggression’) terus menumpuk dan hampir pasti akan memperburuk kesehatan mental seseorang. Riset menunjukkan bahwa anak muda LGBTQIA+ yang terekspos pesan-pesan berbasis keagamaan secara drastis lebih tinggi kemungkinannya untuk mengekspresikan keinginan melukai diri sendiri (self-harm) atau keinginan bunuh diri (suicide ideation).
Baca juga: Al-Qur’an Tak Ajarkan Membenci Kelompok LGBT: Akademisi Muslim
Yang Dibutuhkan Queer Religius untuk Merasa Aman
Karena mereka merupakan bagian dari komunitas termarjinalkan, pemeluk agama – yang dalam konteks riset saya adalah agama Kristen – yang queer tak serta merta mendapatkan manfaat dukungan sosial dan faktor pelindung yang secara umum tersedia bagi populasi pemeluk agama tersebut.
Pihak yang semestinya memberikan keamanan dan perlindungan bagi mereka (orang tua, guru, dan pastor), dalam banyak kasus, justru menjadi pihak yang menyebabkan dampak buruk dan trauma. Para peniliti ilmu perilaku mengkategorikan pengalaman ini sebagai bentuk stres minoritas.
Seorang partisipan membagikan pengalamannya:
Ketika kita belajar di sekolah Kristen, hal terakhir yang kita harapkan adalah perundungan frontal oleh guru dan pimpinan sekolah. Merekalah yang harusnya bisa kita andalkan ketika kita butuh bantuan, tapi mereka malah menjadi orang terakhir yang ingin saya temui dan justru membuat saya merasa tidak aman.
Semua ini dibangun atas dasar interpretasi kitab suci yang menekankan bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya sebagai makhluk yang heteroseksual dan cisgender – selain itu adalah bentuk “kerusakan”.
Penting untuk kita catat bahwa beberapa kritik paling keras terhadap Citipointe Christian College justru datang dari pemeluk Kristen lainnya (banyak di antaranya punya koneksi dengan sekolah).
Ini adalah bukti, ada sebagian besar (dan terus tumbuh) dari gereja yang tengah berupaya memahami kembali pesan-pesan kitab suci seiring munculnya temuan-temuan riset terkait gender dan seksualitas.
Solusi legislatif hanya satu dari sekian respons terhadap kompleksitas eksklusi komunitas LGBTQIA+. Sebagai masyarakat, kita perlu terus berupaya memahami isu-isu ini tanpa jatuh pada perangkap “Kristen versus komunitas queer”.
Dan, meski memahami berbagai pengalaman terkait trauma ini adalah hal yang vital, perbaikan hanya bisa dilakukan ketika orang-orang queer merasa aman untuk berhubungan dengan komunitas keagamaan tanpa adanya ancaman diskriminasi. Para tokoh agama kini perlu bergelut dengan bagaimana caranya melakukan ini. Perubahan tengah terjadi, tapi jalan menuju inklusivitas masih cukup jauh.![]()
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.






















