Seksisme dalam Sains: Sudah Sejak Zaman Darwin
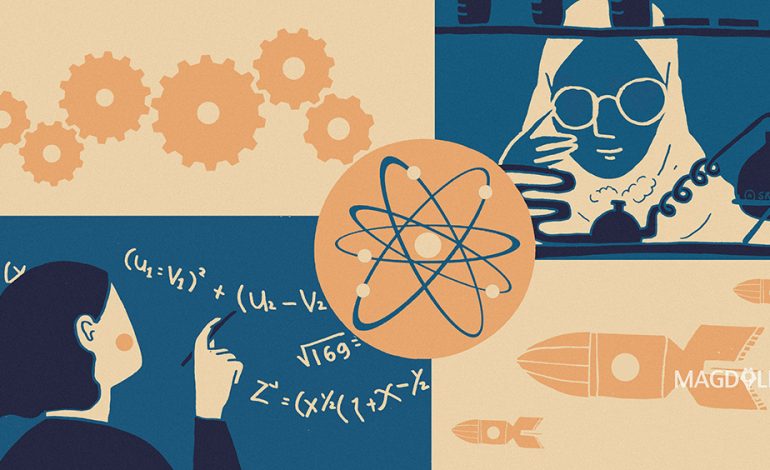
Pada 2014 lalu, Silicon Valley dan dunia sempat dihebohkan dengan sebuah memo yang kemudian dikenal dengan Google Manifesto. Memo itu ditulis James Damore, karyawan laki-laki Google yang mempertanyakan kebijakan keberagaman dan inklusi di Google dan mengklaim bahwa sains mendukung pernyataannya.
Baca Juga: 11 Perempuan Berpengaruh dalam Bidang Sains di Dunia
Melalui memo 10 halaman yang ia unggah secara daring, Damore menyuarakan keraguannya terhadap program-program yang ia anggap membuang-buang waktu dan biaya. Menurutnya, perempuan kurang cocok untuk peran-peran teknis dibandingkan laki-laki.
“Saya hanya mau bilang, distribusi preferensi dan kemampuan laki-laki dan perempuan berbeda sebagian karena alasan biologis dan perbedaan ini mungkin menjelaskan mengapa kita tidak melihat representasi yang setara antara perempuan di bidang teknologi dan posisi pemimpin,” tulis Dermore dikutip dari Inc.
Damore melanjutkan, permasalahan ini hadir karena rata-rata perempuan lebih terbuka pada perasaan dan estetika daripada ide layaknya laki-laki. Menurutnya, perempuan juga lebih cenderung memiliki ketertarikan pada manusia dalam hubungannya dengan relasi sosial daripada benda seperti laki-laki.
Untuk mendukung pernyataannya ini ia pun mengutip karya Simon Baron-Cohen, The Essential Difference. Dilansir dari Vox, karya psikolog Inggris ini dikenal membahas perbedaan signifikan antara otak laki-laki dan perempuan. Ia menyebut otak laki-laki sebagai “otak sistematisasi” sedangkan otak perempuan adalah “otak empati”. Artinya, secara biologis laki-laki diprogram untuk fokus pada objek. Ini membuat mereka cenderung akrab dengan matematika dan sistem pemahaman, sementara perempuan diprogram untuk fokus pada orang dan perasaan.
Merespons memo Damore, CEO Google Sundar Pichai pun memutuskan memecatnya dan dalam keterangan di CNN ia mengatakan manifesto Damore telah melewati batas dengan “melanggengkan stereotip gender yang berbahaya” di tempat kerja.
Baca Juga: Dekolonisasi Sains: Memerdekakan Ilmu Pengetahuan dari Watak Kolonial
Seksisme dalam Sains yang Terus Langgeng
Manifesto Google yang ditulis Damore memang mengejutkan banyak pihak. Lebih mengejutkan lagi, karena pengikutnya mungkin tak sedikit. Pemahaman begini mengakar kuat. Misalnya, seperti yang ada dalam buku Men Are from Mars, Women Are from Venus karya John Gray masih populer hingga sekarang. Atau perbincangan soal kesetaraan gender di media sosial selalu berujung pada argumen angkot galon dan kuli bangunan.
Sains memang sering dijadikan patokan perbedaan kemampuan tubuh laki-laki dan perempuan, serta dianggap sebagai patokan objektif dan netral. Hal yang membuatnya jadi tidak terbantahkan. Padahal jika ditelusuri sejarahnya, sains sejak dulu hingga kini tak pernah lepas dari bias peneliti. Salah satunya bias gender yang berakar dari seksisme.
Bias gender dalam sains contoh terdekatnya bisa dilacak sejak Charles Darwin menuliskan teori seleksi seksual. Angela Saini, jurnalis asal Inggris dalam Inferior: How Science Got Women Wrong-and the New Research That’s Rewriting the Story (2017) menuliskan, teori seleksi seksual Darwin secara spesifik jadi fondasi perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki.
Perbedaan ini tidak mengacu pada fungsi reproduksi mereka, seperti menstruasi, hamil, dan melahirkan, tetapi pada peran seksual perempuan dan laki-laki dalam hubungan heteroseksual. Makhluk hidup berjenis kelamin perempuan menurut Darwin hidup untuk menemukan pasangan laki-lakinya agar mereka bisa bereproduksi. Sedangkan laki-laki hidup untuk “membuahi” perempuan dan seharusnya saling bersaing untuk mendapatkan kesempatan bereproduksi.
Lewat persaingan dalam bereproduksi, Darwin menekankan dominasi laki-laki atas perempuan adalah dinamika sosial universal laki-laki—semacam tujuan alamiah laki-laki eksis di dunia ini. Secara alamiah harus mereka penuhi untuk bertahan hidup. Karenanya, secara biologis perempuan dan laki-laki, menurutnya, memiliki kemampuan berbeda.
Sementara perempuan secara biologis diciptakan memiliki kecerdasan yang lebih inferior dari laki-laki. Mereka lebih pasif, lemah secara fisik, dan emosional. Berkebalikan dengan laki-laki yang ia anggap lebih cerdas, superior, dengan fisik yang lebih kuat.
Fondasi teori tentang perbedaan biologis perempuan dan laki-laki ini lalu berusaha ditelusuri oleh Saini. Hal ini ia lakukan lewat penelusuran korespondensi surat antara Caroline Kennard, anggota aktif gerakan perempuan di Boston dengan Darwin pada akhir tahun 1881.
Dalam sebuah surat, Kennard menuliskan bahwa ia sangat yakin orang jenius seperti Darwin tidak mungkin percaya bahwa perempuan secara alamiah lebih rendah daripada laki-laki. Ia berasumsi pandangan ini hadir karena karya Darwin telah disalahartikan. Namun sayangnya asumsi yang dilontarkan Kennard ditolak mentah-mentah oleh Darwin. Ia menuliskan balasannya.
“Saya tentu saja berpikir bahwa perempuan, meskipun secara umum lebih unggul daripada laki-laki (dalam hal) kualitas moral, (tetap) lebih rendah secara intelektual,” ia menuliskan pada Kennard, “Dan menurut saya, susah sekali membuat perempuan setara dengan laki-laki secara intelektual (jika mengacu pada Hukum Pewarisan Mendel).”
Tidak berhenti sampai di situ, Darwin melanjutkan jika perempuan mau mengatasi ketidaksetaraan biologis ini, mereka harus menjadi pencari nafkah seperti laki-laki. Tetapi menurutnya, ini bukan cara yang baik karena dapat merusak anak-anak dan kebahagiaan rumah tangga.
Seksisme dalam fondasi teori Darwin ini sayangnya dikembangkan ulang, secara terus-menerus, dalam penelitian selama ratusan tahun ke depan. Salah satunya dalam perkembangan penelitian sains mengenai hormon testosteron dan estrogen.
Cordelia Fine, filsuf sains dan profesor psikologi di Universitas Melbourne dalam bukunya mengatakan, sains hormon testosteron selalu diasosiasikan dengan hak biologis yang membuat laki-laki cenderung lebih fokus mencari pasangan seksual (lebih seksual dari perempuan), cenderung lebih berani mengambil risiko, berpikir kritis, dan seterusnya.
Pemahaman sains tentang hormon ini memberikan pandangan ajek di masyarakat bahwa karakteristik kelelakian dan keperempuanan berakar pada faktor biologis. Sehingga tidak dapat diubah. Itu yang membuat perempuan dan laki-laki punya kemampuan berbeda, termasuk kondisi psikologi mereka.
Misalnya ginekolog Inggris terkemuka William Blair-Bell percaya bahwa psikologi perempuan bergantung pada hormon tubuh yang dihasilkan. Ini yang menjaga mereka tetap berada dalam lingkup “tindakan normalnya”. Artinya, perempuan dijaga untuk tetap hidup dan bertindak sesuai dengan “kodrat” sosial semestinya, yaitu menjadi istri dan ibu. Sehingga jika perempuan melangkah keluar dari batas-batas sosial ini, Bell menyimpulkan pasti akibat dari kadar hormon mereka yang tidak seimbang.
Para ilmuwan seperti Bell berpikir bahwa hormon seks tidak hanya memengaruhi perilaku reproduksi. Mereka juga bertanggung jawab untuk “membuat laki-laki menjadi lebih jantan dan membuat perempuan menjadi lebih feminin”. Dengan alasan ini, para ilmuwan berasumsi bahwa hormon seks memiliki keunikan tersendiri bagi setiap jenis kelamin. Hormon laki-laki—testosteron—hanya dapat diproduksi oleh laki-laki, dan hormon perempuan—estrogen—hanya dapat diproduksi oleh perempuan.
Perempuan yang Dikecualikan dalam Sains
Lalu kenapa pemahaman yang bias gender ini ada di dalam sains dan langgeng hingga sekarang? Jawabannya ternyata cukup sederhana.
Sejak ratusan tahun lalu hingga kini, perempuan masih dikecualikan dalam sains. Tidak mudah menemukan ilmuwan perempuan dalam catatan publik, tak semudah menemukan ilmuan laki-laki. Bahkan hingga saat ini, jumlah perempuan yang masuk ke dunia sains masih berada di bawah jumlah laki-laki, terutama dalam disiplin ilmu tertentu. Pada 2018, dua psikolog dari Inggris menerbitkan jurnal penelitian berjudul “The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education.”
Paradoks ini merujuk pada fakta bahwa perempuan lebih cenderung kurang terwakili dalam bidang sains di negara-negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi. Angka-angka A-level (jenis program berfokus pada bidang ilmu tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para siswa) menunjukkan hanya 12 persen kandidat perempuan di bidang komputasi dan 22 persen di bidang fisika. Ini disampaikan oleh Gina Rippon, Profesor Emeritus Pencitraan Saraf Kognitif, Universitas Aston dalam artikelnya yang diterbitkan di The Conversation.
Ketidakterwakilan perempuan ini menariknya juga karena anggapan perempuan tidak sesuai dengan citra umum seorang ilmuwan. The lone male genius researcher. Claire Jones, dosen Senior Sejarah Ilmu Pengetahuan, Universitas Liverpool memberikan penjelasan mengapa sains masih memiliki bias maskulin dan perempuan dalam sejarahnya selalu menjadi bayang-bayang laki-laki. Persis seperti karakter Judith Shakespeare dalam buku Virginia Woolf bertajuk A Room of One’s Own (1929).
Jones pertama mencontohkan astronom abad ke-19, Caroline Herschel. Herschel hidup dalam bayang-bayang kakaknya, William. Lalu, fisikawan Lise Meitner yang tidak mendapatkan Hadiah Nobel 1944 untuk penemuan fisi nuklir. Hadiah yang justru jatuh ke tangan kolaborator juniornya, Otto Hahn. Atau Marie Curie diserang di media karena dianggap mengambil kredit karya suaminya, Pierre.
Sejarawan Margaret Rossiter menjuluki bias sistematis terhadap perempuan ini sebagai “Efek Matilda”.
Sebelum abad ke-20, satu-satunya cara perempuan dapat menegosiasikan akses ke ilmu pengetahuan adalah berkolaborasi dengan anggota keluarga atau teman laki-laki, dan itu pun hanya jika mereka kaya. Hal ini membuat mereka menjadi mangsa dari asumsi hierarkis tradisional bahwa perempuan adalah pendukung dan penolong laki-laki.
Sikap ini pun diperparah karena perpindahan sains ke lingkungan institusional. Lingkungan yang secara sistematis lebih mengakomodir ilmuwan laki-laki. Tak heran, ilmu pengetahuan mereka menjadi tidak terlihat dalam sejarah. Terlihat dari hanya sedikit orang yang tau Henderina Scott, salah satu orang pertama yang menggunakan time-lapse photography untuk merekam pergerakan tanaman pada 1903.
Ini juga jadi satu alasan mengapa perempuan menjadi lebih aktif dalam disiplin ilmu yang masih sangat bergantung pada kerja lapangan, seperti astronomi dan botani. Di sinilah ilmu pengetahuan mulai terpecah menjadi hierarki ilmu-ilmu “keras” yang didominasi laki-laki, seperti fisika, dan ilmu-ilmu “lunak”, seperti botani dan ilmu biologi, yang dipandang lebih dapat diterima oleh perempuan.
Baca Juga: Magdalene Primer: Memahami Gender dan Seksualitas
Dalam gempuran seksisme di dunia sains, perempuan pun tak tinggal diam. Perempuan merasa perlu mendekonstruksi ulang pemahaman gagasan sains yang sudah terlanjur langgeng. Caranya adalah mempertanyakan ulang gagasan yang ada dengan menganggap sains adalah produk manusia yang perlu terus diperbaharui. Dalam hal ini banyak perempuan berusaha melakukan penelitian atau riset kembali untuk mencari jawaban atas asumsi-asumsi yang ada.
Dalam buku Angela Saini misalnya, ia mencantumkan banyak penjelasan dari perempuan ilmuwan yang melakukan dekonstruksi penelitian lama.
Salah satu contohnya adalah Adrienne Zihlman, antropolog dari Universitas California. Dalam penelitiannya Woman the Gatherer, Zihlman menyanggah gagasan sains tentang pemburu-pengumpul pada masyarakat purba. Pemburu dan pengumpul sendiri adalah gagasan yang sering dipakai jadi landasan pemahaman bahwa laki-laki lebih superior karena perannya sebagai pemburu.
Dalam penelitian itu, Zihlman justru menemukan adanya pembagian kerja manusia yang tidak terlalu kaku. Semua orang mempelajari segala sesuatu tanpa ada pembagian peran gender. Di masa lalu, ribuan tahun yang lalu, ada kemungkinan besar laki-laki lebih banyak terlibat dalam pengasuhan anak dan meramu, sementara perempuan menjadi pemburu. Perempuan pemburu bahkan lebih cenderung menggunakan anjing untuk membantu mereka membunuh mangsa.
Lewat penemuan-penemuan seperti inilah perempuan mencoba merebut narasi mereka kembali. Tidak hanya di dalam dunia sains yang mengecualikan mereka, tetapi di masyarakat yang selama ini berperan dalam melanggengkan ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender. Hal yang sayangnya berasal dari ilmu pengetahuan yang dianggap objektif dan netral.






















