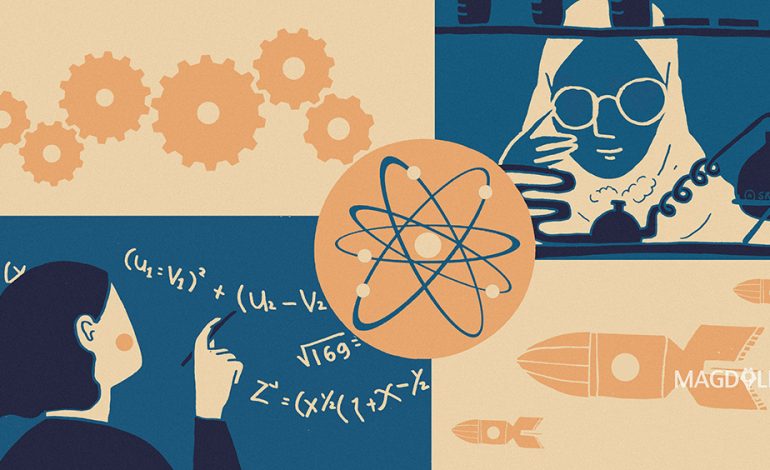Sherina, Keadilan untuk Canon, dan ‘Whataboutism’

“Mungkin akan lebih baik lagi jika Sherina ikut bersuara untuk anjing lain yang dipukul dan dibakar setiap hari di Tomohon, Medan, dan Solo.”
“Sherina ini bukan benci anjing dibunuh, tapi dalam hatinya ada Islamophobia karena kejadiannya di Aceh. Ini anjing tiap hari dimakan oleh kaum Batak, Manado, Solo, elu diam saja.”
Kalimat di atas hanyalah contoh dari banyaknya tanggapan warganet di Twitter, ketika penyanyi Sherina mengungkapkan kekecewaannya terhadap gerombolan orang berseragam yang menyakiti Canon, seekor anjing di Aceh, hingga mati.
Apabila dilihat sekilas, mungkin ada kesamaan antara yang disuarakan bintang film Petualangan Sherina itu, dengan sekelompok warganet yang membahas perdagangan daging hewan di beberapa kota di Indonesia. Ya, mereka sama-sama membicarakan anjing yang menerima perlakuan enggak pantas dari manusia.
Namun, fokus keduanya jelas berbeda. Sherina menginginkan keadilan bagi Canon dan kesejahteraan hewan agar kasus ini tidak terulang, tetapi warganet malah menyalahkannya. Mereka menganggap Sherina tidak pernah menggunakan suaranya selama ini di media sosial, dan menggeser fokus pembicaraan.
Fenomena ini merupakan whataboutisme. Merriam-Webster mendefinisikannya sebagai alat retorika yang dilakukan dengan menuduh orang lain, untuk mengalihkan perhatian dari sebuah perbuatan. Dan merupakan salah satu contoh kesalahan logika dalam berpikir, tepatnya tu quoque, yakni berusaha mendiskreditkan lawan dengan menuduh kemunafikan, tanpa menyangkal argumen secara langsung.
Dalam artikel Wall Street Journal, leksikograf Ben Zimmer menjelaskan penggunaan istilah tersebut berawal di Britania Raya dan Irlandia pada 1970-an. Whataboutisme terdapat dalam sebuah surat yang dipublikasikan The Irish Times, tentang sekelompok orang yang membela Irish Republican Army (IRA), dengan menunjukkan kesalahan yang diduga dilakukan oleh musuhnya.
Terkait persoalan yang terjadi pada Sherina, Wahyu Budi Nugroho, seorang sosiolog dari Universitas Udayana, Bali, melihatnya sebagai nilai-nilai global yang masih berlawanan dengan nilai-nilai lokal.
“Ekologisme dan animalisme itu isu-isu gerakan sosial baru dan belum diterima dengan ramah di tanah air, karena ada beberapa nilai lokal yang bertentangan dan sudah diwariskan dari generasi ke generasi,” katanya pada Magdalene, (27/10). Namun, ia menilai sebagai sebuah wacana, ide-ide baru seperti itu perlu tetap disuarakan dan dikomunikasikan.
Baik disengaja atau tidak, penggunaan whataboutisme akan mengaburkan konteks permasalahan sesungguhnya lantaran dianggap tidak valid. Alih-alih masalahnya terselesaikan, justru menimbulkan debat kusir di antara kedua isu yang berbeda.
Baca Juga: Tuhan, Aku Tidak Mau Jadi Manusia
Whataboutisme Membuat Komunikasi Kontraproduktif
Seseorang yang menanggapi whataboutisme belum tentu melakukannya secara sadar, bisa jadi menurutnya argumen yang diutarakan sepadan atau apple to apple. Tanpa bermaksud membenarkan, hal ini menunjukkan adanya blind spot dalam diri setiap orang, karena sesuatu cenderung dilihat berdasarkan pengalaman pribadi, atau lebih bersimpati terhadap hal-hal yang bersifat lebih dekat dalam hidupnya.
Menurut Wahyu, ada faktor lain yang membentuk seseorang merespons isu dengan whataboutisme. “Sebetulnya cukup sederhana, bisa disebabkan perbedaan nilai, kepentingan, budaya, bahkan ideologi. Atau secara sosiologis diakibatkan oleh perbedaan rasionalitas,” katanya.
Wahyu memetakan rasionalitas ke dalam empat jenis; instrumental, nilai, tradisional, dan afeksi. Jika diuraikan pada persoalan Canon, ia menilai pihak yang menyakiti anjing tersebut hanya menggunakan cara yang dianggap paling efektif untuk memusnahkan hewan yang dianggap mengganggu, tanpa memikirkan dampaknya. Ini termasuk dalam rasionalitas instrumental.
“Di sisi lain, pihak yang iba karena melihat hewan juga memiliki perasaan, cenderung memiliki rasionalitas afeksi. Nah, kalau di sebuah daerah terbiasa memakan daging hewan tertentu, termasuk rasionalitas tradisional,” jelasnya. Namun, jika di daerah lain menganggap tabu saat seseorang memakan daging hewan tertentu, alasannya didasarkan oleh rasionalitas nilai atau afeksi.
Baca Juga: Bukan Budak Kucing, Rico Lebih dari Sekadar Keluarga
Dari perbedaan rasionalitas itu, komunikasi pada setiap orang tidak akan bertujuan membangun pemahaman atau kesepakatan bersama, tetapi lebih menjatuhkan lawan bicara karena mengutamakan ego. “Komunikasinya menjadi kontraproduktif, alhasil masing-masing pihak tidak akan memperoleh apa pun,” kata Wahyu.
Meskipun demikian, whataboutisme dapat digunakan untuk suatu hal baik, ibarat melawan kekerasan dengan kekerasan karena tidak ada jalan lain.
Wahyu menjelaskan, dalam pemikiran eksistensialisme, terdapat istilah “etika ambiguitas”, yaitu memosisikan diri layaknya lawan bicara. Ia pun menggarisbawahi, penggunaannya hanya dapat dilakukan saat kita berhadapan dengan lawan yang fanatik, cenderung memonopoli kebenaran, dan tertutup untuk argumen apa pun.
“Bagi saya, whataboutisme dapat digunakan saat menghadapi pihak-pihak dengan karakter tersebut, atau bisa disebut sebagai ‘manusia satu dimensi’, tetapi hanya sebatas itu saja, bukan lainnya,” terangnya.
Baca Juga: Yang Hilang dari Perbincangan Soal Vandalisme di tengah Aksi
Yang Dilakukan Untuk Merespons Whataboutisme
Jika berada di posisi Sherina, sebagai orang yang menyuarakan sebuah isu dan menerima perlakuan whataboutisme dari orang lain, Wahyu menyebutkan agar kita tidak terpancing pada pengalihan isu yang dilakukan.
“Perlu ditekankan kembali, fenomena sosial budaya di setiap daerah berbeda, tanpa melupakan nilai-nilai universal yang bisa dianut bersama, seperti penghargaan dan kasih sayang terhadap makhluk hidup dan kehidupan,” ucapnya.
Oleh karena itu, kita tetap fokus terhadap permasalahan yang sedang dibahas tanpa menanggapi serangan secara pribadi, mengingat pandangan mereka juga subjektif.
Namun, perlu diperhatikan bahwa yang disuarakan orang lain bukan berarti tidak lebih penting, seperti penjualan daging hewan di beberapa daerah di Indonesia yang tentunya layak untuk lebih disuarakan.
Kita dapat meresponsnya dengan memvalidasi isu yang mereka sampaikan, lalu kembali pada hal yang sedang dipermasalahkan, serta menambahkan data yang sudah dibuktikan apabila diperlukan. Sebab dalam persoalan yang dialami Sherina, memperhatikan kesejahteraan hewan akan menghindari kasus Canon berikutnya, sekaligus lebih sadar dan mengambil tindakan terhadap penjualan daging hewan tertentu.
Kemudian, apabila diri sendiri yang melakukan whataboutisme, kita selalu memiliki opsi untuk mengoreksi atau merevisi pernyataan kita, saat melakukan kesalahan.
“Persoalannya hanya kita mau atau tidak melakukannya. Kalau kita memprioritaskan ego, komunikasi yang tercipta akan irasional, dan cenderung mengobjekkan lawan bicara,” ujar Wahyu.
Ilustrasi oleh Karina Tungari