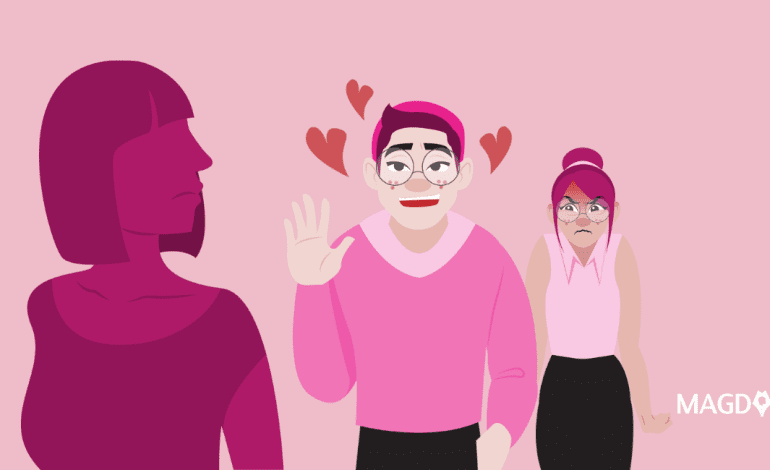
Pada 2022, banyak kasus perselingkuhan yang muncul ke publik. Dari Adam Levine, Arawinda Kirana, Ned Fulmer eks The Try Guys, Reza Arap, hingga skandal Rozy Hakiki dan ibu mertuanya.
Ada kesamaan dari setiap kasus yang muncul: Netizen selalu merespons dengan kemarahan. Saat direct message Levine dan Sumner Troh terekspos misalnya, netizen merutuk lantaran vokalis Maroon 5 itu tega berkhianat. Terlebih sang istri sedang mengandung anak ketiga.
Kemarahan serupa juga tampak dari kasus Arawinda yang di-cancel habis-habisan. Enggak cuma dikomentari fisiknya (body shaming), Arawinda dinilai netizen enggak sejalan dengan nilai-nilai feminisme yang sering diunggahnya di media sosial. Bahkan, cancel culture ini berdampak pada jumlah penonton Like & Share (2022), film terbaru yang dibintangi Arawinda.
Respons senada juga dilakukan The Try Guys. Di video-video terbarunya, mereka menghapus suara dan penampilan Fulmer, sebagai langkah mengatasi skandal perselingkuhannya. Sementara di bagian tertentu yang editing-nya tidak dapat dilakukan sempurna, wajah Fulmer ditutup dengan animasi gajah berwarna pink.
Respons sejumlah kasus di atas menunjukkan bagaimana masyarakat begitu tidak menoleransi perselingkuhan. Dalam hemat mereka, hubungan monogami jadi satu-satunya jenis relasi yang wajar dan legal.
Lantas, apa yang membuat netizen begitu marah dengan kasus perselingkuhan?
Hubungan Monogami yang Ideal dan Heteronormativitas
Setiap orang mengenal jenis hubungan monogami sejak mereka dilahirkan, lewat representasi orang tua, lingkungan tempat tinggal, juga pendidikan. Begitu juga dalam budaya populer yang memotret keluarga ideal, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Pun, plot-plot romantis yang menceritakan happily ever after layaknya pernikahan Disney, atau kegagalan hubungan monogami.
Idealisme yang tumbuh di masyarakat itu, membuat kita terbiasa dengan konsep laki-laki dan perempuan hanya boleh memiliki satu pasangan. Entah pasangan saat pacaran, berhubungan seksual, dan menikah.
Enggak jarang, kita sering mendengar kalimat berikut sebagai alasan pasangan yang menikah: “Kami mencintai satu sama lain.” Padahal, cinta dan monogami merupakan dua hal berbeda. Cinta mendeskripsikan perasaan, sedangkan monogami adalah sistem yang mengikat.
Jika menarik sejarahnya, para ilmuwan sebenarnya masih memperdebatkan kapan manusia menjalin relasi monogami.
Walaupun demikian, Dieter Lukas dan Tim Clutton-Brock–peneliti dari University of Cambridge, Inggris menyebutkan, ada tiga hipotesis yang terus dibicarakan. Di antaranya, menghindari pembunuhan bayi, pengasuhan orang tua laki-laki, dan female spacing. Hal itu disampaikan keduanya dalam The Evolution of Social Monogamy in Mammals (2013).
Dalam kasus ini, female spacing yang dimaksud adalah hubungan monogami muncul, setelah mamalia betina membangun wilayah lebih luas. Tujuannya adalah mendapatkan lebih banyak akses terhadap makanan, sekaligus membangun jarak satu sama lain.
Keadaan itu membuat mamalia jantan lebih sulit memiliki banyak pasangan. Alhasil, itu mendorong mereka untuk tinggal dengan satu pasangan, memastikan anak yang dilahirkan dari pasangan adalah keturunannya, dan mengurangi risiko terluka ketika mengawasi wilayahnya.
Namun, Lukas dan Clutton-Brock mengakui, ketiga hipotesis tersebut lebih cocok diterapkan pada mamalia selain manusia. Sebab, sulit untuk merekonsiliasi lingkungan yang berhubungan erat dengan manusia, saat hipotesisnya bergantung pada populasi betina yang rendah.
Di sisi lain, hipotesis itu dapat berlaku untuk manusia apabila hominin–istilah untuk spesies ordo primata–menganut sistem monogami. Dengan catatan, manusia belum punya kecenderungan untuk berkelompok.
Terlepas dari sejarah, awalnya pernikahan monogami bukan dilakukan karena hubungan antarindividu, melainkan memperluas ikatan keluarga dan bisnis. Seperti pada zaman Mesir Kuno, ketika Cleopatra dan Mark Antony menikah. Keduanya berasal dari kerajaan yang kuat di dunia, sehingga pernikahan itu ditujukan untuk mempersatukan pemerintahan kedua kerajaan.
Lama-kelamaan, hubungan monogami semakin terbangun di masyarakat sebagai konstruksi sosial. Ini tak bisa dilepaskan dari keterlibatan agama yang mengikat pernikahan. Ajaran Islam misalnya, memang mengizinkan suami berpoligami–dengan syarat mampu bersikap adil pada istri. Namun, istri diwajibkan taat terhadap suami dan dilarang melakukan poliandri. Sementara, Kristen dan Katolik tidak melegalkan perceraian antara perempuan dan laki-laki. Ajarannya meyakini, yang telah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia, sehingga perceraian dilihat sebagai dosa.
Di samping itu, sudut pandang heteronormatif ikut berperan, dalam memandang hubungan monogami sebagai satu-satunya jenis relasi ideal. Ini dipengaruhi oleh karakteristik gender; perempuan lemah lembut, keibuan, dan sopan, sedangkan laki-laki lebih kuat, agresif, dan bersikap protektif. Karena itu, laki-laki dan perempuan dianggap mampu melengkapi satu sama lain.
Kemudian, sebagian orang menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan pernikahan–dengan harapan pernikahan akan berlangsung seumur hidup. Membuat persepsi keluarga nuklir yang sempurna, meliputi orang tua cis-heteroseksual beserta anak-anaknya.
Karena itu, ketika kasus perselingkuhan mencuat ke publik, segelintir masyarakat menilai tak ada harapan akan masa depan keluarga tersebut–terutama anak-anak.
Anggapan tersebut seolah melupakan kenyataan, keluarga nuklir yang “ideal” pun–lengkap dengan ayah dan ibu–tidak luput dari permasalahan. Misalnya keluarga yang abusifsecara fisik maupun emosional, terhadap pasangan dan anak. Pun, relasi orang tua yang tidak sehat, di mana terjadi pertengkaran dengan konflik berulang.
Heteronormativitas juga menganggap lebih aman menjalani hubungan monogami. Sebab, komunikasi dan kepercayaan dengan pasangan akan lebih mudah dibangun, dibandingkan terlibat dalam relasi dengan lebih dari satu orang.
Sudut pandang heteronormatif kemudian membentuk gagasan dan penilaian masyarakat, terhadap berbagai aspek kehidupan.
Contohnya ide tentang soulmate, cinta sejati, dan mengukur komitmen dengan kesetiaan secara emosional maupun seksual. Lalu memahami kesetiaan sebagai persamaan dari monogami, memandang perselingkuhan sebagai hubungan non-monogami, dan hanya boleh memiliki ketertarikan romantis maupun seksual terhadap pasangan.
Akademisi asal Australia, Jessica Kean, mendeskripsikan gagasan-gagasan itu sebagai contoh mononormativity. Artinya, relasi romantis maupun seksual dapat berjalan, atau dianggap normal, ketika dijalani oleh pasangan monogami. Dalam riset A stunning plurality: Unravelling hetero- and mononormativities through HBO’s Big Love (2015), Kean menjelaskan sudut pandang heteronormatif dan mononormative yang saling berkaitan.
Keduanya memperkuat tatanan sosial, yang kemudian dikuatkan dalam penetapan hukum bigami–melarang pernikahan ketika pasangan terikat dalam pernikahan lain. Di Indonesia, hukum bigami itu diatur dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu melarang pernikahan, apabila diketahui ada pernikahan lain menjadi penghalang yang sah, untuk pernikahan tersebut. Jika melanggar, pelaku dikenakan pidana paling lama lima tahun penjara.
Lebih lanjut, Indonesia juga mengatur pernikahan monogami dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di sana diatur, suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, begitu pun sebaliknya.
Terlepas dari sistem dan hukum yang berlaku, perspektif masyarakat terhadap perselingkuhan dapat dipengaruhi oleh pengalaman setiap individu. Rusaknya pernikahan orang tua, misalnya, atau menjadi korban perselingkuhan dengan pasangan.
Kejadian tersebut menimbulkan luka dan berdampak pada diri–seperti menyebabkan depresi, kecemasan kronis, post-traumatic stress, dan tidak mampu percaya pada orang lain. Karena itu, melihat kasus perselingkuhan akan membangkitkan emosi dan trauma, atas peristiwa yang dialami.
Beberapa kondisi itu menjawab pertanyaan, mengapa relasi selain monogami dinilai menyimpang–sekaligus menegaskan pandangan masyarakat, bahwa perselingkuhan dianggap pelanggaran. Kemudian ikutan “membalas” pelaku, lewat komentar-komentar julid di media sosial.
Menanggapi Kasus Perselingkuhan
Dalam merespons kasus perselingkuhan, mayoritas netizen menuturkan ujaran kebencian terhadap pelaku. Yang paling kentara, adalah body shaming terhadap Arawinda. Netizen ramai-ramai mengomentari, dan membandingkan penampilan fisik aktor 21 tahun itu dengan Amanda Zahra.
Mungkin netizen beranggapan, perlakuan itu layak didapatkan Arawinda dan pelaku lainnya, setelah merusak hubungan orang lain. Bisa juga karena netizen menilai “sanksi sosial” Arawinda itu belum sebanding dengan dampak perselingkuhan terhadap hidup korban.
Namun, respons yang terbentuk tampaknya berbeda, apabila pelakunya adalah orang-orang di sekitar kita. Bahkan, jika pelakunya diri sendiri. Mungkin kamu–kita semua–akan diam sejenak, berusaha mendengarkan, dan memproses apa yang terjadi, dibandingkan buru-buru menghakimi.
Kalau ada di posisi tersebut, mungkin kamu akan berpikir dua kali sebelum menghukum pelaku perselingkuhan dengan cacian. Mungkin kamu berharap orang-orang di sekitarmu enggak main cancel begitu aja, dan membantu pelaku mencari jalan keluar. Mungkin kamu memilih jadi support system, sekaligus memastikan pelaku tetap memiliki ruang aman, sama seperti korban. Mungkin kamu menyadari, ujaran kebencian bukanlah solusinya. Pada akhirnya, yang pelaku butuhkan adalah ruang untuk tumbuh. Ruang untuk mereka mengevaluasi perilakunya, yang bisa diberikan lewat kesempatan kedua. Sementara, yang dibutuhkan oleh korban perselingkuhan adalah ruang aman dan dukungan, memastikan dia bisa pulih dari lukanya, mendoakan dia, membantu dia bisa mengakses semua yang dibutuhkan. Pun, memastikan dunianya yang runtuh tak makin terbakar karena netizen sibuk menyulut apinya.






















