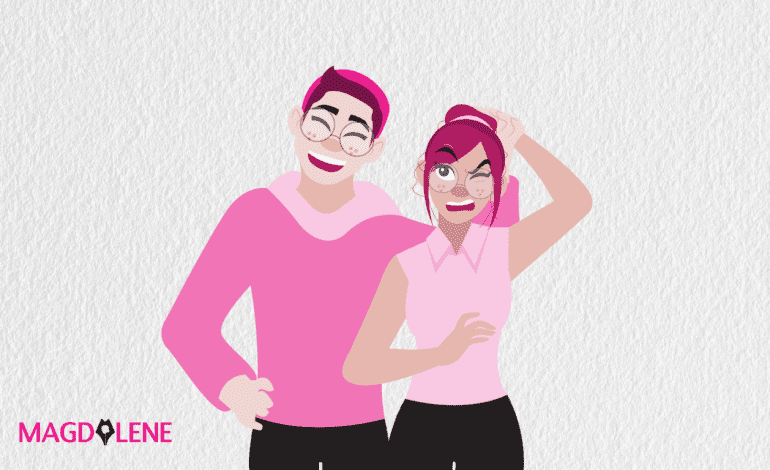Jadi Mahasiswa Bebaskan Saya dari Prasangka

Mengenyam pendidikan dua belas tahun di sekolah swasta bikin saya hafal betul cara bercanda para siswa, pasti enggak jauh-jauh dari mengejek fisik. “Gendut” dan “hitam” sudah lumrah disematkan, layaknya panggilan wajib selain nama yang diberikan ibu dan bapak. Sebagai korban body shaming, saya sudah menyiapkan mental begitu akan melanjutkan pendidikan strata satu, di sebuah perguruan tinggi swasta di Tangerang Selatan.
“Namanya sekolah swasta, pasti anak-anaknya begitu juga lah. Tinggal tunggu saja, panggilan apa lagi yang akan diterima,” pikir saya. Terlebih namanya perguruan tinggi, mahasiswanya berasal dari beragam latar belakang.
Malu punya kulit gelap, wajah enggak rupawan, belum mengerti skincare, makeup, dan cara berpakaian, saya berjalan menunduk layaknya seekor anak babi, setiap memasuki gedung menyerupai telur dinosaurus itu. Bagaimana tidak, banyak teman seangkatan dan kakak tingkat berpenampilan menarik, selalu jadi buah bibir teman-teman satu geng dan bikin harga diri saya makin ciut.
Keadaan diperparah saat diterima sebagai reporter radio kampus, artinya harus membiasakan diri bekerja dalam tim dan bersosialisasi dengan lebih dari 70 anggota lainnya. Tentu mereka menyambut hangat “adik-adik” yang meneruskan tongkat estafet, tapi saya selalu berasumsi ada perbedaan sikap kepada kru baru yang berpenampilan menarik.
Suatu siang setelah perkuliahan berakhir, saya nekat mengunjungi studio radio seorang diri. Ingin keluar dari zona nyaman menjadi motivasi saat itu, biasanya saya mengajak teman dan enggak cakap memulai pembicaraan. Pun pintu radio selalu terbuka untuk anggotanya, bahkan alumni, untuk sekadar berkunjung tanpa keperluan siaran.
Baca Juga: Bagaimana Pandemi Bikin Saya Belajar Mencintai Diri Sendiri
Baru sampai di depan pintu studio, suara hati saya mengajak putar balik ketika melihat tumpukan sepatu dalam rak, menandakan sedang banyak kru yang berkunjung. Ibarat sudah mencemplungkan kaki, tanggung jika seluruh badan tidak basah sekalian. Begitu kenop pintu digerakkan, sumpah serapah ikut tersampaikan dalam hati.
Pasalnya, ada lima orang senior laki-laki dan seorang teman perempuan angkatan saya berparas cantik, sedang menyaksikan video di layar komputer. Kami sempat bertukar sapa ala kadarnya, dan percakapan berhenti di sana. Alih-alih bergabung dengan perbincangan mereka, saya memilih duduk di belakang pintu berwarna biru tua.
Selain takut mengganggu dan enggak tahu cara nimbrung yang enggak menyebalkan, berada di satu ruangan dengan laki-laki yang belum akrab kerap mengintimidasi. Mungkin penyebab utamanya insecurity yang tinggi, karena saya 100 persen yakin ini bukan androphobia—rasa takut terhadap laki-laki.
Tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun, siang itu saya menyimpulkan penampilan fisik yang enggak menarik memengaruhi cara orang lain berinteraksi pada seseorang. Alhasil, saya membangun tembok dengan rekan-rekan di radio kampus.
“Enggak ada yang lebih penting dari bekerja 100 persen dan akrab dengan teman-teman satu divisi,” janji saya tiga tahun lalu.
Baca Juga: Mereka Bilang, Jadi Orang Dewasa Melelahkan
Semua Hanya Prasangka
Hampir setahun menjalani rutinitas sebagai mahasiswa, saya teringat dengan “kondisi mental” yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelum memulai perkuliahan. Setelah “menantikan” sekian lama, kenyataannya enggak ada satu pun mahasiswa yang menjuluki hitam atau gendut. Pun saya jarang mendengar teman-teman satu tongkrongan saling mengejek berdasarkan kondisi fisik.
Sampai hari ini masih terheran, mungkinkah keragaman latar belakang itu membuat mahasiswa bisa menerima satu sama lain? Atau saya beruntung berada di lingkaran pertemanan yang pemikirannya cukup dewasa?
Ibarat lilin yang membutuhkan pemantik api, perjalanan memupuk kepercayaan diri dimulai ketika seorang senior laki-laki yang menjabat general manager baru di radio kampus, menunjuk saya sebagai editor dan kepala reporter. Antara excited dan takut gagal membimbing tim, peluang itu saya terima, sambil terus mempertanyakan kapabilitas diri. Bagi versi 19 tahun diri saya, rasanya enggak pantas-pantas amat menyandang jabatan tersebut.
Baca Juga: Untuk Perempuan Generasi ‘Sandwich’: Kamu Berhak Bahagia
Dari seseorang yang sepertinya tidak pernah “dilihat”, saya masuk ke jajaran “pejabat” yang menerima sorotan. Perlahan saya fokus pada perkembangan diri, dan melupakan kurangnya penampilan fisik, sambil belajar berinteraksi dengan anggota lainnya.
Masa-masa itu cukup sulit, terlebih saya bukan pribadi yang terbiasa beraspirasi dalam diskusi, sehingga kekhawatiran melontarkan ide konyol selalu mampir, membuat tidak bersuara menjadi opsi andalan. Kedua tangan ini tidak pernah absen berkeringat, ketika harus bicara di depan puluhan orang sambil memegang mikrofon, setiap rapat pleno bulanan pada 2019.
Namun, berkat kepercayaan serta dukungan kru lainnya, peran editor yang diemban bukan hanya membawa keberhasilan tim maupun mengadopsi kemampuan baru dalam bidang jurnalistik, melainkan kesempatan melihat ke dalam diri, ada sebuah potensi besar yang bisa digali dan menjadi bekal perjalanan karier.
Itu bukan satu-satunya peristiwa besar yang membuat saya berpikir keras, tentang kelayakan sebagai seorang individu. Satu hari di akhir September 2019, sebuah tawaran jabatan sebagai general manager menghampiri. Tidak seperti tawaran sebagai editor, saya langsung menolak pertama kali mendengarnya. Alasannya enggak lain dan bukan, enggak mampu jadi nahkoda selama setahun masa jabatan.
Lagi-lagi berkat dorongan teman-teman yang memercayakan, keputusan itu berhasil dipertimbangkan dan saya maju ke debat calon general manager, sebagai satu-satunya kandidat perempuan di antara dua laki-laki. Memang, sih saya kalah pada hasil vote. Namun, sejak mengambil kesempatan bertarung modal visi misi di atas panggung, saya sudah menang melawan ketakutan dan pertanyaan besar yang melekat dalam diri sendiri.
Momen-momen itu menjadi titik balik saya harus memberdayakan diri sendiri, bukan bersandar pada buah pikir atau suara orang lain.
Seperti bawang merah yang memiliki banyak lapisan, satu per satu bagian diri saya berhasil dikelupas. Perlahan, saya melihat banyak aspek lebih penting dibandingkan kecantikan bak bintang iklan. Kepercayaan diri itu yang membawa saya terus bergerak sampai hari ini.
Tentu insecurity terhadap penampilan fisik masih ada, bahkan sesekali muncul hingga detik ini. Namun, saya tidak lagi membiarkan diri terkungkung dalam prasangka tanpa jawaban konkret. Mungkin kecantikan adalah privilese bagi yang memilikinya, seperti magnet untuk mendatangkan orang lain di sekitarnya, tapi kemampuan berelasi dan berkomunikasi juga bisa mengatasinya.
Bagi saya, ini perkara membuka diri untuk mengenal nilai dan menerima diri apa adanya, dengan tuntunan orang-orang di sekitar sebagai pembuka jalan. Layaknya bunga yang membutuhkan waktu memekarkan diri, perjalanan ini terus berlangsung seumur hidup dan tidak akan berhenti, kecuali kamu memilih terpenjara dalam asumsi tidak berdasar.