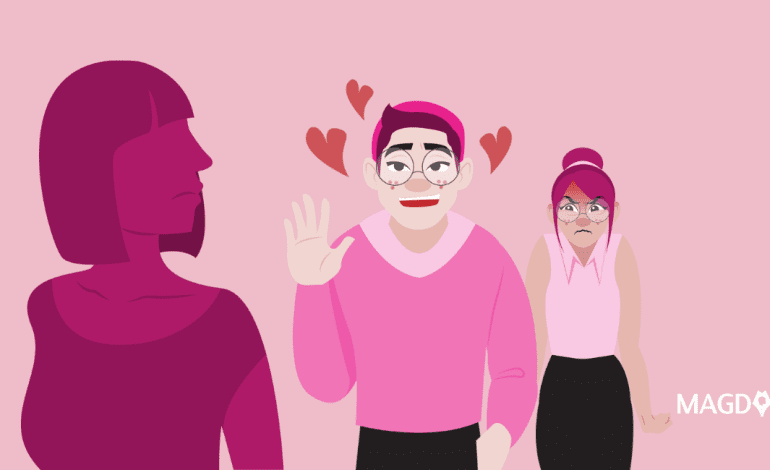Pengalamanku Empat Hari Nonton Film Sedih: Traumatis tapi Juga Lega

Sedari Sekolah Dasar (SD), aku enggan menonton film apapun yang bikin menangis. Pasalnya, menonton film sedih membuatku merasakan trauma panjang. Aku masih ingat, saat serial anime Petualangan Hachi si Lebah Madu diputar di TV zaman 2000-an awal, aku jadi lebih sering mewek.
Baca Juga:Buat Ekspektasi Tak Realistis, Yang Saya Pelajari dari Film Romcom Remaja
Series tersebut menceritakan sosok Hachi yang mencari ibunya. Proses pencarian itu selalu digambarkan secara dramatis dengan scoring yang bikin air mata auto-menetes di pipi. Alhasil, tiap menonton aku serasa menyiksa diri.
Ada lagi tontonan sedih yang membuatku selalu banjir air mata. Adalah Grave of Fireflies film keluaran Studio Ghibli, yang mengorek-ngorek trauma sepanjang cerita. Film ini mengisahkan kesulitan yang dialami oleh Seita dan Setsuko, kakak beradik yang ditinggal mati orang tuanya pada 1945. Tahun di mana Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada Sekutu pasca-dijatuhi dua bom atom.
Dengan plot demikian berat untuk ditonton anak-anak, Grave of Fireflies ternyata sukses membuat banyak generasi 90-an sepertiku trauma. Gara-gara film ini, mataku bengkak kemerahan dan sempat sesak napas karena aku menangis saking kerasnya. Sensasi saat menonton inilah yang akhirnya membuatku memutuskan: Pokoknya aku enggak akan pernah mau menonton film ini lagi seumur hidup.
Sampai akhirnya keputusan yang aku buat lebih dari 15 tahun lalu, aku ingkari pekan ini. Tak ada motivasi khusus selain ingin melihat, apakah aku bisa melawan ketakutan dan traumaku di masa lalu.
Pada (2/1), masih di awal 2023, aku berencana menonton empat film sedih selama empat hari berturut-turut pasca-bekerja. Film-film ini, antara lain Grave of Fireflies (1988), A Silent Voice (2016), Hope (2013), dan Miracle in Cell No. 7 (2013).
Pemilihan keempat film ini didasarkan rekomendasi teman-teman kantorku, pengalaman pribadi, dan rekomendasi yang kubaca di internet. Dengan berbekal Bismillah, aku mengawali percobaanku dengan menonton Grave of Fireflies. The legendary traumatic film I ever watched in my whole life.
Awalnya, aku berasumsi percobaan ini hanya akan membuat kantong air mataku habis dan berpengaruh pada mood-ku yang bisa tiba-tiba jadi gloomy di awal tahun baru. Ternyata tidak. Selama empat hari menonton film sedih, aku mendapatkan pengalaman baru yang unik tapi juga ada yang cukup traumatis.
Baca Juga: Seminggu Nonton Film Horor Asia: Makin Yakin Hantu Barat Enggak Mutu
1. Menangis Sambil Marah-Marah
Saat pertama kali menonton Grave of Fireflies, Jasmine kecil tak pernah satu kali pun marah-marah. Menangis adalah satu-satunya hal yang dia lakukan. Namun, berbeda sekali dengan Jasmine dewasa. Aku baru menyadari jika dahulu aku masih fokus menonton penderitaan Seita dan Setsuko saja. Sebaliknya, kini aku bisa lebih baik memahami penderitaan dua kakak beradik itu semua diakibatkan oleh orang dewasa yang egois.
Orang-orang dewasa ini seenaknya berperang. Menjajah negara lain tanpa memedulikan kondisi masyarakatnya sendiri yang kelaparan dan mati terbunuh karena serangan Sekutu.
Mereka tak ikhlas menampung sanak saudaranya yang masih belia tapi sudah ditinggal mati orang tua. Mereka menjarah makanan anak-anak yatim piatu ini hingga kekurangan gizi, sudah jadi hal biasa. Menampung anak yatim piatu yang butuh suaka tapi di saat bersamaan menyakiti perasaan mereka. Berulang kali mengatakan mereka tak berguna bahkan tak layak hidup.
Inilah realitas yang harus dihadapi Seita dan Setsuko sampai akhirnya mereka berdua memutuskan keluar dari rumah sang bibi dan tinggal berdua di sebuah gua kecil di sekitar danau. Tak punya uang dan tak ada orang dewasa yang mau berbelas kasihan pada mereka, Seita dan Setsuko hidup sehari-hari mengandalkan makanan tak layak tanpa sanitasi yang mumpuni. Akibatnya, jelas terlihat. Setsuko yang masih kecil meninggal karena diare dan malnutrisi disusul oleh kakaknya, Seita tak berapa lama kemudian.
Melihat efek domino dari keegoisan para orang dewasa inilah, selama menonton Jasmine dewasa menangis sambil marah-marah. Memaki-maki dengan segala kata kasar sambil memegang erat meja karena tak habis pikir dengan kelakukan para manusia yang termakan oleh egonya sendiri. Hanya berpikir tentang diri mereka sendiri hingga anak kecil, kelompok yang paling rentan harus menerima konsekuensinya.
Lewat pengalaman ini Jasmine dewasa, aku, menyadari film ini bukan dibuat hanya untuk mengosongkan kantong air mata. Namun, sengaja dibuat untuk menyampaikan pesan anti-fasisme. Pesan yang aku yakin dibuat agar generasi muda jadi lebih paham bahwa tak ada hal baik yang didapatkan dari perang atau konflik besar apapun. Hal satu-satunya yang didapat hanya kesengsaraan berkepanjangan.
2. Tontonan Sedih Bisa Membangkitkan Trauma
Pada hari ketiga, (4/1) aku memutuskan menonton A Silent Voice. Aku dulu pernah menontonnya semasa kuliah dan ku akui memang film ini sedih. Tapi aku merasa pengalaman pertama menonton film ini belum utuh karena terdistraksi bukan main. Hasilnya aku hanya sekilas mengingat fragmen-fragmen kecil dari film ini bahkan satu-satunya adegan yang masih kuingat jelas hanya bagian ending-nya saja.
Karena pengalaman menonton yang kurang khusyuk ini, aku akhirnya putuskan menonton kembali. Ternyata keputusanku ini bagaikan buah simalakama. Aku menemukan film ini begitu apik meramu narasi tentang perundungan dan penerimaan diri. Tetapi, di satu sisi narasi ini memantik trauma masa kecilku dulu.
Ya, aku adalah penyintas perundungan semasa sekolah. Tubuhku gemuk, kulitku sawo matang, dan dibandingkan teman-teman sekelasku (kelas akselerasi), aku adalah anak yang tak begitu pintar. Tak pernah dapat ranking di atas 10. Dengan keadaanku ini, dulu aku dirundung. Aku dipanggil black country karena ciri fisik dan kecerdasanku yang tak sama dengan mereka.
Aku sudah biasa dikucilkan. Tak diajak main atau mengobrol. Kalau pun mengobrol di depanku, mereka selalu memberikanku julukan black country serasa berkata dengan sinis.
Dulu aku sempat melaporkan perundungan ini kepada guru wali kelasku. Tapi dibilang teman-temanku lumayan licik karena mereka mengaku tak pernah merundungku dan justru memasang topeng baik di saat ditanyai wali kelasku.
Trauma pernah dirundung ini membuatku selama menonton A Silent Voice lumayan tak menyenangkan. Aku sudah lama sekali tidak menangis sekeras Rabu lalu. Bahkan di salah satu adegan aku sampai sesak nafas dan harus berpegangan pada meja karena tak sanggup melihat adegan yang begitu mengingatkanku pada masa lalu.
Rasanya sungguh tidak enak. Apalagi selama menonton aku menyadari satu hal. Berbeda dengan film ini di mana si perundung Shōya Ishida meminta maaf pada korbannya, Shouko Nishimiya, orang-orang yang merundungku tidak pernah meminta maaf padaku. Aku tidak pernah mendapat a proper closure dan harus menerima konsekuensinya bertahun-tahun seorang diri.
Dari pengalamanku menonton A Silent Voice aku jadi paham. Ternyata apa yang kita tonton bisa memantik trauma. Sehingga, jika kita memutuskan untuk menonton sesuatu, setidaknya pikirkan satu dua hal yang setidaknya bisa membuat kita terdistraksi agar trauma tersebut tidak terlalu berdampak pada kesehatan mental kita selanjutnya.
Baca Juga: ‘Emily In Paris’ Serial Absurd, Tapi Tontonan Sempurna di Kala Pandemi
3. Film Sedih Ternyata Bisa Membuat Lega
Film sedih memang bisa memantik trauma, tapi ternyata juga membuat kita merasa lebih lega. Inilah yang aku rasakan dalam setelah puas menangis menonton film-film sedih. Memang pada saat kejadian, rasanya tidak enak. Apa enaknya sih nangis sampai marah-marah atau sesak nafas? Tapi efeknya setelah itu ternyata cukup menakjubkan.
Susah dijelaskan dalam kata-kata, tapi pasca menangis keras, aku merasa lebih lega. Kalau memakai bahasa sehari-hari mungkin bisa dideskripsikan dengan lebih plong. Rasanya seperti ada sesuatu yang tersumbat lalu dicoba dikeluarkan dalam satu helaan nafas.
Terdengar absurd memang, untungnya pengalamanku ini bisa dijelaskan lewat sains. Dilansir dari Nancy Soekarno, psikolog yang diwawancarai oleh Refinery29 mengatakan menonton film sedih dapat membuat kita merasa lebih baik apalagi jika kita memang sedang dalam suasana hati yang buruk alias bad mood. Hal ini tak lain karena ada peningkatan endorfin. Senyawa kimia yang membuat kita merasa senang karena berfungsi layaknya painkiller atau obat pereda sakit.
Ini terbukti pada sebuah studi yang dilakukan Universitas Oxford merekrut pada 169 orang, yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Mayoritas dari mereka menonton film sedih, Stuart: A Life Backwards (2007) yang bercerita tentang tunawisma muda yang juga seorang difabel, pecandu narkoba, dan alkoholik. Pada saat yang sama, 69 orang lainnya menonton beberapa film dokumenter tentang sejarah alam, arkeologi, dan geologi.
Hasilnya, rata-rata orang yang menonton film Stuart: A Life Backwards menunjukkan perubahan suasana hati yang luar biasa. Toleransi rasa sakit mereka meningkat sebesar 13,1 persen, sedangkan pada mereka yang menonton film dokumenter menurun sebesar 4,6 persen. Jadi kalau kamu sedang bad mood mungkin menonton film sedih bisa jadi opsi barumu nih. Tapi tetap ingat ya, jika kamu merasa apa yang kamu tonton bisa memantik trauma, lebih baik kamu coba cari opsi tontonan lain saja.