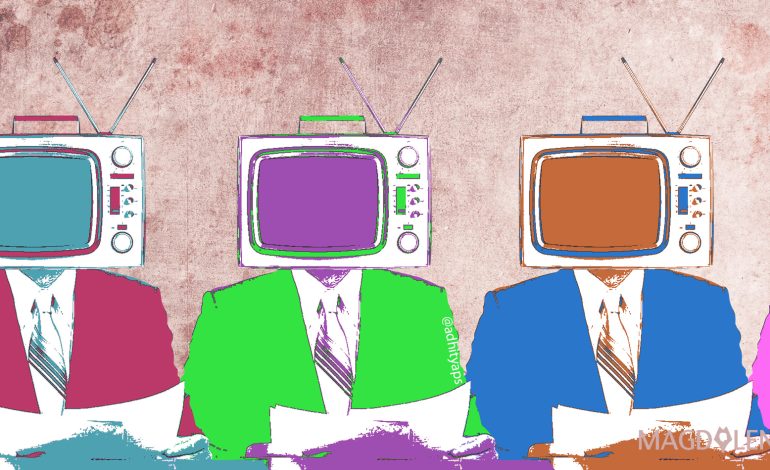Siapkah Indonesia Usung ‘Genderless Fashion’?

November 2020 lalu, penyanyi sekaligus aktor Harry Styles menggegerkan dunia maya sebagai laki-laki pertama yang tampil solo di cover Vogue Amerika Serikat edisi Desember 2020. Saat itu, ia mengenakan gaun rancangan Harris Reed, desainer asal Inggris dan Amerika yang mengklaim dirinya non-biner.
Caranya mengekspresikan diri pada majalah itu menuai pro dan kontra. Misalnya penulis asal Amerika Serikat, Candace Owens, berkomentar lewat akun Twitternya, tidak ada masyarakat yang bisa bertahan tanpa peran kuat laki-laki. Di akhir tweet-nya ia menambahkan, “Bring back manly men.”
Kepada The Guardian, Styles mengatakan terdapat garis batas yang kabur dalam cara berpakaian dan ia ogah memusingkan kategorisasi pakaian antara laki-laki dan perempuan. Konon, itu jadi salah satu caranya merefleksikan dan menerima diri.
Peristiwa itu kembali memunculkan istilah genderless fashion ke permukaan, dilanjutkan dengan London Fashion Week 2021 yang memilih menggabungkan pakaian laki-laki dan perempuan menjadi gender neutral.
Baca Juga: Potensi ‘Sustainable Fashion’ di Indonesia
Perbedaan Genderless & Androgynous Fashion
Istilah genderless fashion digunakan untuk penggunaan pakaian tanpa dibatasi oleh gender tertentu, sehingga seseorang dapat lebih bebas mengekspresikan dirinya.
Meskipun kembali diperbincangkan selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya ungkapan “clothes have no gender” yang merujuk pada genderless fashion telah dimulai sejak 1968, ketika desainer Pierre Cardin, Andre Courreges, Paco Rabanne, dan Mary Quant membuat “Space Age”.
Keberadaannya menandakan era baru para desainer yang bertujuan untuk melengkapi era mode berikutnya, yakni dengan tampilan busana sederhana, memiliki siluet ramping, dihias pola grafis dan kain sintetis tanpa asosiasi gender.
Meskipun sebelumnya rumah fesyen membatasi pakaian laki-laki dan perempuan, kini beberapa brand telah mengusung konsep genderless fashion pada pakaiannya, seperti Bode, Gucci, Zara, dan H&M.
Sementara androgynous fashion merupakan cara berpakaian seseorang dengan menggabungkan karakteristik feminin dan maskulin. Meskipun tidak selalu demikian, gaya berpakaian ini menjadi sarana seseorang mengekspresikan identitas gendernya, tanpa ada keterkaitan dengan orientasi seksual dan jenis kelamin saat dilahirkan.
Jovi Adhiguna Hunter, seorang influencer Indonesia, adalah salah satu figur publik yang mengusung androgynous fashion dalam cara berpakaiannya. Ia mengombinasikan pakaian laki-laki dan perempuan, misalnya mengenakan kemeja dengan celana pendek, dan sepatu heels.
Dalam wawancaranya bersama VICE, Jovi menceritakan gaya busananya sesuka hati tanpa terikat pada satu gender, asalkan ada elemen laki-laki dan perempuan dalam satu penampilan.
Selain Jovi, David Bowie bahkan mempresentasikan alter ego-nya, Ziggy Stardust, sebagai simbol ambiguitas seksual, saat ia merilis album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars pada 1972. Saat itu, androgini menjadi arus utama dan berdampak besar pada budaya pop, disusul dengan aktor John Travolta yang membintangi Grease dan Saturday Night Fever.
Baca Juga: Bisnis Baju ‘Preloved’ Stabil Selama Pandemi
Sederet figur publik internasional lainnya juga mengusung gaya berpakaian androgini, seperti Dave Navarro, Jared Leto, Timothée Chalamet, Anne Hathaway, Lily Collins, dan Victoria Beckham.
Fesyen Bagian dari Konstruksi Sosial
Lebih dari sekadar pakaian, dalam penelitian yang berjudul “Looking the part: Identity, meaning and culture in clothing purchasing —Theoretical considerations (1998), C.A. Dodd dkk. menyampaikan fesyen merupakan produk sosial dan memiliki sifat rangkap, yakni memberikan rasa aman dan keseragaman, serta kesempatan untuk personalisasi diri dengan merepresentasikan kepribadian.
Hingga abad ke-18, tidak ada perbedaan signifikan antara cara berpakaian laki-laki dan perempuan. Keduanya mengenakan gaun panjang berdekorasi, bahkan para bangsawan mengenakan wig, atasan renda, setelan sutra berwarna pink dengan hiasan bernuansa gold dan silver. Pakaian ini menunjukkan kelas sosial yang lebih tinggi.
Barulah di abad ke-19, perbedaan seks dinilai lebih penting ketimbang tatanan sosial. Di saat itulah laki-laki mengalami perubahan ekspresi identitas lewat pakaian, sehingga meninggalkan pakaian dan pernak-pernik pada perempuan. Mereka mengesampingkan keindahan berpakaian dan hanya melihatnya sebagai sesuatu yang berguna.
Baca Juga: Tren Hijab Syar’i: Murni untuk Agama atau Kapitalisme?
Senior Analyst di World Global Style Network (WGSN), Nick Paget, mengatakan secara teori, pakaian inklusif gender dapat diwujudkan dalam bentuk pakaian apa pun. Dikutip NBC News, Paget menjelaskan pakaian hanya dapat mengekspresikan satu gender merupakan contoh konstruksi sosial lain yang perlu dibongkar.
Tanpa disadari, secara autopilot kita memilih dan mengenakan pakaian dengan bentuk dan warna yang dianggap layak, sesuai konstruksi sosial tentang gender. Tentunya ini berawal dari pakaian yang dipilihkan orang tua sejak kita dilahirkan, termasuk pemilihan warna; biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan.
Kategorisasi pakaian laki-laki dan perempuan juga ditemui pada setiap toko pakaian, mengkotak-kotakkan preferensi sesuai jenis kelamin. Pun itu dianggap merepresentasikan karakteristik keduanya; laki-laki ingin menunjukkan sisi maskulin dan kekuatan, sedangkan perempuan merepresentasikan keanggunan dan kelembutan.
Ditambah kehadiran tren fesyen yang dinilai dengan standar kecantikan, memastikan setiap orang berpakaian sesuai dengan gender yang dibangun dalam masyarakat.
Ada satu hal yang mengganggu pikiran saya. Saat perempuan mengenakan setelan, mereka dianggap memiliki aura powerful. Lalu, mengapa saat laki-laki mengenakan rok atau gaun, pakaian berwarna cerah, berenda, dan bermotif bunga disebut mengurangi kejantanan mereka?
Padahal, jika kita berkaca pada pakaian adat Indonesia, ada beberapa daerah yang tidak menggunakan celana sebagai bawahan laki-laki, seperti payas agung dari Bali dan jarik dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, tampaknya penggunaannya hanya di acara tertentu, membuat rok atau gaun pada laki-laki tidak dinormalisasi dan dianggap feminin.
Merujuk pada penelitian Nadiah Pambudi dkk., berjudul Studi Preferensi Masyarakat Jakarta Terhadap Genderless Fashion (2019), sepertinya Indonesia membutuhkan waktu panjang untuk mengadaptasi genderless fashion, lantaran pakaian seperti rok, berwarna cerah, dan memiliki siluet seperti dikenakan perempuan, tidak memiliki unsur maskulin untuk dikenakan oleh laki-laki.
Untuk saat ini, mungkin kita bisa mengamini agar setidaknya warganet yang julid atas laki-laki dengan gaya berpakaian androgini bisa berkurang.