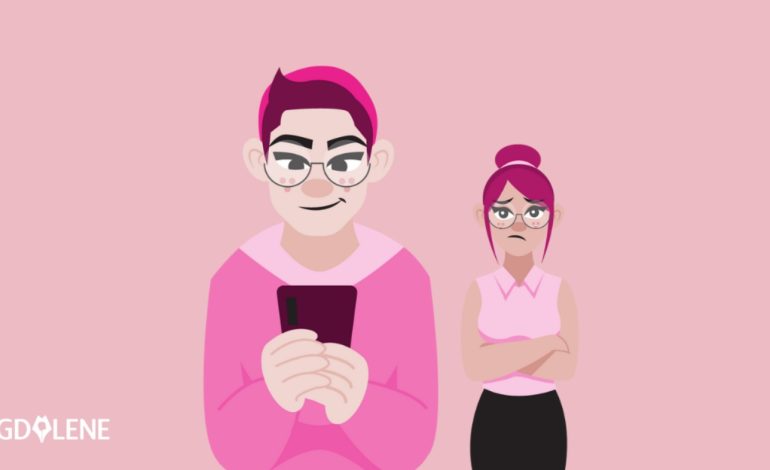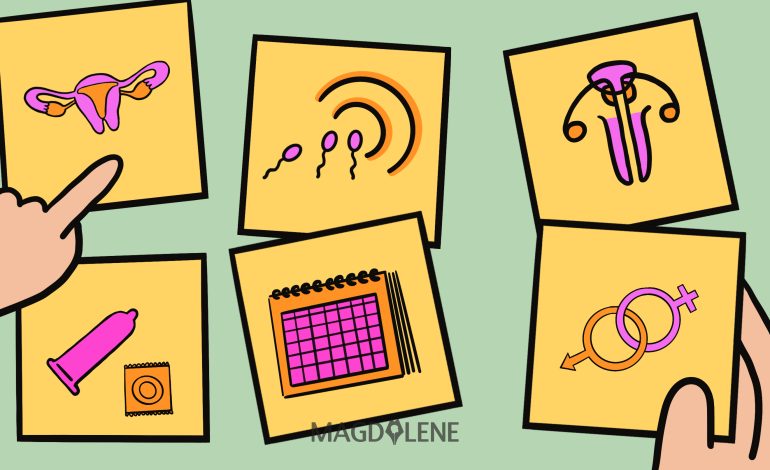Kematian Mahsa Amini, Pemaksaan Jilbab, dan Protes Massa di Iran
Lebih dari perkara pemaksaan jilbab, unjuk rasa atas kematian Mahsa Amini merupakan perlawanan terhadap masalah struktural.

Perempuan asal Iran Mahsa Amini, meninggal pada (16/9). Itu berawal ketika polisi moral menangkapnya di stasiun metro Teheran, ibu kota Iran, sepulangnya ia dari kampung halaman di Saqqez, Provinsi Kurdistan. Penangkapan tersebut dilakukan lantaran Amini tidak menggunakan jilbabnya dengan benar.
Soal pemakaian jilbab di Iran ini memang diatur tegas dalam Undang-undang setempat. Iran yang ditetapkan sebagai Republik Islam pada 1979, mewajibkan perempuan mengenakan mantel atau tunik panjang sebagai outer dari pakaian mereka, dan harus menutupi kepalanya dengan syal. Sementara, laki-laki wajib memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang.
Mengutip Bloomberg, aturan berpakaian yang diatur dalam undang-undang itu mulai berlaku ketika ulama Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke Iran setelah diasingkan, menggantikan posisi Mohammad Reza Shah Pahlavi yang pro-Barat.
Baca Juga: Tubuhku Bukan Milikku: Perkara Ruwet Dipaksa Berjilbab
Kemudian, para aktivis perempuan yang telah berjuang untuk revolusi mulai terpecah. Mereka mendorong berbagai batas yang diizinkan dalam berpakaian. Karena itulah, sebagian perempuan mulai mengenakan syal dan jubah yang longgar, serta kompak memakai celana legging. Gaya berpakaian tersebut seperti yang dikenakan Amini ketika ditangkap. Padahal, sebenarnya gaya ini cukup umum dikenakan di sebagian besar kota.
Secara kronologis, Amini ditahan di pusat penahanan di Vozara bersama sejumlah perempuan lain, yang dianggap melanggar aturan berpakaian. Di tempat tersebut, seharusnya ia menerima ceramah terkait berpakaian yang layak sesuai ketentuan yang ada. Namun, setelah berita tentang kematiannya terdengar, stasiun televisi di Iran merilis rekaman CCTV, di mana Amini jatuh ke lantai dari tempat duduknya.
Berdasarkan keterangan kepolisian di Teheran, Amini mengalami gagal jantung. Namun, keluarga menilai kejanggalan dari keterangan itu. Dalam hemat mereka, polisi telah memukuli perempuan 22 tahun itu dan menutupinya. Pasalnya, Amini tidak memiliki kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan gagal jantung, dan terdapat perubahan warna pada wajah dan kakinya.
Melansir Financial Times, sejumlah perempuan yang pernah ditahan di Vozara oleh polisi moral mengatakan, mereka pernah menyaksikan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan terhadap perempuan. Perlakuan itu dilakukan sebagai hukuman bagi mereka yang melawan penangkapan, atau meneriaki polisi.
Atas peristiwa yang terjadi pada Amini, warga Iran melakukan unjuk rasa di sejumlah kota sebagai bentuk protesnya. Mereka meminta agar undang-undang yang mewajibkan untuk berhijab dihapuskan, atau setidaknya bersifat menjadi pilihan agar perempuan memiliki kebebasan. Sebab, mereka diwajibkan berjilbab sejak berusia sembilan tahun.
Lebih dari itu, sebagian demonstran juga meneriakkan kalimat-kalimat agar negara tersebut tidak lagi menjadi republik Islam. Pun ada yang menyebutkan, mereka tidak menginginkan keberadaan pemimpin (mullah). Bahkan, sejumlah perempuan menggunting rambut dan membakar penutup kepalanya, sebagai bentuk solidaritas terhadap Amini.
Unjuk rasa tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Iran. Namun, sebenarnya yang melatarbelakangi aksi masyarakat lebih besar dari ketidakadilan yang terjadi pada Amini.
Baca Juga: Represi Tubuh Perempuan Lewat Larangan Berjilbab di India
Protes terhadap Sistem
Melihat besarnya unjuk rasa yang terjadi, Jasmin Ramsey, direktur komunikasi di Center for Human Rights—organisasi nonprofit asal New York yang juga terletak di Iran mengatakan, aksi tersebut adalah cara mereka menyuarakan krisis impunitas di Iran.
“Ini adalah puncak dari usaha masyarakat selama lima tahun terakhir, meskipun negara merepresi mereka dengan kejam,” ujar Ramsey kepada The New York Times.
Sebab, demonstran yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut berasal dari berbagai latar belakang sosial. Mulai dari mahasiswa, buruh, guru, hingga pensiunan. Situasi semakin meradang akibat unggahan yang tersebar di media sosial.
Seperti disebutkan Ramsey, aksi yang sedang dilakukan masyarakat Iran lebih dari menyerukan satu permasalahan. Mereka marah terhadap sistem negara yang sudah mengakar. Sebut saja korupsi hingga sikap hipokrit dan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah.
Sama halnya dengan tugas utama polisi moral di Iran. Mereka berperan untuk menangkap masyarakat yang pakaiannya tidak sesuai dengan undang-undang, termasuk perempuan yang tidak memakai jilbab. Namun, tanggung jawab itu sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai kebajikan sepenuhnya, lantaran termasuk merampas kebebasan perempuan dalam berpakaian.
Lebih dari itu, mereka terus menekankan, perempuan harus berjilbab. Pun upaya penegakan dilangsungkan lewat tindakan kekerasan, seperti yang terjadi pada Amini dan beberapa perempuan lainnya yang dihukum akibat melawan. Mirisnya, pada 2018, polisi moral melecehkan seorang transpuan lantaran dianggap gendernya tidak sesuai. Saat itu, polisi juga enggan membantunya.
Realitas ini semakin membebankan perempuan yang terkungkung dalam rezim kuno. Ditambah pada akhir Agustus lalu, pemerintah Iran berencana memberlakukan denda bagi perempuan yang melanggar aturan penggunaan hijab di tempat umum—sebagaimana dilaporkan oleh Hamshahri Online.
Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, sekretaris di Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil Iran itu mengatakan, denda akan diberlakukan di 11 tempat. Di antaranya adalah di mobil dan kantor. Menurunnya tingkat kesopanan di publik menjadi alasan Golpayegani. Karena itu, nantinya akan ada kamera yang memotret warga yang bersangkutan, kemudian dendanya akan dikirimkan ke rumah mereka yang dianggap melanggar.
Adapun rencana pemberlakuan denda tersebut dipandang, sebagai pemanfaatan sistem untuk meraup keuntungan finansial dengan berlandaskan agama.
Selain urusan pakaian, awal September lalu Ensieh Kazhali, salah satu wakil presiden Iran, dilaporkan dalam pengawasan karena anaknya diduga mendirikan perusahaan untuk menjual virtual private networks (VPN) di Kanada.
Tak dimungkiri, banyak masyarakat Iran yang menggunakan VPN untuk tetap mengakses layanan internet yang dibatasi oleh rezim. Melansir BBC News, pada 2013, setidaknya ada setengah dari 500 situs teratas di dunia yang diblokir pemerintah Iran.
Selain media sosial dan layanan hiburan seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan Netflix, situs-situs itu juga menyangkut akses ke informasi lainnya. Misalnya kesehatan, sains, pornografi, olahraga, berita, dan belanja.
Bahkan, sejak (21/9), pemerintah Iran telah membatasi akses ke Instagram dan WhatsApp, dua jaringan sosial terakhir yang bisa digunakan di negara tersebut, dengan alasan keamanan.
Hal ini serupa dengan yang terjadi pada 2019, ketika pemerintah menonaktifkan internet selama seminggu, untuk meredam protes kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berubah menjadi politik.
Dengan kata lain, masyarakat tidak mendapatkan kebebasan atas haknya untuk berbicara di ruang sosial dan mengakses informasi. Terlebih di situasi saat ini ketika keselamatan mereka kembali terancam.
Baca Juga: Apakah Feminisme Bisa Selaras dengan Ajaran Islam?
Rezim Iran Belum Ramah buat Perempuan
Bukan sebuah rahasia bahwa sampai saat ini, pemerintahan di Iran belum ramah bagi perempuan, terutama setelah kematian Khomeini pada 1989. Saat itu, para mullah mulai melakukan pelarangan hak-hak perempuan.
Penindasan terhadap perempuan kemudian berlanjut, bahkan menjadi semacam landasan dalam aturan rezim, untuk melanggar kebebasan perempuan. Bahkan, mereka minim memiliki lapangan pekerjaan. Pada 2017, Human Rights Watch mencatat, meskipun 50 persen perempuan Iran lulus dari perguruan tinggi, hanya 17 persen di antaranya yang termasuk dalam angkatan kerja.
Kesenjangan itu terjadi lantaran pemerintahnya sendiri yang membuat peraturan diskriminatif, dengan membatasi partisipasi perempuan di dunia kerja. Namun, marginalisasi perempuan juga tidak lepas dari ideologi politik yang terbentuk sejak revolusi Islam, yang memandang peran ideal perempuan hanya sebatas menjadi istri dan ibu.
Berdasarkan laporan National Council of Resistance of Iran (NCRI) Women’s Committee, pandangan itu juga dipengaruhi perspektif misoginis, yakni menganggap Tuhan telah menciptakan perempuan untuk peran khusus, dan masalah pekerjaan mereka bukanlah isu utama.
Lebih dari itu, konstitusi yang dibangun mullah juga memosisikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki, seperti menjadi budak seksual. Contohnya anak perempuan berusia 13 tahun, yang pendidikannya bisa dicabut begitu saja apabila ayahnya diberikan persetujuan oleh hakim, untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang berusia jauh lebih tua. Sebab, mereka sudah dianggap dewasa ketika berusia delapan tahun sembilan bulan.
Situasi tersebut menampilkan bagaimana perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Sampai saat ini, mereka dikontrol oleh laki-laki, baik ayah, pasangan, hingga pemerintah. Kondisi itu membuat mereka sulit untuk memberdayakan diri.
Namun, bukan berarti sama sekali tidak ada perempuan yang mampu memberdayakan diri. Mungkin kamu familier dengan nama Shirin Ebadi, aktivis politik dan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pengacara asal Iran.
Awalnya, ia membuka praktik hukum dan membela orang-orang yang dipersekusi oleh para otoriter. Kemudian, pada 2002 ia sempat dipenjara akibat mengkritisi hierokrasi di negaranya. Namun, peristiwa itu tidak menghentikan langkah Ebadi. Ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.
Salah satunya kasus Arian Golshani, seorang anak yang bertahun-tahun disiksa dan dipukuli ayah dan kakak tirinya sampai meninggal. Ia menggarisbawahi kasus tersebut sebagai contoh kebijakan di Iran yang problematik. Pasalnya, negara tersebut memberikan hak asuh anak dalam kasus perceraian kepada ayahnya, sekalipun ayahnya bersikap kasar seperti yang dilaporkan ibu Golshani kepada pengadilan.
Atas upayanya, pada 2003 Ebadi mendapatkan penghargaan Nobel Peace untuk perannya dalam menyuarakan demokrasi dan HAM—terutama hak perempuan, anak-anak, dan pengungsi.
Itu bukan berarti keselamatannya saat melakukan itu semua tidak terancam. Pada 2008, Ebadi menerima sejumlah tuduhan, seperti meminta dukungan dari Barat. Atau menerima kritik dari berbagai pihak atas tindakannya untuk membela homoseksual, berpenampilan tanpa penutup kepala, dan mempertanyakan hukuman Islam.
Namun, lewat perjuangannya, Ebadi membuktikan bahwa setiap perempuan, termasuk di Iran, mampu memberdayakan diri dan membawa perubahan bagi lingkungan di sekitarnya.