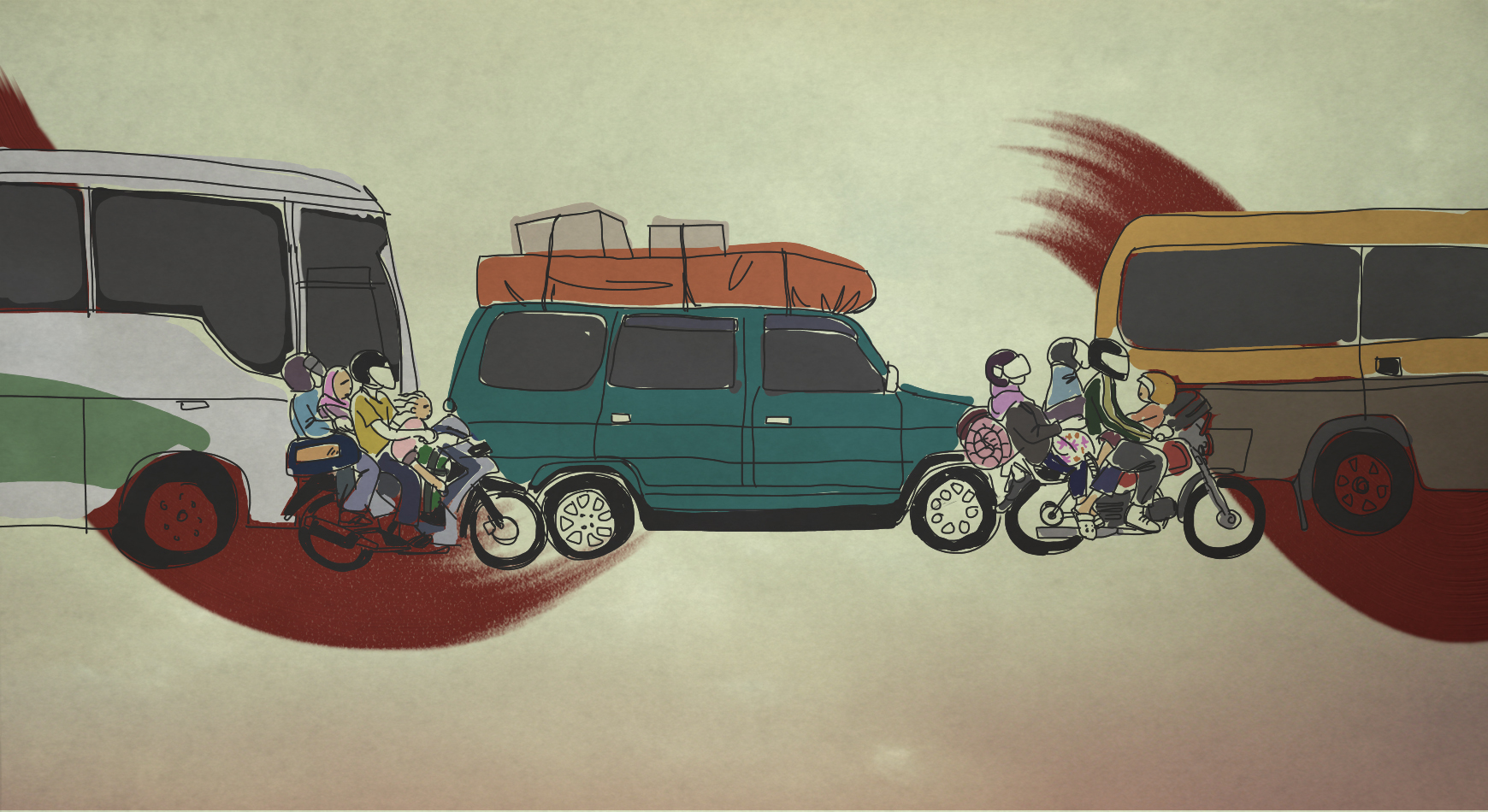Kekerasan Seksual Aktivis Kiri, Saatnya Bersih-bersih Gerakan Sendiri
Budaya pemerkosaan dan budaya imunitas masih mengakar dalam cara pandang masyarakat, termasuk di kalangan aktivis.
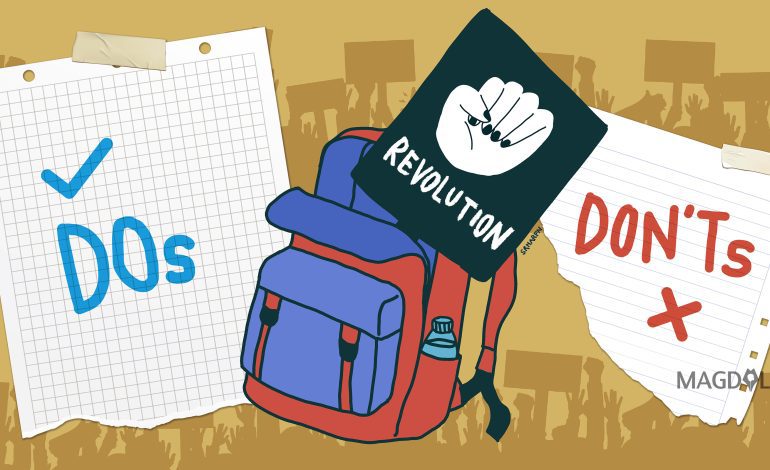
Linimasa Twitter belakangan dihebohkan dengan kabar kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktivis Appridzani Syahfrullah. Sejumlah korban perempuan diperkosa dan atau mendapat kekerasan seksual pada kurun waktu beberapa tahun sejak 2018.
Lewat penjelasan di akun Twitter @LAMRISURABAYA, (1/11) diketahui, pelaku melakukan kekerasan dengan modus yang nyaris seragam: Membantu tugas kuliah, membantu agar puisi korban dilirik penerbit, dan sejenisnya. Mirisnya, itu dilakukan kebanyakan saat korban sedang dalam kondisi tak berdaya, sehingga tak ada consent sama sekali. Lebih buntung lagi, sejumlah korban mengalami trauma psikologis bahkan sakit fisik karena pemerkosaan tersebut.
Kejadian ini mengingatkan kita dengan tuduhan kekerasan seksual terhadap aktivis dari Serikat Pekerja Media dan Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) tahun lalu. Kala itu, beberapa aktivis perempuan yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan tidak merasa kaget.
Theresia Sri Endras Iswarini, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mengatakan isu kekerasan seksual mulai diperbincangkan masyarakat pada 1990an, tapi sampai sekarang masih sering dianggap sebagai isu privat, bahkan di kalangan aktivis sendiri.
Asumsi bahwa semua aktivis kemanusiaan mengerti soal isu gender terkadang menyebabkan orang-orang kaget ketika kasus kekerasan seksual di lingkup progresif muncul, ujarnya. Padahal, menurut Theresia, tidak semua aktivis mengerti soal keadilan gender, apalagi soal ragam kekerasan seksual. Sehingga ketika isu ini mencuat, masih banyak aktivis hak asasi manusia yang enggan membicarakannya, bahkan membela pelaku, ujarnya.
“Di dunia yang patriarkal, tantangan untuk membicarakan soal isu gender ini besar sekali, apalagi untuk aktivis laki-laki karena memang tidak menarik, apalagi soal berbagi kuasa. Dan yang terpenting di sini, perspektif korban sulit juga diimplementasikan,” kata Theresia kepada Magdalene Rabu (5/8).
Ia mengatakan kritik sering kali dilayangkan kepada community organizer laki-laki (CO) laki-laki yang sering kali bertugas ke lapangan.
“Ketika melakukan live in di masyarakat, di lapangan mereka suka memacari perempuan yang tinggal di desa itu atau memacari CO perempuan lainnya. Ini kami kritik karena menyangkut soal etika profesionalisme sebagai aktivis kemanusiaan,” ujarnya.
Aktivis perempuan Faiza Marzoeki mengatakan, belum ada perubahan yang cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir ketika membicarakan soal isu kekerasan seksual dalam gerakan progresif.
“Banyak aktivis perempuan yang menjadi korban dan menahan diri untuk melapor dengan berbagai alasan. Kalau dulu alasannya karena situasi politik saat itu. Atau dibilangnya hal ini akan mengganggu gerakan,” ujar Faiza kepada Magdalene (3/7).
Baca juga: Pentingnya Organisasi Miliki SOP untuk Tangani Kekerasan Seksual
Fenomena global
Lily Puspasari, Program Management Specialist Badan PBB untuk Perempuan UN Women, mengatakan isu kekerasan seksual di kalangan aktivis HAM tidak hanya terjadi di Indonesia. Ia mengacu pada survei di tahun 2016 yang dilakukan oleh Humanitarian Women Works, sebuah jaringan internasional yang dibentuk oleh pera pekerja kemanusiaan perempuan. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.005 responden perempuan dari 70 organisasi kemanusiaan internasional.
“Dari jumlah responden tersebut, 55 persen pernah satu kali mengalami pendekatan secara sensual yang tidak diinginkan dari pekerja laki-laki, dan 33 persennya pernah mengalami berkali-kali,” ujar Lilly kepada Magdalene (5/8).
Selain itu, 48 persen responden pernah satu kali mengalami kontak fisik yang tidak diinginkan, dan 27 persennya sering mengalami hal tersebut. Kemudian 27 persen pernah satu kali mengalami dicium secara paksa oleh rekan kerja laki-lakinya, dan 9 persen mengalaminya berkali-kali. Temuan lain dari survei tersebut memperlihatkan bahwa 69 persen dari total responden tidak melaporkan kasusnya.
“Alasan tidak melapor macam-macam: Konsekuensi pekerjaan, tidak dapat promosi, ketakutan pelaku akan membalas, tidak mempercayai sistem yang ada, atau victim blaming (menyalahkan korban),” ujar Lily.
Ia menambahkan, sebetulnya sejumlah organisasi atau organisasi non pemerintah (NGO) internasional sudah memiliki prosedur operasional standar (SOP) prosedur terkait dengan kekerasan seksual. Namun Lily mengingatkan kembali bahwa budaya pemerkosaan dan budaya imunitas masih mengakar dalam cara pandang masyarakat, termasuk di kalangan para aktivis.
Tribunal sebagai alternatif
Menurut Theresia, autokritik terhadap gerakan terkait kekerasan seksual sudah mulai berjalan, namun memang masih banyak tantangannya. Salah satu cara yang dulu pernah dilakukan adalah tribunal rakyat atau pengadilan rakyat, sebuah bentuk peradilan yang diinisiasi warga untuk menyelesaikan sebuah perkara.
Baca juga: Sebagai Penyintas, Ini yang Saya Pelajari dari Kasus Sindikasi
Pada era 90an akhir hingga awal 2000an, tribunal menjadi wadah aktivis perempuan untuk menceritakan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Faiza Mardzoeki pernah menghadirinya pada tahun 2000an, ketika sebuah tribunal publik diadakan untuk mengadili seorang aktivis HAM yang melakukan kekerasan seksual terhadap seorang aktivis perempuan.
“Pengadilan tersebut diadakan di gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, dan dihadiri oleh pelaku, korban dan para ahli, yang di sini bisa dibilang sebagai hakim lah. Ada (aktivis) Munir Said Thalib, Karlina Supelli, Asmara Nababan, Kyai Hussein,” ujar Faiza.
Aktivis perempuan Yeni Rosa Damayanti, salah satu pihak yang membantu penyelenggaraan tribunal tersebut, mengatakan bahwa pengadilan publik tersebut dilakukan secara terpisah antara pelaku dan korban. Tribunal diadakan atas dasar permintaan korban, yang kebetulan seorang pengacara yang tahu betul yang akan ia hadapi lewat mekanisme hukum formal.
“Kami bersepakat membuat pengadilan gerakan lah. Para aktivis perempuan mulai rapat dan lobby ke mana-mana. Akhirnya terkumpullah dewan juri itu, salah satunya (aktivis dan pengacara) Nursyahbani Katjasungkana,” ujar Yeni pada Magdalene (6/8).
Ia menambahkan bahwa sidang tersebut hanya diadakan selama satu hari saja dan tidak hanya membicarakan satu kasus, tetapi juga menghadirkan beberapa testimoni lain dari aktivis perempuan yang juga mengalami kekerasan seksual dari aktivis HAM.
“Walaupun saat itu kasus utamanya memang teman kami si A ini, tetapi ada juga beberapa teman aktivis perempuan yang menyumbang testimoni, dari balik tirai. Ketika testimoni keluar, kami shock sekali dengan banyaknya nama-nama aktivis HAM mumpuni yang disebut sebagai pelaku,” kata Yeni.
RUU PKS menjadi sangat penting, baik dalam lingkup masyarakat maupun di dalam gerakan, karena perlu ada payung hukum formal untuk melindungi hak-hak korban.
Sidang dilakukan secara terbuka dan publik dapat bertanya jawab secara langsung. Kata Yenni, waktu itu yang datang ratusan orang dari berbagai lini aktivisme progresif, dan tentunya aktivis perempuan.
Theresia dari Komnas Perempuan juga pernah dua kali menyaksikan tribunal untuk mengadili kasus kekerasan seksual dengan mekanisme yang sama dengan yang disebut Faiza dan Yeni.
“Jadi itu adalah alternatif atau terobosan merespons kekosongan hukum tentang kekerasan seksual di gerakan sosial. Selain itu juga sebagai efek kejut lah untuk aktivis laki-laki, bahwa ini bukan isu main-main. Pada akhirnya, pelaku dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi sosial,” ujarnya.
Yeni mengatakan tribunal memang salah satu cara aktivis perempuan saat itu bukan hanya sebagai autokritik, tetapi sebagai hantaman besar terhadap gerakan progresif yang dahulu masih sangat macho.
“Saya lebih puas dengan bagaimana tribunal ini diselenggarakan dan respons publik di dalam acara tersebut, dan merasa cukup puas dengan sanksi sosial untuk pelaku. Hanya saja saya menyayangkan, pada akhirnya tidak ada keputusan akhir yang konklusif seperti menyatakan pelaku bersalah. Jadinya mengambang saja begitu,” ujarnya.
Pengesahan RUU PKS semakin mendesak
Yeni mengatakan bahwa pandangan aktivis progresif terhadap isu gender mulai berubah di awal tahun 2000an akibat tekanan donor, penyelenggaraan tribunal, dan juga aturan pengarusutamaan gender yang membuat isu gender kembali di posisi sentral.
“Waktu itu beberapa lembaga donor internasional mensyaratkan pemahaman gender seperti pelatihan gender. Aktivis perempuan kemudian mulai bergerak untuk memberi pelatihan ke lembaga non-isu perempuan,” ujarnya.
Pelatihan-pelatihan gender seperti ini menurut Yeni sangat intensif dilakukan di organisasi-organisasi HAM di awal 2000an, dan saat itu gerakan perempuan berada di puncak kejayaannya.
“Dulu autokritik berjalan dengan lancar dan menurut saya pengawasan di dalam gerakan lebih terpantau. Namun, memang sejak konservatisme agama meningkat dan saat ini aktivis perempuan juga sibuk melawan narasi seberang, akhirnya kita lengah juga ke dalam gerakan sendiri,” ujar Yeni.
Baca juga: Komnas Perempuan: Sahkan RUU PKS atau Risiko Dipermalukan di Dunia Internasional
Untuk mendorong agar isu kekerasan seksual kembali menjadi isu sentral dan diperbincangkan secara serius, Theresia dari Komnas Perempuan mengatakan, perlu ada kebijakan tentang perlindungan perempuan pembela HAM dan tentu saja pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
“RUU PKS menjadi sangat penting dengan keadaan saat ini, baik dalam lingkup masyarakat maupun di dalam gerakan sendiri. Perlu ada payung hukum formal agar korban terlindungi hak-haknya,” ujarnya.
Sepakat dengan Theresia, Yeni mengatakan bahwa untuk menghentikan kasus-kasus kekerasan seksual memang perlu ada hukuman yang membuat pelaku kapok.
“Korban perlu dikuatkan untuk bersuara. Memang menggugat secara hukum itu lelah, tetapi itu sangat perlu. Makanya RUU PKS harus disahkan,” ujarnya.
Selain mendorong pengesahan RUU PKS, Lily dari UN Women mengatakan, perlu ada niat yang lebih dari organisasi untuk membangun mekanisme pelaporan khusus kekerasan seksual yang komprehensif dan berpihak kepada korban.
“Mekanisme ini juga akan membantu kampanye seperti #Metoo untuk meningkatkan kesadaran dalam gerakan terhadap isu ini,” ujarnya.
Lily menambahkan, organisasi juga perlu membangun mekanisme untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang bagus dan komprehensif. Selain itu, perlu disediakan alternatif lain di luar organisasi, misalnya berkomunikasi dengan pihak ketiga untuk mediasi, demi menghindari campur tangan relasi kuasa organisasi.
“Menurut saya, satu kejadian itu sudah menjadi tamparan besar untuk kita. Satu kasus itu kan sebuah puncak gunung es ya, jadi sensitivitas gender itu harus mulai dari awal dan dimonitor,” kata Lily.
Artikel ini pertama kali terbit pada 8 Agustus 2020 dan diunggah kembali dengan sedikit pengantar untuk tujuan jurnalistik.