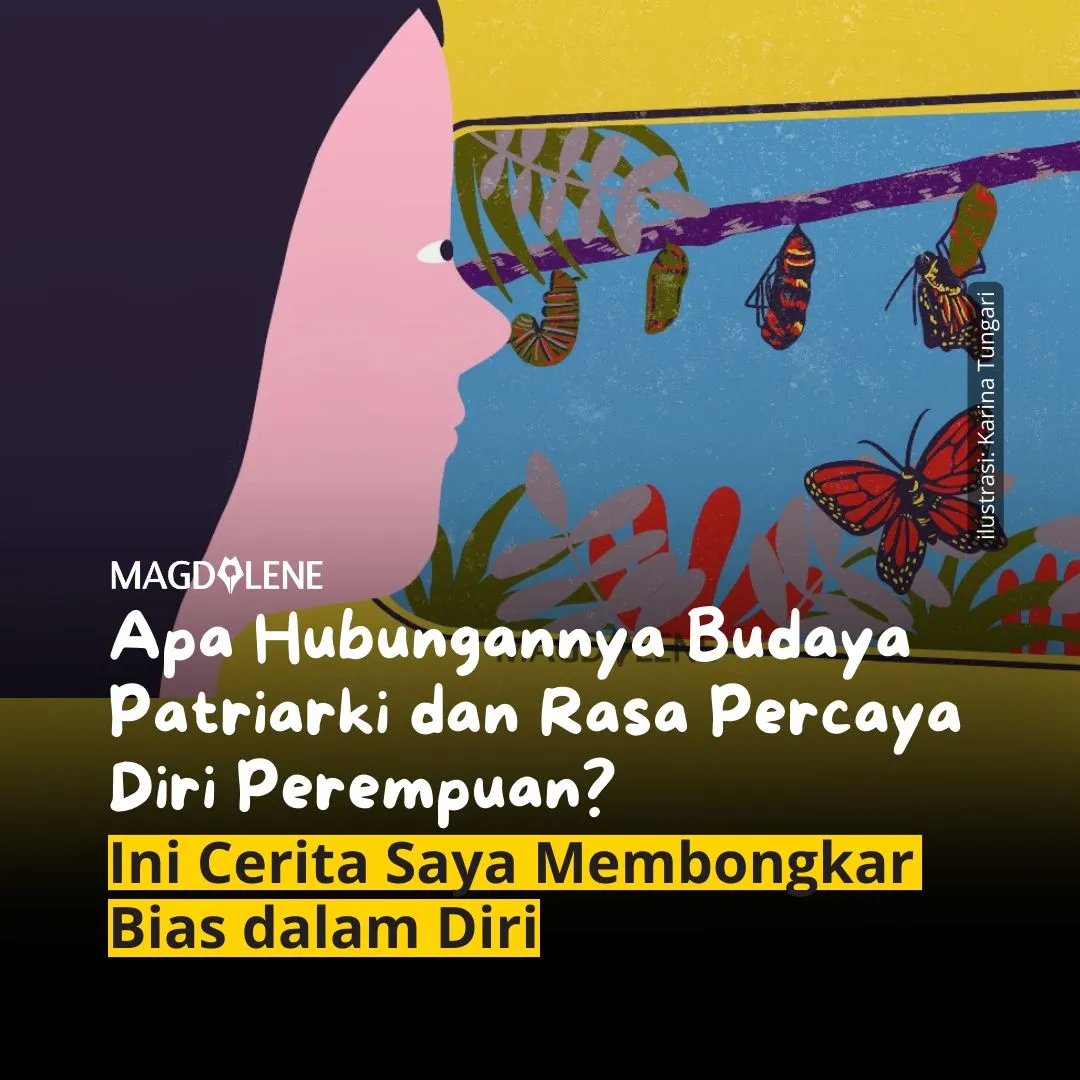Terpasung dalam Kepala Sendiri Akibat Gangguan Bipolar
Penyakit jiwa bukanlah aib yang sepatutnya dipermalukan, melainkan sesuatu yang seharusnya dipulihkan, diperbaiki, diobati.

Setiap malam, sedetik sebelum memejamkan mata untuk tidur, saya selalu memutar Nocturne No. 2 in E Flat gubahannya Chopin, dan di antara kegelapan yang saya peroleh begitu memasuki alam mimpi, perlahan saya merasa berpusar-pusar. Pusaran berwarna biru, kuning, hitam, dan putih, mirip lukisan The Starry Night milik Vincent Van Gogh. Saya seperti tersedot, teraduk, bergumpal-gumpal, dan perlahan terpisah dari realitas.
Kepala saya seperti disusupi angin ribut, dan bisikan-bisikan itu kembali datang layaknya rutinitas. Nada-nada yang seharusnya masih mengalun lewat pemutar musik sudah berganti dengan caci-maki dan kata-kata yang membuat saya kehilangan harga diri. Sontak saya terbangun dengan air mata bercucuran, berusaha menekan suara tangis supaya tidak terdengar orang lain, dan bisikan-bisikan itu semakin menusuk telinga.
“You’re a failure.”
“You’re a waste of space.”
Dan ketika saya mencoba mengingat wajah-wajah orang yang saya sayangi, bisikan itu seolah menepis, “Kamu enggak berguna. Kamu enggak penting. Mereka cuma pura-pura peduli karena kamu menyedihkan.”
Keadaan itu selalu berulang, dan kerap terjadi setiap kali saya melewati episode campuran, karena tepat di satu tahun yang lalu, di usia yang ke dua puluh, saya didiagnosis mengidap Bipolar Affective Disorder.
Sebetulnya, sebelum saya mengetahui apa yang saya derita, saya telah lama mengalami gejala dengan suasana hati naik-turun yang mengganggu kehidupan sosial saya. Kondisi tersebut bermula saat saya masih duduk di kelas dua SMP, dan semakin terasa ketika saya menginjak bangku SMA. Saya kesulitan mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Terkadang menjadi impulsif dan ekstra percaya diri, di lain waktu saya bakal menolak untuk berkumpul dan lebih memilih mengurung diri di kamar selama berhari-hari, merasa sedih sendiri tanpa alasan yang jelas.
Saya mengira kalau kondisi itu cuma kepribadian pasca-pubertas alih-alih sebuah penyakit. Sampai akhirnya, di pertengahan 2016, keadaan saya kian berantakan.
Saya tidak ingin keluar kamar. Saya kesulitan bangun dari tidur dengan perasaan tidak menentu. Saya merasa khawatir, tapi tidak tahu apa yang harus dikhawatirkan. Saya takut, tapi tidak mengerti apa yang membuat saya takut. Saya menjadi murung, memutuskan koneksi dengan dunia luar, paranoid, dan gemar menangis. Saya pun tidak paham apa yang sebetulnya terjadi, yang jelas semua orang membuat saya takut. Perasaan saya mulai dipenuhi agitasi, mental saya tiba-tiba terguncang, membuat saya memutuskan berhenti dari pekerjaan sampingan karena tidak ingin membuat masalah lebih banyak.
Hari demi hari berlanjut, dan saya malah merasa orang-orang mulai membicarakan saya. Tidak peduli sejauh apa saya menghindar, pemikiran-pemikiran tersebut terus membanjiri saya, menguasai saya, dan akhirnya bermuara pada perasaan curiga yang sesat. Saya beranggapan bahwa manusia-manusia yang bersedia mengulurkan tangannya kepada saya hanya sekumpulan cecunguk palsu. Saya memiliki masalah kepercayaan. Saya tidak bisa percaya dengan niat mereka. Bukan tidak ingin, tapi tidak bisa.
Ketika itu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya. Saya hanya bisa menangis, menangis, dan menangis. Di ruangan yang sepi, saya menangisi penderitaan yang sungguh menyakitkan, dan saya bisa mendengar tawa-tawa membahana di kepala saya. Ada banyak kabut dalam benak saya sehingga saya kesulitan berpikir jernih, dan saya tidak punya siapa pun untuk membicarakan keadaan ini—karena saya yakin, mereka tidak akan mengerti.
Lalu saya mencoba memberi sugesti kepada diri sendiri dengan melakukan kegiatan spiritual seperti beribadah, membaca kitab suci, merapal doa-doa yang diajarkan oleh agama saya, tetapi “iblis” dalam kepala saya justru bertambah kuat. Energi negatif, yang mulanya hanya sebesar biji kedelai, terasa membesar dan, entah bagaimana, kekuatannya seperti berhasil menjajah alam bawah sadar saya. Hal itu diperparah dengan mimpi-mimpi buruk yang kerap menghantui saya.
Kemudian, setelah hampir dua pekan bergulat dengan hari-hari yang kelabu, keadaan justru berbalik; saya merasa jadi manusia paling gagah sedunia, manusia paling penting, dan bertingkah berlebihan. Saya bisa tidak tidur semalaman untuk melakukan banyak kegiatan saking semangatnya—seolah-olah sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa.
Anehnya, keadaan itu selalu berulang laksana siklus. Dalam sebulan, saya bisa merasa depresi, lalu seminggu kemudian, saya akan kembali kepada teman-teman dengan wajah bersinar dan gerakan energik.
Kejanggalan dalam perilaku tersebut mendorong saya untuk memeriksakan diri ke puskesmas, dan mendapat rujukan ke rumah sakit jiwa.
Rumah. Sakit. Jiwa.
Kenyataan itu membuat saya tiba-tiba terpuruk.
Di sepanjang jalan menuju RSJ, saya refleks menangis. Kondisi ini, selain menyakiti fisik dan pikiran, juga menyakiti hati saya. Terbayang bagaimana orang-orang bakal berpikir tentang saya jika mereka tahu apa yang sudah terjadi dengan saya. Terbayang bagaimana tatapan-tatapan jijik itu terhunus ke wajah saya. Terbayang bagaimana sedihnya orang tua saya ketika mengetahui kalau anaknya mengidap gangguan jiwa.
Mendadak, saya menjadi jijik dengan diri sendiri.
Lalu, usai psikiater mendiagnosis saya dengan Gangguan Afektif Bipolar (perubahan suasana hati ekstrem dengan gangguan afektif), saya diberi sejumlah obat, di antaranya Chloropromazine, Risperidone, Nopress, dan THP.
Saya tidak mengerti. Obat-obat itu seharusnya membantu meredam gejala yang muncul. Namun ketika mengonsumsinya, kondisi saya justru semakin memburuk. Tremor, dehidrasi, disorientasi, kognisi yang terganggu, dan berat badan yang menurun drastis, membuat beberapa teman mulai bertanya-tanya; kamu kenapa? Kok kamu kurus banget kayak orang penyakitan?
Tentu saya tidak bisa bilang kalau saya sakit jiwa, maka saya cuma tertawa untuk mengaburkan pertanyaan-pertanyaan itu.
Namun, akhir-akhir ini, setelah mempelajari fase depresif-mania yang kerap melanda, saya bisa mengeluarkan seluruh cairan hitam itu dari dalam kepala. Saya berupaya menyembuhkan diri sendiri tanpa obat-obatan, tanpa harus mengganggu aktivitas sehari-hari. Hubungan saya bersama orang lain juga semakin terkendali, dan kondisi saya mengalami banyak kemajuan.
Beruntung, ketika saya memberanikan diri untuk terbuka, beberapa teman akhirnya bisa paham (atau mencoba paham) dan menerima keadaan saya. Mereka tidak menuntut macam-macam, tidak pula mengatakan kalimat-kalimat yang bisa memicu gejala penyakit saya. Meski Bipolar secara tidak langsung telah mempersempit lingkaran pertemanan saya, saya senang dianugerahi orang-orang terdekat yang selalu mendukung, yang bisa kembali membuat saya percaya kalau hidup ini masih layak diperjuangkan.
Untuk siapa pun yang beranggapan kalau orang-orang dengan gangguan jiwa adalah orang-orang buangan, kalian seharusnya malu. Karena penyakit ini bukanlah aib yang sepatutnya dipermalukan, melainkan sesuatu yang seharusnya dipulihkan, diperbaiki, diobati. Sama seperti kanker, sama seperti penyakit-penyakit fisik pada umumnya.
Happy (belated) World Bipolar Day!
Happy belated birthday, Vincent Van Gogh!
Amaliah Black, 21 Tahun, penyintas Bipolar Disorder dan penggemar teh Thailand sekaligus Cole Sprouse. Masih kuliah di Universitas Sriwijaya, tapi sebentar lagi lulus, kok.