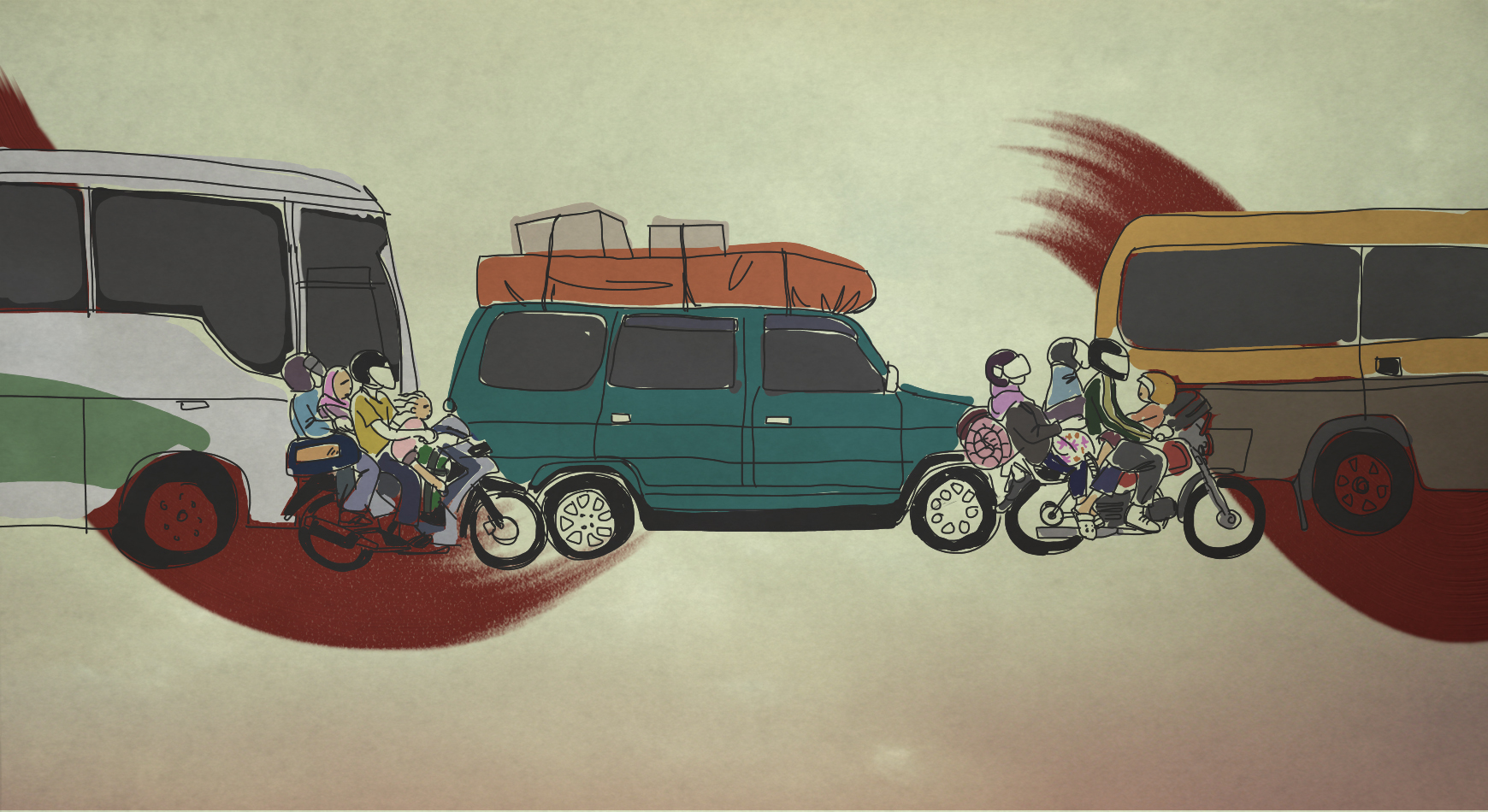‘Fleabag’ dan Narasi Perempuan yang Tak Sempurna
Serial ‘Fleabag’ menampilkan karakter dan kisah perempuan yang lebih realistis.

“I have a horrible feeling that I’m a greedy, perverted, selfish, apathetic, cynical, depraved, morally bankrupt woman who can’t even call herself a feminist.”
Kalimat ini tercetus di episode pembuka Fleabag, serial komedi Inggris yang baru saja menyapu bersih hampir semua kategori penghargaan dunia pertelevisian Hollywood dan Inggris, termasuk Emmy Awards, Golden Globes Award, dan BAFTA. Dari satu kalimat ini saja, kita diperkenalkan kepada sang tokoh utama, yang hanya kita kenal sebagai Fleabag, sebagai perempuan milenial London yang jauh dari sosok perempuan idaman yang sempurna.
Ditulis dan diperankan oleh Phoebe Waller-Bridge, Fleabag adalah wanita yang memiliki banyak cacat dan cela. Ia terobsesi dengan seks; ia menjalankan usaha kafe yang terancam bangkrut; ia bolak-balik berkencan dengan berbagai lelaki tanpa keseriusan; ia pesimistik, canggung, sarkastik, dan tidak mau berurusan dengan hal-hal yang menyangkut emosi dan perasaan.
Hal ini diperparah (atau mungkin merupakan salah satu penyebab perilakunya) oleh keluarga Fleabag yang tidak harmonis. Ayahnya (Bill Paterson) tidak tahu cara berkomunikasi dengan kedua putrinya. Godmother, calon ibu tiri Fleabag yang merupakan sebuah intisari dari sikap pasif-agresif khas Inggris (Olivia Colman bermain brilian sekali di sini). Kakak perempuan Fleabag, Claire (Sian Clifford), yang selalu ingin terlihat sempurna.
Singkat cerita, lupakan semua bayanganmu mengenai sesosok tokoh perempuan yang anggun, lembut, dan menawan. Fleabag adalah kekacauan. Fleabag adalah sosok berantakan di tengah dunia patriarkal yang menuntut kesempurnaan perempuan.
Penggambaran realistis
Karakter Fleabag sepertinya memang diciptakan untuk menggambarkan kehidupan perempuan, terutama perempuan metropolitan, secara riil. Tidak seperti gambaran glamor yang menjual mimpi konsumtif, atau gambaran patriarkal yang penuh dengan male-gaze yang mengobjektifikasi perempuan, Fleabag menggambarkan tanpa basa-basi segala konflik, amarah, dan kebingungan perempuan muda dalam menjalani kehidupannya.
Konflik Claire, kakak Fleabag, dalam menentukan pilihan antara kariernya yang menanjak atau rumah tangganya (dengan suaminya yang pemabuk), sambil terus berusaha memberi citra bahwa ia seorang perempuan yang “memiliki segalanya”, adalah sentilan bagi ilusi “perempuan sempurna” yang sering tergambar di media sosial.
Begitu juga konflik internal Fleabag, yang sebenarnya sedang sangat berduka cita atas kematian sahabatnya, namun terus-menerus menolak untuk berbicara mengenai luka batinnya. Alih-alih, Fleabag malah melarikan diri kepada seks dan kencan satu malam sebagai semacam obat pembunuh sakit untuk kesedihannya. Ini adalah sebuah realitas yang lucu namun menampar kita, para Milenial urban yang terbiasa untuk melimpahkan segala tekanan hidup ke hal-hal penghiburan sesaat semata.
Namun, tidak ada konflik yang lebih dahsyat di dalam hidup Fleabag selain dengan pertemuannya dengan seorang pendeta Katolik, yang hanya dikenal sebagai The Priest (atau Hot Priest, begitu internet menjulukinya, dimainkan oleh Andrew Scott yang sangat karismatik).
Fleabag, seseorang yang sekuler, menghadapi fakta bahwa ia jatuh cinta kepada Hot Priest, yang sudah bersumpah tidak akan memiliki hubungan emosional dan seksual seumur hidupnya. Tapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain; Hot Priest sendiri bukan tipikal gambaran pendeta yang suci dan bersih dari dosa. Ia sering mengumpat, hobi meminum wiski, dan secara literal menyatakan bahwa di dalam dirinya pun masih terdapat pertentangan mengenai kepercayaannya.
Interaksi antara Fleabag dan Hot Priest merupakan tulang punggung dari keseluruhan season kedua (dan terakhir) serial ini. Kontras dari perspektif mereka yang begitu bertolak belakang—pesimisme Fleabag versus optimisme Hot Priest—secara tanpa sadar membawa kita menuju tarik-menarik perenungan mengenai makna agama, kepercayaan, cinta, dan harapan di era modern yang segalanya terasa serba artifisial dan instan. Klimaks dari hubungan mereka memberikan sebuah episode terakhir yang sungguh pahit-manis, penuh dengan harapan, namun juga memilukan. Pada akhirnya, Fleabag belajar bahwa seks dan cinta adalah dua hal yang berbeda, dan bahwa ia harus belajar untuk jujur dengan perasaan dirinya sendiri.
Baca juga: Pasangan dalam Film yang Tak Seharusnya Jadi #CoupleGoals

Suara dan kritik perempuan
Di setiap episode, Fleabag sering mengajak mengobrol kita para penonton, breaking the fourth wall, dengan segala komentarnya yang sarkastis namun menggelitik. Tak jarang, komentar ini hanya berupa sebaris kata, atau bahkan hanya ekspresi sekilas semata, namun tak ayal membuat kita merasa dekat dengan Fleabag, seakan memiliki teman di layar kaca.
Dari masalah keluarga, lelaki, karier, fashion, gaya rambut, persahabatan, feminisme, hingga agama, semua tidak luput dari observasi Fleabag yang segar namun tetap tajam.
Siapa yang tidak pernah merasakan berkumpul dengan keluarga, kemudian dihujani dengan berbagai sindiran, dan ingin segera kabur dari acara? Siapa yang tidak pernah merasa kesal setengah mati dengan saudara kandung kita—namun pada ujungnya, kita tetap harus menjaga dan membela mereka? Siapa yang tidak pernah jatuh cinta dengan seseorang yang tidak mungkin akan kita dapatkan? (Dalam hal ini, kisah Fleabag sungguh juara: ia jatuh cinta kepada seorang pendeta!) Semua komentar jujur Fleabag ke penonton, di tengah-tengah segala kepura-puraan dan sikap pasif-agresif para karakter di sekelilingnya, menjadi pancingan tawa absurd dari komedi kelam ini.
Namun, segala komentar Fleabag ini juga bersifat kritik sosial, kontemplatif, dan cenderung introspektif. Contohnya, saat Fleabag mempertanyakan apakah dirinya akan menjadi “lesser feminist” seandainya ia terlahir dengan payudara yang lebih besar—sebuah pengandaian yang merupakan introspeksi sekaligus kritik terhadap privilese fisik yang mengobjektifikasi perempuan.
Di lain waktu, Fleabag mengungkapkan opini (sekaligus kritik) mengenai standar mode dan kecantikan ala Prancis, yang begitu seragam, begitu terstandar, namun menjadi kiblat dunia: “’Chic’ means boring. Don’t tell the French.” Baik itu masalah keluarga, lelaki, karier, fashion, gaya rambut, persahabatan, feminisme, hingga agama, semua tidak luput dari observasi Fleabag yang segar namun tetap tajam.
Baca juga: Ini Satu Alasan Lagi Mengapa Harus Menonton Drama Korea
Pada akhirnya, di sepanjang dua season yang terasa sangat singkat ini, kita merasa bahwa Fleabag adalah sahabat kita. Ia adalah suara yang berkecamuk di dalam hati semua perempuan, yang berusaha menjalani hidup yang penuh dengan tuntutan dan penghakiman masyarakat, namun tak punya pilihan lain selain untuk bertahan—dan mungkin, sambil sedikit menertawakan diri sendiri atas segala keabsurdan kehidupan.
Karenanya, kemenangan Fleabag di berbagai penghargaan pun tak ayal seperti memberikan sedikit ruang untuk bernapas bagi para perempuan sebagai manusia, yang begitu jauh dari kata sempurna. Ruang tersebut masih jauh dari utuh, jauh dari sepenuhnya menerima, namun Fleabag setidaknya membuka pintu untuk bernapas tersebut. Karena pada akhirnya, Fleabag adalah saya, adalah kamu, dan adalah kita semua.