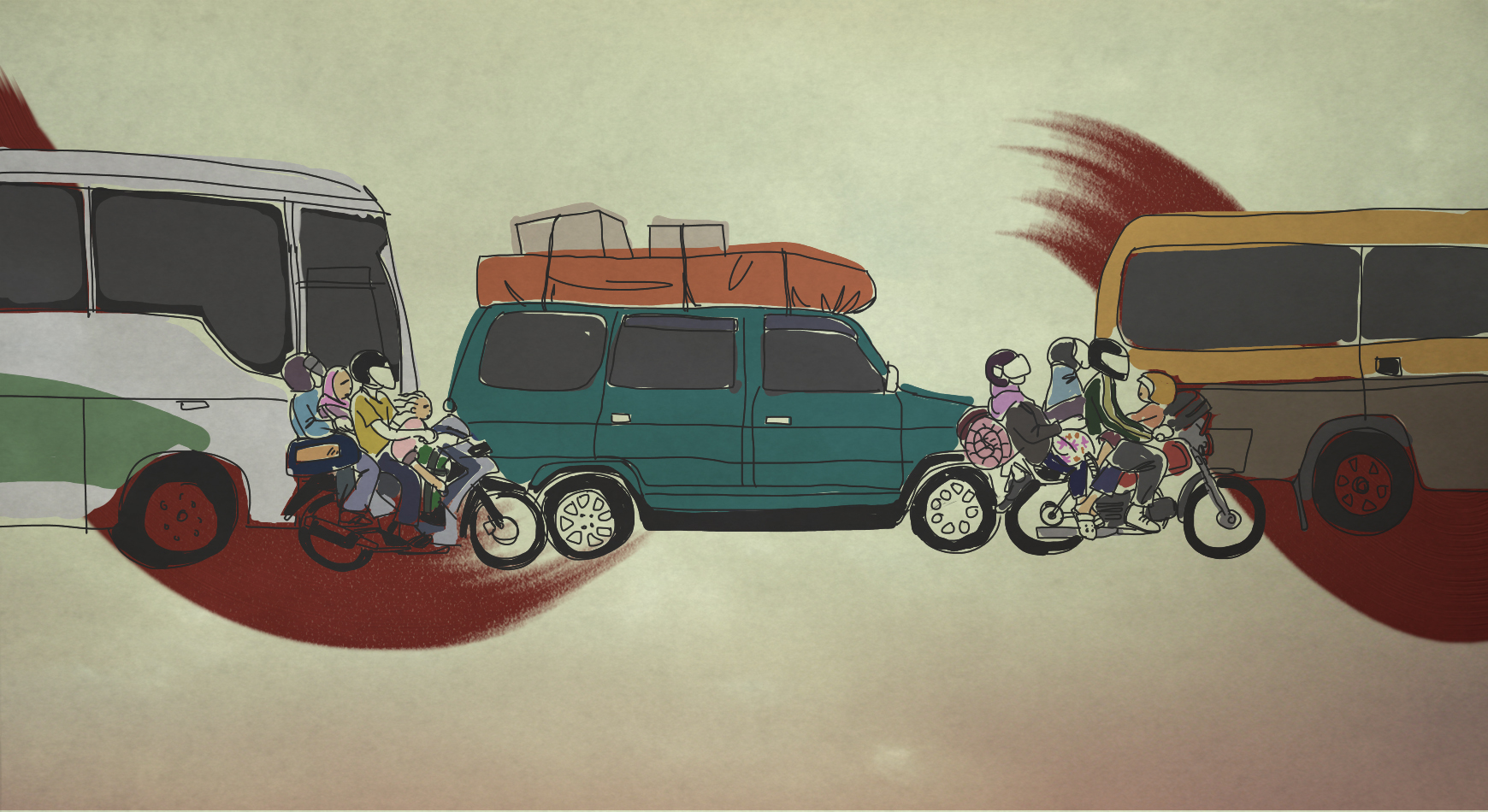“Hany” menangis tersedu-sedu saat sedang mengerjakan skripsi di perpustakaan kampusnya. Ia merasa tertekan dan kewalahan karena jika ia tidak menyelesaikannya pada semester ini, ia bisa dikeluarkan dari jurusannya.
Tidak lama setelah itu, tangisannya berhenti secara mendadak dan ia kembali bersemangat untuk menyelesaikannya lagi. Salah seorang temannya, yang juga sedang mengerjakan skripsi di perpustakaan, mendekatinya dan berkata, “Hany, jangan tersinggung ya. Tapi sepertinya kamu memiliki ciri-ciri seseorang yang bipolar.”
Hany tersentak oleh pernyataan itu, ditambah lagi karena temannya memang mahasiswa Psikologi. Pikiran bahwa ia memang bipolar sempat menghantuinya sampai akhirnya ia memutuskan menemui seorang psikolog. Ternyata ia tidak mendapatkan diagnosis bipolar, melainkan ada kecenderungan depresi akibat tekanan yang luar biasa.
Sayangnya, tidak banyak orang seberuntung Hany dalam mengakses layanan kesehatan mental dan mendapatkan diagnosis resmi dari profesional. Banyak orang kemudian suka melakukan self-diagnose atau diagnosis mandiri mengenai kesehatan mental. Di satu sisi hal ini baik karena menandakan adanya peningkatan kesadaran mengenai kesehatan mental. Di sisi lain, hal ini bisa menimbulkan sejumlah masalah.
Menurut Benny Prawira Siauw, seorang suicidologist atau ahli isu bunuh diri, kecenderungan diagnosis mandiri muncul karena manusia biasanya berusaha untuk mencari penjelasan tentang kondisi mereka sendiri.
“Kita ingin memahami diri sendiri, yang lebih mudah dilakukan dengan memasukkan diri kita ke dalam kotak-kotak. Misalnya, mengidentifikasi diri sebagai Aquarius karena sifatnya mirip. Atau mungkin memilih tipe-tipe dalam MBTI (Myers-Brigs Type Indikator, tes kepribadian psikologi),” ujarnya.
Menurut Benny, dalam kesehatan mental, label-label ini sedikit lebih rumit. Seseorang dapat bisa saja mengenali ciri-ciri dari depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan lainnya, tetapi belum tentu mereka bisa menentukan kategorinya dengan akurat.
Baca juga: Film ‘Joker’, Kematian Sulli, dan Gagal Paham Tentang Gangguan Mental
“Mungkin seseorang menyimpulkan bahwa kalau ia moody, ia seorang bipolar. Mereka tidak belajar tentang gejala-gejala itu secara mendalam. Padahal dalam kesehatan mental, satu gejala juga harus diperhatikan dari banyak perspektif,” lanjutnya.
“Sudah baik sebenarnya bahwa banyak komunitas yang membagikan infografik dan informasi tentang kesehatan mental. Orang-orang jadi semakin sadar dengan gangguan mental. Tetapi mereka merasa bahwa informasi yang ada di internet ini sudah cukup untuk mendiagnosis kondisi mental mereka,” kata Benny.
Menurut Benny, ada beberapa masalah yang mungkin timbul jika seseorang melakukan diagnosis mandiri mengenai kondisi mental mereka.
-
Penanganan yang salah
Dengan diagnosis yang salah dan hanya mengira-ngira tanpa konfirmasi dari seorang ahli, kita dapat menangani kesehatan mental kita dengan tidak tepat. Misalnya, saat kita merasa cocok dengan ciri-ciri seseorang yang depresi, kita akan mencari tahu apa penanganan yang tepat atau pengobatan apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang depresi. Padahal hal ini dapat membahayakan kita sendiri karena kita belum tentu mengidap gangguan mental tersebut.
“Walaupun kita menunjukkan semua ciri-ciri dari sebuah gangguan, semua ciri-ciri ini pun harus dilihat dengan berbagai perspektif,” kata Benny.
“Dari beberapa perspektif ini kemudian seorang profesional dapat menentukan diagnosis yang sesuai dan baru akan mencari penanganan yang terbaiknya.”
-
Justifikasi untuk perilaku tidak baik
Seseorang dengan mood swings atau perasaan yang berubah-ubah dapat menjustifikasi perilakunya dengan label yang mereka sematkan sendiri. Misalnya mereka merasa bahwa perilaku yang suka berubah-ubah itu adalah karena mereka bipolar. Lalu seseorang menjustifikasi kemalasannya dengan beralasan itu karena depresi. Padahal mereka sendiri belum mendapatkan diagnosis yang profesional, tetapi menjadikannya sebagai sebuah justifikasi.
“Hal ini dapat menghambat perkembangan perilaku seseorang. Dengan justifikasi seperti ini, mereka merasa mereka benar dengan menjadikan gangguan mereka sebagai sebuah alasan untuk perilakunya,” kata Benny.
Baca juga: Bunuh Diri pada Anak Muda dan Bagaimana Menghadapinya
-
Meningkatkan stigma
Stigma terhadap orang-orang yang memiliki gangguan mental sudah banyak, dan ini dipersulit dengan adanya orang-orang yang melakukan diagnosis mandiri. Mereka tidak memiliki informasi yang akurat atau mendalam tentang gangguan-gangguan mental, sehingga mereka juga tidak memberikan informasi yang akurat kepada orang-orang sekitarnya.
Maka, yang orang-orang sekitarnya tahu adalah bahwa orang yang memiliki gangguan mental spesifik ini memiliki ciri-ciri yang seperti mereka, padahal belum tentu itu benar. Misalnya seseorang mengaku dirinya sendiri sebagai seseorang yang bipolar, dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki emosi yang meledak-ledak. Orang-orang di sekitarnya kemudian akan mengidentifikasikan orang bipolar sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya.
Menurut Benny, kita harus terus mengingatkan dan membangun kesadaran pentingnya mendapat diagnosis resmi dari ahli seperti psikolog untuk masalah gangguan mental.
“Di setiap tes atau infografik seharusnya disediakan informasi bahwa ini hanya bisa ditegakkan oleh diagnosis, bukan acuan untuk diri sendiri,” kata Benny.
“Kita juga harus terus sadar dan lebih berhati-hati kalau ada yang membahas tentang gangguan mental. Kalau teman kita membahas tentang ciri-ciri gangguan mental, jangan takut untuk bertanya kalau mereka sudah pernah mendatangi psikolog atau psikiater untuk diagnosis dan mengatasi itu. Jangan hanya mengiyakan mereka, karena akhirnya bisa bahaya ke mereka dan juga ke orang-orang sekitarnya.”
Artikel ini adalah bagian dari kampanye 1001 Cara Bicara, hasil kerja sama Magdalene dan SKATA, sebuah inisitiaf digital yang membantu pemerintah Indonesia dalam membangun keluarga melalui perencanaan yang lebih baik.